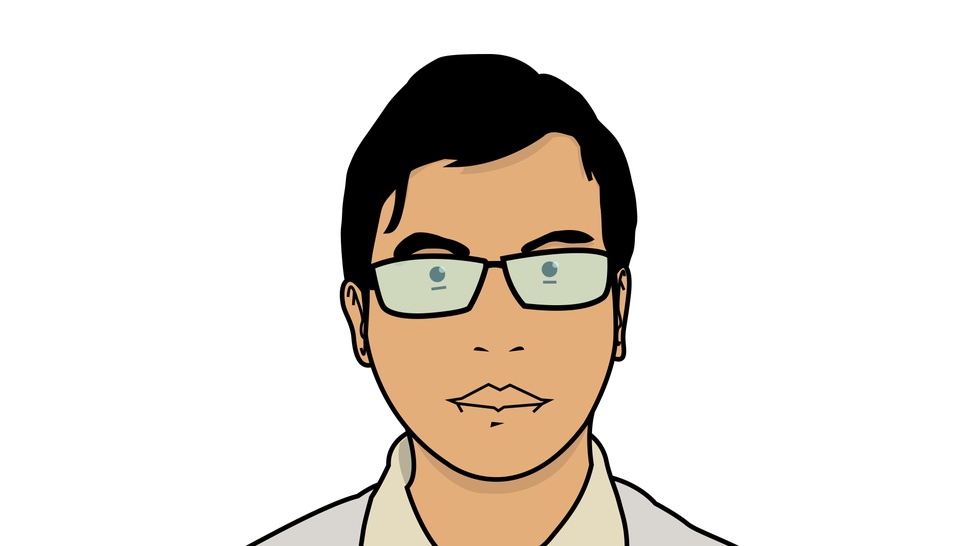tirto.id - Hal yang dianggap tidak mungkin sejak beberapa hari ataupun setahun yang lalu menjadi kenyataan: Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat. Seseorang yang diejek selama masa kampanye sebagai badut, bertingkah kekanakan, megalomania, rasis, narsis, dan penjahat seksual justru diberi kesempatan memegang tali kekang kekuasaan oleh rakyat Amerika.
Banyak yang mengkawatirkan masa depan dunia setelah terpilihnya Trump. Macam-macam kecemasannya: dari keruntuhan Amerika Serikat, kekacauan sosial akibat kerusuhan etnis, hingga Perang Dunia III.
Namun dalam pidato kemenangannya, hal yang tak disangka diucapkan: ia menyerukan persatuan untuk semua orang di Amerika Serikat, dari segala macam suku dan ras. Ia juga mengulang slogan-slogan populisnya untuk membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, melakukan negosiasi ulang kesepakatan dagang internasional, dan membuat Amerika berjaya kembali.
Kemudian dengan lihai dia mengubah jargon populisme itu menjadi gerakan bersama: As I've said from the beginning, ours was not a campaign but rather an incredible and great movement, made up of millions of hard-working men and women who love their country and want a better, brighter future for themselves and for their family.
Meskipun tampak bertujuan mulia, satu hal yang tak bisa ditolak: selain terpilih karena menjual populisme, Trump menang karena mengedepankan politik identitas.
Cara berpolitik dengan menjual sentimen agama, ras, atau nasionalisme itu tidak dapat dipungkiri sedang berkembang luas di hampir seluruh dunia dekade ini. Gejala itu paling tampak terjadi justru di negara-negara kampiun kebebasan, kebhinekaan, dan hak asasi manusia seperti di Eropa dan AS sendiri.
Naiknya popularitas partai ekstrim kanan di banyak negara Eropa tidak terpisahkan dari keresahan sosial akibat membanjirnya imigran ke benua tersebut. Dan partai-partai kanan itu dengan baik sekali menunggangi kecemasan itu dan mengartikulasikannya sebagai kecemasan bersama.
Referendum Brexit juga dihantarkan dengan kondisi serupa. Ketakutan akan adanya “mereka” yang datang ke negara “kita”, mereka yang akan mencuri kesempatan kerja, ruang hidup, dan mengubah nilai-nilai masyarakat, diumbar dan diartikulasikan dengan takaran yang membuat politik rasa takut merajalela.
Namun berbagai liputan media seolah luput melihat logika di belakang semua gejala ini. Politik identitas tidak akan mampu bekerja tanpa diikuti narasi populis yang melandasinya.
Anda bisa saja berkoar-koar betapa berjayanya ras A, negara B, atau agama C, namun dalam negara demokrasi masalah kepentingan rakyat hampir selalu menjadi penentu utama. Dengan demikian, dalam kasus Trump, ia juga tak lupa menjual janji-janji akan kehidupan yang lebih baik bagi.
Hal ini lah yang menjatuhkan si pesaing Hillary Clinton karena terlalu fokus menjual narasi identitasnya saja: sebagai presiden perempuan pertama, kepentingan kaum minoritas, dan sebagainya. Masalah-masalah seperti kesulitan ekonomi sehari-hari, ketakutan tidak mendapat pekerjaan, pendidikan dan harga hunian mahal, kejahatan yang meningkat, dan birokrasi yang bobrok, terkesan (atau dikesankan) seolah tidak menjadi prioritas.
Terlebih kesan Hillary sebagai kelanjutan pemerintahan Obama memang tidak bisa dihindarkan sepenuhnya. Inilah yang membuat Hilary agak kikuk, setidaknya ia tak dapat menjual jargon “perubahan”. Hilary tak bisa lepas dari cap sebagai bagian dari “kekuatan lama”.
Padahal cukup jelas pemerintahan Obama masih jauh dari sempurna sehingga bisa dianggap tidak memerlukan perubahan. Program-program Obama yang secara makro terlihat mulus, namun banyak bocel di sana sini. Selain malah makin meningkatnya sentimen rasial pada warga kulit hitam, banyak program kesejahteraan Obama tidak memberikan dampak signifikan ke daerah sub-urban.
Karenanya publik Amerika menantikan sosok yang benar-benar memberikan alternatif: antara politik identitas Trump atau “sosialisme demokratis”-nya Bernie Sanders. Dan kita tahu bahwa partai Demokrat sendiri menganaktirikan Sanders dan memilih Hillary yang mempunyai segudang permasalahan.
Secara singkat, politik identitas tak bisa dilawan dengan politik identitas “yang lebih lunak”. Ia harus dilawan dengan politik yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Lalu kepentingan publik yang mana? Bukankah akan jauh lebih populer kalau kita bilang saja kandidat X akan membela mati-matian agama A, ras B, atau warga negara C?
Justru di sinilah kita perlu mencermati kenapa jargon populis dan politik Identitas meluas. Pertama, adanya frustasi terhadap sistem politik yang ada, yang membuat banyak orang merasa aspirasi mereka tak didengar dan banyak masalah tak diselesaikan rezim yang berkuasa. Oleh karena itu orang berpikir perlu adanya terobosan ekstrim seperti kebutuhan untuk pemimpin yang “kuat”, “tegas”, atau “galak” untuk memimpin negeri yang kacau balau itu.
Kedua, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tampak begitu rumit dan susah untuk dimengerti awam: terorisme, persaingan ekonomi global, imigran, perubahan iklim, runtuhnya bank-bank besar, penyakit menular, dan sebagainya. Karenanya jalan keluar yang simpel dan tampak tegas seperti yang ditampilkan kampanye Trump menjadi mempesona.
Banyak yang membandingkan terpilihnya Trump kali ini mirip dengan saat terpilihnya Hitler pada 1933: sama-sama terpilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Baik referendum Brexit atau naiknya suara partai-partai sayap kanan di Eropa juga menunjukan bahwa demokrasi saja tidak cukup. Selalu akan ada bibit-bibit anti demokrasi yang mau tidak mau harus difasilitasi dalam sistem itu.
Hal yang serupa sudah lama kita rasakan di Indonesia dan kian terasa menguat akhir-akhir ini. Dalam pilkada DKI Jakarta ini, misalnya, narasi tentang identitas agama jauh lebih menguasai ruang perdebatan publik daripada hal-hal yang seharusnya lebih penting dibahas: tentang kesejahteraan warga, keadilan bagi yang miskin, infrastruktur ramah lingkungan.
Karenanya sesuatu yang selama ini absen dalam perpolitikan sudah selayaknya dihidupkan kembali: peran pendidikan politik warga. Agar kepentingan publik tidak menjadi alat jualan selama kampanye semata, agar kepentingan publik perlu dijaga dan diberdayakan lewat partisipasi politik.
Masalahnya sekarang istilah partisipasi politik juga tereduksi sejauh urusan mencoblos, berkampanye, atau berkomentar. Apalagi dengan asosiasi partai politik sebagai sarang korupsi, partisipasi publik jadi lebih merajai dunia sosial media dan protes jalanan. Politik dalam artian mengumpulkan daya, mengorganisasi kepentingan, dan menggunakannya untuk kepentingan bersama menjadi redup.
Mengorganisir kumpulan orang, berdiskusi tentang permasalahan yang ada, dan menjalankan langkah yang harus diambil tidak bisa terjadi di dunia maya semata. Mungkin itu pula sebab terbesar Hillary kalah: elok di televisi, memikat di sosial media, ngehits diberbagai media lain karena didukung orang yang biasa cuap-cuap, namun kalah dalam mengisi kesadaran orang banyak -- persisnya mereka yang selama ini diam dan menjadi minoritas bisu.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.