tirto.id - Frasa 'korupsi berjamaah' yang kerap didengungkan publik dan media massa kini sedang menemukan contoh yang sempurna: sekitar 70 nama-nama besar, mulai dari jajaran legislatif sampai eksekutif elite di Indonesia, terseret kasus megakorupsi e-KTP dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 2,5 triliun (versi Komisi Pemberantasan Korupsi).
Sejumlah penelitian dari para psikolog menerangkan bahwa korupsi berjamaah tak muncul dari ruang hampa. Ia tak bisa dipandang sebagai fenomena di permukaan saja. Akademisi University of Toronto Scarborough Pankaj Anggarwai dan profesor Nina Mazar dari University of Toronto misalnya, mencoba mengurai persoalan ini dengan sebait pertanyaan “mengapa di sejumlah tempat (institusi) lebih rentan terhadap suap dan korupsi dibanding yang lain?”
Keduanya menemukan bahwa orang yang hidup dalam budaya kolektif alias penganut kolektivisme cenderung lebih mudah terseret perilaku korup daripada masyarakat di dunia yang menjunjung sikap individualistis.
Dalam kolektivisme, individu selalu melihat dirinya “interdependen” dan sebagai bagian integral dari kelompok yang lebih besar. Sebagaimana teori aksi massa, penganut kolektivisme pun merasa kurang bertanggung jawab atas tindakan mereka dan rasa bersalah saat korupsi juga rendah.
"Kolektivisme dapat turut mempromosikan suap dengan menyebarkan tanggung jawab [kepada banyak pelaku]," kata Profesor Nina Mazar.
Ada keberanian lebih saat seseorang bertindak korup bersama-sama ketimbang sendirian. Semakin besar anggota korupnya, ada semacam rasa lebih aman yang lebih, mengingat jika kasusnya terbongkar mereka tak akan masuk bui sendirian.
Dalam paper yang dipublikan di Jurnal Psychological Science, kedua peneliti menggunakan data dari lembaga pemerhati korupsi Transparency International yang berisi sejauh mana kecenderungan pebisnis dari 22 negara dalam melakukan praktik suap dalam bisnis mereka. Kecenderungan tersebut dipatok dengan standar nilai tertentu yang kemudian dibandingkan dengan tingkat kolektivitas dan besarnya kekayaan dari masing-masing negara.
Hasilnya menguatkan asumsi awal: semakin besar kekayaan dan tingkat kolektivitas sebuah negara berpengaruh terhadap semakin tingginya tradisi suap menyuap kepada mitra bisnis.
Namun, bukan berarti koruptor memandang bahwa suap dan tindakan korup lain itu normal. Dalam bagian lain penelitian disebutkan bahwa mereka rata-rata menilai apa yang mereka lakukan sesungguhnya menjijikkan dan jauh dari pedoman moralitas. Moralitas disini pun berlaku di semua negara, semua budaya. Dengan kata lain, secara universal, suap dan korupsi dikategorikan sebagai penyimpangan moral.
Peneliti dari Jerman Magnus Thor Torfasn dan kawan-kawannya di Universitas Harvard menguatkan temuan dalam riset Anggarwai dan Mazar. Ia juga menemukan fakta bahwa negara dengan budaya memberikan tip (baca: suap) yang tinggi memiliki tingkat korupsi yang tinggi pula. Disebutkan bahwa budaya memberi tip tak lain lahir dari kolektivisme di masyarakat yang bersangkutan.
Temuan logis lain dalam riset Torfasn menyebutkan jika sebuah organisasi yang korup akan dengan mudah mengeksklusi anggotanya yang tak mau mengikuti aturan main. Dalam konspirasi penyelewengan anggaran di DPR RI, misalnya, anggota DPR yang 'bersih' dipastikan akan menghadapi tekanan dan pengasingan yang kuat dari para pelaku.
Dalam upaya yang rapi tapi memiliki semangat yang tinggi ini, Torfasn juga menyebut akan tumbuh “kebutaan etika” di kalangan mayoritas anggota. Etika dikesampingkan, dan lagi-lagi semua bermula dari pemahaman bahwa “apa yang kulakukan tidak sendiri, melainkan bersama-sama yang lain.” Serupa dengan tindakan baik, tindakan jahat akan lebih mudah dilakukan jika bersama-sama.
Kolektivisme juga menjadi salah satu pokok temuan pokok Guelirmo Wated dalam penelitiannya “The Role of Attitudes, Subjective Norms, Attributions, and Individualism-Collectivism in Managers.” Orang dengan kepribadian kolektivistik, tulisnya, lebih mampu memberikan “atribusi eksternal” pada perilaku suap.
Ini artinya individu penganut kolektivisme lebih rentan terseret perilaku korup atas pengaruh dari luar diri mereka. Pengaruh dari luar ini, dalam konteks korupsi dalam sebuah institusi, berasal dari orang-orang satu profesi di sekelilingnya. Implikasinya pelaku bisa menjustifikasi serta mentolerir perilaku tak etis dengan menyalahkan lingkungan eksternal di mana ia bekerja. Misal, politisi yang duduk di sebuah komisi di DPR RI bisa menyalahkan badan legislatif itu sendiri jika namanya terseret sebuah kasus korupsi.
Riset Wated dijadikan salah satu rujukan akademisi Binus University, Juneman Abraham, yang menulis paper berjudul “Corruptive Tendencies, Conscientiousness, and Collectivism” yang ia publikasikan di kanal Researchers Gate. Ia menemukan bahwa kolektivisme (dalam tindakan korup) memang memiliki korelasi dengan rasa bersalah.
Namun, rasa bersalah itu bersifat adaptif: menjadi cenderung normal setelah tindakan korup dilakukan. Dengan kata lain, seiring berjalannya waktu, rasa bersalah akan menjadi rasa yang sepele saja. Salah satu faktor lain yang membuat rasa bersalah menjadi adaptif adalah tindakan-tindakan baik lain yang dilakukan sang koruptor yang seakan membuat tindakan korupnya terbayar tuntas.
Logika ini kerap dipakai untuk menjustifikasi tindakan korupsi oleh pejabat negeri, dan bahkan diamini oleh masyarakat sendiri. Masyarakat, kata Abraham, di satu titik merasa perlu untuk mentolerir perilaku bejat para pejabat kenegaraan karena yang lebih esensial adalah melihat kontribusi apa yang mereka berikan selama berkuasa. Ditambah lagi, dalam masyarakat yang mudah lupa seperti masyarakat Indonesia, perilaku korup di masa lampau tak akan menjadi pengingat serius di masa depan saat si pelaku mencalonkan diri dalam pemilu, misalnya.
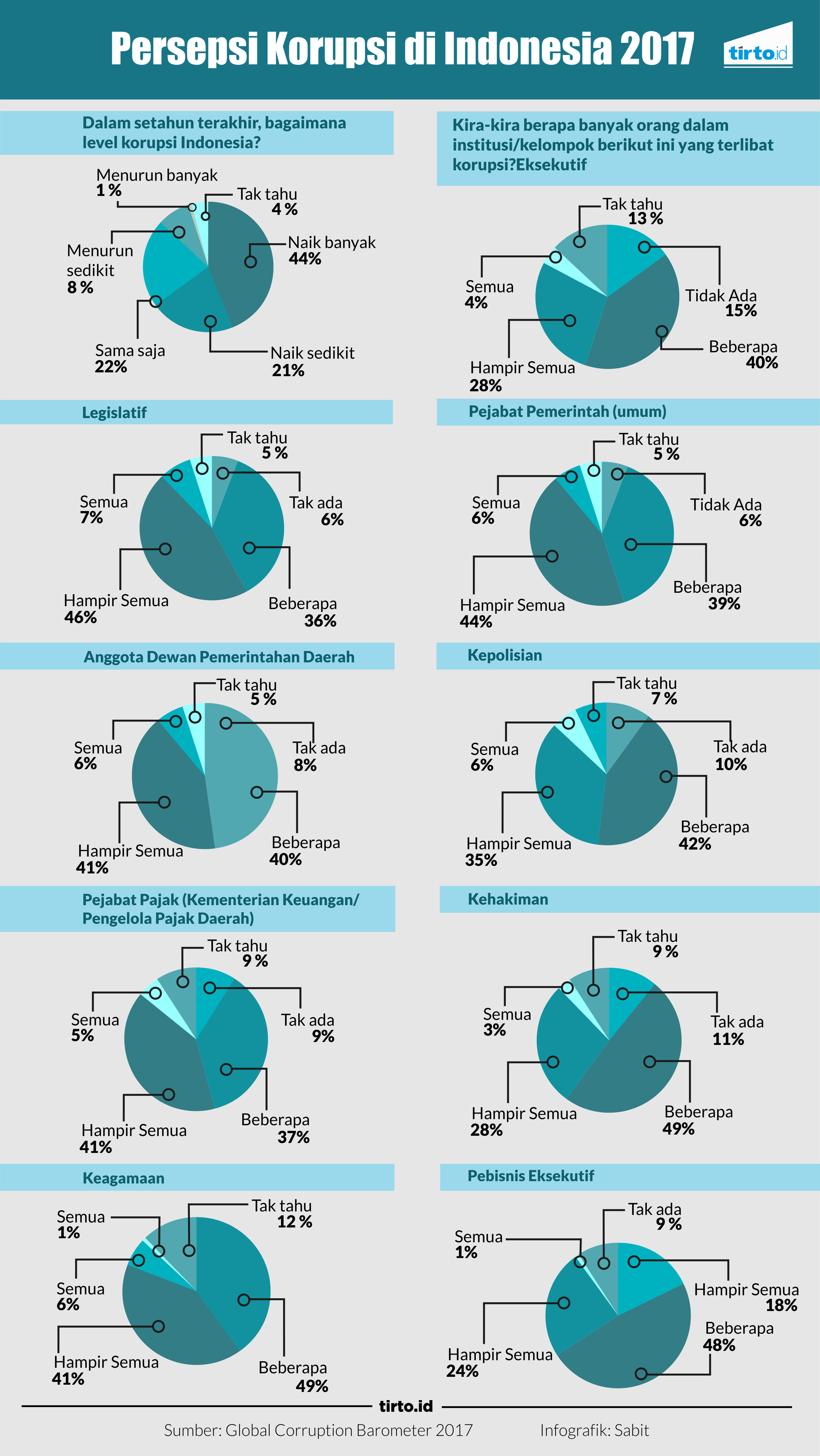
Rakyat Awam Ketularan Korup
Bahaya budaya korupsi yang dilakukan oleh gerombolan elite di tubuh pemerintahan, menurut kandidat doktor University of Waterloo Kanada, Justin Friesen, nanti akan melahirkan sebuah status quo yang sayangnya lambat laun diterima secara wajar oleh orang-orang awam.
Dalam penelitiannya yang berjudul "Why Do People Defend Unjust, Inept and Corrupt Systems", yang diterbitkan oleh Jurnal Psychological Science, status quo dari budaya korup membuat orang-orang menyerah pada idealisme tentang pemerintahan yang bersih.
Pada akhirnya, orang-orang justru makin gampang mempraktikkan budaya korupsi maupun suap dalam kehidupan sehari-hari. Alih-alih memberontak, kata Friesen, orang-orang justru memprioritaskan kelancaran proses administrasi, misal, daripada mencari keributan dengan petugas. Saat dibenturkan dengan kenyataan ekonomi sehari-hari yang keras, orang akan lebih mudah berbuat korup sebab ada hal lain yang lebih penting: bertahan hidup.
Lanjut Friesen, dengan melihat orang di sekeliling kita berbuat curang, terutama mereka yang merupakan teman sekantor atau teman sebaya, kita lebih mungkin mencurangi diri sendiri. Ia tak ragu untuk menyimpulkan bahwa ketidakjujuran sebagai sesuatu yang sangat amat mudah menular. Bahayanya lagi, orang lebih mudah untuk mengabaikan keinginan untuk menjadi baik jika mereka melakukan kecurangan secara sedikit demi sedikit daripada langsung melakukan kecurangan skala besar.
Mengutip pepatah lama dengan sedikit modifikasi, sedikit demi sedikit lama-lama tak akan terasa sebagai sebuah dosa. Kata psikologis Amerika Serikat David G. Myers dalam bukunya “Exploring Social Psychology” (1994):
“Orang baik pun bisa menjadi korup saat ditempa oleh tekanan sosial dengan beban yang terlalu besar...”
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Maulida Sri Handayani












