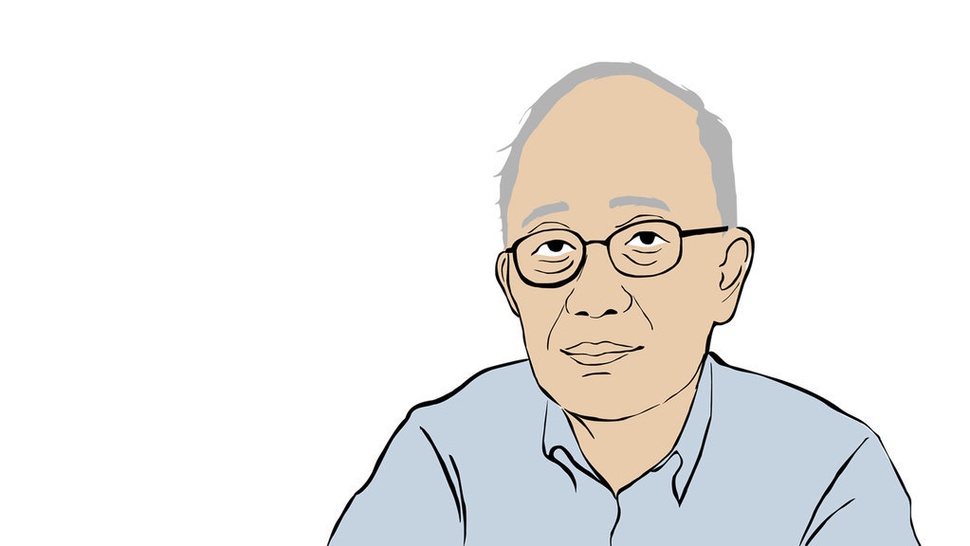tirto.id - Penurunan muka tanah atau land subsidence di Jakarta, pusat politik dan ekonomi Indonesia, sudah lama menjadi perhatian. Sejumlah kajian pun terus dikerjakan untuk mencari solusi terbaik mengingat bakal ada banyak kerugian jika Jakarta benar-benar tenggelam. Salah satunya berupa proyek 'Giant Sea Wall' atau tanggul laut raksasa Teluk Jakarta.
Namun, keputusan ini menuai kontroversi termasuk dipakai sebagai pembenaran buat mengembangkan 17 pulau buatan alias pulau reklamasi, yang sebagiannya untuk hunian super mewah. Benarkah mega proyek satu ini benar-benar efektif? Jika tidak, apa solusi terbaik menangani ibu kota yang sedang sakaratul maut?
Jan Sopaheluwakan, pensiunan peneliti senior Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, memprediksi pada 2050 menjadi tahun deadline bagi Jakarta jika iktikad politik untuk membugarkan kembali kota ini mandek. Berikut wawancara Sopaheluwakan kepada Restu Diantina Putri pada 3 Januari 2018.
Soal penurunan muka tanah di Jakarta, apa yang sebenarnya terjadi?
Masalah penurunan muka tanah sudah menjadi perhatian publik. Hanya masalahnya, ada persepsi yang harus diluruskan. Misalnya, soal penurunan tanah DKI Jakarta mencapai 7 sentimeter per tahun, ada yang bilang 24 sentimeter per tahun. Memang turun, tapi bukan seperti meja yang turun seragam di seluruh Jakarta.
Kekeliruan persepsi ini membuat beberapa pihak memanfaatkan untuk memuluskan kepentingannya menyangkut proyek-proyek infrastruktur dengan alasan dan dramatisasi “Jakarta tenggelam.” Misalnya membuat bendungan maupun tanggul-tanggul. Memang perlu tapi persoalan penurunan tanah sangat kompleks.
Pemicunya karena ekstraksi air tanah, kompaksi secara alamiah, penurunan wilayah, dan beban bangunan. Persentasenya beda-beda di setiap wilayah.
Sekarang yang jadi hot issue, khususnya Jakarta Utara, katanya 40 persen di bawah permukaan laut karena ekstraksi air tanah. Tapi sebenarnya ini masalah control, monitoring, dan penegakan hukum terhadap mereka yang diberikan hak untuk pengambilan air tanah.
Nah, datanya memang bervariasi tapi saya merujuk kajian dari Jepang. Data itu terkait jumlah titik bor yang hanya sepersepuluh dari yang terdata di Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta. Cukup banyak yang tidak terpantau. Saya yakin yang ilegal jauh lebih banyak. Yang terdata pun belum tentu mengambil sesuai kuota mengambil sekian liter per detik; juga kedalaman pengeborannya belum tentu sesuai izin.
Untuk daerah di sekitar Pluit dan sekitarnya memang menurun cepat. Faktor penyebabnya: tanahnya sendiri dalam proses konsolidasi secara alamiah.
Kalau anda tahu, di Pasar Ikan [Penjaringan atau Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara] ada menara miring, Syahbandar. Itulah posisi pantai waktu kapal Belanda mendarat. Sekarang posisi pantai sudah jauh ke depan. Artinya, itu akibat sedimentasi Sungai Ciliwung, juga reklamasi. Nah, daerah Pluit dan sekitarnya sampai Ancol itu daerah reklamasi. Tanahnya masih dalam proses memadat. Ditambah beban kawasan berlipat-lipat.
Tidak heran bila tanah di daerah Pluit turun 3-4 meter di bawah permukaan laut karena memang dulunya laut.
Saya mencoba membuat ekstrapolasi dari data Institut Teknologi Bandung. Terbukti penurunan pertama memang tidak sama; kedua, tidak terus-menerus menurun. Contoh, Blok M dan Senayan pada 2002 cepat sekali penurunannya. Setelahnya diam lama.
Kenapa?
Karena dulu gencar pembangunannya. Ada mal baru, ada ekstraksi air tanah. Memang kalau lihat peta, makin ke selatan makin kecil untuk ekstraksi air tanah. Dalam bahasa ilmiahnya: ada differential subsidence. Penurunan tanah secara berbeda dalam ruang dan waktu.
Sekarang dalam konteks 'Giant Sea Wall' atau NCICD (North Capital Integrated Coastal Development), sekarang Jepang yang melakukan monitoring. zaman Jokowi dan Ahok, pada 2013-2014, saya membantu Dinas Perindustrian dan Energi DKI. Kami sempat melakukan penelitian dengan menggunakan alat namanya extensiometer. Namun kemudian berhenti.
Padahal melakukan pengukuran harus jangka panjang, minimal sepuluh tahun. Sehingga pada saat melakukan intervensi infrastruktur, katakanlah membuat tanggul, badan sungai, dan sebagainya, terpaksa dengan asumsi. Misalnya, penurunan 5 sentimeter per tahun. Karena asumsinya penurunan merata seperti itu tiap tahun maka dibangunlah tanggul sekian meter yang kuat hingga mencapai tahun tertentu sesuai perhitungan.
Karena pakai asumsi ini bahaya. Kenapa? Karena kalau penurunan justru lebih cepat, kan, bahaya. Kalau lebih lambat, ya pemborosan. Tapi tetap harus dilakukan. Di sinilah kelemahan kita: tidak pernah berpikir jauh ke depan. Tidak usah jauh-jauh 20-30 tahun ke depan. Bagaimana kita mau bersaing kalau kita hanya berpikir lima tahunan?
Artinya tanggul raksasa ini hanya solusi jangka pendek?
Ya, untuk saat ini begitu. Ini yang kita sebut tahap darurat. Kan sedang dibangun tanggul di daerah pesisir.
Untuk mengatasi masalah banjir Jakarta ditempuh tiga strategi besar. Untuk banjir yang diakibatkan oleh kenaikan air laut yang kecepatannya hanya beberapa millimeter per tahun, dibuatlah 'Giant Sea Wall'. Kemudian dibuat tanggul sepanjang pesisir, lalu memperkuat sungai karena dianggap sungai menurun.
Tapi yang belum ditangani adalah masalah folder. Karena banjir yang terjadi, kan, di daerah-daerah folder. Di daerah-daerah rendah. Itu harus dibangun tanggul lalu dipompa. Karena ini menurun terus tanahnya.
Jakarta punya 60 tanggul kecil. Ke depan justru yang kita waspadai adalah hujan di tengah kota karena perubahan iklim. Hujan dikit, kan, bisa banjir. Apalagi kalau makin banyak bangunan-bangunan tinggi di Jakarta Utara.
Jadi saya menyarankan: sebelah utara harus lebih banyak ruang biru, untuk air, bukan sumur resapan, artinya dibangun waduk.
Tapi Jakarta juga butuh ruang penduduk?
Nah, maka harus naik ke atas. Harus sejalan peremajaan kota. Dibuat kampung susun di tengah kota. Sehingga makin terbuka ruang. Memang harus rekayasa ruang sehingga ruang untuk air lebih banyak di daerah yang memang rendah seperti Sunter, Kelapa Gading, Cakung, Pluit, dan Penjaringan, sampai Kamal dan Meruya. Ukurannya bisa disesuaikan. Tidak perlu pakai biopori. Ini sekaligus menjadi solusi untuk banjir: ketersediaan air bersih dan menghentikan penurunan tanah, dan mungkin 'Giant Sea Wall' tak akan perlu sebesar itu.
Ada anggapan 'Giant Sea Wall' dibuat untuk mendukung proyek reklamasi dengan melindungi pulau-pulau reklamasi ...
Tidak ada urusan. 'Giant Sea Wall' itu diusulkan oleh Belanda sebagai solusi banjir. Karena anggapannya tanah turun terus, otomatis sungai ikut turun sehingga sungai menjadi lebih rendah dari laut, sehingga jika masih ingin air mengalir secara gravitasi, air laut dipompa ke luar. Itu usulan Belanda.
Menurut saya itu proyek juga. Memang ada revisi dari Bappenas terkait tahapan pembangunan tanggul. OK, ini tahap emergency yang tak bisa dihindari. Setelah itu kita lihat lagi, subsidence sampai mana? Baru kita kaji lagi bagaimana tahap 'Giant Sea Wall' berikutnya. Jadi proyek ini diusulkan Belanda kepada Indonesia tapi nanti yang membangun Korea. Karena mereka punya masalah seperti ini. Tapi kondisinya jelas berbeda di sana dari di sini. Tidak apple to apple. Dan dia untuk lahan pertanian.
Artinya model yang diusulkan Belanda lebih tepat untuk kondisi Jakarta?
Tetap beda. Sungainya beda. Mereka juga tidak bilang kalau setelah seribu tahun penurunan tanah di sana 6 meter, lautnya naik 8 meter. Mereka juga tidak cerita soal folder. Saya tidak bilang kita ditipu. Tapi kurang ada menceritakan best practice. Lagi pula disiplin mereka luar biasa dalam mengelola air. Antara pemerintah dan warga kompak. Di sini saja Bogor dan Jakarta tidak bekerja sama. Belum lagi warganya.
Contohnya yang tidak mau direlokasi?
Ah itu soal komunikasi saja. Tergantung pendekatan ke publik bagaimana. Survei kami ke sejumlah wilayah seperti Penjaringan atau Kapuk yang memiliki industri dan permukiman, mereka mau kok direlokasi. Asalkan terjamin pencaharian mereka. Syukur-syukur tidak memutus mata rantai sosial. Ya kalau relokasi jauh seperti di Marunda ya susah. Ini, kan, manusia.
Kalau dilihat peta penurunan tanah di daerah Priok juga tinggi. Itu karena beban bangunan. Kalau warga sih tidak banyak. Industrilah yang banyak menyedot air tanah. Nah mereka kena akibatnya. Banyak yang tergenang rob.
Anda punya prediksi kapan Jakarta benar-benar tenggelam?
Istilah "tenggelam" itu mengerikan. Istilah ini memang sengaja ditiupkan. Kalau berdasarkan skenario perubahan iklim dan sebagainya, Jakarta Utara akan tenggelam semuanya pada 2050. Hanya saja itu berdasarkan asumsi. Tidak ada data akurat hasil monitoring.
Ada kemungkinan, jika kita berhenti menggunakan air tanah, tanah bisa naik kembali?
Itu yang terjadi di Tokyo dan Seoul. Tapi mereka melakukan bersamaan dengan peremajaan kota. Menurut saya, daerah rendah yang sering tergenang sekalian saja dibanjiri permanen. Digali saja sedalam 15 meter dengan dengan ketinggian air normal 7,5 meter lalu di sekelilingnya dibangun kota. Idealnya begitu.
Saya baca penelitian anda soal Mega City Syndrome. Itu kah yang terjadi di Jakarta?
Ada enam sindrom: tekanan ruang, kerawanan banjir, kelangkaan air minum, infrastruktur yang menua, erosi pantai, dan terakhir adalah kehilangan keanekaragaman hayati. Ini biasa diderita kota-kota delta di dunia. Seperti Jakarta, Rotterdam, Shanghai, kemudian Alexandria (Mesir).
'Giant Sea Wall' tidak efektif?
Banyak prasayarat. Pertama, sungainya perbaiki dulu, dong. Kalau tidak, yang masuk comberan besar. Air polusi itu ngumpul di muara. Pertanyaannya, siapa yang mau membayar pompa? Kan, diklaim sebagai pompa terbesar di dunia. Ketiga, OK-lah bisa dibangun jalan tapi prinsip saya, benahi dulu daratan, baru kita bicara 'Giant Sea Wall'. Kita bugarkan dulu kotanya sebelum reklamasi. Masih banyak lahan sebenarnya. Ini hanya soal penataan.
Bisa dibilang Jakarta sedang sakit?
Ya kalau begini terus. Sakit karena kebodohan bersama.
Ada kemungkinan kita akan menghadapi water war ke depannya?
Oh ya. Indonesia merupakan water hotspot. Ada enam komponen: polusi, membuang racun ke sungai, kelangkaan air bersih, hingga perebutan air bersih. Tidak hanya di Indonesia, ini mulai terjadi di dunia. Seperti negara-negara kecil di Asia yang dilewati sungai lintas negara.
Penulis: Restu Diantina Putri
Editor: Fahri Salam