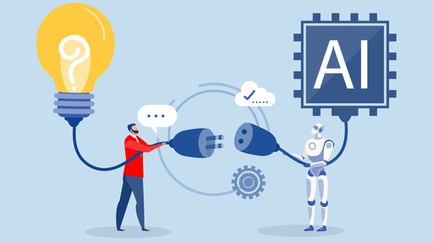tirto.id - Minggu siang, 25 Februari 2018, sekelompok perempuan berjalan ke sebuah tempat di San Jacinto Amilpas, Meksiko, guna mengikuti upacara pernikahan. Mereka mengenakan gaun pengantin berwarna putih lengkap beserta perkakas lainnya dan ditemani rombongan yang terdiri keluarga, kerabat, maupun teman dekat.
Sesampainya di lokasi, para perempuan itu langsung menjalani upacara yang dipimpin Richard Torres, aktor cum aktivis lingkungan asal Peru. Torres membacakan sumpah sehidup semati yang kemudian ditirukan mempelai perempuan. Setelah selesai, mempelai tersebut menghampiri, memeluk, serta mencium pasangannya yang diketahui bukan laki-laki melainkan sebatang pohon.
Gambaran di atas dirangkum dalam video berjudul “RAW: Women Marry and Kiss Trees in Bizarre Ceremony” yang dipublikasikan Russia Today. Nyatanya, tidak kali ini saja upacara semacam itu terjadi. Torres—yang memimpin upacara di Meksiko—total telah melakukan ritual serupa sebanyak 17 kali di seluruh dunia.
Torres sendiri sudah “menikah” dengan pohon sebanyak dua kali. Pernikahan pertama dilakukan Torres pada 2013 di Argentina. Lalu, disusul setelahnya, pada 2014, di Kolombia. Upacara maupun pernikahan tersebut hanya simbolis belaka yang didasarkan pada tradisi Inca dari Peru. Tujuan pernikahan itu, menurut Torres, ialah untuk “meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah lingkungan di seluruh dunia.”
Menghadang Korporasi
Apa yang dilakukan Torres dengan menggunakan pohon sebagai medium perlawanan sudah dilakukan lebih dulu di India. Latar belakangnya juga sama: ancaman kerusakan lingkungan dan pelestarian hutan.
Menurut Vandana Shiva dan J. Bandyopadhyay dalam “The Evolution, Structure, and Impact of the Chipko Movement” (1986) yang diterbitkan Mountain Research and Development, konflik lingkungan—terutama sumber daya hutan—di India disebabkan oleh tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup oleh negara hingga pertumbuhan industri dan perdagangan.
Situasi itu lantas membuat negara tamak mencaplok sumber daya hutan demi memenuhi kepentingannya. Aksi negara sontak memantik respons masyarakat yang ramai-ramai menolak pencaplokan hutan. Mereka merasa negara telah merebut hak-hak masyarakat atas hutan. Masyarakat kemudian membentuk gerakan non-kekerasan yang bertujuan mengkampanyekan pelestarian lingkungan bernama “Chipko.”
Gerakan Chipko (Chipko Movement) bisa dibilang kelanjutan dari aksi “Satyagraha.” Gerakan satyagraha menitikberatkan pada pendekatan non-kekerasan dalam menentang eksploitasi sumber daya alam di India yang dipopulerkan Mahatma Gandhi. Baik satyagraha dan Chipko sama-sama terinspirasi gerakan serupa oleh komunitas Bishnoi di Rajasthan pada 300 tahun silam.
Satyagraha merebak di India pada 1930-1931. Pemicunya adalah hak eksklusif yang dimiliki Inggris dalam mengolah sumber daya hutan menjadi komoditas komersial di wilayah Himalaya, Ghats sebelah barat, serta perbukitan India Tengah.
Shiva dan Bandyopadhyay mencatat pengelolaan hutan oleh pemerintahan kolonial Inggris ditempuh lewat dua cara. Pertama, perubahan kepemilikan lahan dari kepemilikan yang sifatnya komunal menjadi pribadi. Kedua, eksploitasi hutan dengan begitu masif untuk pembangunan kapal hingga jaringan jalur kereta api. Masyarakat India beranggapan kedua langkah tersebut membawa dampak kehancuran bagi lingkungan.
Masyarakat lalu memutuskan untuk melawan, salah satunya dengan memindahkan hasil hutan secara besar-besaran. Akan tetapi, aksi itu ditanggapi dengan kekerasan oleh pemerintah kolonial Inggris. Di India Tengah, penduduk setempat ditembaki aparat. Hal serupa juga terjadi di Desa Tilari dan Tehri Garhwal tatkala masyarakat tak bersenjata tewas diberondong peluru pada Mei 1930.
Perjuangan dan pengorbanan gerakan satyagraha sempat membuahkan hasil. Upaya damai mereka sukses mengembalikan beberapa hak tradisional masyarakat terhadap sumber daya hutan seperti hak kepemilikan hasil hutan. Namun, masalah tidak berhenti begitu saja. Pasca-kemerdekaan India pada 1947, negara menggantikan peran pemerintah kolonial Inggris dalam mengeksploitasi hutan.
Eksploitasi hutan oleh pemerintah India dilakukan atas nama “kepentingan nasional” dan “pertumbuhan ekonomi.” Harga yang mesti dibayar dari aktivitas tersebut ialah hancurnya ekosistem hutan, kekeringan, hingga banjir.
Kondisi itu membuat masyarakat kembali melawan dengan payung “Chipko” yang dalam bahasa India berarti “merangkul pohon.” Gerakan ini mempunyai pendekatan non-kekerasan dan ditujukan untuk melindungi kelestarian hutan, sama seperti satyagraha. Konteks “merangkul pohon” mereka gunakan sebagai simbol perlawanan terhadap segala macam eksploitasi terhadap isi hutan.
Seperti yang dijelaskan Shiva dan Bandyopadhyay dalam “The Evolution, Structure, and Impact of the Chipko Movement,” Chipko muncul pada awal 1970an di wilayah Garhwal, Uttar Pradesh. Pemicunya adalah perusakan hutan di Kawasan Himalaya oleh kontraktor swasta yang mengakibatkan ketidakstabilan ekologis (banjir sampai tanah longsor) di daerah tersebut. Gerakan Chipko lantas menuntut pemerintah menghentikan pelelangan hutan kepada kontraktor agar pohon-pohon tidak ditebangi.
Upaya gerakan Chipko berhasil. Pemerintah bersedia menganulir aturan pelelangan hutan kepada kontraktor. Keberhasilan itu membawa dua dampak: menyebarnya semangat perlawanan di berbagai daerah seperti Karnataka, Rajasthan, Bihar, sampai Vindhyas, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
Pada 22 Oktober 1971, Chipko kembali melakukan perlawanan di Gopeshwar. Mereka menolak pemerintah dan Simon Company—produsen barang olahraga—menghentikan penebangan pohon. Selama dua tahun, sampai 1973, masyarakat yang tergabung dalam Chipko konsisten menyuarakan tuntutannya. Walhasil, Departemen Kehutanan India mencabut izin operasional Simon Company akibat desakan yang kuat dari masyarakat.
Menurut “The Evolution, Structure, and Impact of the Chipko Movement,” terdapat kebingungan ihwal siapa pendiri gerakan Chipko. Namun, Shiva dan Bandyopadhyay buru-buru memberi jawaban. Mereka berpendapat, Chipko merupakan gerakan yang tidak bertumpu pada satu orang saja melainkan dibentuk melalui kolektifitas.
Seiring waktu, Chipko terus bergerak. Pada Oktober 2017, gerakan Chipko muncul di Mumbai untuk melindungi 3 ribu pohon di wilayah Aarey agar tidak ditebang sehubungan dengan pembangunan jalur kereta Mumbai Metro.
“Ini bukan pembangunan, tapi penghancuran yang dilakukan Mumbai Metro Rail Corporation Ltd. (MMRCL) tanpa mendapat izin dari instansi terkait. Pengadilan Hijau Nasional (NGT) telah jelas mengatakan bahwa UU Metro tidak dapat berada di atas UU Perlindungan Lingkungan. Namun, mereka berani melanggar,” ujar Stalin Dayanand, perwakilan aksi.
Sementara awal Februari lalu, warga Desa Dang Uttarkashi juga melakukan aksi Chipko untuk menolak penebangan pohon dalam rangka pembangunan jalan baru Dang-Pokhri.
Masalah penebangan hutan secara liar di India sudah seperti penyakit kronis. Berdasarkan studi International Union of Forest Research Organisations, India menempati tiga besar dunia importir pohon hasil illegal logging dengan nilai impor sebesar Rs 40 miliar—atau setara 10 persen dari nilai total perdagangan kayu ilegal secara global.

Peran Penting Perempuan
Dalam “The Evolution, Structure, and Impact of the Chipko Movement” dijelaskan perempuan punya porsi besar di gerakan Chipko. Hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan mereka dalam aksi-aksi Chipko. Pada Maret 1974, 27 perempuan di bawah komando Goura Devi turun ke jalan menolak penebangan hutan di Uttar Pradesh. Aksi mereka berhasil menghentikan pembalakan.
Desember 1977, kelompok berjumlah besar di bawah pimpinan Bachhni Devi melakukan hal yang sama menolak penebangan pohon di hutan Adwani. Tiga bulan berselang, kelompok perempuan kembali turut serta dalam aksi massa terbesar di Narendranagar menolak lelang hutan. Sebagian dari mereka ditangkap aparat.
Shobita Jain, profesor sosiologi dan mantan peneliti di Universitas Jawaharlal Nehru dalam “Standing Up for Trees: Women’s Role in the Chipko Movement” menyatakan bahwa di balik keikutsertaan perempuan dalam pelestarian hutan, terdapat tuntutan kesetaraan.
Gerakan Chipko, bagaimanapun, merupakan gerakan yang didasarkan pada distribusi pemanfaatan sumber daya, bersifat ekologis, dan lebih penting lagi perempuan punya andil besar dalam memperkuat keberlangsungan gerakan kendati diragukan laki-laki.
Vandana Shiva dalam Staying Alive: Women, Ecology, and Survival in India (1988) mengatakan perempuan memegang peran krusial dalam keberlangsungan gerakan Chipko. Alasannya, segala dampak buruk yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan ekologis begitu memengaruhi perempuan sebab mereka melakukan 98% kegiatan yang berhubungan dengan hutan seperti bertani, berkebun, sampai berternak.
Tak hanya itu, masih mengutip Staying Alive: Women, Ecology, and Survival in India, alasan lain yang menegaskan mengapa peran perempuan dalam gerakan Chipko penting adalah karena di saat mereka berjuang melestarikan hutan dan melindungi lingkungan, mereka juga menghadapi suami mereka sendiri yang bekerja untuk perusahaan penebangan kayu.
Gerakan Chipko, tulis Shiva, memperlihatkan pembebasan perempuan bukan sekadar pembebasan dari penindasan masyarakat patriarkal melainkan juga pembebasan dari penjajahan ekonomi maupun eksploitasi alam dengan modal.
Salah satu pria pernah berkata, “Anda perempuan bodoh. Bagaimana Anda bisa mencegah penebangan pohon oleh mereka yang mengetahui nilai hutan? Tahukah Anda apa yang dihasilkan hutan? Mereka menghasilkan keuntungan dari kayu!”
Namun, para perempuan tak ambil pusing. Mereka terus bernyanyi.
“Apa yang hutan tahan hasilkan? Tanah, air, dan udara. Tanah, air, dan udara yang menopang bumi serta semua isinya.”
Penulis: Faisal Irfani
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id