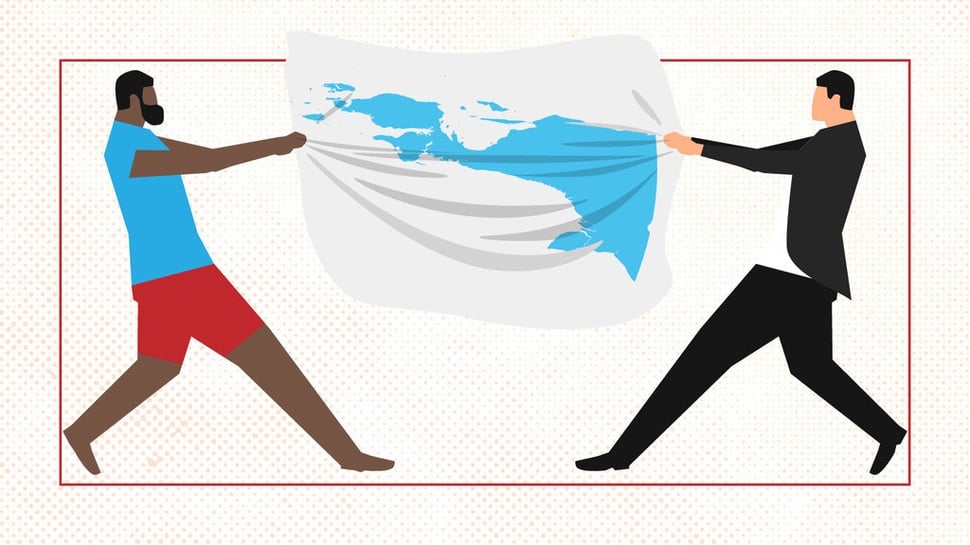tirto.id - Amnesty International Indonesia menerbitkan laporan tahunan 2020/2021 seputar hak asasi manusia (HAM) di Indonesia termasuk Papua. Dalam laporan tersebut Amnesty menyatakan situasi HAM memburuk sepanjang 2020.
Salah satu yang mereka soroti adalah pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi. Sepanjang tahun lalu tercatat 157 orang dikriminalisasi dengan pasal karet UU ITE atau KUHP. 56 di antaranya menimpa jurnalis yang melakukan peliputan aksi protes UU Cipta Kerja pada 7 dan 21 Oktober 2020.
Jumlah kasus tersebut adalah yang terbanyak dalam enam tahun terakhir.
“Penerapan UU ITE yang tidak sesuai juga menjadi salah sau ancaman terbesar kebebasan berekspresi,” ujar peneliti dari Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya dalam konferensi pers virtual, Selasa (7/4/2020).
Pengekangan juga dialami para pembela HAM lewat berbagai cara, mulai dari peretasan digital hingga yang terkait fisik seperti perampasan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran secara represif, kriminalisasi, dan kekerasan.
Pada 2020, terdapat 89 kasus serangan terhadap pembela HAM dengan 248 korban. Tertinggi terjadi pada jurnalis dengan 32 kasus dan 60 korban.
Intimidasi di ranah digital juga terjadi pada mahasiswa, akademisi, dan aktivis yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pelanggaran HAM di Papua. Amnesty mencatat 66 kasus dengan 86 korban.
Amnesty mengingatkan bahwa hak seluruh masyarakat atas kebebasan berekspresi dan berpendapat telah dijamin oleh Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Komentar Umum No. 34 atas Pasal 19 ICCPR. Sedangkan dalam hukum nasional, hak tersebut telah dijamin dalam Konstitusi, tepatnya pada Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, serta Pasal 23 ayat (2) UU No. 39/1999 tentang HAM.
Laporan tahunan Amnesty juga menyoroti kealpaan pemerintah Indonesia dalam penegakan dan perlindungan HAM di Papua (termasuk Provinsi Papua Barat). Di sana Amnesty mencatat 19 kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan dan menimbulkan 30 korban jiwa.
Data yang dikumpulkan Amnesty sejak 2018 sampai Maret 2021 menunjukkan bahwa kondisi Papua belum juga membaik. Terdapat 50 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan dengan total 84 korban.
Dari 50 kasus tersebut, belum ada satu pun yang divonis oleh pengadilan umum maupun militer. Bahkan baru empat kasus yang diproses hukum: tiga yang diduga melibatkan anggota TNI ada di tahap penyidikan oditur militer dan satu kasus baru dilimpahkan ke kejaksaan negeri.
“Dari semua kasus di tahun 2020, belum ada satu pun kasus yang divonis oleh pengadilan militer maupun pengadilan sipil,” ujar Ari.
Melumpuhkan Papua
Lemahnya komitmen pemerintah dalam penegakan dan perlindungan HAM di Papua berdampak pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) Latifah Anum Siregar menyitir data IDI versi the Economist Intelligence Unit (EIU) yang menyebut Indonesia berada pada peringkat ke-64 dengan skor 6,3. Posisi Indonesia stagnan dibanding tahun lalu, namun skor yang didapat lebih rendah dari tahun lalu sebesar 6,48.
“Skor ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat,” ujarnya dalam konferensi pers yang sama, Selasa.
IDI di Papua dan Papua Barat tahun 2019 versi Badan Pusat Statistik (BPS) tidak kalah buruk. Dari tiga variable: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi; Papua Barat mencatat poin 57,62 dan menurun dari tahun sebelumnya, 58,29 poin. Sementara Papua tercatat dengan 62,25 poin.
Dalam ukuran BPS, poin di bawah 60 menunjukkan kualitas demokrasi buruk, poin 60-80 menunjukkan demokrasi sedang, dan di atas 80 berarti demokrasi baik.
Menurut Anum, pemerintah menggunakan beberapa cara untuk meniadakan kebebasan berekspresi di Papua. Misalnya membubarkan aksi massa dengan dalil tak berizin seperti yang diatur dalam UU 9/1998, lalu situasi pandemi yang tidak memperbolehkan pengumpulan massa, hingga Maklumat Kapolda Nomor I/XI/2020.
“Maklumat itu, tidak bisa dibohongi, untuk mencegah Majelis Rakyat Papua (MRP) saat RDP (rapat dengar pendapat). Ada 54 tim dan beberapa anggota MRP di Merauke pada 17 November ditangkap,” ujar Anum.
Pembatasan hak berekspresi di ruang publik menyebabkan orang asli Papua berpindah ke media sosial. “Semisal 1 Desember, tidak ada bendera berkibar di tempat-tempat secara fisik tapi di medsos banyak sekali,” ujarnya. Sayangnya, menurut Anum, di ruang virtual itu juga mereka menemukan pembatasan, salah satunya dengan UU ITE.
“Pemerintah ini takut, sehingga medsos diperkatat untuk orang Papua,” tambahnya.
Menurut pengacara Papua Gustaf Kawer, situasi HAM di Papua pada 2020 memburuk seiring meningkatnya aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Ia menyitir data milik PAHAM Papua dan Kontras Papua yang menyebut sepanjang Januari-Desember 2020 terdapat 63 kasus kekerasan yang melibatkan TNI dan Polri dengan 371 warga sipil menjadi korban penembakan, pembunuhan, intimidasi, penculikan, pembubaran demonstrasi tanpa prosedur, hingga penggeledahaan.
“Kalau di Papua, orang demo dihambat dan menggunakan media sosial juga dihambat. Orang Papua dilarang bicara,” ujar Gustaf dalam kesempatan yang sama.
Aksi kekerasan dipicu karena pemerintah belum bisa menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua dan sejarah masa lalu Papua. Pemerintah memilih cara militeristik sebagai solusi dan hal tersebut hanya memperpanjang konflik.
“Kami merekomendasikan dibentuknya pengadilan HAM, komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Papua yang independen bagi penuntasan kasus pelanggaran HAM, serta perwakilan Komnas HAM Papua perlu direformasi agar mempunyai kewenangan pro justicia,” tandas Gustaf.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Rio Apinino