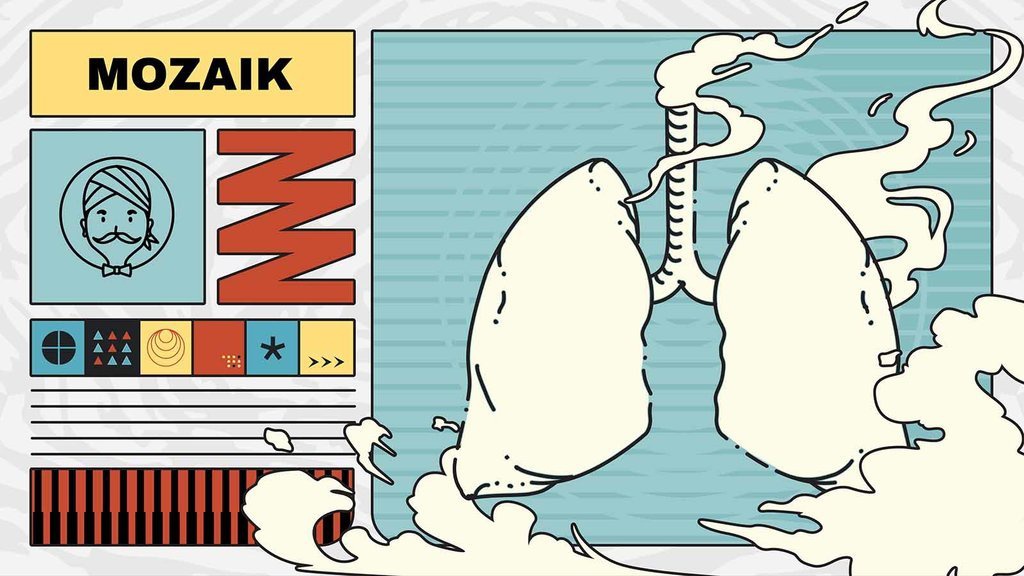tirto.id - Saat diresmikan pada 1844, orang-orang tidak ada yang mengira bahwa teknologi jaringan telegram akan bertransformasi menjadi alat untuk memprediksi cuaca. Demikian tulis Andrew Blum dalam The Weather Machine: A Journey Inside the Forecast (2018).
Empat tahun sejak diresmikan, jaringan ini telah merentang sepanjang 3.400 kilometer ke pelbagai tempat di Amerika Serikat. Kebiasaan operator mengirim "ping" kepada rekan kerja di kota lain membuat mereka tersadar bahwa telegram tidak bekerja dengan baik saat hujan.
"Ketika saya tidak menerima balasan 'ping' dari Cincinnati, saya cukup yakin badai timur laut sedang mendekat [dari daerah itu ke tempat saya berada]," ujar seorang operator bernama David Brooks.
Di tangan operator lain asal Michigan bernama Jeptha Homer Wade, informasi ini lantas dikumpulkan dalam papan pengumuman untuk menjadi "mesin prediksi cuaca dengan akurasi yang kuat hingga menimbulkan decak kagum tersendiri," klaim Wade.
Bertransformasinya telegram menjadi alat untuk memprediksi cuaca terjadi karena teknologi ini berhasil mengerucutkan dunia hingga membuat "potongan langit yang berbeda [di pelbagai wilayah] bisa disatukan seperti teka-teki [...] dapat digunakan untuk melihat pola cuaca,” tulis Blum.
Ramalan cuaca, lanjut Blum, bukan hanya soal terik matahari dan hujan, tetapi rasionalitas dari informasi yang diperoleh di banyak titik.
"Kemampuan untuk mengetahui kondisi cuaca di banyak tempat di waktu yang sama, merupakan langkah pertama untuk mengetahui kondisi cuaca di satu tempat di waktu berbeda,” imbuhnya.
Di tahun yang sama saat Wade mengumpulkan catatan cuaca, Smithsonian meluncurkan program observasi meteorologi. Karena program ini didasari teknologi mengirim pesan bukan teknologi khusus untuk mengamati cuaca, maka relawan dari pelbagai titik di Amerika Serikat jadi andalan dalam mengamati cuaca yang mengirim hasil pengamatannya lewat telegram.
Dikumpulkan di kantor pusat Smithsonian di sebuah mall yang berlokasi di Washington, peta visualiasi cuaca pertama di dunia tercipta.
"Tidak hanya menarik bagi pengunjung untuk mengetahui cuaca yang dialami teman-teman mereka di lokasi berbeda, juga penting untuk menentukan kemungkinan perubahan cuaca yang akan terjadi,” klaim Smithsonian.
Pada 1859, dengan cara serupa serta didasari karamnya kapal berbendera Inggris akibat badai di laut Wales, seorang kapten yang sempat menahkodai bernama Robert Fitzroy mengumpulkan setiap informasi pengamatan meteorologi untuk dapat berspekulasi secara presisi tentang cuaca, khususnya badai, bernama synoptic chart.
"Synoptic chart tak ubahnya mata yang mengangkasa, bird eye, yang melihat ke bawah ke seluruh penjuru Atlantik Utara untuk menuntun awak kapal bersiap-siaga terhadap segala perubahan cuaca,” terang Fitzroy.
Dari tangan Fitzroy inilah Inggris kemudian membentuk Badan Meteorologi yang memanfaatkan 15 telegram untuk memperoleh informasi cuaca dari para petugasnya di pelbagai tempat. Saban pagi pukul 08.00, kumpulan informasi tersebut disiarkan dari London ke tengah-tengah masyarakat dalam tajuk "prakiraan cuaca".
Pada 1873, karena kian banyaknya negara yang mengikuti jejak Amerika Serikat dan Inggris, International Meteorological Organization (IMO) dibentuk lewat konferensi yang digelar di Vienna, Austria. Dihadiri 32 negara, konferensi ini menyepakati pembentukan pusat pengamatan cuaca di seluruh titik di dunia dalam medium segi empat per 10 derajat garis bujur (longitude) dan garis lintang (latitude).
Selain tetap memakai mesin telegram yang wajib tersedia di tiap-tiap pusat pengamatan, konferensi juga menyepakati penggunaan alat baru dalam mengamati cuaca dan metode baru dalam menentukan prakiraan cuaca.
Soal metode ini, tulis Andrew Blum dalam The Weather Machine: A Journey Inside the Forecast (2018), prakiraan cuaca secara klasik hanya ditentukan oleh catatan masa lampau dan dihubungkan catatan yang diperoleh saat ini.
Saat melihat langit dan menganggap awan kumulonimbus yang dilihat berukuran satu kilometer persegi, misalnya, para petugas akan membolak-balik catatan masa lampau tentang pengamatan yang pernah dilakukan. Ketika di catatan lampau ditemukan kata-kata soal awan kumulonimbus satu kilometer persegi, petugas beranjak dari situ. Mereka menganggap apa yang terjadi di atmosfer saat itu, terjadi juga sekarang.
Metode ini tentu sangat subjektif karena didasari oleh pengalaman pribadi petugas. Padahal, menurut James Vincent dalam Beyond Measure: The Hidden Story of Measurement (2022), subjektifitas dalam melakukan pengamatan merupakan pangkal kekeliruan.
Pengamatan wajib dilakukan secara objektif dengan mengubah subjektivitas menjadi angka-angka yang terukur, atau menukil perkataan fisikawan William Thomson, "Ketika Anda dapat mengukur apa yang Anda bicarakan dan mengungkapkannya dalam angka, Anda tahu sesuatu tentangnya.”
subjektivitas dalam menentukan prakiraan cuaca berakhir pada dekade kedua abad ke-20 melalui keberhasilan Vilhelm Bjerknes dan Lewis Fry Richardson mengawinkan cuaca dengan matematika, misalnya sepetti terdapat dalam buku berjudul Weather Prediction by Arithmetic Finite Difference.
Berpijak pada pemikiran mereka berdua, pada 1910 persatuan badan meteorologi Eropa menerbangkan 150 balon dan 35 layangan di langit Eropa sebagai "alat baru" untuk memperoleh data tentang cuaca dari langit. Lalu disusul dengan pencarian data di darat dan laut untuk membentuk "mirror world".
Secara fundamental, prakiraan cuaca akhirnya hanya bisa ditentukan melalui hitung-hitungan matematis memanfaatkan lima variabel, yakni densitas, tekanan udara, temperatur, kelembapan, dan kecepatan angin, yang diperoleh dari alat-alat baru nan modern penjaring data.
Seiring waktu, pelbagai badan meteorologi di dunia akhirnya menjaring data lain, seperti tentang kondisi ruang udara di sekitar manusia: polusi.
Inversi Cuaca Mengancam Paru-paru
"Bagi orang yang meninggal 97 tahun lalu, aneh rasanya melihat nama Carl Flugge bersinar saat ini," tulis Michael J. Stephen dalam Breath Taking: The Power, Fragility, and Future of Our Extraordinary Lungs (2021).
Kemunculan SARS-CoV-2 (Covid-19) pada awal 2020 membuat nama Carl Flugge mrnjadi populer.
Lahir di Jerman pada 1897, dokter cum ilmuwan ini terobsesi dengan kebersihan, membuatnya mencoba mengungkap musabab epidemi tuberkolosis yang terjadi di New York pada awal abad ke-20 yang menewaskan 10.000 orang per tahun.
Lewat rekomendasi koleganya bernama Hermann Biggs yang meminta semua kasus tuberkulosis dilaporkan secara presisi, Flugge kemudian paham bahwa bakteri TBC, yakni Mycobacterium tuberculosis, kesulitan hinggap di inang baru selama manusia menjaga jarak antara sesamanya sejauh enam kaki atau dua meter—jarak ini lantas diimplementasikan WHO dalam menghadapi Covid-19.
Sebagai dokter dan ilmuwan yang mengkhususkan diri mempelajari paru-paru, Flugge percaya bahwa paru-paru sangat berbeda dan unik dibandingkan organ-organ vital lain yang dimiliki manusia.
Jika jantung, misalnya, hanya bekerja dengan sesama organ dalam tubuh lain, paru-paru bekerja atas korespondensinya dengan dunia luar, atmosfer atau ruang udara di sekitar manusia.
Bekerja sebagai mekanisme untuk menukar gas internal dengan atmosfer, paru-paru lantas diberdayakan melalui mekanisme kimiawi dan imunologi.
Seperti ditulis Michael J. Stephen, dengan 20.000 embusan napas yang kita ambil dalam sehari, udara bergerak melalui saluran berbelit-belit ke salah satu dari sekitar 500 juta alveoli (kantung udara kecil yang berkelompok) yang dimiliki paru-paru kita.
Oksigen bergerak dari paru-paru ke aliran darah, dan karbon dioksida mengalir kembali ke paru-paru sebagai mekanisme kimiawi itu. Karena berhubungan dengan dunia luar, maka sistem pernapasan manusia rutin diserang patogen, yang umumnya berhasil diatasi berkat sistem imunologi.
Namun, kian rusaknya udara yang dihirup, kerja paru-paru pun terancam.
"Dalam beragam bahasa dan agama di dunia embusan napas diasosiasikan sebagai tanda kehidupan, rusaknya udara yang dihirup paru-paru dapat dianggap tanda hancurnya kehidupan,” tulis Stephen.
Kiwari, pelbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan menjadi penyebab kematian nomor dua di dunia.
Dalam "Fifteen Thousand Quarts of Air" (The New Yorker, edisi 7 Maret 1964) yang ditulis Edith Iglauer disebutkan, rusaknya ruang udara di sekitar manusia terjadi karena polusi, khususnya ketidakberhasilan mesin dalam kendaraan bermotor atau pabrik-pabrik melakukan mekanisme pembakaran dengan sempurna hingga, misalnya, melepaskan begitu saja gas sulfur dioksida ke ruang udara manusia.
Ketidakbecusan mesin ini kian menjadi-jadi setelah Revolusi Industri, akhirnya menyebarkan pelbagai zat kimia ke atmosfer. Weather inversion atau inversi cuaca kemudian terbentuk dengan kabut sebagai indikator utamanya. Kabut polusi ini bak selimut yang menyebabkan terjebaknya semua zat kotor di ruang udara manusia ketika suatu kota didera udara dingin dan lembap.
Jika angin bertiup dalam kecepatan rendah, polusi tak hanya terbang di sekitar manusia, tetapi hinggap dan terperangkap di permukaan Bumi.
Mengutip hasil wawancara dengan Morris Jacobs, peneliti pada Columbia School of Public Health yang mendedikasikan diri menelaah inversi cuaca, Edith Iglauer menegaskan bahwa weather inversion sangat berbahaya. Bukan hanya membuat jarak pandang mengerucut, tapi paru-paru yang bekerja dengan berkorespondensi dengan dunia luar menjadi terganggu dan terancam.

Karena meredam atau menghentikan proses pencemaran udara sulit dilakukan—mesin dan kendaraan menjadi pondasi hidup manusia modern--ilmuwan, khususnya yang berasosiasi dengan badan meteorologi, lantas mencari cara untuk mengukur polusi dan menerbitkan semacam prakiraan cuaca khusus untuk polusi sebagai pedoman peringatan bagi masyarakat.
Dalam "Reporting Air Pollution" (Weatherwise, Vol. 31 2010) yang ditulis Janice Crossland, usaha ini dilakukan pertama-tama, pada dekade 1950-an, dengan mengukur masa kabut yang diakibatkan inversi cuaca, lalu dicacah partikel apa saja yang termuat dalam kabut tersebut.
Memanfaatkan alat khusus baru bernama virtual impactor, kabut diembuskan ke dalam alat tersebut untuk disaring berdasarkan ukurannya, yakni antara 0,1 hingga 1 mikrometer dan 1 hingga 100 mikrometer.
Partikel dalam kabut yang telah dibeda-bedakan itu kemudian dianalisis. Hasilnya, di tiap-tiap kabut inversi cuaca, ditemukan paling tidak lima zat berbahaya, yakni karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, oksidan fotokimia, dan partikulat tersuspensi dengan kuantitas yang berbeda-beda dalam ukuran mikrogram per meter kubik kabut.
Lewat pembentukan gugus tugas Air Quality Indicator pada 1975 sebagai organisasi yang berada di bawah naungan Badan Meteorologi Amerika Serikat yang kemudian diikuti negara-negara lain, kuantitas berbeda-beda di antara zat berbahaya tersebut dijadikan patokan dalam memublikasikan prakiraan cuaca khusus tentang polusi udara atau Pollutant Standars Index yang berbentuk.
Laporan kualitas udara yang mereka publikasikan biasanya berupa keterangan singkat agar mudah dimengerti masyarakat, seperti "baik", "bersih", "dapat diterima", "rata-rata", "cukup", "berbahaya", "buruk", dan "sangat berbahaya".
Atau, keterangan juga bisa berupa "tahap 1", "tahap 2", dan "tahap 3", hingga angka-angka koefisien yang merentang dari 0 hingga 500. Di awal kemunculan indeks polusi udara ini, tak kurang dari 44 deskripsi berbeda digunakan dalam mengabari masyarakat tentang kondisi udara di sekitar mereka.
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id