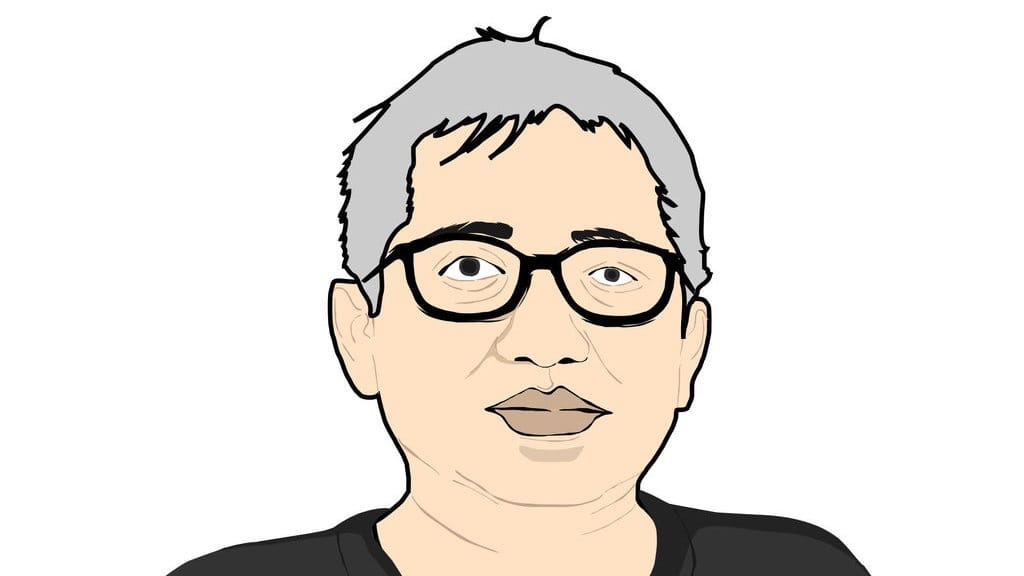tirto.id - Saat ini hanya ada antara satu sampai enam tahanan politik (tapol) Papua di balik jeruji besi, turun dari angka 37 orang pada akhir Agustus 2016. Angka ini kami dapatkan dari sejumlah sumber Human Rights Watch, yang biasa mengunjungi atau mengurus keperluan hukum tapol.
Namun, jumlah tapol Papua yang sesungguhnya belum bisa dipastikan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tak menjawab permintaan data resmi tapol yang dimohonkan oleh Human Rights Watch, organisasi pemantau hak asasi manusia berbasis di New York, tempat saya bekerja sebagai peneliti untuk Indonesia.
Keengganan Kemenkumham untuk memastikan jumlah tapol yang berkurang itu menyiratkan gambaran menarik: tak hanya bahwa puluhan orang Papua yang didakwa dan dihukum penjara ini memang menghadapi ketidakadilan lantaran semata menyuarakan aspirasi politik secara damai, tetapi juga menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo memenuhi janji membebaskan tahanan politik Papua “… dalam rangka bingkai rekonsiliasi untuk terwujudnya Papua damai.”
Pada Mei 2015, Jokowi mengambil langkah yang belum pernah ada sejarahnya: seorang kepala negara Indonesia datang ke penjara Abepura di Jayapura dan secara pribadi menyerahkan dokumen pengampunan atau grasi bagi lima narapidana Papua. Dalam upacara sederhana di penjara, Jokowi mengatakan pembebasan para tahanan politik tersebut “hanya awal” dari upaya pemerintah untuk mengosongkan penjara di Papua dari para tapol.
Enam bulan kemudian, Kemenhukam membebaskan Filep Karma, tahanan politik Papua yang menjadi simbol internasional atas pelanggaran negara Indonesia terhadap kebebasan bereskpresi dan berserikat orang Papua.
Menurut Karma, pembebasan tapol Papua oleh Kemenhukam lewat mekanisme grasi dan remisi—bukan amnesti atau abolisi yang menuntut pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
“Saya maunya abolisi, karena saya tidak bersalah, saya menyampaikan aspirasi secara damai,” katanya. Ia bahkan dipaksa keluar dari penjara Abepura.
Pemerintah Indonesia menghadapi masalah keamanan yang masuk akal di Papua: dari serangan para gerilyawan Organisasi Papua Merdeka hingga demonstrasi yang disertai kekerasan. Namun, tanggapan aparat keamanan sering ngawur terhadap ketidakpuasan orang Papua, termasuk pembatasan akses ke Papua dan Papua Barat selama puluhan tahun terhadap media internasional, akademisi, dan pengamat Perserikatan Bangsa-bangsa, serta kegagalan aparat keamanan untuk membedakan antara tindak kekerasan dan penyampaian aspirasi politik secara damai.
Sayangnya, langkah-langkah yang diambil Jokowi untuk membebaskan tahanan politik Papua bakal berumur pendek, kecuali pemerintah menghapuskan pelbagai aturan soal “makar” yang terbukti bisa dipakai bagi orang macam Filep Karma.
Orang seperti Karma menyuarakan aspirasi politik “Papua Merdeka” secara damai tetapi dipenjara puluhan tahun lewat pasal 106 dan 110 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aparat keamanan Indonesia melakukan banyak penangkapan dan pengadilan terhadap para aktivis yang mengibarkan simbol-simbol “separatisme” seperti bendera Bintang Fajar (Papua) dan bendera Republik Maluku Selatan.
Para aktivis tersebut melakukan demonstrasi politik secara damai, tanpa kekerasan sama sekali. Ia terjadi terus-menerus meski pada era Presiden Jokowi, aksi para aktivis tersebut—termasuk dari Komite Nasional Papua Barat, Aliansi Mahasiswa Papua, dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua—dibubarkan dan kerap kali disertai pemukulan dan ditahan hingga malam hari. (Human Rights Watch tidak mengambil sikap apa pun soal hak menentukan nasib sendiri atau self-determination, tetapi menolak hukuman penjara bagi orang yang secara damai menyatakan dukungan bagi penentuan nasib sendiri.)
Banyak orang Papua mengeluh pertanggungjawaban minim selama berpuluh tahun sejak 1960-an terhadap pelbagai pelanggaran oleh aparat keamanan Indonesia. Reaksi keras dari aparat keamanan terhadap aksi damai “Papua Merdeka” ini mengakibatkan segudang pelanggaran hak asasi manusia.
Lebih dari sepuluh tahun terakhir, Human Rights Watch mendokumentasikan puluhan kasus aparat keamanan—dari kepolisian, militer, intelijen, hingga sipir penjara—menggunakan kekuatan berlebihan saat menghadapi orang-orang Papua yang memperjuangkan hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai.
Pada April 2016, pemerintahan Jokowi mengumumkan pembentukan sebuah “tim terpadu” untuk penanganan dugaan lebih dari selusin pelanggaran hak asasi manusia paling serius di Papua. Namun, pemerintahan Jokowi tak memberi kekuasaan dan pendanaan memadai agar tim tersebut bisa bekerja secara layak.
Dan pemerintahan Jokowi gagal total untuk menghadirkan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang lebih baru di Papua.
Contohnya, tanggapan resmi atas pembunuhan yang dilakukan aparat keamanan terhadap beberapa pemuda di Enarotali, Kabupaten Paniai, pada 8 Desember 2014. Meski telah dilakukan tiga penyelidikan resmi yang terpisah atas penembakan itu, ditambah janji Presiden Jokowi pada Desember 2014—untuk secara menyeluruh menyelidiki dan menghukum aparat keamanan yang terlibat dalam kematian tersebut—sejauh ini tak ada pertanggungjawaban sama sekali. Dan saat kasus Enarotali belum ada jawaban, pada 1 Agustus 2017, polisi kembali menembak mati pemuda Yulius Pigai dari Kabupaten Deiyai, Papua Barat.
Saya khawatir, kita mungkin tak akan pernah mengetahui duduk perkara dan siapa yang bertanggungjawab terhadap kematian Pigai—sama dengan puluhan kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
Tutup Mata atas Penderitaan Tapol Maluku
Pemerintahan Jokowi juga menutup mata terhadap penderitaan para tahanan politik dari Kepulauan Maluku.
Sebanyak 13 tapol Maluku tetap berada di penjara Nusakambangan dan Porong di Pulau Jawa. Mereka adalah sekumpulan tapol terakhir Maluku dari total 28 tahanan yang dinyatakan bersalah dalam kasus makar karena melakukan demonstrasi dan menari cakalele pada Juni 2007 saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Jarak penjara dan rumah mereka di Ambon sekitar 3.000 kilometer. Biaya perjalanan antara Ambon dan penjara-penjara tersebut sungguh memberatkan keluarga-keluarga mereka. Kebanyakan 13 tapol tersebut adalah petani dan nelayan, dan belum pernah bertemu sama sekali dengan anggota keluarga mereka—orangtua, saudara, istri dan anak—sejak pemerintah Indonesia memindahkan mereka dari Ambon ke Jawa pada 2009. Isolasi tersebut menimbulkan tekanan finansial, psikologis, dan emosional bagi para tahanan dan keluarga mereka.
Pada April 2016, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly secara lisan menyatakan komitmen saat bertemu delegasi Human Rights Watch untuk mengatur agar para tahanan Maluku dipindahkan ke penjara Ambon. Namun, lebih dari setahun kemudian, mereka tetap di balik jeruji besi, jauh dari keluarga mereka, tanpa harapan bisa melihat pertumbuhan anak-anak mereka, hingga masa tahanan mereka berakhir pada 2027.
Saya kira segenap upaya pemerintahan Jokowi untuk membebaskan tahanan politik adalah langkah baik yang telah lama tertunda. Tetapi Indonesia tak bisa menyebut diri sebagai negara demokratis, negara berkemajuan, selama masih memenjarakan warga negara hanya karena menggunakan hak berekspresi dan berserikat.
Editor: Fahri Salam
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id