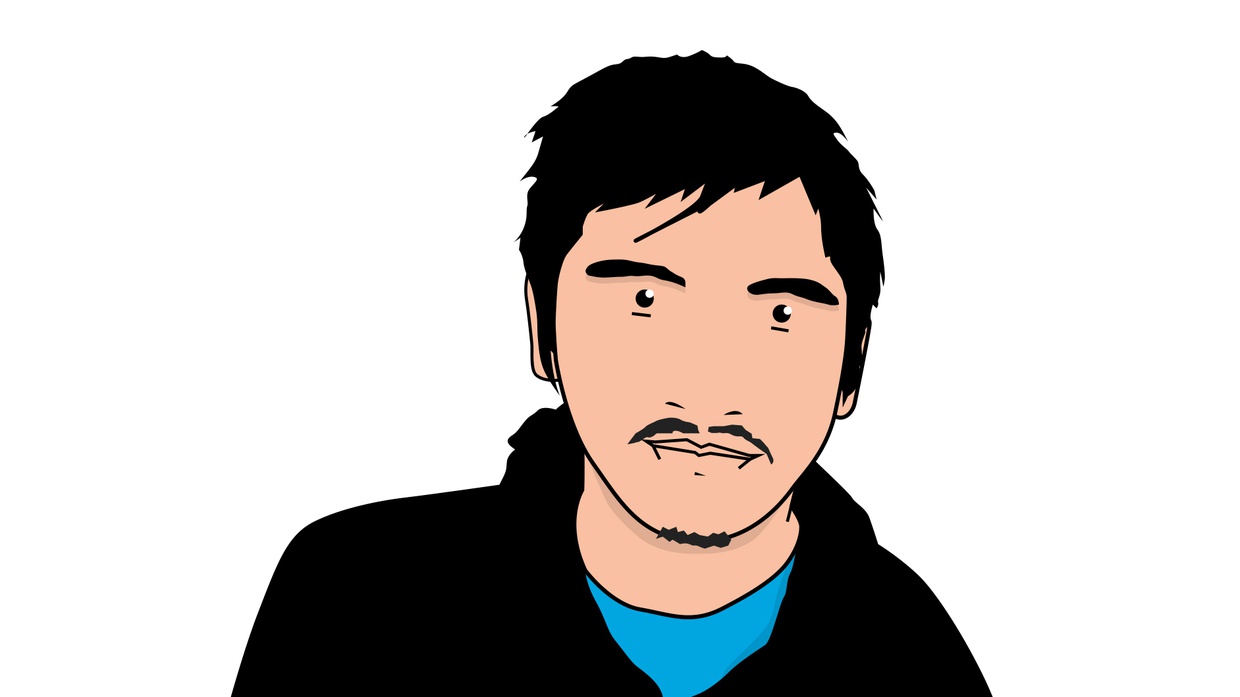tirto.id - Pendukung penggusuran sering mengingatkan: orang miskin belum tentu benar. Saya kira peringatan macam itu tidak terlalu tepat, atau malah kurang jujur. Jika ingin lebih tepat, atau mau jujur, katakan saja begini: orang miskin hampir pasti salah.
Kemiskinan membuat seseorang bukan hanya terbatas dalam soal uang, tapi juga terbatas ke dalam berbagai hal. Jangankan properti legal, bahkan kartu identitas pun sudah lazim mereka tak memilikinya. Kemiskinan, dalam dirinya sendiri, mempersempit ruang gerak dan akses. Jadi jujur sajalah, mari akui sama-sama: bukan orang miskin belum tentu benar, tapi orang miskin memang hampir pasti salah.
Kalau kalah, sih, itu sudah pasti. Menjadi miskin dengan sendirinya berada dalam situasi sebagai orang-orang yang kalah. Mereka kalah dalam pertarungan nasib, kalah dalam tawuran tak seimbang dalam upaya mengakses modal, kalah dalam memperebutkan alat-alat produksi.
Alih-alih memberi peringatan bahwa "orang miskin belum tentu benar", akan sangat baik jika disodorkan peringatan yang boleh jadi lebih mendasar: negara sangat sering berbuat "salah".
Bedanya: si miskin tak leluasa mengubah posisinya yang salah menjadi benar, sedangkan negara sanggup melakukan apa pun. Negara punya legitimasi, aparatus, infrastruktur dan segalanya untuk memutarbalikkan yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Cukup banyak contoh dalam sejarah kekuasaan, di berbagai tempat dan berbagai zaman, ketika negara mampu melakukan apa pun yang dikehendaki.
Langsung meloncat ke dalam kriteria benar-salah, dan berhenti hanya sampai di sana, adalah penalaran yang bisa bermasalah jika ditilik dari perspektif historis. Dari Diponegoro, Sukarno hingga Marsinah, semuanya berbuat salah jika ditakar dari kriteria benar-salah secara hukum. Diponegoro jelas salah secara hukum saat mencabut patok-patok pembangunan jalan di era kolonial. Begitu juga Marsinah. Dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kodim hingga Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, pada masanya, memandang tindakan perlawanan Marsinah, dkk., sebagai hal yang salah. Semua menganggap tindakan Kodim Sidoarjo yang memaksa buruh-buruh yang terlibat dalam demonstrasi untuk mengundurkan diri kala itu sebagai hal benar.
Bahkan Sukarno pun salah. Upayanya membangkitkan kesadaran nasional, terutama melalui metode penggalangan massa dan propaganda, jelas bukan tindakan yang benar dalam takaran benar-salah secara hukum. Dan ini sudah dibuktikan pengadilan Landraad di Bandung. Pada 1930, bersama tiga koleganya yang lain, Sukarno dinyatakan bersalah karena berniat menggulingkan pemerintahan yang sah. Perspektif benar-salah macam itu, dengan merujuk Sukarno sebagai salah satu contoh yang paling menonjol, membuat Indonesia pun bahkan bisa dianggap sebagai ide yang salah sejak awal.
Mencurigai si miskin, apalagi dengan berpatokan kepada kriteria benar-salah secara hukum, adalah pilihan gampang(an). Sebaliknya, mencurigai negara, bukan tindakan yang mudah. Negara sudah telanjur mengurat-akar dalam tata kehidupan, sehingga dipandang sebagai entitas yang alamiah, sudah sewajarnya ada. Pertanyaan seperti "mengapa negara harus ada?", "kenapa saya harus membayar pajak"", "mengapa saya harus taat kepada negara?" secara umum dianggap sudah tidak relevan. Sebab negara sudah telanjur ada, tak terbantahkan eksistensinya, dari urusan pajak hingga urusan alat kelamin.
Bukan berarti negara tidak pernah dicurigai. Hanya saja, mencurigai (eksistensi) negara butuh kerja ekstra, juga risiko yang besar. Sulit menggugat negara dari kriteria benar-salah secara hukum, terutama karena negara adalah pencipta hukum itu sendiri. Negara dan hukum adalah manunggal. Hukum adalah perwujudan eksistensi negara dan kemudian menjadi teknologi negara.
Negara bisa melakukan apa pun atas nama hukum. Menggusur si miskin yang tak punya sertifikat tanah menjadi tindakan benar karena hukum memungkinkan hal itu. Jangankan menggusur, bahkan negara pun bisa "menghilangkan nyawa", entah dengan mengeksekusi para terpidana mati maupun menembak begal motor yang melawan.
Saya menggunakan kata "menghilangkan nyawa", bukan kata "membunuh". Bukankah kata "membunuh" terdengar ganjil jika dilekatkan kepada negara, bukan? Tidak jamak kata "membunuh" digunakan kepada penghilangan nyawa yang dilakukan negara. Bahkan (eksistensi dan legitimasi) negara pun diafirmasi oleh (rasa) bahasa.
Maka si miskin yang tak memiliki sertifikat tanah sudah pasti tak akan berdaya di hadapan negara. Jangankan tak punya sertifikat, punya sertifikat pun belum tentu bisa mempertahankan tanah. Atas nama pembangunan, di mana hukum mengesahkan negara untuk melakukan apa pun termasuk pembangunan, ribuan kepala keluarga yang punya sertifikat tanah toh harus tetap meninggalkan rumah, tanah, sawah dan kampung halamannya untuk memberi tempat bagi Waduk Kedung Ombo atau Waduk Jati Gede atau Bandara Kertajati.
Negara hanya perlu menyesuaikan sedikit pendekatan yang bergantung kepada kekuatan posisi mereka. Dalam negara otoriter, apalagi totaliter, negara bisa bertindak seenak-udelnya. Dalam iklim demokrasi, negara tentu tidak bisa asal main kasar. Mungkin lebih halus, barangkali lebih memakan waktu dan menyita tenaga, namun bukan berarti negara menjadi tidak berdaya. Negara tetap jauh lebih kuat daripada warga karena mereka punya segala hal yang dibutuhkan untuk menuntaskan agenda-agendanya.
Ini tampak dalam Undang-Undang (UU) Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. UU ini lahir, mengikuti penalaran pada paragraf-paragraf sebelumnya, sebagai teknologi negara untuk melegitimasi agenda-agenda negara. Salah satu pertimbangan dari UU tersebut adalah peraturan dan perundangan yang sudah ada masih belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan. Karena itulah dibuatkan UU Pengadaan Tanah No. 12 tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan Perpres No. 71 tahun 2012.
UU itu memang mengatur hak-hak warga negara para pemilik tanah agar mereka diperlakukan dengan manusiawi, demokratis dan adil. Ini sumbangan proses demokratisasi di Indonesia sehingga negara dipaksa untuk tidak bisa seenaknya memuluskan agenda-agendanya. Akan tetapi, pada praktiknya, warga negara tetap berada dalam posisi yang rentan karena -- kendati dilindungi UU-- mereka memang pada akhirnya sulit untuk mempertahankan tanahnya.
Demokrasi memang memaksa negara bersikap persuasif, tapi ini hanya soal waktu saja. Teknologi negara selain hukum dan aparatnya, seperti aparat birokrasi, pertahanan dan keamanan, juga akses kepada modal dan media massa, membuat negara tetaplah raksasa yang sukar dihadapi. Infrastruktur negara memungkinkan kampanye tentang "mengutamakan kepentingan umum" mendominasi diskursus sehingga mereka yang keras kepala mempertahankan tanahnya bisa benar-benar terasing. Butuh tekad baja, keberanian untuk terasing dan diasingkan, juga tali solidaritas yang kokoh, untuk membuat seseorang dapat bersikukuh berdiri mempertahankan tanah, sawah dan kampung halamannya.
Sangat tidak gampang bertahan hanya dengan beberapa gelintir tetangga, sementara di sekeliling buldoser, alat berat, dan truk-truk hilir mudik setiap hari sibuk membangun infrastruktur. Pilihan menjadi sangat terbatas karena, en toch, tak mungkin lagi warga bertindak seperti -- misalnya-- Diponegoro yang memilih angkat senjata. Jika itu terjadi, sebagaimana yang dialami Diponegoro, ujung-ujungnya warga akan dianggap sebagai pengkhianat, pemberontak, tukang rusuh, dan deretan cap yang tak enak ditelan.
Sangat banyak kasus di mana, pada akhirnya, toh negara memperlihatkan jati dirinya sebagai "si tangan besi" kendati UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjamin hak-hak warga. Tidak terbilang kriminalisasi kepada para penentang agenda-agenda pembangunan negara, juga tidak terbilang warga yang menolak digusur akhirnya menjadi korban kekerasan aparat negara. Tiap tahun selalu ada korban kekerasan maupun kriminalisasi.
Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2015 terdapat korban tewas lima orang, tertembak aparat 39, luka-luka 124 dan ditahan (kriminalisasi) 278 orang. Dua tahun sebelumnya, masih merujuk laporan KPA, korban tewas oleh aparat negara dalam konflik agraria bahkan mencapai 21 orang. Korban lain, 30 orang tertembak, 130 mengalami penganiayaan dan 239 warga ditahan.
Maka menjadi hal yang sangat menarik, dalam kasus di Jakarta, ketika banyak warga memandang aksi penggusuran kaum miskin kota sebagai (dikesankan) tindakan yang benar. Seperti sudah saya uraikan di atas, sangat biasa negara menggunakan kategori benar-salah, pendeknya pendekatan hukum, untuk melegitimasi segala tindakannya. Namun baru kali ini, koreksi jika saya salah, penggusuran mendapatkan afirmasi yang cukup massif dari warga dan bahkan dipandang sebagai tindakan keren, hebat, berani, jujur dan tulus.
Salah satu argumen yang kerap dipakai para pendukung penggusuran adalah soal pertaruhan popularitas. Penggusuran itu tidak populer, rentan dituduh sewenang-wenang. Maka jika ada seorang pejabat publik berani melakukan penggusuran, apalagi menjelang Pilkada, hal itu dibayangkan sebagai tindakan yang tulus, menjadi bukti bahwa pejabat tersebut tidak memikirkan kepentingan (popularitas) diri sendiri. Efek lanjutannya mudah ditebak: jika tak memikirkan kepentingan sendiri, sudah pasti tindakan penggusuran itu dilakukan demi kepentingan publik -- termasuk untuk kepentingan orang-orang yang digusur.
Eufemisme bahasa, dari "penggusuran" menjadi "relokasi", digenjot dengan berbagai metode untuk melegitimasi tindakan penggusuran. Karena negara sudah menyediakan hunian pengganti yang (dikesankan) lebih layak, penggusuran pun tiba-tiba mendapatkan elemen etis yang seakan tidak ada padanannya dalam sejarah. Padahal penggusuran warga di Kedung Ombo pun dulu ya memuat elemen "relokasi" dalam bentuk transmigrasi yang juga dikesankan akan memberikan penghidupan yang lebih layak.
Eufemisme ini, juga UU Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, agaknya diarahkan untuk memberi kesan bahwa kali ini negara tidak lagi sama dengan negara pada zaman sebelumnya. Bahwa kali ini negara punya maksud baik, punya niat baik, untuk memperbaiki taraf hidup warganya, untuk memperlakukan mereka yang harus pindah tempat dengan cara-cara yang adil dan manusiawi.
Melihat rekam jejak negara yang kerap melakukan kekerasan terhadap warganya, yang terus terjadi bahkan setelah reformasi 1998 di berbagai wilayah, tidak terkecuali pada rezim sekarang, sangat penting untuk mengingat dan mengulang pertanyaan yang diutarakan Rendra dalam sajak "Pertemuan Mahasiswa": maksud baik saudara untuk siapa?
UU Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang sudah saya sebut diniatkan untuk mempermudah negara "merebut" tanah warga. Kata "merebut" yang saya pakai jelas praktik disfemisme, anggap saja sebagai penyeimbang gejala eufemisme yang sedang meruyak lagi.
Mengapa harus menggunakan disfemisme?
Karena dalam banyak sekali kasus, yang dimaksud "untuk kepentingan umum" itu lebih sering menjadi "untuk kepentingan orang-orang kaya atau korporasi". Warganya disingkirkan -- ini bukan disfemisme-- dengan alasan akan digunakan untuk kepentingan umum, tapi pada praktiknya ternyata untuk mall, apartemen, dan pembangunan properti maupun pabrik-pabrik. Kadang "kepentingan umum" itu menjadi dalih negara untuk mengambil-alih lahan demi alasan pertahanan-keamanan (tempat latihan tentara), namun ujung-ujungnya perusahaan juga yang masuk. Dalam kasus konflik lahan di Urut Sewu, Kebumen, misalnya, "kepentingan umum" berupa tempat latihan militer itu digunakan oleh Kodam Diponegoro untuk mengizinkan perusahaan tambang pasir besi beroperasi.
"Melawan lupa" itu, kawan, tidak boleh hanya berlaku untuk Munir atau Wiji Thukul saja. Jika mengingat Munir atau Wiji Thukul, tapi pada saat yang sama bungkam saat ada (tipikal) orang-orang yang dulu dibela dan diperjuangkan Munir dan Wiji Thukul disingkirkan, itu sih meremehkan Munir dan Wiji Thukul -- semacam mereduksi keduanya menjadi hanya semata nostalgia dan sebagai sebuah etos. "Melawan lupa" dalam kontestasi antara negara dan warga di Indonesia, tuan dan puan sekalian, seharusnya diimbuhi sikap menaruh syak-wasangka seperlunya kepada negara.
Sebab, dengan membaca sejarah dan menyimak kabar-kabar dari lapangan, jauh lebih banyak alasan untuk mencurigai negara ketimbang mencurigai orang-orang miskin.
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id