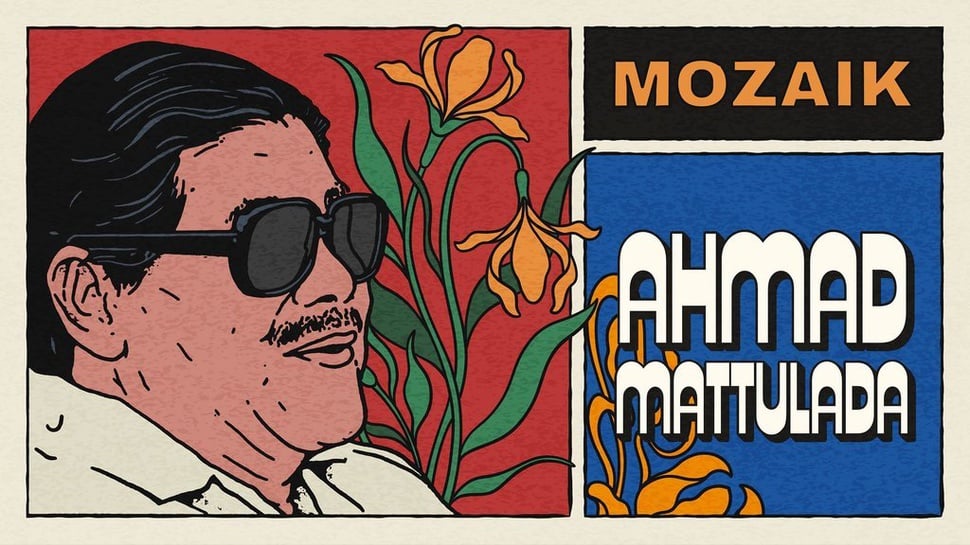tirto.id - Saat Westerling membantai ribuan rakyat Sulawesi Selatan, Mattulada yang saat itu berusia 18 tahun, nyaris menjadi korban. Ia waktu itu mendekam di penjara Bulukumba, sebuah kabupaten di tenggara kota Makassar.
“Saya resah menunggu giliran dihabisi Westerling. Saya hanya bisa berdoa,” ujarnya.
Kala itu, banyak tawanan yang sering dijemput tentara dan tidak pernah kembali.
“Seandainya Kepala Polisi Sulawesi Selatan, La Tippa, tidak kebetulan berkunjung ke penjara Bulukumba, pada 7 Januari 1947, barangkali kita tak kenal lagi Mattulada, seorang pemikir dari Ujung Pandang,” tulis salah satu muridnya, M. Dahlan Abu Bakar, dalam Mattulada, dari Pejuang hingga Ilmuwan (2023).
Pada 17 Juli 1976, Mattulada menentang pergantian julukan kota Makassar menjadi Ujung Pandang. Bersama Andi Zainal Abidin Farid dan H.D. Mangemba, mereka mengeluarkan Petisi Makassar yang ditujukan kepada Walikota Daeng Pattompo dan DPRD Kota Ujung Pandang.
"Berdasar penemuan, keyakinan dan tanggung jawab kami, baik secara bersama-sama maupun masing-masing, kota ini bernama Makassar. Demi ketulusan dan hasrat kita semua untuk menegakkan kejujuran dan keluhuran namanya Makassar," isi petisi itu.
Mattulada percaya bahwa nama Makassar memiliki makna dan nilai historis yang sangat penting bagi identitas masyarakat Sulawesi Selatan. Menurutnya, perubahan nama tersebut akan mengaburkan sejarah dan merusak warisan budaya yang telah ada sejak zaman dulu.
Tidak Betah Jadi Polisi
Prof. Dr. Ahmad Mattulada merupakan sosok yang memiliki banyak sisi, tidak hanya unggul dalam bidang akademis tetapi juga dalam dinas militer saat menjadi anggota Gerilya Sulawesi Selatan pada masa revolusi.
Hingga tahun 1950, ia menjadi anggota Dinas Pengawasan Keamanan Negara (DPKN) dan ditunjuk sebagai Ajudan Inspektur yang tugasnya menyelidiki para penjahat politik.
Ia lahir di Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada 15 November 1928 sebagai anak sulung dari lima bersaudara. Nama kecilnya Mattola Adeq, diberikan oleh sang ayah seorang kepala adat di tanah kelahirannya yang memiliki makna “Pengemban Adat” dalam bahasa Bugis.
Sementara nama panggilannya, Mat, kerap disandarkan kerabat dan teman sebayanya. Sembari mengenyam pendidikan dasar Schakel School pada 1942, ia juga sekolah agama di Mualimin Muhammadiyah.
Karakternya yang luwes dan kuat dalam memegang prinsip merupakan didikan ayahnya, A. Palellungi Dg. Manrapi, seorang pensiunan kepala negeri dan anggota aktif Muhammadiyah.
“Terciptalah dalam diri saya dua pola secara bersamaan, adat dan agama,” tuturnya dalam Apa & Siapa Sejumlah Orang Indonesia (1986).
Setelah Indonesia merdeka, ia pindah ke Makassar dan menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA. Pada masa inilah ia mulai aktif dan bergabung dalam barisan tentara pelajar hingga berpangkat letnan, lalu mengantarkannya berkarier di kepolisian.
Memasuki tahun 1953, ia menikahi Asia Ressang sebagai komitmen terhadap keluarga di samping sebagai penyemangatnya dalam berkarier. Mereka dikarunia empat orang anak.
Bosan jadi polisi, pada 1956 Mattulada kerja menjadi guru di SMA Negeri 1 Makassar sembari menimba ilmu di Pendidikan Guru SLA yang diselesaikannya pada 1957. Di tahun itu pula ia menorehkan akte B1--setingkat Diploma 1—bidang ilmu hukum.
Gayung bersambut, prestasinya sebagai pendidik mendapat kepercayaan dari pemerintah Sulawesi Selatan dengan menempatkannya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 3 Makassar dari tahun 1956 hingga 1961, dan di SMA Negeri 1 Makassar pada 1961 hingga tahun 1966.
Selama menjadi kepala sekolah, selain membenahi sistem pembelajaran yang masih belum stabil, Mattulada juga menerapkan disiplin yang ketat, termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa dan guru, termasuk peningkatan kualitas pembelajaran.
Sambil kuliah sastra di Universitas Hasanuddin, dia meraih gelar sarjananya pada 1964.
Latoa dan Kaili
Kontribusi Mattulada yang beragam sebagai akademisi, tokoh sastra, dan pegiat budaya meninggalkan dampak yang besar bagi perkembangan pendidikan dan kebudayaan, khususnya bagi orang Bugis.
Perjalanan hidupnya yang penuh peristiwa, dari bertahan hidup di penjara pasca kemerdekaan hingga menjadi tokoh kunci dalam pendirian lembaga pendidikan, menunjukkan ketangguhan dan dedikasinya yang tinggi.
Ia telah menulis banyak buku dan artikel mengenai sejarah, kebudayaan, dan bahasa daerahnya, yang telah memberikan wawasan yang berharga bagi masyarakat luas.
Usai meraih gelar sarjana, Mattulada dipercaya sebagai dosen di Fakultas Sastra hingga tahun 1966 yang mengantarkannya menjadi dekan di fakultas yang sama. Pada 1970 ia berangkat ke Belanda untuk mengikuti pelatihan pascasarjana di Rijks Universiteit Leiden hingga tahun 1972.
Pada periode inilah ia mulai menulis Latoa, Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis yang diselesaikannya tahun 1975 sebagai disertasi meraih gelar doktor antropologi di Universitas Indonesia.
Latoa merupakan hasil penelitian mendalam Mattulada tentang sistem politik tradisional masyarakat Bugis. Dia menganalisis konsep Latoa sebagai bentuk pemerintahan yang unik, khas masyarakat Bugis. Melalui karyanya ini, Mattulada tidak hanya mendeskripsikan sistem tersebut, tetapi juga melakukan analisis mendalam yang menggabungkan perspektif antropologi dan politik.
“Jadi Latoa adalah suatu menuskrip Bugis lama dan Makassar yang terkenal dengan nama 'Lontara'. Karena Lontara mempunyai karakter unik yang dipergunakan untuk pedoman orang-orang Bugis terutama dalam mengambil keputusan pihak berwenang,” ujar Andy Maryam dalam Ensiklopedia Tokoh Kebudayaan IV (1999:93).
Menurut Mattulada, dalam kesehariannya orang Bugis kerap berpikir dan menganut tiga prinsip dalam mengarungi kehidupan dan mengembangkan kebudayaannya.
“Pertama, manusia itu, apa pun dan bagaimanapun tingkat atau derajat sosialnya adalah makhluk yang sama derajatnya sebagai ciptaan Tuhan. Kedua, manusia itu, dalam tujuan hidupnya berhasrat untuk selalu berbuat kebajikan. Dan ketiga, manusia itu, dalam membangun nilai-nilai dan pranata-pranata sosial kebudayaannya selalu berusaha mencapai keselarasan antara kepentingan kolektif dengan kepentingan individualnya,” tuturnya.
Mattulada merupakan sosok yang sangat gigih terhadap pendidikan dan budaya lokal. Pada tahun 1977 hingga 1978, ia dipercaya sebagai Direktur Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial di Makassar. Ia lalu diangkat menjadi Guru Besar Tamu di Kyoto University, Jepang, dan sempat menelurkan buku Pedang dan Sempoa: Sejarah Kebudayaan dan Perasaan Kepribadian Orang Jepang yang terbit pada 1981.
Kepada mahasiswanya, Mattulada sering mengajarkan pentingnya mencatat sebagai kebiasaan yang harus jadi budaya sehari-hari. Ia selalu membawa catatan untuk menuliskan ide-ide penting, meskipun di era teknologi.
Ia kerap mendorong pendekatan pendidikan yang melibatkan transkultur dan transdisiplin, di mana pembelajaran tidak terbatas pada satu disiplin ilmu saja, tetapi mengintegrasikan berbagai perspektif.
Warsa 1991, ia kembali menulis buku berjudul To-Kaili, Manusia dan Kebudayaan di Sulawesi Tengah. Buku ini merupakan pengalamannya menggali budaya orang-orang Kaili ketika ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Dr. Daoed Joesoef, sebagai rektor di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah dari tahun 1981 hingga 1990.
Mattulada mendeskripsikan kehidupan masyarakat Kaili lewat berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari sejarah, sosial, budaya, hingga pandangan hidup. Masa-masa ini pula ia mulai fokus dalam pengkajian lingkungan hidup dan manusia. Pemikirannya mencakup bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan ekologi, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
Jejak yang Tertinggal
Ahmad Mattulada wafat pada 12 Oktober 2000 di rumah sakit akibat stroke dan diabetes, meninggalkan warisan ilmiah dan amal ibadah yang tak ternilai bagi orang Bugis dan masyarakat Indonesia. Melalui karya-karyanya, Mattulada memberikan kontribusi dalam membentuk kurikulum dan pemikiran pendidikan di Indonesia.
Setelah menjabat sebagai rektor di Palu, ia kembali ke kampung halamannya dan dipercaya sebagai Ketua Senat Guru Besar Universitas Hasanuddin hingga pensiun pada 1994. Masa senjanya disibukkan dengan seminar terkait kebudayaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Lain itu, sesekali ia mengajar di Unhas dan di Universitas 45 Makassar.
Selama hidupnya, ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan menekankan pentingnya pendidikan bagi masyarakat lokal. Mattulada melihat pendidikan sebagai kunci dalam menjalani karier dan kehidupan, serta sebagai etos perjuangan yang harus diadopsi oleh generasi muda.
Meski begitu, ia memiliki pemikiran yang kontroversial, kerap mengkritik pejabat yang tidak kompeten, mencetuskan Petisi Makassar yang menolak penamaan Ujung Pandang, termasuk sepakat dengan hak otonomi yang digagas kelompok Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).
Ia mendapat pengakuan sebagai Pelopor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998. Ia juga dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma pada tahun 2000.
Sebagai prajurit, Prof. Dr. Ahmad Mattulada diganjar Bintang Gerilya dari Presiden RI dan Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan dari Menteri Pertahanan RI.
Meski telah tiada, nama dan kontribusinya diabadikan lewat aula dan perpustakaan yang memakai namanya di Universitas Hasanuddin.
Penulis: Ali Zaenal
Editor: Irfan Teguh Pribadi