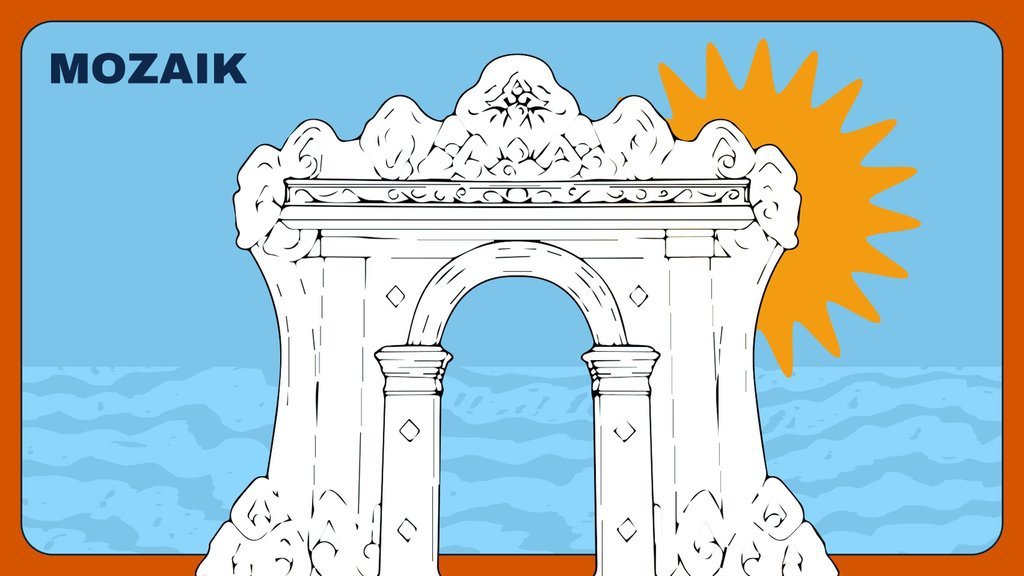tirto.id - Naskah Wangsakerta yang berisi enam judul tulisan danterus-menerus menjadi bahan perdebatan disebut-sebut muncul atas prakarsa Pangeran Wangsakerta dari Cirebon yang memimpin "konferensi ilmiah" bernama gotrasawala.
Ditulis pada sekitar abad ke-17, isi dari naskah ini menguraikan sejarah kebudayaan di Nusantara paling tidak sejak abad pertama Masehi.
Meski seakan mengisi kekosongan data sejarah kuno, naskah ini justru janggal di mata para sejarawan dan filolog. Ahli sejarah kebudayaan Hindu-Buddha, Boechari, secara khusus membuat kritik tajam terhadap NaskahWangsakerta lewat tulisannya berjudul "Beberapa Kritik atas Naskah-Naskah Wangsakerta” (1988).
Menurut Boechari, kejanggalan utama naskah ini terletak dari unsur kebahasaan, si penulis naskah entah mengapa menggunakan bahasa Jawa Kuno. Padahal. bahasa Jawa Kuno tidak lazim digunakan di lingkungan keraton Islam seperti Cirebon.
Bahasa Jawa Kuno terakhir digunakan di keraton Jawa yakni pada masa akhir Kerajaan Majapahit atau terpaut tiga abad dari naskah tersebut. Keanehan lainnya yang dijumpai Boechari adalah keabsahan narasi sejarah, asal-usul penemuan naskah, dan aspek-aspek krusial lainnya.
Di luar tudingan palsu terhadap Naskah Wangsakerta, sosok Pangeran Wangsakerta bukanlah tokoh ahistoris. Sosok ini muncul sebagai salah satu aktor utama dalam drama pergolakan politik Jawa setelah mangkatnya Sultan Agung pada akhir abad ke-17.
Kendati Wangsakerta menjadi semacam monumen bagi sejarah Cirebon, dalam arus sejarah sosok ini malah seakan dicurangi takdir. Ia tersisih dari panggung sejarah tanpa meninggalkan jejak berarti selain naskah yang membingungkan para sejarawan dan filolog.
Raja Cirebon Disandera
Penghujung abad ke-17 menjadi periode yang genting dalam sejarah Kerajaan Mataram. Setelah mencapai puncak kejayaannya di tangan Sultan Agung pada awal hingga pertengahan abad ke-17, api pemberontakan akhirnya tiba juga ke jantung Jawa.
Sunan Amangkurat I sebagai Raja Jawa kala itu, kewalahan menghadapi amukan Pangeran Trunojoyo dari Madura. Perlahan wilayah timur Mataram satu persatu jatuh ke tangan Trunojoyo. Kondisi ini sebagaimana disampaikan Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris (2018), merupakan hulu ledak dari berbagai konspirasi untuk menggulingkan Amangkurat I.
Sebelumnya rezim Amangkurat I sudah dibayang-bayangi Persekongkolan Kajoran (1672-1677), klimaksnya justru diraih oleh Trunojoyo yang berhasil menduduki Istana Mataram di Plered pada 1677. Pukulan keras Trunojoyo itu berhasil membuat Sunan Amangkurat I lari dari keratonnya dan memperumit konflik suksesi Mataram satu abad berikutnya.
Di tengah-tengah suasana politik yang demikian panas, Cirebon sebagai salah satu vasal Mataram juga turut mendapat efek dari pemberontakan Madura. Menurut Tendi dalam "Kontrak Cirebon-VOC Tahun 1699: Peran VOC dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Cirebon" (2022), sejak kekalahan armada Cirebon dalam pertempuran melawan Banten di Laut Tanara pada tahun 1650-an, Raja Mataram kecewa dengan raja Cirebon bawahannya.
Sebagai hukuman, Panembahan Girilaya yang kala itu merupakan penguasa di Cirebon kemudian ditahan oleh Amangkurat I di ibu kotanya. Hukuman yang lahir dari ketakutan Mataram akan berpihaknya Cirebon pada Banten, rupanya melahirkan suatu sistem baru di Cirebon.
Panembahan Girilaya harus rela diwakili oleh seseorang dalam memerintah, yakni putra bungsunya, Pangeran Wangsakerta.
Perubahan sistem yang muncul dari cawe-cawe Raja Mataram ini kelak menjadi bola panas bagi Wangsakerta ketika Trunojoyo dari Madura sekali lagi mendatangkan angin pembaruan bagi sistem pemerintahan kerajaan di Kota Udang ini.
Campur Tangan Sultan Banten
Pangeran Wangsakerta memiliki dua kakak laki-laki, yakni Pangeran Martawijaya sang sulung dan Pangeran Kertawijaya sang penengah. Keduanya terjebak bersama Panembahan Girilaya karena turut serta bersama dengan ayah mereka sewaktu bertandang ke Mataram.
Itulah sebabnya Wangsakerta yang kemudian kejatuhan durian runtuh takhta Cirebon, karena ia satu-satunya anak Girilaya yang tidak ditahan ke Mataram. Takhta Wangsakerta sebagai Raja Wali Cirebon ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Kendati ia adalah wali Panembahan Girilaya yang sah, ia tetap harus tunduk pada perintah duta Mataram yang ditempatkan di Cirebon.
Menurut Sobana Hardjasaputra dalam Cirebon dalam Lima Zaman: Abad ke-15 hingga Pertengahan Abad ke-20 (2011), perwakilan Mataram yang menjadi penasihat Wangsakerta adalah Martadipa selaku syahbandar Pelabuhan Cirebon. Wangsakerta menjadi raja boneka di Cirebon bahkan sampai ayahnya wafat di Mataram pada tahun 1662.
Setelah ayahnya meninggal, kedua kakaknya tidak kunjung dilepaskan oleh Amangkurat I.

Kondisi demikian baru menemui titik balik ketika Trunojoyo berhasil menguasai Keraton Mataram pada 28 Juni 1677. Selama pengepungan, Trunojoyo yang bersekutu dengan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, segera menyelamatkan kedua pangeran Cirebon yang disandera Mataram.
Segera setelah itu, secara estafet Trunojoyo mengirimkan Pangeran Martawijaya dan Kertawijaya ke Banten via Kediri. Kedua anak Panembahan Girilaya itu kemudian tiba di Banten pada awal Oktober 1677.
Sementara itu, menurut F.T. Deviani dalam "Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Politik Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681 M - 1755 M)" (2016), pada Januari 1677 tentara Trunojoyo telah menyerbu Cirebon.
Tujuan utama penyerangan untuk membasmi pejabat-pejabat Mataram yang masih bercokol di sana. Sesudahnya, Martadipa diminta untuk kembali ke Mataram sembari menyampaikan pesan bahwa Cirebon telah merdeka dan berada di bawah perlindungan Kesultanan Banten.
Setelah Cirebon dianggap bersih dari pengaruh Mataram, Sultan Ageng Tirtayasa yang sebenarnya masih kerabat raja-raja Cirebon (sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati), lantas mengangkat tiga pangeran Cirebon sebagai raja.
Pangeran Martawijaya yang sulung dibri gelar Sultan Sepuh, kerajaannya bernama Kasepuhan. Sedangkan Kertawijaya sang anak tengah diberi gelar Sultan Anom dengan kerajaannya yang bernama Kanoman.
Masalahnya, Wangsakerta yang selama bertahun-tahun memerintah di Cirebon menggantikan ayahnya justru hanya mendapat gelar Panembahan dan tidak kebagian wilayah kerajaan. Ia malah mendapat wewenang untuk mengelola naskah-naskah keraton.
Karena keputusan Sultan Ageng Tirtayasa, tiga raja bersaudara dari Cirebon kelak akan berebut menjadi raja tunggal di Cirebon. Keadaan baru berangsur stabil setelah VOC mengambil alih kekuasaan Cirebon dari Banten dengan meneken kontrak pada 7 Januari 1681.
Penulis: Muhamad Alnoza
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id