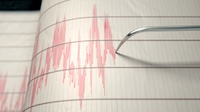tirto.id - “Kalau boleh diceritakan, apa yang sedang dilakukan saat tsunami terjadi?”
Setiap pertanyaan itu saya ajukan, saya mendapati mata orang di depan menerawang entah ke mana. Seperti sedang mengais ingatan tentang sejarah yang jauh dan dekat secara bersamaan. Lalu, cerita mengalir tentang gempa pukul 8 pagi di Aceh, disusul panik teriakan "air laut naik, air laut naik".
Setelahnya adalah tragedi.
Cerita-cerita itu saya kumpulkan dari ingatan mereka yang berselancar di ombak-ombak Aceh, tepatnya di lepas laut barat Lhoknga dan Lampuuk. Mereka secara langsung mengalami musibah tsunami 2004, tepat 17 tahun silam, yang menghempas Aceh dan tempat-tempat lain di sekitar Samudra Hindia. Lalu, selang berapa waktu, para peselancar Aceh itu kembali ke ombak, ke laut yang telah mengambil orangtua, saudara, dan kawan mereka.
Pertanyaannya kemudian: Mengapa kembali ke laut? Relasi manusia-laut macam apa yang memungkinkan proses ‘kembali’ itu terjadi? Dan, bagaimana rasanya bermain di ombak setelah ombak raksasa tsunami meratakan gampong-gampong?
Masak Garam dan Manoe Laot
Pertama-tama, untuk memahami kenapa peselancar Aceh kembali ke ombak setelah tsunami, kita perlu menengok tradisi masak garam yang dulu ada di pesisir-pesisir Lhoknga dan Lampuuk. Setiap musim timur, ketika angin bergerak dari daratan ke samudra, ibu-ibu di Lhoknga dan Lampuuk akan membangun pondok-pondok (jamboe) sederhana di pinggir pantai. Sepanjang musim, mereka akan masak garam di sana: menyaring pasir dengan karung goni untuk menampung air laut, kemudian memasaknya di kuali (beulangong) hingga butir-butir garam bermunculan. Musim angin timur berlangsung sekitar setengah tahun, kira-kira dari bulan Oktober hingga April.
Dalam tradisi masak garam itulah banyak peselancar asal Lhoknga dan Lampuuk memulai relasi intimnya dengan laut. Selama musim masak garam, anak-anak akan langsung menuju pantai begitu sekolah berakhir. Di pantai mereka akan menemui ibu masing-masing, lalu bermain bersama. Anak-anak itu akan berenang di tepi laut, sekadar bermain di pantai, dan sebagian lain mulai bermain ombak.
Andi, 36 tahun, mengingat bagaimana ia dan kawan-kawannya dulu bermain ombak dengan memakai papan kayu seadanya, berukuran sekitar 100x20 cm.
“Saya mulai main ombak saat masih SD, ketika orang-orang tua masak garam. Kami selancar dengan papan kayu, kita bentuk seperti papan selancar. Saat ombak pecah, kita lari dan tiduran di atas papan itu,” tuturnya.

Sementara itu, Ikhsan, 31 tahun, menceritakan permainan laut yang disebut phok geulombang (tabrak ombak), di mana anak-anak akan berlari ke arah ombak yang pecah dan menabrakan tubuhnya ke ombak. Gengsinya terletak pada ukuran ombak; siapa yang menabrak ombak terbesar hari itu dianggap paling keren. Setelah itu, baru mereka terbiasa berselancar dengan bodyboard dan kemudian papan selancar (surfboard).
Tradisi masak garam berkelindan dengan permainan laut dan membentuk pelbagai kebiasaan lain terkait laut. Dalam konteks yang lebih luas, di Aceh dikenal ungkapan sehari-hari manoe laot (mandi laut), yang merujuk pada beragam kegiatan rekreasional di laut. Orang-orang dari kota akan pergi ke pesisir untuk mandi laut di akhir pekan. Sedang, di pesisir, terlebih saat hari sedang panas betul, orang-orang pergi mandi laut hampir saban sore. Selancar, pada akhirnya, tercakup pada ekspresi budaya manoe laot itu, sebagai salah satu permainan dan olahraga yang dilakukan di laut. Sering saya dengar orang mengajak temannya berselancar dengan mengatakan, “Ayo mandi kita [ayo selancar kita]”.
“Kami Tak Pernah Membenci Laut”
Hubungan itu telah terjalin, antara manusia dengan laut, lewat tradisi masak garam dan budaya mandi laut. Kemudian, datangnya turis-peselancar di Aceh sejak 1970-an turut menebalkan hubungan itu. Orang-orang jadi makin mengenal selancar, papan selancar makin mudah didapat, dan makin banyak peselancar lokal. Maka, sekian waktu setelah tsunami, pelan tapi pasti para peselancar Aceh kembali ke laut.
Saya awalnya membayangkan proses ‘kembali ke laut’ itu sebagai sesuatu yang heroik. Di lapangan, saya mendapati bahwa proses itu ternyata berlangsung secara organik, secara biasa-biasa saja, seakan-akan tsunami hanyalah interupsi sesaat saja, yang takkan memutus hubungan panjang yang sudah dijalin para peselancar Aceh dengan lautnya.
Memang, tak bisa dipungkiri, beberapa orang kembali ke laut dengan perasaan yang gamang dan campur aduk. Adon, 35 tahun, mengaku sedih dan senang ketika berselancar lagi. Sedih karena banyak teman-teman selancarnya yang jadi korban, senang karena bisa kembali ke hobi selancar. Ia pun mengingat pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya ketika pertama kali mendayung papan selancar ke laut setelah tsunami.
“Pas pertama turun ke laut lagi, saya teringat tsunami. Saya berpikir, seandainya saya lebih cepat tahu, mungkin saya bisa membawa orangtua pergi, tidak sampai terkena tsunami. Lalu, sambil melihat air laut, saya bertanya, kenapa kok bisa ada tsunami? Sampai saya berpikir, kenapa Tuhan kasih musibah sebesar ini? Apa salah kami orang Aceh?”
Ketika saya menjumpai Adon, di kafe pinggir pantai miliknya di Lampuuk, ia memakai kaus abu-abu bertuliskan ‘Kami Tak Pernah Membenci Laut’, dibuat pada 2014 untuk memperingati 10 tahun tsunami. Kaus itu seakan mewakili perasaan para peselancar Aceh.
“Kami semua kembali ke pantai. Walau musibah saat itu datangnya dari pantai, kami tidak dendam dengan pantai,” Ikhsan menambahkan.
Umumnya, sekelumit perasaan takut dan traumatis hanya dirasakan di awal mula kembali ke laut. Memori tsunami sempat menghantui sebagian orang saat melihat laut dan ombak. Namun, begitu kembali berselancar, segalanya terasa normal lagi dan yang tinggal hanya kesenangan.
“Untuk menghilangkan trauma, kami anggap ombak sebagai sahabat. Kalau sudah selancar, rasanya lupa semuanya. Senang aja,” jelas Dery, 37 tahun.
Ada banyak cara untuk memahami kenapa perasaan tidak takut, tidak dendam, atau tidak benci laut mendominasi di kalangan peselancar Aceh. Pertama, waktu-waktu yang mereka habiskan di laut telah membentuk ikatan tersendiri yang, menurut pengakuan banyak orang, “hanya peselancar yang memahaminya”.
Kedua, banyak peselancar menganggap bahwa jalan hidup sebagai orang pesisir memang menggariskan mereka untuk selalu hidup dekat dengan laut. Ketiga, dengan bekal nilai-nilai agama, mereka menganggap bahwa tsunami adalah musibah yang ada hikmahnya. Contoh yang paling sering disebut adalah betapa tsunami telah membuat konflik GAM-RI berakhir di meja perdamaian.
Lebih lanjut, setelah tsunami, dukungan kepada komunitas selancar di Aceh berdatangan, termasuk dari turis-peselancar asing yang rutin ke Aceh. Salah satu cerita yang selalu saya dengar adalah soal bantuan papan selancar dari Akira, peselancar Jepang yang rutin mengunjungi Aceh sejak akhir 1990-an. Beberapa bulan setelah tsunami, Akira datang ke Aceh dan membawa sejumlah papan selancar. Ia ingin teman-teman selancarnya di Aceh kembali ke laut dan tidak meninggalkan hobi selancar. Papan-papan pemberian Akira itulah yang kemudian digunakan para peselancar lokal untuk kembali berselancar.
Selain itu, dukungan antarsesama peselancar lokal juga penting dalam proses mereka kembali ke laut. Hendra, 43 tahun, mengakui itu.
“Memang awalnya kami takut. Tapi lantaran ada kawan-kawan yang selalu mengajak berselancar, maka hilang pikiran-pikiran jelek soal tsunami. Lalu, masuk pikiran yang positif.”
Hampir semua menyadari peran teman-teman sesama peselancar dalam memotivasi mereka untuk kembali ke laut. Bisa dibilang, proses ‘kembali’ itu sebenarnya adalah proses yang kolektif.
Menatap Masa Depan Selancar Aceh
Sudah 17 tahun berlalu sejak tsunami. Banyak hal berubah setelahnya. Ombak-ombak, misalnya. Salah satu ombak pasir di Lampuuk tak ‘hidup’ lagi, akibat gelombang tsunami menyapu pasir-pasir ke darat, membentuk dasar laut jadi lebih dalam, dan membuat ombak-ombak tak pecah lagi di sana. Tak hanya ombak, orang-orang yang bermain di laut juga mengalami proses regenerasi. Sekarang, di ombak-ombak Lhoknga, kita lihat banyak anak kecil dan remaja berselancar. Jam 3 atau 4 sore mereka akan pergi ke pantai membawa papan selancar, lalu bermain di ombak hingga magrib menjelang.

Proses regenerasi peselancar lokal itu bisa terjadi karena ada orang-orang yang kembali berselancar setelah tsunami. Sebagian dari mereka yang ‘kembali’ itu kini aktif dalam urusan membina dan melatih peselancar junior. Apalagi, belakangan selancar menjadi olahraga yang lebih serius di Aceh. Terma ‘atlet selancar’ mulai membayang di imajinasi peselancar muda Aceh. Ketika selancar untuk pertama kali dipertandingkan pada PON 2024 nanti di Aceh dan Sumatra Utara, banyak dari mereka berharap bisa mewakili Aceh.
Di luar geliat selancar sebagai olahraga kompetitif, memasyarakatkan selancar pada level akar rumput di Aceh sebenarnya masih jadi tugas yang relevan. Aulia, 37 tahun, melihat potensi selancar sebagai sarana pendidikan lingkungan. Ia membayangkan suatu saat selancar bisa masuk sebagai mata pelajaran atau kegiatan ekstrakulikuler di sekolah-sekolah Aceh, terlebih di daerah pesisir. Lewat selancar, anak-anak Aceh di masa depan harapannya akan lebih memahami ekosistem bahari dan betapa pentingnya menjaga laut. []
*Riset lapangan untuk artikel ini didukung oleh hibah riset The Sumitomo Foundation.
Editor: Nuran Wibisono