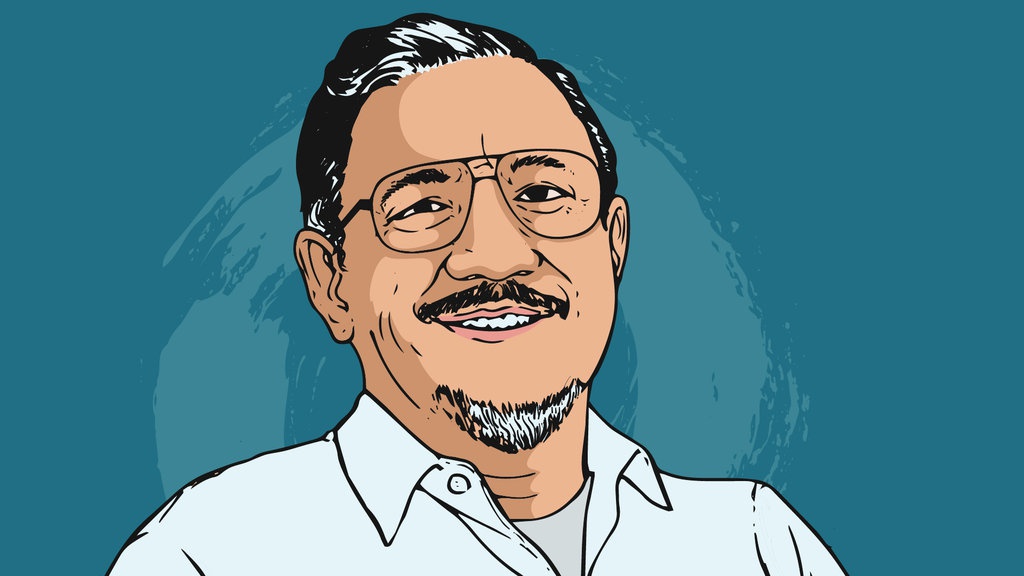tirto.id - Wajah Umar Kayam tegang. Setelah mempersilakan tamunya duduk, suaranya bergetar ketika berbicara kepada enam tamu yang bersamanya mengitari sebuah meja.
“Kejadian seperti ini adalah biasa dalam revolusi. Kita harus mampu meletakken peristiwa ini di dalem kancahnya sejarah semesta. Ini hanya sebutir.... sebutir.... darah dalem sejarah!”
Itu bukan kejadian faktual. Kayam tengah memerankan Presiden Sukarno dalam film “terbesar yang tak mungkin terulang lagi” besutan sutradara Arifin C. Noer, Pengkhianatan G30S/PKI. Pagi itu, dia memanggil sejumlah perwira, termasuk Amoroso “Soeharto” Katamsi, yang siap membuktikan keterlibatan Angkatan Udara dalam peristiwa Gerakan 1 Oktober 1965.
Ketokohan Bung Besar yang diperankan Kayam memang meninggalkan citra yang kuat. Didukung racikan sinematografi Arifin C. Noer, Kayam menampilkan kebimbangan seorang pemimpin negara menghadapi peristiwa berdarah yang masih sumir informasinya. Sukarno di film itu adalah pemimpin negara yang sudah uzur, sakit-sakitan, tapi belum mampu menentukan sosok yang laik menggantikannya.
Di luar peran itu, Kayam sendiri adalah seorang yang gelisah kala peristiwa berdarah itu terjadi. Dia pun tak memendamnya sendiri. Kegelisahan yang sama juga tersurat dalam beberapa novelet dan cerita pendeknya.
Misalnya, simaklah novelet Sri Sumarah dan Bawuk (1975) yang merekam jelas kegelisahan Kayam sebagai penulis kala menyaksikan bangsanya bertukar wajah perlahan-lahan.
Harus dan Tidak Harus: Tono dan Bawuk
Umar Kayam baru saja meraih gelar Doctor of Philosophy dari Cornell University saat Sukarno mengangkatnya menjadi Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film Departemen Penerangan RI pada 1966. Jabatan ini disandang Kayam selama dua tahun delapan bulan. Kayam berhenti pada 1969 untuk menggantikan Trisno Sumardjo sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta.
Bersamaan dengan tugasnya sebagai birokrat, Kayam memulai kiprahnya sebagai pengarang. Dia menerbitkan sejumlah cerita pendek di majalah Horison yang kala itu baru diterbitkan. Salah satu cerita pendeknya, “Seribu Kunang-Kunang di Manhattan” bahkan terpilih sebagai cerita pendek terbaik majalah Horison 1966/1967.
Kayam mengemban dua predikat itu saat Indonesia mengalami masa-masa genting Pasca-1965. Partai Komunis Indonesia (PKI) baru saja dibubarkan. Perburuan, penangkapan, dan pembunuhan terhadap para terduga komunis terjadi di beberapa daerah dan kesemuanya nyaris tanpa prosedur peradilan. Ribuan keluarga kehilangan tulang punggung dan puluhan ribu anak-anak seketika menjadi yatim piatu.
Sebagai sosiolog fresh graduate,Kayam tergerak untuk menyelami apa yang terjadi di tanah airnya. Kayam juga termasuk dalam barisan orang-orang yang mengharapkan Orde Baru menjadi penyelamat bangsa dan negara kala itu.
“Dengan kegairahan seorang anak muda yang percaya pada datangnya suatu orde yang baru yang mesti menggantikan orde yang lapuk, saya bekerja membersihkan lingkungan kerja saya dari semua unsur orde yang lapuk itu,” tutur Kayam dalam esainya yang terhimpun dalam Proses Kreatif: Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang (2009, hlm. 119).
“Akan tetapi,” lanjut Kayam, “bersamaan dengan itu, saya juga melihat korban-korban berjatuhan. Korban yang seharusnya [tidak] menjadi korban. Siapakah yang menentukan ‘harus’ dan ‘tidak harus’ menjadi korban itu? [....] Kebimbangan dan ketidakmengertian [itu] saya coba pertanyakan dalam cerita.”
Kebimbangan itulah yang menjadi hulu dari cerpen-cerpen Kayam yang berlatar Peristiwa 1965. Cerita pendek pertama yang menjadi tempat Kayam bertanya perihal kebimbangannya adalah “Musim Gugur Kembali ke Connecticut” yang dimuat Horison (No. 10, Tahun IV, Agustus 1969).
Cerpen itu mengangkat peri kehidupan Tono, seorang anggota Himpunan Sardjana Indonesia (HSI) dan Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra). Bosan dengan kegiatannya di dua organisasi itu, Tono sempat berencana untuk keluar.
“Aku sudah capek menulis yang itu-itu saja. Aku sudah cukup banyak mengganyang kabir, mengganyang Malaysia, mengganyang tuan-tuan tanah, mengganyang baju hijau,” keluh Tono ketika dikritik Samsu, temannya, yang tidak lain adalah aktivis partai yang getol dan teoritis (Kayam, 2003, hlm. 79).
Tragisnya, G30S pecah sebelum dia sempat menyatakan diri keluar organisasi dan namanya terseret. Tono sempat ditahan beberapa waktu sebelum “dibebaskan”, lalu ditangkap lagi untuk dieksekusi di sebuah perkebunan karet.
Lima bulan setelah terbitnya “Musim Gugur Kembali ke Connecticut”, Kayam menerbitkan novelet “Bawuk” di majalah Horison (No. 1, Tahun V, Januari 1970). Kali ini, protagonisnya adalah Bawuk, istri seorang tokoh komunis. Kayam menarasikan kepribadian Bawuk melalui ingatan sang ibu, Nyonya Suryo.
“Bawuk yang dikenalnya selama tiga puluh lima tahun adalah perempuan periang, murah dengan kata-kata, dan selalu memberi nada hiruk-pikuk dalam surat-suratnya [....] Di luar hubungan surat-menyurat, Nyonya Suryo mengenal anaknya yang paling muda itu sebagai anaknya yang paling ribut, tetapi juga paling mengasyikkan, paling cerdas, dan pemurah.” (Kayam, 2003, hlm. 100)
Nasib Bawuk sama-samangenes. Suaminya, Hassan, adalah komunis yang menolak tunduk. Bersama teman-temannya, Hassan bergerilya dari satu kota ke kota lain. Bawuk dan dua anaknya, Wowok dan Ninuk, mau tidak mau harus mengikuti Hassan.
Saking seringnya berpindah tempat, anak-anaknya bahkan menjadi terbiasa. “Berpindah-pindah tempat pada setiap waktu, membungkus pakaian mereka dengan cepat dan tidak terlalu banyak mengeluarkan suara, adalah keterampilan baru yang telah mereka kuasai.”
Ketika Bawuk dan anak-anaknya terpisah dari Hassan, prioritas Bawuk malah jatuh pada Hassan. Terlebih dulu, Bawuk menitipkan anak-anaknya pada Nyonya Suryo di Karangrandu.
Kedatangan Bawuk disambut kakak-kakaknya yang sukses dan mapan—iparnya bahkan sudah jadi brigadir jenderal—sehingga dia merasa begitu paria. Kakak-kakaknya tentu menganjurkan agar Bawuk tak usah mencari Hassan lagi. Tapi, Bawuk yang telanjur cinta pada Hassan sudah mengambil keputusan yang tak bisa ditawar.
“Tapi Mas-Mas, mBak-mBak, Mammie-Pappie, itulah pilihanku. Dunia abangan yang bukan priyayi, dunia yang selalu resah dan gelisah [....] Kenyataannya Hassan masih di sana, di tempat yang lain sama sekali. Dunia dan impiannya sekarang penuh asap dan mesiu. Penuh pengejaran dan pelarian,” tukas Bawuk kepada kakak-kakak dan ibunya.
Bawuk tak bisa dicegah. Persis pukul tiga, dia pamit kepada ibunya, meninggalkan Wowok dan Ninuk yang telah lelap dalam tidur.
Kayam menutup cerpen ini dengan narasi yang longgar: Nyonya Suryo membaca koran tentang tumpasnya PKI di Blitar Selatan sambil menemani cucu-cucunya mengaji Alquran dalam bimbingan seorang guru.
“Iyyaka na’budu waiyyaaka nasta’iin. Ayo, Gus, Den Rara, dicoba, Iyyaka na’budu....”
Kisah Bu Guru Pijit dan Sisi Gelap Seminaris
Berbeda dengan kedua cerpen sebelumnya yang ditulis dalam kegelisahan akan nasib korban-korban sapu bersih ala Orde Baru, novelet Sri Sumarah dan cerpen “Kimono Biru Buat Istri” ditulis Kayam dalam suasana serba mapan.
Kayam menulis dua karya itu kala diundang seminar di Oahu, Hawaii, “....dalam kondisi kecukupan $1500 sebulan dan apartemen yang sunyi dan mewah, lengkap dengan kolam renang di bawahnya” (Rahmanto, 1998, hlm. 44).
Hasilnya, plot kedua karya terakhir tak berkelok dan naik-turun sebagaimana cerita sebelumnya. Sebagai pencerita, dia lebih tenang. Barangkali, atmosfer Hawaii turut memengaruhi pembawaan ceritanya.
Meski begitu, Kayam tetap menyiratkan kegelisahan yang panjang. Dia tak hanya mimikirkan babak sesudah G30S 1965, tapi juga melirik apa yang terjadi sebelumnya dan membandingkan reaksi tokoh-tokohnya. Dengan kata lain, ketika Kayam lepas dari kebimbangan dan ketidakmengertian, karyanya menjadi semakin kompleks dan mendalam.
Simaklah novelet Sri Sumarah.Judul itu sejatinya diambil dari nama kecil si tokoh utama. Dibesarkan neneknya, Sri hanya menyelesaikan jenjang Sekolah Kepandaian Putri. Dia kemudian dinikahkan dengan seorang guru bernama Sumarto yang kelak memiliki nama tua Martokusumo.
Cobaan pertama yang menguji sikap sumarah (Jawa: pasrah) Sri adalah ketika suaminya meninggal dalam usia muda. Sejak itu, Sri harus merawat Tun, anak perempuan mereka, sendirian. Guna menyambung hidup dan menyekolahkan anaknya, Sri membuka jasa menjahit.
Sri merawat Tun laiknya “telur dalam pengeraman”. Dari banyak telur dalam satu tempat pengeraman, tentu akan ada satu-dua telur yang rusak. Tapi, Tun hanya satu-satunya “telur” dalam eraman Sri. Karenanya, Sri bertaruh habis-habisan menyekolahkan Tun setinggi mungkin.
Nasib ternyata tak memihak ibu dan anak ini. Tun hamil di luar nikah. Kekasihnya, Yos, mahasiswa sarjana muda cum aktivis Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) diakui Tun sebagai pelakunya. Untung, Yos mau bertanggung jawab. Mereka berdua dinikahkan dalam pesta besar-besaran yang ditanggap Sri dengan menggadai separuh sawahnya kepada tuan tanah Pak Mohammad.
Gelagat Yos dan teman-teman seorganisasinya memang tidak banyak ditanggapi Sri. Dia menganggap itu sebagai kelaziman pergaulan zaman sekarang. Meski begitu, Sri pernah pula merasa kurang berkenan. Misalnya, ketika teman-teman Yos memanggungkan ketoprak yang “suka mempermainkan raja-raja Jawa”.
Sri makin gelisah ketika Yos menuntut Pak Mohammad agar mengembalikan tanah yang dilepas Sri karena tak sanggup menebus gadai. Sri sudah merelakan, tapi Yos menuntut agar rumah serta sawah itu direbut kembali. Keterangan Yos bahwa Sri cukup “senang-senang sama anak cucu” membuat Sri menganggukkan kepala tanda setuju.
Kekhawatiran Sri memuncak ketika Tun mengabarkan adanya perebutan kekuasaan di Jakarta. Sri tak menduga bahwa setelah itu Tun dan Yos menitipkan anak mereka kepadanya. Sri makin kebingungan kala Pak RT dan beberapa tentara mendatanginya beberapa hari kemudian.
Sri hanya menerangkan apa yang dia ketahui dari Tun, yang ternyata merupakan keterangan yang sudah tidak berlaku.
“Lho, berontak bagaimana, Pak? Katanya yang berontak jenderal-jenderal,” kata Sri
“Lha, lha, lha. Keliru, Bu. Anak Sampeyan sama teman-temannya itu yang berontak!”
Sri diuji sekali lagi untuk tetap bersikap sumarah ketika memutuskan mengantar Tun menyerahkan diri ke Kodim. Sejak itu, demi masa depan Ginuk, cucunya, Sri mengajarinya untuk menyebut dia “ibu” dan menyebut Tun sebagai “Yu” atau kakak.
Lagi-lagi, dalam sikap sumarah, Sri bertahan hidup lewat kepandaiannya memijat. Dia pun kemudian dikenal orang sebagai Bu Guru Pijit.
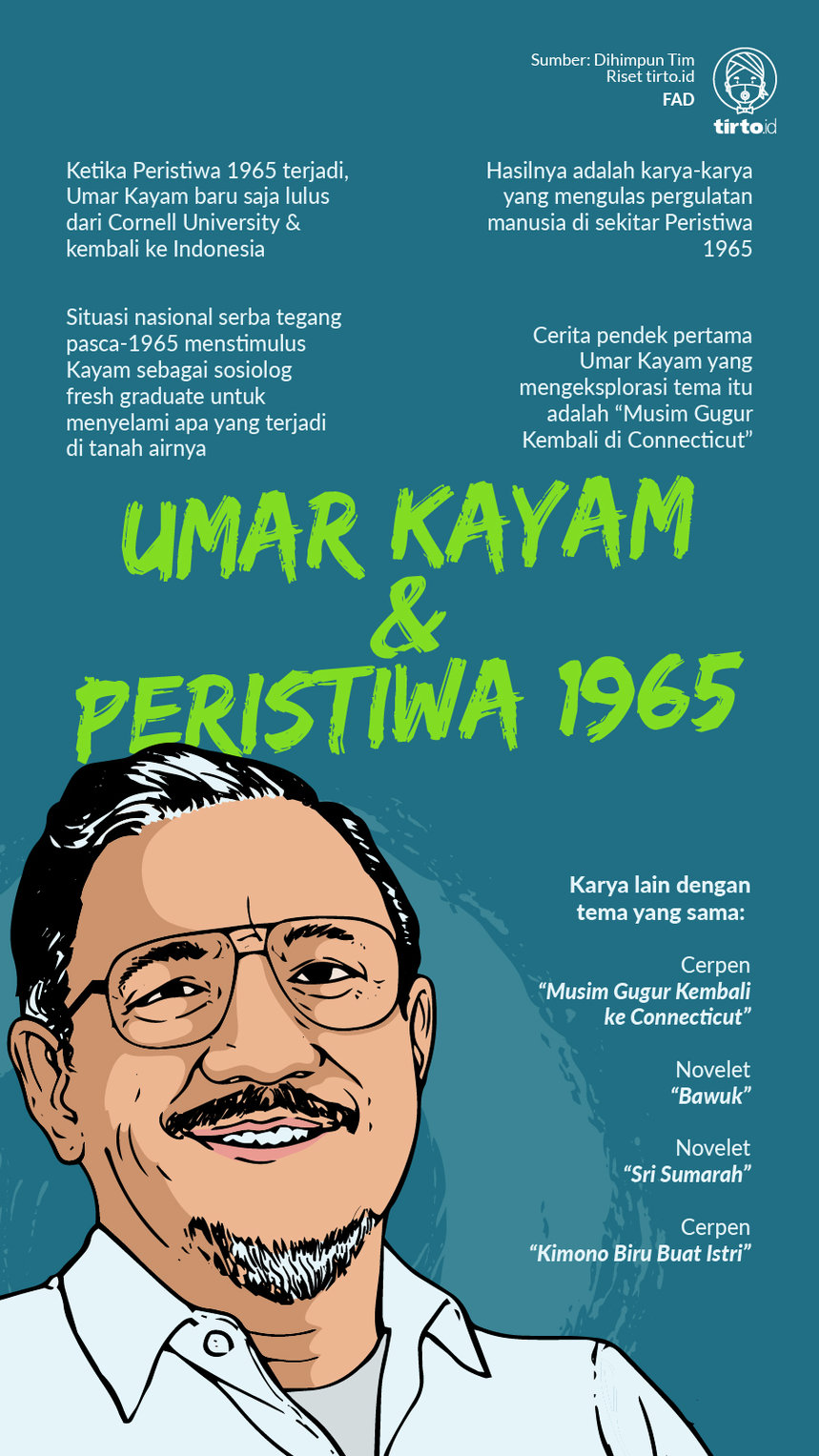
Kemelaratan Sri Sumarah sangat berbeda dibandingkan dengan Mustari, tokoh utama cerpen “Kimono Biru Buat Istri”. Mustari adalah seminaris. Tapi, bukan calon rohaniwan, melainkan pejabat yang hobinya seminar ke luar negeri. Jangan tanya apa hasil seminar-seminar itu karena memang tak ada. Lagi pula, seminar pun lebih sering menjadi bagian dari acara pelesir.
Jika dibandingkan dengan ketiga karya Kayam yang lain, cerpen adalah yang paling tipis persinggungannya dengan Peristiwa 1965. Juga, sekali ini Kayam mengambil perspektif dari protagonis yang bukan korban sapu bersih Orde Baru. Meski begitu, Mustari pernah pula menjadi pihak yang kalah saat polarisasi politik jelang 1965 mencapai puncaknya.
Mustari sejatinya adalah dosen yang tergulung gelombang demonstrasi mahasiswa pada 1964 karena dianggap mengajarkan ekonomi liberal. Setelah tersingkir dari universitas, Mustari ditampung oleh Wandi, sahabatnya sejak zaman revolusi, di sebuah kantor dagang dengan titel konsultan ekonomi.
“Tetapi kau tahu itu tahi kucing saja. Ini markas catut. Dan ekonom textbook thinking macam kau, bisa jadi konsultan apa di ilmu catut?” demikian Wandi meledek Mustari (2003, hlm. 163-164).
Jalan hidup mereka berubah kala Orde Baru bersemi. Mereka yang sebelumnya dianggap subversif dan dikalahkan, kini kembali ke posisinya semula. Bahkan, sekalangan lainnya bisa bisa pegang kendali. Roda sejarah selalu berputar.
Mustari pun kembali ke kampus, meski gajinya pas-pasan. Untuk bertahan pun dia harus “sepak sana sepak sini”. Hanya saja, dia kini menjadi seminaris yang kerap mampir ke sana ke mari membawakan makalah, sambil menikmati hasil korupsi teman-temannya.
Dalam suatu perjalanan seminar ke Jepang, Mustari kembali bertemu Wandi. Kini, Wandi adalah pejabat yang diperhitungkan. Konsesi hutan di Kalimantan dipegangnya. Selain berbisnis kayu, dia pun mengaku juga berpolitik.
Mustari sejatinya segan kepada Wandi yang kini berkantong tebal meski uangnya adalah uang panas. Meski begitu, setiap kali hendak menolak tawaran uang dari kawannya itu, Mustari teringat bahwa uangnya tidak akan cukup untuk kembali ke tanah air dengan membawa jinjingan.
Karenanya, dengan sikap “tahu sama tahu”, Mustari mendekati Wandi demi mengharap sedikit cipratan uang dari kantongnya. Perkiraan Mustari benar. Suatu malam, sesudah dansa-dansi dan karaoke, Mustari diajak Wandi untuk menginap di apartemen, lengkap dengan wanita penghiburnya.
Pagi hari saat terbangun, Mus tak lagi melihat Wandi, namun mendapati sebuah amplop tebal berisi 50.000 Yen kontan. Dia tahu, uang itu tidak berkah. Tapi, hanya dengan uang itulah dia bisa membelikan istrinya sebuah kimono biru dengan ornamen bangau.
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id