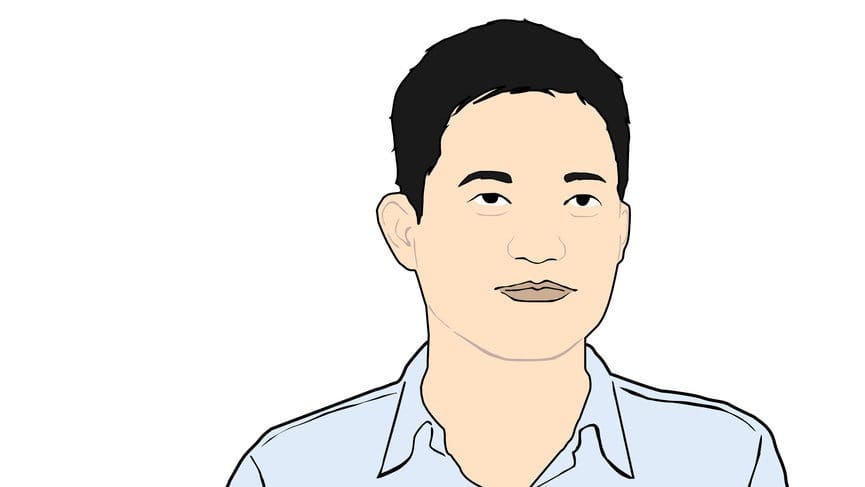tirto.id - Seorang kawan pernah coba-coba meyakinkan saya, yang sedang pelesir di kampung halaman, bahwa satu-satunya cara membereskan masalah-masalah Indonesia adalah dengan mempermaknya jadi negara Islam. “Dan kita,” katanya sambil mengepalkan tangan, “generasi muda, harus turut serta.”
Dia mengangankan sebuah dunia ideal dan menyampaikannya kepada saya seperti membacakan hafalan panjang. Saya membantahnya dengan hafalan lain dan kami jadi seperti dua tukang es yang saling memaksakan dagangan. Agak jengkel, saya bilang: “Mendirikan negara Islam segampang melepas kolor jika kaum muslim telah membuktikan, bukan sekadar meyakini, bahwa Islam benar-benar rahmat bagi semua orang, tapi toh itu tak pernah dan tak bakal terjadi.”
Dia langsung memutuskan berhenti bicara dengan saya, yang menurutnya telah jadi “kafir, vulgar, liberal”, dan berlalu. Saya sedih karena merasa dia terlampau mudah membuang apa-apa yang berharga di antara kami. Saya menyesal karena sayalah yang mendorongnya buat melakukan itu.
Kami sekelas pada tahun pertama di SMA. Saya termasuk dalam rombongan yang bergantung pada uluran tangannya dalam pelajaran-pelajaran ilmu alam (dia juara olimpiade biologi nasional tingkat pelajar SMP). Kami memilih jurusan berbeda, tapi saya tahu dia meneruskan peran itu, dengan kemurahan yang sama, di kelasnya yang baru. Tamat sekolah, saya pergi ke Yogya dan dia tetap di kampung. Saya mendengar kabar dia mengikuti pengajian-pengajian Hizbut Tahrir di kampusnya.
Kadang, setelah perpecahan itu, saya teringat pagi ketika kami menengok kebun sayur kecil milik orangtuanya. Duduk di atas gundukan tanah lembap, berbual-bual sambil memandangi daun-daun sawi, kami kira akal kami merupakan jari-jari terampil yang siap mengurai soal-soal gawat dunia kapan saja.
Saya tak tahu apakah kawan saya itu masih merawat gagasan yang sama. Mungkin tidak, sebagaimana pikiran dan sistem nilai yang saya yakini telah berkali-kali dibongkar dan disusun kembali. Dunia ideal, bagi saya kini, cuma selaput tipis di kaki langit yang terus menjauh saban kita mendekatinya. Yang ada hanyalah dunia ini, beserta hidup yang bergulir terus, terus, di dalamnya.
Namun, seandainya obrolan kami terulang, saya takkan berbantah-bantahan lagi dengannya. Ia boleh coba-coba menjejalkan kegawatan jenis apa pun, dan saya bakal mengingatkannya kepada kegembiraan-kegembiraan kecil yang kami miliki bersama.
Saya akan membicarakan penampilannya dalam liga sepakbola antar kelas bertahun-tahun lalu, di mana dia bermain seperti Ronaldinho dan berpakaian seperti kue jongkong; atau membicarakan kawan kami Komarudin, yang kelewat memuliakan tamu sampai-sampai ada ungkapan kekal dalam lingkar pergaulan kami, “Memangnya ini rumah Komar, hah?” buat memperingatkan manusia-manusia yang melampaui batas dalam bicara kotor atau menggasak isi kulkas kala bertamu.
Saya tak membenci, apa lagi memusuhi, narasi-narasi besar. Di kantor, tempat saya menghabiskan sebagian besar waktu, ada banyak tukang capruk kelas pagi-ketemu-pagi dan kami membahas urusan-urusan itu hampir setiap hari. Yang saya hendak elakkan cuma parasit yang kerap menempel di punggung topik-topik besar itu, ialah pembicaraan tentang dunia ideal.
Dunia ideal bisa berwujud apa saja: surga, negara teokratik, masyarakat tanpa kelas, komune mualaf Richard Dawkins sedunia, alam raya yang terbuat dari kue apem. Apa saja, selama ia menjanjikan kehidupan yang lebih baik, bukan dunia yang kita diami saat ini, dan tak bercacat bagi orang-orang yang mengidamkannya.
Menjelang saya naik ke kelas dua SMA, ibu dan adik saya pindah ke rumah Nenek, di kota lain, sementara saya tinggal dan dititipkan di rumah kawan lama Ayah. Para kerabat tak bosan-bosannya mengingatkan lewat telepon agar saya sering-sering menengok ke belakang saat berjalan. Barangkali seseorang menghunus badik atau bersiap melemparkan telur berisi air keras, kata mereka. Saya tak boleh pergi selain buat berangkat dan pulang sekolah, yang jaraknya kurang dari setengah kilometer dari rumah tumpangan. Tiap sore, saya hanya telentang di kasur sambil menonton awan-awan bergeser di balik jendela.
Merasa ancaman ada di mana-mana, saya mudah marah dan sukar tertawa. Saya meninju jidat kawan sekelas yang menjadikan saya bahan olok-olok. Padahal dia orang yang ceria dan lumayan lucu, dan bapaknya tukang bakso. Dalam situasi lain, saya yakin kami bakal terpingkal bersama.
Bertahun-tahun kemudian saya baru sadar bahwa saat itu pun sebenarnya hidup tak melulu buram. Keluarga yang menampung saya, Bapak dan Ibu Robani beserta anak-anak mereka, mengasihi saya seperti darah-daging mereka sendiri. Kawan-kawan dekat, termasuk orang yang saya ceritakan di awal, mencurahkan perhatian tulus dengan cara mereka masing-masing. Pacar... baiklah, tak ada pacar, tapi beberapa teman perempuan bilang saya adalah murid laki-laki paling tampan di kelas kami. Dilihat dari sisi mana pun, itu pujian yang mewah buat seorang remaja murung yang kegemukan.
Saya terlambat menyadari keselamatan-keselamatan dalam hari-hari penuh ancaman itu karena pikiran saya terancang buat menganggap situasi yang semestinya adalah situasi di mana “segalanya baik-baik saja.” Itulah pikiran optimistik, yang selalu tak siap kecewa.
Optimisme lahir dari keputusasaan. Para optimis menghendaki dunia di mana segalanya baik, dunia yang ideal, yang naif, yang tak ada, sebab mereka tak kuasa mengalihkan fokus dari mala. Pada akhirnya, angan-angan yang sia-sia itu mencekik mereka.
Dunia ini, yang tak suci dari kejahatan dan bencana, kasak-kusuk dan pengkhianatan, memang bukan le meilleur des mondes possibles atau “dunia terbaik dari semua dunia yang mungkin”. Namun, dunia juga bukan kakus mampat. Setiap saat, puas dan kecewa menantikan kita, berdampingan. Suka dan dukacita, baik dan buruk, elok dan teruk, juga apa-apa yang berada di antara mereka, senantiasa mengisi kehidupan kita yang bakal retak dan tak perlu diabadi-abadikan ini.
Tidak ada bukti faktual bahwa dunia bertujuan, dan kita tinggal di dalamnya tanpa pernah meneken kontrak tanda setuju. Namun, kita bisa menikmatinya sebagaimana adanya. Kita dapat bersandar pada banyak alasan dan berkata, tanpa berteriak, bahwa hidup ini layak dijalani: musik, sepakbola, humor, belas kasih, cinta.... Dan dari pemahaman yang demikian, harapan bisa terus lahir.

Hari-hari ini kita takut dan sedih dan marah lantaran serangan-serangan keji para teroris. Jelas, mereka bersalah pada kemanusiaan dan patut dihukum seberat-beratnya. Jelas pula bahwa perbuatan serupa jangan sampai terulang, sehingga negara tak boleh asal gebah dan gebuk dan malah memberikan alasan bagi ISIS buat menerjang kita. Banyak hal terang-benderang, atau setidaknya kita kira demikian. Tetapi kita heran, dan mungkin akan selamanya heran: “Pikiran macam apa dalam kepala seorang ibu yang memaksa putrinya, berumur 9 tahun, ikut meledakkan diri dan orang-orang yang tak bersalah kepada mereka?”
Emil Cioran, salah satu penulis filsafat paling menggugah di abad ke-20, pernah mengatakan: tak ada yang bunuh diri kecuali orang-orang optimis.
Saya kira, Puji Kuswati sama seperti kebanyakan ibu di dunia ini dalam satu perkara: dia menghendaki yang terbaik buat anaknya. Dia ingin si anak berada dalam situasi di mana segalanya sempurna. Dia mencari yang ideal, yang tak ada, dengan cara yang dianggapnya paling jitu dan masuk akal.
Yang masuk dan tak masuk bagi akal Puji boleh jadi berbeda, sehingga apa-apa yang dia lakukan pada 13 Mei pun berbeda, andaikan dia tak putus asa terhadap dunia ini.
Kalau tak putus asa, dia pun bisa mengingat perasaan-perasaannya ketika mendengar kata pertama yang diucapkan putrinya; ketika tahu bahwa dirinya mengandung; ketika jatuh cinta buat pertama kali; dan ketika dia, dengan muka berlumuran bedak, bermain lompat tali dengan kawan-kawannya di teras rumah, sementara ibunya berseru-seru dari dalam: “Hati-hati, Nak, hati-hati, jangan sampai jatuh!” dan bersandar pada semua itu, menyadari bahwa hidup begitu indah dan hanya itu yang dia punya.
Editor: Maulida Sri Handayani
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id