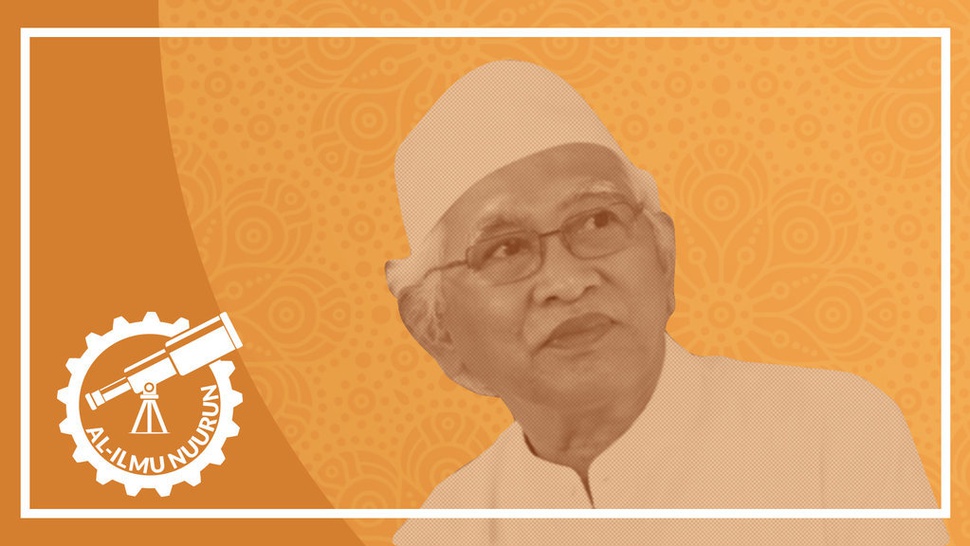tirto.id - Di halaman rumahnya, para petani itu disalaminya satu demi satu. Pria berwajah cerah dengan rambut lunas memutih itu menjabat erat dan menatap mereka dengan tajam. Ada keharuan. Ada air mata. Juga barangkali ada doa yang dinudubkan di sana.
Begitulah Ahmad Mustofa Bisri yang karib disapa Gus Mus melepas petani-petani Kendeng yang hendak menyuarakan aspirasi ke ibu kota. “Tetaplah melawan dengan kesederhanaan,” demikian pesan Gus Mus.
Sebaris kalimat yang diutarakan Gus Mus barangkali merupakan rumus hidup dan perjuangan yang digamitnya sepanjang hayat. Pria kelahiran Rembang, 10 Agustus 1944 ini memang istikamah melakukan perlawanan-perlawanan dengan cara yang sederhana namun indah.
Malah urusan keindahan, Gus Mus adalah jagonya. Ia acap menggunakan bermacam-macam media untuk menyampaikan kegusaran, kegelisahan, aspirasi, dan gugatan kepada nilai-nilai yang mengingkari kemanusiaan—temasuk yang dilakukan penguasa.
Abdul Munir Mulkhan, cendekiawan Muslim terkemuka dan guru besar UIN Yogyakarta, menggambarkan Gus Mus sebagai sosok yang visioner dan mampu meracik kepiawaian seorang sarjana agama dengan intuisi seorang penyair. Bagi Mulkhan, seperti diungkapkannya dalam buku kumpulan tulisan sahabat-sahabat Gus Mus, Gus Mus: Satu Rumah Seribu Pintu (2009), senarai karya-karya Gus Mus meninggalkan jejak yang tidak bisa dipandang kecil bagi perkembangan sastra Indonesia modern (hlm. 243).
Emha Ainun Nadjib, Cak Nun, dalam sebuah artikelnya bertajuk "Air Zam-zam di negeri Comberan" (2009) mengatakan, “sesungguhnya Gus Mus adalah seorang Al-Mufti. Hanya saja beliau terlalu rendah hati. Sekurang-kurangnya Al-Mufti adalah kwalitas dan maqam beliau. Dan kalau beliau hampir tidak pernah menduduki kursi itu dan tidak ‘nyuwuk’ fatwa apa-apa kepada bangsa dan ummat yang tidak mengerti kegelapan (apalagi cahaya) ini, kita orang dusun tahunya barangkali memang beliau tidak memperoleh ‘wangsit’ untuk berfatwa. Allah sendiri menerapkan sifat As-Shobur kepada bangsa Indonesia, Gus Mus nginthil di belakang-Nya.”
Gus Mus lahir dan berkembang dari rahim pesantren. Putra kedua dari sosok ayah berjuluk singa podium dan intelektual pesantren yang prolifik: K.H. Bisri Mustofa, penganggit kitab tafsir makna pegon Al-Ibriz yang sangat fenomenal itu. Namanya, Ahmad Mustofa Bisri, merupakan tafaulan-epigonik dari nama ayahnya yang dibalik. Jadi jika diurut, alur silsilahnya seperti ini: Bisri Mustofa memiliki anak Mustofa Bisri dan memiliki cucu Bisri Mustofa (putra bungsu Gus Mus).
“Nama ayah Anda Bisri Mustofa. Nama anda Mustofa Bisri. Tinggal di Jalan Bisri Mustofa. Ini keluarga, kok, ndak kreatif kalau bikin nama,” demikian kelakar Andy F. Noya dalam acara Kick Andy beberapa tahun silam.
Demi menghindari anggapan membebek dan bernaung pada kebesaran nama orang tua, Gus Mus kerap mengubah dan membuat nama pena untuk dirinya. Slamet Effendy Yusuf, mantan Ketua Umum GP Ansor, kala menjadi redaktur Arena—sebuah majalah mahasiswa yang bermarkas di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta—pada 1974, memberi kesaksian bahwa pihaknya kerap menerima kiriman karya dari penulis bernama M. Ustov Abisri.
Pada pertengahan 1970 sampai 1980-an, Gus Mus kerap menggunakan nama pena itu, M. Ustov Abisri, untuk menulis di pelbagai media massa seperti Intisari dan Warta Nahdlatul Ulama.
Setelah menamatkan sekolah di MHM (Madrasah Hidayatul Mubtadiin) Pesantren Lirboyo, Kediri, Gus Mus muda melanjutkan kuliah ke Universitas Al-Azhar, Kairo. Di kampus itu, Gus Mus diterima di program studi Keislaman dan Bahasa Arab. Pada waktu berada di Mesir itulah ia menjalin hubungan yang karib dengan Gus Dur. Keduanya bak tumbu ketemu tutup: saling melengkapi.
Banyak cita-cita dan gagasan besar yang dirancang bangun oleh keduanya, termasuk gagasan Gus Dur tentang rencana pulang ke tanah air berdua dengan Gus Mus menggunakan jalur darat via Eropa. Tujuannya untuk silaturahim, menghimpun kekuatan, menyerap energi dan gagasan dari anak-anak muda Indonesia yang sedang studi di belahan bumi Eropa.
Gagasan itu tidak pernah terwujud karena di waktu bersamaan, Gus Mus harus menemani ibunda untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci. “Dahulukan Ibu sampean. Kita nanti ketemu di tanah air,” demikian tulis Gus Dur dalam sepucuk suratnya sepada Gus Mus.
Puisi Balsem
Puisi-puisi Gus Mus dikenal tajam dan menyentil. Bukan saja urusan sosial-politik, Gus Mus juga kerap mengkritik dan menyindir tingkah polah beragama masyarakat luas. Dalam syair bertajuk "Keluhan", sebuah syair yang hanya berisi satu larik kalimat, Gus menulis: "Tuhan, Kami Sangat Sibuk."
Ini adalah tamparan yang luar biasa bagi siapapun yang diam-diam menomorsatukan urusan selain Tuhan. Barangkali inilah awal mula lahirnya berhala-berhala baru yang belakangan oleh banyak kalangan disebut sebagai zaman ultrajahiliyah, di mana kebodohan menjadi sedemikian murakab dan berkuadrat.
Gus Mus merupakan satu di antara sedikit orang yang berani mengkritik pemerintah Orde Baru. Kala rezim itu masih kokoh berdiri, Gus Mus kerap melancarkan serangkaian kritik sosial lewat sajak.
Puisi-puisi Gus Mus kemudian hari dikenal sebagai puisi balsem. Mengapa balsem? Sebab balsem itu, meski panas, memiliki khasiat untuk mengobati. Maka, kritik-kritik sosial Gus Mus dalam pelbagai puisinya, walaupun menohok, diandaikan tetap menyegarkan dan mencerahkan.
Dalam puisi yang sangat populer dan secara vulgar dan terang-terangan menyerang Orde Baru bertajuk "Kau Ini Bagaimana", Gus Mus menulis: "Kau bilang kritiklah//Aku kritik kau marah//Kau bilang carikan alternatifnya//Aku kasih alternatif kau bilang jangan mendikte saja".
Menurut D. Zawawi Imron, puisi-puisi Gus Mus menelanjangi Orde Baru tanpa tabir, tanpa tedheng aling-aling.
Pada puisi lainnya, misalnya yang berjudul "Negeri Amplop", Gus Mus mengkritik keras praktik budaya culas yang merajalela kala itu, bahkan sampai sekarang. Gus Mus menulis: "Amplop – amplop menguasai penguasa//dan mengendalikan orang – orang biasa//amplop amplop membeberkan dan menyembunyikan//mencairkan dan membekukan//mengganjal dan melicinkan//Orang bicara bisa bisu//Orang mendengar bisa tuli//Orang alim bisa nafsu//Orang sakti bisa mati//Di negeri amplop, amplop – amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja."
Sekali tempo di zaman Orde Baru, Gus Mus juga secara terang-terangan mengkritik pelaksanaan nilai-nilai Pancasila ala Soeharto. Bagi Gus Mus, Pancasila yang berhenti pada tataran slogan tanpa pengamalan dan kehadiran nyata bagi kehidupan setiap warga negara sama belaka dengan pepesan kosong.
Dalam puisi bertajuk "Mantraku, Mantra Sakti", Gus Mus menulis: "Mantraku tak sembarang matra//aji-ajiku sakti tak terkira//Tak jin tak peri boleh dicoba sendiri//Dor!//Hidup Ketuhahan yang Mahaesa//Dor! Dor!//Hidup Kemanusiaan yang Adil dan Beradab//Dor!Dor! Dor!// Hidup Persatuan Indonesia// Dor! Dor! Dor! Dor!// Hidup Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan// Dor! Dor! Dor! Dor! Dor!// Hidup keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia//Dor!// Dor!// Dor!// Hidup Pancasila// Dor!// Dor!"

Menjadi Manusia Utuh
Selain melalui puisi, Gus Mus juga menuangkan kritik-kritiknya melalui lukisan. Pada 2003, ia membuat lukisan bertajuk “Berzikir Bersama Inul”. Dalam lukisan tersebut digambarkan seorang perempuan sedang menjogetkan diri dan kegembirannya di tengah-tengah lelaki bersorban dan bergamis—lazimnya pakaian agamawan dan kiai—yang sedang berzikir.
Ketika ramai-ramai khalayak mencecar Gus Mus dan menganggap lukisan tersebut sebagai lukisan yang kontroversial dan merobohkan sakralitas dan kredibilitas ulama, Gus Mus mengatakan bahwa lukisan tersebut merupakan kritik atas budaya-budaya materialisme yang sudah sangat mendarah daging di masyarakat kita.
Menurut Gus Mus, seperti diungkap F.X. Rudi Gunawan dalam Mengebor Kemunafikan: Inul, Seks dan Kekuasaan (2003), pada masyarakat kedagingan agama yang sesungguhnya berdimensi ruhaniah dan spiritualitas acap kali dicampuradukkan dengan hal-hal yang duniawi. Bagi masyarakat kedagingan, yang-profan dibaurkan dengan yang-sakral (hlm. 51).
Bahkan Gus Mus mengatakan kepada Koran Tempo (4/5/2003), “ini—kondisi ribut-ribut soal inul—membuktikan tesis saya bahwa perhatian bangsa kita masih pada daging, tidak pada ruh dan jiwa. Gegeran ini berkisar soal daging.”
Pada akhirnya, sebagaimana yang kerap dipesankan Gus Mus di banyak kesempatan, bahwa tugas manusia adalah tetap menjadi manusia, mencoba memahami dan mengerti manusia, dan memanusiakan manusia. Sebuah gagasan dan visi paripurna yang juga pernah digaungkan Multatuli dalam Max Havelaar: "tugas manusia adalah menjadi manusia."
====================
Sepanjang Ramadan hingga lebaran, redaksi menyuguhkan artikel-artikel yang mengetengahkan pemikiran para cendekiawan dan pembaharu Muslim zaman Orde Baru dari berbagai spektrum ideologi. Kami percaya bahwa gagasan mereka bukan hanya mewarnai wacana keislaman, tapi juga memberi kontribusi penting bagi peradaban Islam Indonesia. Artikel-artikel tersebut ditayangkan dalam rubrik "Al-Ilmu Nuurun" atau "ilmu adalah cahaya".
Editor: Ivan Aulia Ahsan