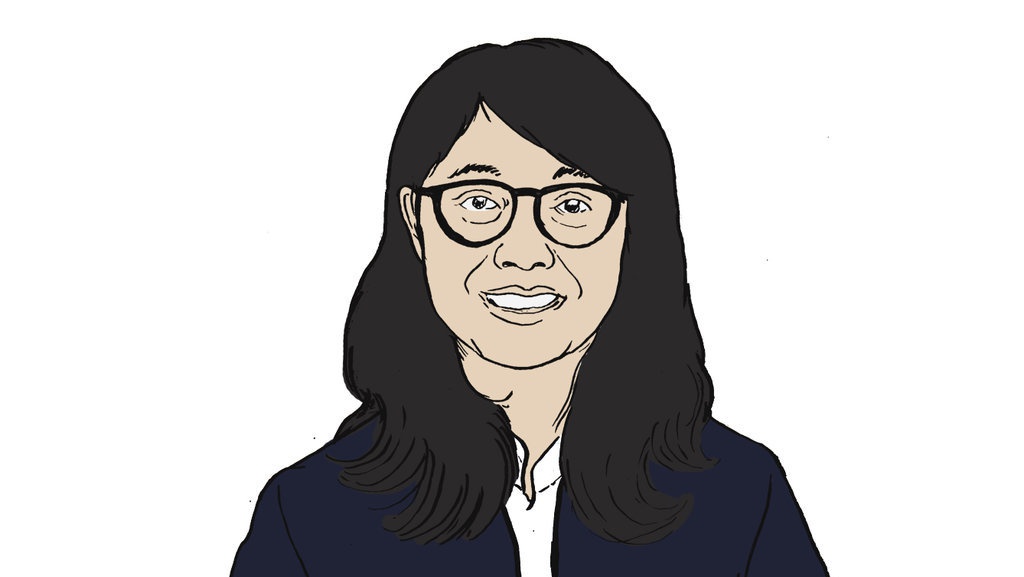tirto.id - Ketika proses penghitungan suara selesai, ada kemenangan kecil yang patut dirayakan aktivis perempuan: meningkatnya jumlah perempuan yang lolos ke DPR RI dari 17,3% pada Pemilu 2014 menjadi 20,4% pada Pemilu 2019. Wajar bila banyak feminis berharap peluang untuk mendorong kebijakan yang lebih sensitif gender akan semakin terbuka lebar seiring dengan peningkatan jumlah representasi perempuan di jajaran pembuat kebijakan.
Namun, tak semua anggota parlemen yang terpilih secara tegas memiliki perspektif gender, beberapa bahkan menyatakan diri mereka anti-feminis. Watak patriarkal di partai politik Indonesia dan pergeseran masyarakat ke arah yang lebih konservatif, menambah rintangan dalam advokasi kebijakan gender yang lebih progresif. Maka, meningkatnya jumlah perolehan kursi perempuan di DPR-RI menjadi indikator yang terlampau sederhana untuk mengukur kesuksesan gerakan perempuan. Diskusi akan lebih produktif bila kita berfokus pada potensi dan peluang yang mungkin dimanfaatkan oleh anggota legislatif perempuan yang akan bekerja selama lima tahun ke depan dalam konteks perumusan kebijakan yang jelas berpihak pada perempuan.
Selain kerja-kerja di parlemen, kita juga perlu memberi perhatian pada prospek dan tantangan para feminis di luar parlemen dalam mengampanyekan kebijakan yang pro-kesetaraan gender, serta melawan melawan narasi yang semakin kencang digaungkan sejumlah kelompok konservatif. Saya bertemu beberapa aktivis dari berbagai latar belakang untuk mendengar refleksi mereka tentang gerakan perempuan di Indonesia. Di akhir percakapan, saya sulit menghindari kesimpulan pahit bahwa gerakan feminis Indonesia sekarang relatif rapuh: walau jumlah individu dan yang mengaku sebagai feminis bertambah, gerakan ini kurang solid dan memiliki masalah dalam melibatkan individu dan komunitas akar rumput. Bila kondisi tersebut terus berlarut, keberlanjutan dan potensi dampak yang bisa diciptakan oleh gerakan perempuan di tanah air dalam bahaya. Pegiat hak-hak perempuan perlu mengatasi persoalan tersebut untuk meredam narasi kelompok konservatif.
Feminisme dan Kegelisahannya
Feminisme di Indonesia mengadopsi beragam pendekatan—liberal, radikal, dan interseksional, dan lainnya—sebagai pendekatan untuk melihat sejumlah isu, termasuk hak atas tanah, hak pilih, perlindungan pekerja dan perlindungan dari kekerasan seksual. Namun, pertumbuhan pesat aktivisme feminis di ruang digital menciptakan kesan bahwa gerakan feminis di Indonesia bersifat tunggal. Kelompok konservatif membuat asumsi bahwa gerakan feminisme hanya membela nilai-nilai “liberal”, seperti otonomi tubuh dan hak-hak kelompok minoritas seksual. Hal ini berbeda dengan kenyataan bahwa feminisme sangat beragam bahkan melampaui batasan-batasan yang ada, termasuk interpretasi feminisme berdasarkan pendekatan Islam.
Perkembangan pesat feminisme Indonesia belakangan tidak lain ditopang oleh suksesnya aktivisme digital yang sangat berperan dalam memperkenalkan narasi gender dan feminisme. Pencapaian tersebut menjadi tanda kemajuan yang menjanjikan untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Tidak sedikit feminis muda aktif di dunia maya, berpendidikan tinggi dan terkonseksi dengan jaringan feminis global. Mereka memahami kekuatan media sosial sebagai alat yang efektif untuk memberi edukasi, melibatkan dan memobilisasi pengikut mereka.
Kampanye global “Women’s March” dan #MeToo turut mendorong para feminis muda Indonesia untuk membangun aliansi dan menarik dukungan khalayak secara masif. Pada akhir April 2019 lalu, jumlah partisipan dalam “Women’s March” di Jakarta mencapai 4.000 orang, atau dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Para aktivis memanfaatkan momentum tersebut untuk mendesak DPR RI mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Feminis kawakan Dhyta Caturani menyampaikan kepada saya,
“Ini gerakan feminis terbesar di Indonesia, yang belum pernah saya lihat selama 25 tahun berada dalam perjuangan ini. Ada banyak orang, individu maupun kelompokyang belakangan mau memproklamirkan diri sebagai feminis. Ketika saya aktif di One Billion Rising [salah satu kampanye global anti kekerasan seksual terhadap perempuan] tahun 2013, banyak yang merasa kurang nyaman dengan istilah ‘feminisme’. Tapi sekarang sudah berubah.”
Sejumlah inisiatif online bermunculan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kebutuhan informasi seputar feminisme. Didirikan pada 2013, Magdalene adalah majalah feminisme digital yang menyediakan ruang bagi feminis muda untuk berbagi pengalaman pribadi dan opini tentang kondisi sosial-politik Indonesia dan dampaknya bagi kehidupan mereka masing-masing. Magdalene menerbitkan artikel pendek, wawancara, dan kini menambah variasi produk publikasi mereka dalam bentuk podcast. Setiap bulan, rata-rata jumlah pengunjung laman Magdalene bisa mencapai 150.000. Selain itu, semakin banyak inisiatif-inisiatif kecil yang juga bertumbuh dan bergerak di platform online untuk memperkenalkan konsep-konsep feminis kepada kaum muda Indonesia, seperti Jakarta Feminist Dicussion Group, Indonesia Feminis, Konde.co, dan lain-lain.
Bersamaan dengan itu, gerakan feminis muslim juga terus berkembang, menjadikannya sebuah ruang yang penting untuk memperluas jaringan akar rumput dalam mencapai keadilan gender. Pada 2017, tiga organisasi muslim yakni Alimat, Rahimah, dan Fahmina (ARAFAH) memprakarsai Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon, Jawa Barat, dan berhasil mempertemukan sekitar 2.000 ulama dan akademisi dari berbagai penjuru Indonesia. Forum tersebut menjadi bukti penting bahwa kesetaraan gender adalah bagian integral dan terus hidup dalam ajaran Islam, berbeda dari asumsi kelompok konservatif tentang posisi perempuan dalam hierarki agama. Hasil kongres mengecam keras tiga persoalan utama: kekerasan seksual, pernikahan anak, dan degradasi lingkungan. Tak berhenti di kongres, para ulama juga menyebarkan amanat kongres di lingkaran pengajian masing-masing dan dalam kampanye advokasi kebijakan publik, termasuk RUU P-KS.
Anak muda yang peduli dengan isu keadilan gender dapat membaca tulisan-tulisan individu kritis seperti Kalis Mardiasih, seorang kolumnis dengan latar pendidikan pesantren, dan Laily Fitry, kandidat doktor di bidang teologi. Lebih jauh, inisiatif kecil berbasis komunitas juga terus tumbuh, seperti Forum Islam Progresif—organisasi berbasis pemikiran kiri ikut memfasilitasi pertukaran gagasan dan pendapat mengenai feminisme dan Islam, dan Halaqah Muslim Progresif—forum diskusi daring yang berfokus pada persoalan di seputar isu gender dan Islam. Kedua inisiatif tersebut berupaya menjangkau pelajar dan anak muda di seluruh Indonesia melalui Instagram—platform media sosial paling populer di Indonesia. Naila Fitria, pencetus Halaqah Muslimah Progresif, mengatakan:
“Kami ingin melawan dan menyeimbangkan narasi 'hijrah' yang ditawarkan kaum muslim konservatif. Itu memuakkan. Mereka menggunakan agama sebagai argumen utama mereka. Oleh karena itu, kami tidak dapat menggunakan argumen feminis sekuler untuk melawan kampanye masif mereka. Kita perlu membuat tafsir ulang yang menonjolkan nilai-nilai pro-perempuan dalam ajaran agama untuk bisa menghalau narasi mereka.”
Keretakan Gerakan Feminis
Berbeda dengan gerakan konservatif yang memiliki narasi padu dalam mempromosikan narasi keagamaannya, kelompok feminis yang bergulat dengan berbagai bentuk penindasan, kerap membuat kampanye yang cederung reaktif ketika menanggapi kebijakan tertentu. Seperti yang dikatakan Dhyta Caturani:
"Gerakan feminis di Indonesia tercerai berai, dan itu adalah kerugian di kita. [Kaum konservatif] itu solid; kita tidak. Masing-masing kerja kita sebenarnya saling melengkapi tetapi tidak dijahit dengan baik. Sementara gerakan mereka memiliki satu jangkar, gerakan feminisme berjuang di berbagai isu. Kita tidak memiliki solusi tunggal untuk mengatasi berbagai permasalahan.
Beragamnya bentuk feminisme seringkali menyebabkan ketidaksepakatan dalam menanggapi sejumlah isu, bahkan dapat memukul mundur perjuangan kaum feminis. Mulai dari isu terkait seksualitas perempuan, hingga isu perjuangan petani perempuan dan perempuan muslim. Kasus pertama terjadi pada Maret 2019 ketika seorang atlet bulu tangkis Jonathan “Jojo” Christie menanggalkan pakaiannya setelah memenangkan medali emas. Reaksi publik yang menggila, terutama kalangan perempuan, memicu perdebatan tentang seksualitas perempuan; apakah ini bentuk ekspresi seksual atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh kelompok perempuan sendiri? Tak bisa dipungkiri, perdebatan tersebut berimplikasi pada kontra-produktifnya gerakan kesetaraan gender di Indonesia.
Perdebatan lain yang lebih fundamental berkaitan dengan kelas sosial dan agama. Dhyta Caturani mengatakan bahwa masih ada sekelompok feminis yang menganggap perjuangan petani dan buruh perempuan tidak sepenuhnya bagian dari gerakan feminis karena mereka kerap menjadi korban budaya patriarki di rumah. Perdebatan lain terjadi pada kasus di bulan Maret tahun lalu terkait pelarangan niqab di kampus. Perdebatan ini memancing kontroversi antara mereka yang melihat niqab sebagai pilihan perempuan, dan mereka menganggapnya sebagai bentuk penindasan. Tidak hanya menyebabkan kebingungan publik tentang gerakan feminis, perselisihan pendapat menciptakan keretakan dalam gerakan feminisme itu sendiri.
Pendekatan yang berbeda terhadap feminisme menyebabkan strategi yang juga berbeda untuk menarik simpati dan dukungan publik. Sebagai ilustrasi, feminis muslim lebih memilih istilah “keadilan gender” dibandingkan “kesetaraan gender” dan “feminisme” karena istilah adil gender dianggap lebih dekat dengan nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam. Seperti yang dikatakan Naila Fitria:
“Feminis muslim menggunakan kosakata yang lebih halus untuk bisa diterima masyarakat. Sebagai contoh, saya menggunakan istilah “keadilan gender”, bukan kesetaraan gender, karena lebih aman, terutama jika peserta laki-laki hadir dalam pengajian. Mereka akan protes karena jelas tertulis dalam Al-Quran bahwa pria dan wanita tidak setara. Makanya, saya menyatakan diri saya seorang feminis muslim. Jika saya mengatakan saya seorang feminis, mereka tidak akan menerima saya."

Berbeda dengan pendekatan yang diadopsi feminis muslim, kelompok lain melawan praktik diskriminatif terhadap perempuan dengan konfrontasi langsung. Misalnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan kampanye anti-poligami. Beberapa aktivis hak-hak perempuan mengkritisi strategi PSI, yang dianggap dapat membahayakan kerja advokasi para feminis muslim selama bertahun-tahun. Komisaris Komnas Perempuan, Masruchah, berpendapat:
"Sebagian besar dari kami setuju dengan sikap PSI, tetapi kampanye anti-poligami? Jangan gunakan itu! Kita perlu melihat ini sebagai gerakan kolektif, dan menyadari konsekuensi dari tiap pendekatan yang kita ambil. Jika Anda ingin menolak praktik poligami, bidik UU Perkawinan. Ada banyak bentuk kekerasan berbasis gender, tetapi jika Anda langsung ke isu poligami, Anda bisa dianggap menyerang beberapa kelompok. Ini persoalan strategi."
Sementara kelompok konservatif menggunakan dalih agama dalam menyebarkan pesan mereka, kaum feminis dapat menggunakan strategi yang tak jauh berbeda melalui reinterpretasi dan rekontekstualisasi untuk mengajak masyarakat luas. Sejauh ini, apakah strategi kaum feminis sudah cukup berhasil dalam menjangkau masyarakat luas?
Apakah Gerakan Feminis Indonesia Terlalu Elitis?
Setelah versi terjemahan artikel saya tentang politik anti-feminis muncul di Tirto.id, Aliansi Cinta Keluarga (AILA) mengkritik melontarkan kritik karena artikel ini dianggap mencerminkan feminisme elite yang hanya menguntungkan segelintir orang yang hidup di perkotaan dan mengenyam pendidikan barat. AILA mengatakan, "... Ini yang selalu saya katakan, di mana-mana, bahwa feminisme bukan tentang perempuan, apalagi berjuang untuk kehidupan perempuan. Ini bukan gerakan perempuan, tetapi gerakan eliteperempuan.”
Beberapa aktivis perempuan yang saya temui setuju dengan kritik tersebut. Dhyta Caturani mengatakan:
“Ini adalah kritik saya terhadap gerakan feminis Indonesia. Sebagian besar feminis liberal berasal dari latar belakang perkotaan dan kelas menengah. Mereka memiliki privilese untuk mengakses banyak hal, seperti referensi bacaan feminis dalam bahasa Inggris. Apa upaya mereka untuk mendobrak dinding itu? Apakah interseksionalitas, jargon kita, sudah diterapkan dalam gerakan kita? Ya, tapi hanya oleh segelintir dari kita melakukannya."
Naila Fitria setuju bahwa kaum feminis perlu bekerja ekstra di tingkat akar rumput untuk melawan gerakan konservatif. Dia berkata, “Jika Anda menyebarkan gagasan Anda sebatas di kalangan kelas menengah, Anda akan terus menjadi minoritas. Kaum intelektual harus [terlibat] di akar rumput. Memang melelahkan, dan membutuhkan kerja ekstra, tapi itulah yang mereka [konservatif] lakukan hari ini. "
Pandangan bahwa gerakan feminis mutlak bersifat elitis tentu mengabaikan aktivisme bertahun-tahun yang dikerahkan organisasi-organisasi feminis akar rumput untuk menciptakan perubahan dari bawah. Koalisi Perempuan Indonesia, misalnya, berupaya menyediakan pendidikan kepemimpinan bagi perempuan. Migrant Care tak berhenti melakukan advokasi untuk pekerja migran Indonesia. Lalu PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) aktif melibatkan pekerja perempuan. Organisasi berbasis keagamaan, seperti Fatayat NU dan Aisyiyah Muhammadiyah sejak lama bekerja di isu pemberdayaan perempuan.
Namun, gerakan feminis memang memiliki kecenderungan elitis, dengan banyaknya penggunaan jargon dan privilese. Sebagian besar feminis Indonesia hari ini memiliki latar belakang yang nyaris seragam: kelas menengah, berpendidikan tinggi (mungkin) dari luar negeri, dan fasih berbahasa Inggris, yang memudahkan mereka mengakses lebih banyak literatur feminis. Tidak banyak dari mereka yang memiliki pengalaman bekerja di tingkat akar rumput, sementara perempuan di tingkat akar rumput rentan terhadap kampanye kelompok konservatif yang secara agresif menyasar anggota jaringan kelompok progresif supaya berbalik arah dan menjadi anggota mereka. Di tengah situasi tersebut, kaum feminis perlu lebih terlibat dengan gerakan-gerakan akar rumput untuk mencegah pergeseran sikap anggota mereka yang sudah tergabung dalam jaringan feminis yang ada.
Keberhasilan meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR-RI tak lepas dari peran aktivis perempuan di belakang layar. Kemajuan ini harus diakui. Namun, dalam periode kedua Jokowi, feminis dan aktivis perempuan perlu lebih baik mengorganisir gerakan untuk menghadapi tantangan di depan mata. Kaum feminis harus lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya, membangun jembatan dengan "lawan", dan berkoalisi dengan gerakan-gerakan lain untuk mencegah kemunduran gerakan feminis di Indonesia.
------------
Sebelum diterjemahkan oleh Levriana Yustriani, tulisan ini terbit dalam bahasa Inggris di New Mandala dengan judul "The post-election challenges for Indonesia’s feminist movement". Penulisnya, Dyah Ayu Kartika (Kathy), adalah peneliti pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD Paramadina), Jakarta. Selama Pemilu 2019, ia menjadi New Mandala Indonesia Correspondent Fellow yang menulis isu gender.
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id