tirto.id - Pada Het Nieuws van den Dagedisi 28 Oktober 1938, dalam himpitan berita proyek pembangunan waduk Darma dan potret gagah Wakil Presiden Dewan Hindia, ada berita mungil di pojokan: empat pribumi baru saja mati.
Berita itu 25 kata saja. “Uit Kediri wordt geseind: In Srengat zijn zes Inheemschen na het gebruik van gaplek ziek geworden. Van hen zijn twee kinderen en twee volwassenen overleden”.
Diterjemahkan secara kasar, warta tersebut berarti: “Dari Kediri dilaporkan: Di Srengat, enam pribumi jatuh sakit setelah menggunakan gaplek. Di antara mereka, dua orang anak dan dua orang dewasa telah meninggal.”
Kita tidak tahu siapa mereka, berapa umur mereka, atau apa hubungan darah mereka. Kita juga tidak tahu bagaimana nasib dua orang yang belum meninggal itu. Apakah mereka akhirnya selamat? Atau ikut mati keracunan beberapa waktu kemudian? Di zaman itu, kematian seorang pribumi bukan sebuah tragedi, tapi sekadar statistik. Koran hanya butuh angka, bukan nama.
Meskipun begitu, kita bisa yakin kalau keenamnya adalah kawula miskin. Kemungkinan besar petani gurem atau buruh tani. Status ekonomi mereka tersirat dalam olahan yang mereka konsumsi: gaplek, singkong yang dikeringkan selama beberapa hari di bawah sinar matahari agar tidak mudah basi. Pada 1938, hanya para petani miskin yang makan gaplek untuk asupan sehari-hari. Tanpa mereka ketahui, asupan itu ternyata membawa racun laten.
Sementara itu, pada bulan Mei di tahun yang sama, seorang pegawai Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) di Batavia baru saja mencoret satu komoditas ekspor berharga. Setelah permintaan yang terus menurun selama bertahun-tahun, komoditas itu akhirnya menuju sirna karena kalah saing dengan gandum Amerika Serikat. Pengirimannya tidak lagi menguntungkan para saudagar Hindia Belanda. Padahal, 10 tahun sebelumnya profit ekspor barang tersebut menyentuh nilai 14.780.000 gulden atau setara dengan Rp110 miliar hari ini.
Komoditas apa yang kiranya pegawai itu coret?
Gaplek.
Memeras Sari Pati Singkong
Gaplek als Grondstof voor de Bereiding van Cassavemeelatau Gaplek sebagai Bahan Baku Pembuatan Tepung Singkong adalah kitab mengenai gaplek yang terbit pada 1932. Ia menjelaskan semua hal mengenai gaplek, mulai dari tipenya, metode pengolahannya, hingga nilai dagangnya.
Di dalamnya, dikisahkan bahwa pada penghujung 1920-an, gaplek adalah primadona. Singkong kering ini digemari oleh berbagai negara di Eropa, mulai dari Belgia, Prancis, hingga negara-negara Skandinavia. Bukan orang-orang kulit putih yang ketagihan makan gaplek, melainkan sapi dan babi mereka. Para peternak Eropa menemukan kalau campuran barley, ampas jagung, dan tepung gaplek yang kaya pati adalah pakan ternak yang bernutrisi dan murah.
Lebih jauh lagi, para pengusaha dapat melipatgandakan harga produk mereka dengan mengekstrak tepung bebas gluten dari gaplek. Tepung berkualitas tinggi ini kita sebut sebagai tapioka.
Kegemaran terhadap tapioka meningkatkan permintaan dari Eropa. Hamburg bahkan membuat pabrik tapioka dengan bahan baku dari Jawa. Melihat potensi ini, para pebisnis berbondong-bondong menyuplai gaplek sebagai komoditas ekspor. Dengan sekejap terbentuklah ekosistem persaingan dagang yang memeras singkong sampai ke sari patinya: bukan gaplek, bukan pula tapioka, tetapi uang.
Sari pati itu tidak hanya membasahi kantong-kantong saudagar pelabuhan, tapi juga tangan-tangan petani tegalan. Sebelum bisnis gaplek meledak, singkong adalah komoditas yang kurang menggiurkan di tanah Jawa. Banyak bumiputra sekadar menanamnya sebagai bahan pangan cadangan ketika masa paceklik. Pada hari-hari biasa, petani tentu menanam padi, jagung, tebu, atau kopi.
Setelah gaplek laris, petak-petak sawah mulai dialihfungsikan menjadi tempat menanam singkong, khususnya di lahan-lahan kering. Tanah di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura ternyata menawarkan kondisi yang ideal. Wilayah ini pernah menjadi sebuah imperium gaplek walaupun pada rentang yang sangat singkat.
Contohnya, koran De Locomotief edisi 12 Juni 1928 memberitakan bahwa daerah Patuk di Gunung Kidul, Yogyakarta mampu menyuplai 10 ribu pikul gaplek ke wilayah tetangga, berat yang kurang lebih setara dengan 600 ribu kilogram. Satu kecamatan saja! Harganya pun murah meriah. Di Wonosari, satu pikul singkong bisa dibeli dengan 0,8 gulden. Jika transaksi ini kita cangkok secara kasar pada kondisi sekarang, dia sepadan dengan menghargai satu kilogram singkong dengan harga Rp100.
Namun, racun laten singkong diam-diam menyeruak ke permukaan: pasar jadi terlalu tergantung pada satu komoditas. Racun itu hanya butuh satu sumbu ledak dan dia akan menyeruak, membunuh seluruh rantai pasok dan orang-orang yang bekerja di dalamnya.
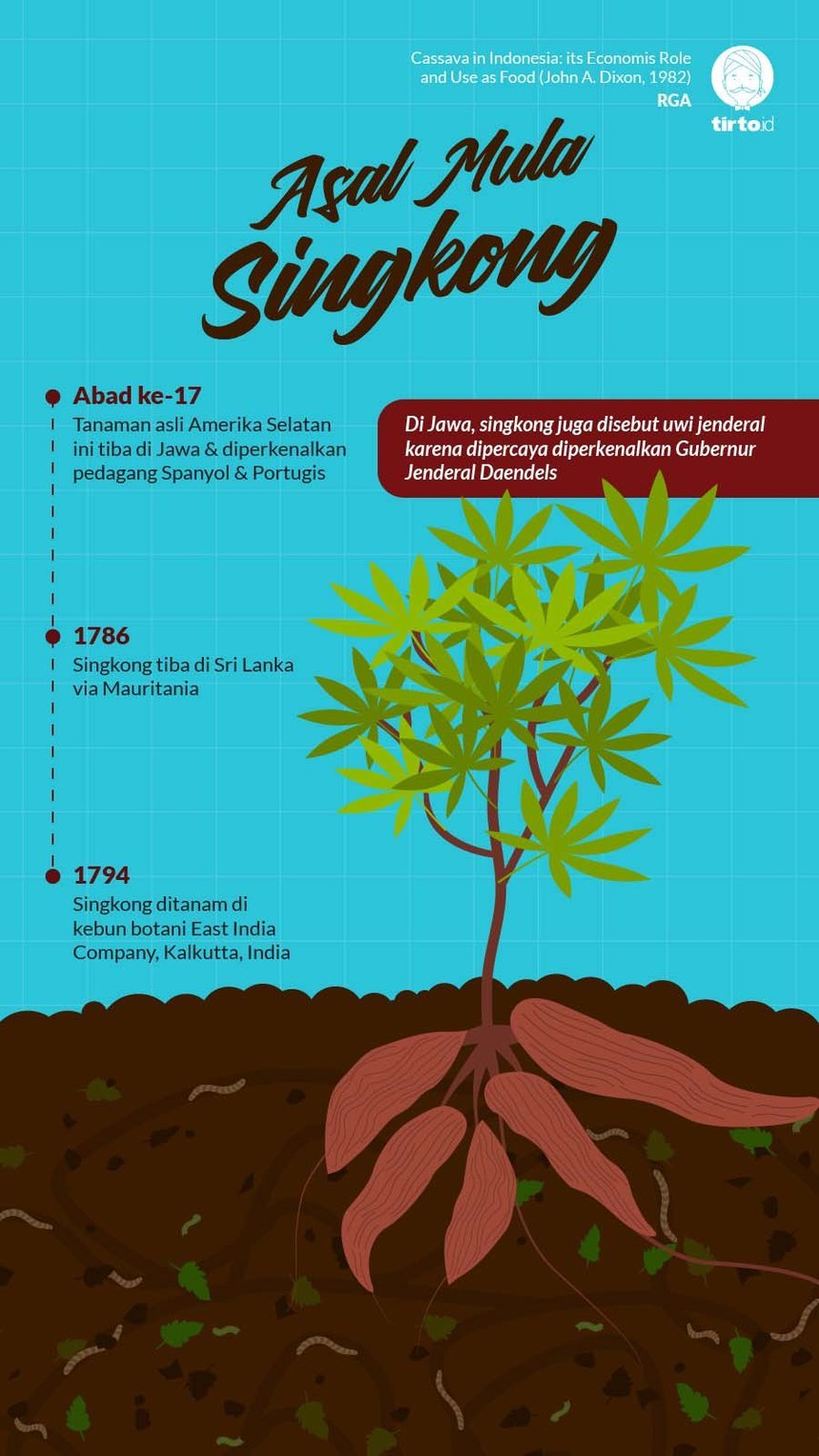
Gaplek-Misère Para Petani
Sumbu ledak menyala pada 1929, tepat satu tahun setelah ekspor gaplek tersukses dalam sejarah Hindia Belanda. Ledakan yang dihasilkannya pun bukan sekadar sentilan, tapi sebuah hantaman besar. Sebuah paceklik ekonomi berskala global. Orang-orang menamainya Depresi Besar, imbas jangka panjang dari Perang Dunia Pertama.
Tanpa daya beli, negara-negara Eropa menghentikan kegiatan impornya, sedangkan timbunan gaplek semakin menggunung di dalam lumbung. Tak ada kapal yang bersedia mengangkut mereka karena betapapun berharganya, komoditas tanpa pembeli adalah seonggok sampah. Akhirnya, gaplek yang terkenal berumur panjang pun membusuk.
Karena lanskap bisnis yang begitu tragis, para pengusaha gaplek sampai memberi periode ini sebuah nama: Gaplek-misère, derita gaplek. Istilah ini pertama kali tercatat pada surat kabar Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indiëedisi 29 September 1933.
Misère tersebut ditandai dengan penutupan tiga pabrik tapioka milik perusahaan Eropa pada 1933 yang waktu itu sudah memiliki sebuah perkebunan di Solo. Aset pabrik dilikuidasikan kepada para pemilik saham, sedangkan perkebunannya dikembalikan kepada pihak Keraton.
Tentu misère yang mereka maksud bukanlah derita para petani, melainkan para saudagar yang harus memutar otak untuk mencari komoditas lain yang masih layak dagang sembari makan nasi lengkap dengan lauk pauknya di meja makan setiap hari.
Sementara itu, misère yang dirasakan para petani benar-benar sebuah penderitaan antara hidup dan mati. Di lahan-lahan, singkong mendekam begitu saja. Tidak ada petani yang berani menjualnya. Mereka hanya akan membuang tenaga dan uang karena tidak ada pengusaha yang bersedia membeli singkong, semurah apapun harga yang mereka tawarkan.
Tanpa penjualan, para petani tak memiliki uang. Tanpa uang, mereka tak mampu membeli beras, sedangkan banyak di antara mereka sudah tak lagi menanam padi.
Akhirnya, beralihlah petani kepada tanah, lalu kepada matahari. Mereka mengonsumsi sebagian singkong yang mereka tanam, lalu mengeringkan sebagian lainnya menjadi gaplek untuk cadangan pangan selama masa paceklik yang ternyata berlangsung sampai satu dekade.
Selama satu dekade juga, para petani hanya bisa mengonsumsi gaplek yang makin lama disimpan makin jadi sekeras batu, dan kerap tanpa lauk tambahan. Semakin mereka bergantung pada gaplek sebagai bahan pangan pokok, semakin besar juga risiko yang mereka lahap ketika mengonsumsinya. Salah satu risikonya sudah dituliskan di awal, yaitu keracunan yang berakibat fatal.
Gaplek yang tidak diolah dengan tepat dapat mempertahankan racun yang secara alamiah ada di dalam singkong. Racun itu bernama linamarin, senyawa glukosida yang mengandung asam sianida.
Bercak biru di permukaan singkong merupakan tanda konsentrasi linamarin tinggi. Para petani yang cermat akan memilih umbi tanpa bercak biru. Pengolahan lebih lanjut akan memecahkan linamarin dan melenyapkan asam sianida. Namun, tak banyak petani yang dapat berpikir panjang tentang memilah dan mengolah makanan dengan tepat jika perut mereka sudah berhari-hari keroncongan.
Yang lebih marak lagi adalah kasus malnutrisi. Di Wonogiri misalnya, kala itu 800 orang dilaporkan menderita penyakit beri-beri karena pola makan yang terlalu didominasi oleh gaplek.
Tidak aneh jika malnutrisi jadi epidemi. Nibbering (1991, hal. 216) menunjukkan pada 1938, nasi hanya mencakup 19 persen dari asupan pangan rata-rata bumiputra pedesaan di berbagai wilayah Gunung Kidul. Jumlah itu pun tidak tersebar rata karena akses terhadap nasi hanya dimiliki bumiputra kaya.
Ini sesuai dengan laporan rubrik Voedseltoestandmilik surat kabar De Locomotief yang memantau rutin kondisi pangan pribumi. Konsumsi gaplek selalu dikabarkan dengan bahasa yang sama, kurang lebih: gaplek dimakan oleh para pribumi miskin, sedangkan pribumi yang lebih berkecukupan akan mencampurkan gaplek dengan nasi dan jagung.
Gaplek, Setelah Hindia Belanda
Dekade-dekade selanjutnya ditandai dengan perang, revolusi, dan kemerdekaan. Perjuangan itu salah satunya digerakkan oleh krisis pangan yang terjadi pada 1930-an.
Namun, gaplek tetap tinggal di lahan tani dan perut warga desa. Pada 1954, singkong meraup 42 persen lahan pertanian di daerah Gunung Kidul, dua kali lipat dari luas lahan pada 1920. Di lain sisi, budidaya padi turun dari 51 persen pada 1920 menjadi 27 persen pada 1954 (Nibbering, 1991, hal. 121).
Ketergantungan warga terhadap singkong pun masih menghantam penduduk desa selama Orde Lama. Salah satu yang terkenal adalah pada 1963, tahun ketika Soekarno melantangkan orasi kondangnya, “lebih baik makan gaplek tapi merdeka, daripada makan bistik tetapi budak!”
Saat itu, Jawa dilanda bencana wabah tikus besar-besaran (Nibbering, 1993). Singkong ludes digerogotinya, baik yang masih tumbuh dalam tanah maupun yang telah disimpan di gudang. Padi menemui ajal yang sama. Para warga beralih mengonsumsi ampas singkong yang disebut gaber. Masa paceklik itu kemudian dikenal sebagai masa begaber, masa ampas singkong. Pada tahun tersebut, dalam keadaan merdeka, gaplek pun mereka tak punya.
Seiring bertambah stabilnya Indonesia, konsumsi singkong dan gaplek relatif menurun. Warga desa punya akses lebih mumpuni kepada bahan pangan lain. Meskipun begitu, singkong tetap jadi sumber pangan utama banyak warga. Di desa-desa Gunung Kidul, singkong masih mencakup setengah dari konsumsi warga bahkan menuju 1990-an. Ledakan komoditas gaplek 70 tahun sebelumnya masih meninggalkan jejaknya dengan kentara.
Sekarang pun kita masih mencicipi jejak itu dalam berbagai bentuk kudapan. Herminingrum (2019) dalam Journal of Ethics Food melacak genealogi makanan singkong tradisional Jawa. Menurutnya, terdapat lima generasi olahan singkong, yaitu yang berbasis singkong segar, singkong rebus, tape (singkong fermentasi), tepung tapioka, dan tentunya gaplek. Kita menyebut produknya dengan berbagai nama: gethuk, tiwul, gathot, cenil, gempho, jemblem, klanting, dan lain-lainnya.
Sebagaimana muasal banyak makanan tradisional, olahan singkong yang kita makan hari ini pada akhirnya berakar dari keterbatasan sumber daya. Maka, meskipun telah mengiringi berbagai sejarah tentang kapital, paceklik, sampai proklamasi, tak perlu ada falsafah dalam segepok gaplek. Yang ada cukup tanah, matahari, dan perut untuk diisi.
Penulis: Finlan Aldan
Editor: Nuran Wibisono












