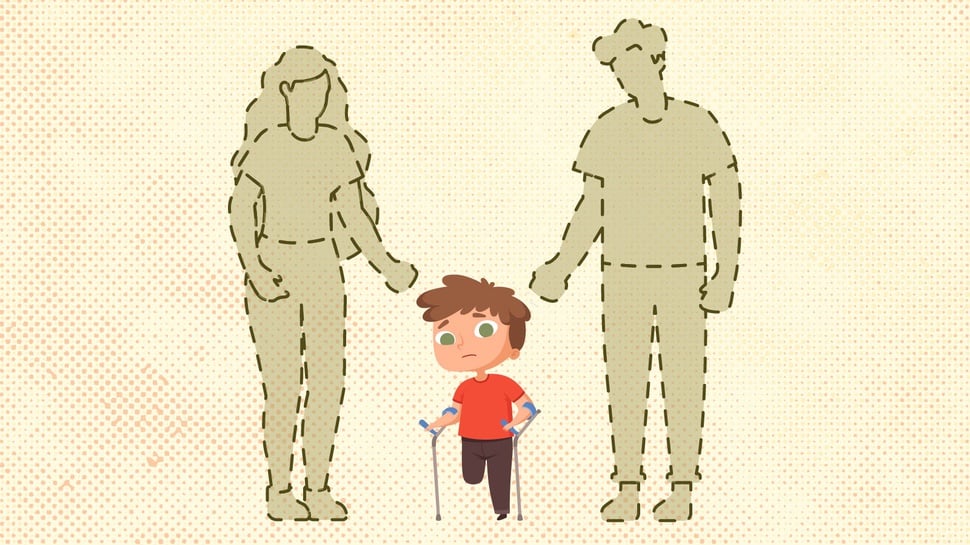tirto.id - Susy Indreswari, 45 tahun, mengawali Senin sore pertama pada bulan Juli dengan gelagapan. Mendadak, ia dimintai bantuan untuk mendampingi keponakan rekannya yang bernama Sekar—bukan nama sebenarnya. Sekar ini perempuan dengan disabilitas intelektual dan autis yang terjangkit Covid-19. Umurnya 20 tahun, akan tetapi kognitifnya masih 5 tahun.
Tak ada pihak keluarga yang mampu berkomunikasi dengan Sekar. Susy dimintai bantuan sebab suaminya, Belly Lesmana, kurang-lebih sudah 10 tahun terakhir bergelut dengan isu disabilitas Yogyakarta.
Saat itu, Sekar baru saja dipulangkan dari RSUP Dr. Sardjito dan menjalani isolasi mandiri di daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Saya dan suami akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke sana. Jaraknya tidak jauh dari rumah, hanya lima menit dengan motor,” cerita Susy kepada saya, kemarin.
Sesampainya di rumah Sekar, sudah ada rekan Susy yang meminta bantuan dan ketua Satgas Covid-19 tingkat RT. Mereka lebih dahulu datang, tetapi tak berani masuk ke dalam rumah. Sebab Sekar bisa saja membawa virus dari rumah sakit tanpa diketahui.
Susy dan Belly bergegas menghubungi beberapa jaringan organisasi disabilitas untuk mencari informasi: bagaimana cara berkomunikasi dengan anak autis dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Mereka berdua juga menghubungi petugas Puskesmas, untuk bertanya: apa saja yang harus dilakukan saat masuk ke dalam rumah dan berkontak erat dengan Sekar.
Akhirnya, Susy mencoba masuk terlebih dahulu ke dalam rumah Sekar. Susy berpikir, mungkin saja, Sekar akan lebih nyaman jika didampingi oleh sesama perempuan.
“Setelah ada kenyamanan dengan kami, ia [Sekar] baru bisa memberi isyarat untuk minta mandi. Anak ini tidak bisa berkomunikasi. Minta mandi, buang air, harus selalu didampingi. Ini menyebabkan kesulitan tingkat tinggi,” ujarnya.
Awalnya Sekar tinggal berdua bersama ibu dan budenya. Namun tiga hari sebelumnya, Jumat (2/7/2021), ibu dan budenya dibawa ke RSUP Dr. Sardjito oleh Ketua Satgas Covid-19 tingkat RT. Sebab keadaannya memburuk usai dinyatakan positif Covid-19.
“Anaknya [Sekar] pun ikut dibawa,” kata Susy.
Sekar hanya dirawat inap selama dua hari. Pada Minggu (4/7/2021), Sekar dipulangkan ke rumahnya. Sebab tidak ada yang memperhatikannya selama dirawat di rumah sakit. Selain itu, ia dipulangkan tanpa pengawasan dari Satgas Covid-19 maupun tes usap terlebih dahulu. Hingga naskah ini tayang, belum ada respons konfirmasi dari RSUP Dr. Sardjito terkait hal ini.
“Tidak ada tes. Padahal sudah dari rumah sakit. Tidak ada datanya baik surat atau apa pun. Tiba-tiba sudah dipulangin saja,” tambahnya.
Awalnya saat di rumah, Sekar masih ditemani oleh seorang asisten rumah tangga (ART). Namun keesokan harinya, ART tersebut mengaku sakit dan tak bisa datang menemani Sekar. Saat itulah Susy dimintai bantuan untuk mendampingi Sekar.
Sehari usai kontak erat dengan Sekar, Susy dan Belly memutuskan tes usap. Kabar baiknya, hasilnya negatif. Namun, kabar buruknya datang dari RSUP Dr. Sardjito: ibu dan bude Sekar tak tertolong, meninggal dunia. Ibu dan budenya Sekar termasuk dalam 52 orang yang tutup usia di Yogyakarta pada hari itu.
Susy mengaku heran mengapa Satgas Covid-19 di Yogyakarta bisa begitu serampangan menelantarkan Sekar: dibawa ke rumah sakit penanganan Covid-19 dan dipulangkan begitu saja tanpa tes usap dan pengawasan. Keadaan Sekar yang serba terbatas justru berpotensi membahayakan anak itu sendiri.
“Memang Satgas tidak bisa berbuat apa-apa, seperti kasus Sekar kemarin, malah hanya menunggu di luar rumah. Sekarang ini diperlukan Satgas di lingkup terkecil untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait, harus menghubungi kemana jika ada kasus positif Covid-19 pada anak-anak disabilitas. Supaya tidak ada pembiaran seperti kasus Sekar,” kata Susy.
Hingga saat ini, Sekar belum tahu sama sekali bahwa ibu dan budenya sudah tiada. Susy dan Wahyu mengaku bingung, bagaimana cara mengabarkan kematian kepada anak dengan autisme. Sekar memiliki banyak keterbatasan dalam berkomunikasi dan tentu membutuhkan waktu yang panjang untuk menerima informasi mengenai kematian.
Saat ini, Sekar sudah tinggal bersama keluarga besarnya. Susy beberapa kali memberi rekomendasi, jika ingin mengabarkan kematian kepada Sekar, sebaiknya mencari seorang psikolog, agar diberi panduan, asesmen, dan hasilnya akan dilaporkan kepada keluarga besar.
“Jadi Sekar saat ini masih menganggap bahwa ibunya masih ada,” kata dia. “Anak ini selalu meminta video call untuk bertemu ibunya. Kalau ada motor datang, ia selalu ingin memastikan bahwa itu ibunya yang telah berpulang.”
Baru Bisa Dirawat Inap Jika Ada Pendamping Khusus
Kesulitan dan kesedihan serupa juga dialami oleh Agustinus Luky Wijaya, 20 tahun. Luky adalah anak dengan disabilitas ganda: tuna netra dan autis, mengalami hambatan komunikasi dan mental. Ayahnya meninggal karena terjangkit virus SARS-CoV-2. Sebelumnya, mendiang ayahnya dirawat di RSUD Kramat Jati, Jakarta Timur, selama dua hari dengan penyakit bawaan darah tinggi, kolesterol, dan stroke di sebelah kiri tubuh.
“Dimakamkan dengan protokol kesehatan Covid-19, kendati dari surat keterangan kematiannya enggak tertulis karena Covid-19,” kata Ruth Ida Meliani, 56 tahun, ibu Luky, bercerita kepada saya, kemarin.
Usai turut mengantar suaminya ke peristirahatan terakhir, Ida tak sempat memberi kabar kematian itu ke anaknya, Luky. Dia langsung memutuskan isolasi mandiri di rumah selama dua pekan. Namun perlahan Ida merasakan gejala Covid-19 berupa deman dan sesak napas. Pertengahan April 2020, Ida dan Luky tes usap, hasilnya: positif Covid-19.
Mereka berdua dibawa ke Rumah Sakit Darurat Khusus Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Jakarta, Selasa (27/4/2021). Kendati sebelumnya ada perdebatan panjang: apakah Luky ikut atau menjalani isolasi mandiri di Asrama Sekolah Dwituna Rawinala saja.
Perdebatan ini adalah efek dari tiga hari sebelumnya, ada empat anak dengan disabilitas ganda Rawinala yang ditolak oleh RSDC Wisma Atlet. Ida membenarkan adanya kasus itu.
“Wisma Atlet tidak punya tenaga khusus atau relawan untuk menangani anak disabilitas,” jelas Ida. “Empat anak enggak bisa dirawat di Wisma Atlet karena mereka kan tidak ada orang tuanya. Terus tidak ada yang dampingi di RS.”
Padahal fasilitas untuk disabilitas di Wisma Atlet sudah cukup memadai. Pada 2018, jelang Asian Games, Pemerintahan Jokowi merenovasi 1.000 kamar di Wisma Atlet agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas: perluasan kamar bagi pengguna kursi roda, penambahan hand railing, hingga toilet yang lebih ramah untuk disabilitas.
Total ada lima tower—tower 3 sampai 7—yang kamarnya direnovasi, dengan jumlah 200 kamar khusus disabilitas per tower, serta penambahan enam elevator baru yang lebih luas hingga bisa maksimal tiga kursi roda. Elevator juga disediakan tombol dengan aksara braille. Total biaya yang dihabiskan menyentuh Rp185 miliar.
Di luar tower juga ada penambahan fasilitas guiding block kuning dan silver untuk tuna netra dan ramp untuk lintasan kursi roda.
“Wisma Atlet adalah RS Darurat, sebaiknya disabilitas tidak diarahkan ke Wisma Atlet,” kata juru bicara Covid-19 saat itu, Achmad Yurianto. “Tidak perlu dibuat baru [protokol khusus]. Ikuti yang ada saja, disesuaikan kondisi.”

Saya mencoba menghubungi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menanyakan mengenai masalah ini. Saya bertanya apakah sudah melakukan rekrutmen terhadap relawan-relawan yang bisa menangani pasien dengan disabilitas. Fokusnya, agar kasus seperti penolakan di Wisma Atlet tidak terulang.
Namun Siti Nadia tak merespons banyak. “Aku cek dulu, ya,” katanya singkat, kemarin.
Berbeda nasib dengan empat kawannya, Luky bisa ikut dirawat karena ada mamanya sebagai pendamping khusus. “Saya bisa diterima karena bisa mendampingi Luky. Saya sama Luky satu kamar,” lanjut Ida.
Ida juga menuturkan, salah satu kesulitan anak dengan disabilitas tuna netra seperti Luky saat terkena Covid-19 adalah masalah komunikasi dua arah. Luky tak bisa mengutarakan apa yang dirasa dan sebelah mana rasa sakitnya.
“Cuma saya lihat dari gerak-gerik [Luky] oke oke aja,” tuturnya.
Menurut Ida, kendala terberat yang dialami anak dengan disabilitas seperti Luky justru terjadi usai sembuh dari Corona. Saat sudah di rumah, mereka seperti dikucilkan oleh tetangga. Ada stigma buruk kepada para penyintas Covid-19, mereka dilabeli membawa penyakit yang menjijikkan.
Padahal anak dengan disabilitas seperti Luky masih harus dapat perhatian dari orang-orang di sekitar. “Orang enggak berani mendekat. Namun saya sendiri memaklumi,” katanya.
Keadaan pandemi—saat semua orang meminimalisir kegiatan di luar rumah—juga akhirnya memengaruhi sisi psikologis Luky. Dia menjadi individu yang penakut saat bertemu orang baru. Sekolah di rumah dan keputusan Ida untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, mengubah pembawaan diri Luky.
“Dengar suara orang langsung tutup telinga, keadaan pandemi mengubah diri Luky. Saya rasakan [pandemi] sangat mengubah Luky,” katanya.
Luky juga akhirnya baru menyadari belakang bahwa papanya sudah tutup usia. Dulu mendiang papanya sering mengajak Luky makan di luar rumah dua minggu sekali. Menikmati waktu bertiga. Kata Ida, saat ini Luky kehilangan momen-momen itu, kendati tak bisa mengungkapkannya.
“Sekarang Luky hanya bisa marah. Kelihatan uring-uringan. Sering nyakitin diri sendiri, mukul bahu, paha, selama satu tahun terakhir setelah Papanya enggak ada,” kata Ida.
Minimnya Edukasi ke Disabilitas
Berjarak 2.600 kilometer dari Jakarta, anak-anak dengan disabilitas di Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjadi kelompok yang paling rentan terpapar Covid-19. Koordinator Riset Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) NTT, Berti Soli Dima Malingara menilai, salah satu masalah paling mendasarnya adalah ketimpangan informasi yang cukup besar antara Jakarta dengan Kupang.
Kata Berti, di Kupang belum ada kebijakan yang jelas mengenai sosialisasi dan edukasi tentang Covid-19 ke anak-anak dengan disabilitas. Tidak ada kunjungan dari tenaga kesehatan atau psikolog yang bisa menjelaskan kepada anak-anak dengan disabilitas: bagaimana agar tidak terpapar atau mekanisme jika harus isolasi mandiri. Apalagi untuk anak-anak disabilitas yang hidup di panti.
“Bagi anak difabel sensorik netra, mencari di mana letak ember cuci tangan dan keran air, apalagi sabun tentunya tidak mudah. Lalu bagaimana jika anak difabel sensorik netra terpapar Covid-19?” kata Berti saat saya hubungi, kemarin.
Apa yang dilihat oleh Berti terhadap anak-anak dengan disabilitas di Kupang, sangat mungkin terjadi juga di banyak daerah di Indonesia. Apalagi, minimnya akses fasilitas kesehatan dan informasi terutama ke daerah-daerah terpencil.
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan pada 2018 lalu tercatat, setidaknya 3,3 persen dari total seluruh anak di Indonesia—dari umur 5 sampai 17 tahun—adalah penyandang disabilitas. Dari semua anak dengan disabilitas, 4,2 persen berumur 15-17 tahun, 3,5 persen berumur 10-14 tahun, dan 2,5 persen berumur 5-9 tahun.
Jika mengacu data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang keluar pada tahun yang sama dengan Riskesdas, dalam rentang umur 2 sampai 6 tahun, setidaknya terdapat 1.150.173 jiwa disabilitas sedang dan 309.784 jiwa disabilitas berat. Sedangkan di umur 7 sampai 18 tahun, ada 1.327.688 jiwa disabilitas sedang dan 433.297 jiwa dengan disabilitas berat.
Dan tentu saja, mereka bukan sekadar angka dan statistika. Mereka punya kehidupan dan masalah konkret sehari-hari yang perlu keterlibatan negara untuk membantunya.
“Harus ada orang lain yang membimbing mereka yang semuanya banyak mengandalkan sentuhan dan rabaan,” ujar Berti.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Dieqy Hasbi Widhana