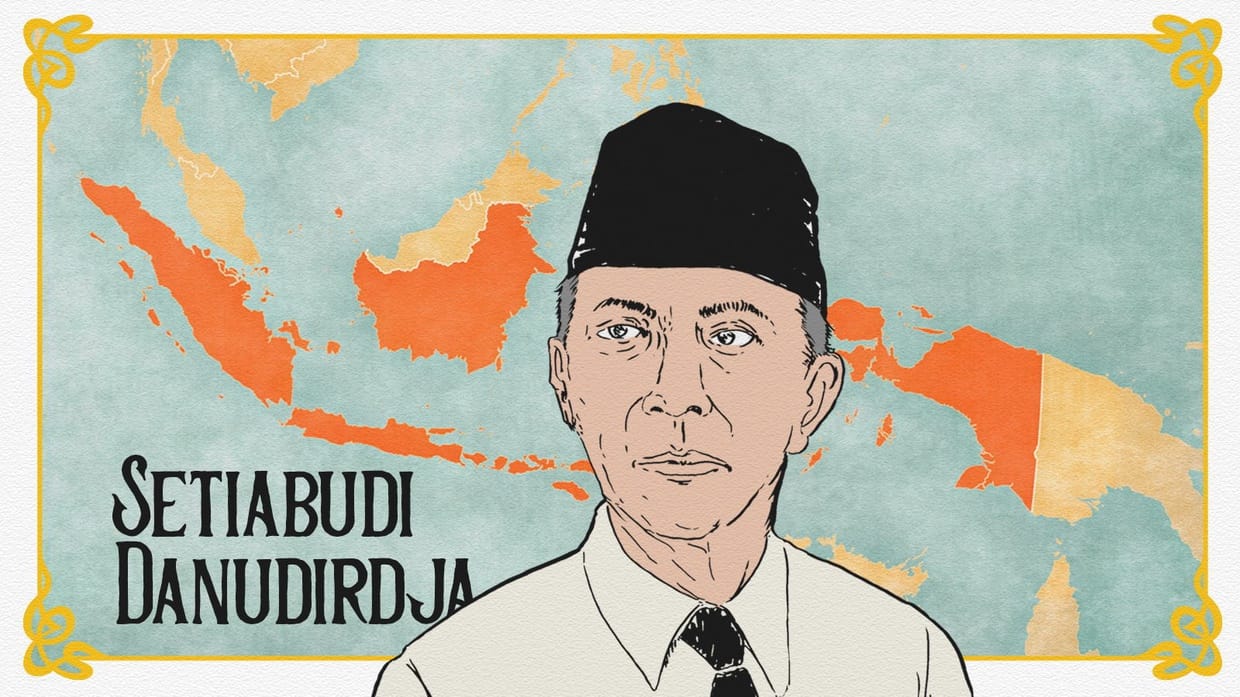tirto.id - Ulbe Bosma mengkritisi pandangan usang yang menyebut kebangunan nasionalisme masyarakat Timur sebagai hasil dari pendidikan modern gaya Barat. Dalamartikel “Citizen of Empire” yang dimuat jurnal Comparative Studies in Society and History (2004), Bosma menjelaskan bahwa nasionalisme yang melahirkan negara pascakolonial seperti Indonesia kemungkinan memang lahir bertepatan dengan perkembangan pendidikan Barat pada awal abad ke-20. Namun, pendapat itu sangat berat sebelah.
Pasalnya, pandangan itu menafikan tindasan kolonialis Belanda terhadap kesadaran kebangsaan lokal demi pendirian imperium Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Contoh akan hal itu dapat disimak melalui Perang Jawa (1825-1830).
Kesadaran kebangsaan lokal itu rupanya tidak mati. Ia tetap bertahan dan kemudian muncul dalam bingkai yang lebih modern melalui organisasi seperti Budi Utomo yang didirikan pada 1908.
Sebagai “gerakan kebangunan Jawa”, Budi Utomo terbuka pada tiga unit geobudaya: Jawa, Sunda, dan Madura. Pendirian Budi Utomo kemudian memicu munculnya gerakan-gerakan nasionalisme lokal di tempat-tempat lain di Hindia Belanda.
Lain itu, ada pula Sarekat Islam yang melintasi batas kesatuan geobudaya. Ia menghimpun anggota yang multietnis. Meski begitu, ideologi yang mempersatukan anggota organisasi ini tetap eksklusif—agama Islam.
Lalu, dari manakah ide persatuan inklusif dapat muncul dalam negara kolonial yang masih terkotak-kotak itu? Jawaban singkatnya, dari kelompok yang tidak memiliki privilese untuk membentuk organisasi berdasarkan kesamaan geobudaya.
Dari kelompok masyarakat itulah Ernest Douwes Dekker (1879–1950) muncul. Dia pernah disebut sebagai “orang asing yang membela Indonesia”. Pasalnya, posisi komunitas Indo-Belanda memang rumit di tanah kolonial.
Dia dianggap liyanoleh bumiputra yang melihat kaum Indo-Belanda sama saja dengan Belanda totok. Tapi, seperti kebanyakan orang Indo-Eropa, Ernest lahir di Hindia, tepatnya di Pasuruan, Jawa Timur. Karena itu, Ernest pun tetap jadi liyan di mata orang-orang Belanda.
Melampaui Politik Etis
Ernest lahir dari seorang ayah Belanda dan ibu peranakan Jerman-Jawa. Karena itu, tepat belaka bila Bosma menggambarkan sosoknya sebagai titisan dari internasionalisme.
Berkat darah Belanda dari ayahnya, Ernest boleh menikmati privilese di masa kecilnya. Ernest dididik di sekolah Eropa di Batavia. Dia kemudian lanjut bekerja di perkebunan kopi dan pabrik gula.
Meski “bermain” di arena kapitalisme, Ernest memutuskan menjadi seorang sosialis. Paul van der Veur dalam artikel “E.F.E. Douwes Dekker: Evangelist for Indonesian Political Nationalism” yang terbitkan The Journal of Asian Studies (1958) menyebut Ernest, “Dipecat [dari pabrik dan perkebunan itu] dalam waktu singkat karena dianggap mengedepankan kepentingan pekerja bumiputra dibandingkan kepentingan perusahaan.”
Ernest kemudian menjadi tentara sukarela Belanda dalam Perang Boer (1899–1902). Dia pun sempat menjadi tawanan perang Inggris di Sailan (kini Sri Lanka). Pada 1903, dia kembali ke Jawa dan mulai berkarier di ranah persuratkabaran. Ernest tercatat pernah bergabung dalam beberapa media, di antaranyaSoerabaiaasch Handelsblad, De Locomotief, dan Bataviaasch Nieuwsblad.
Agaknya, Ernest jadi makin politis dalam masa jadi kuli tinta ini. Setelah mengalami pengalaman kapitalisme kolonial di perusahaan Belanda dan sebuah perang kolonial sebagai pihak yang kalah, kesadaran akan bopengnya wajah kolonialisme mulai terbentuk dalam pikirannya.
Pada saat yang sama, Kerajaan Belanda juga tengah mengubah haluan kolonialnya: dari eksploitasi swasta menjadi semangat etis.
Fokus dari kebijakan etis adalah kebangkitan ekonomi tanah jajahan. Belanda menganggap jatuhnya taraf hidup masyarakat kolonial pada pertengahan hingga akhir abad ke-19 sebagai hulu dari semua permasalahan di Hindia. Namun, Ernest menaruh skeptisisme atas politik etis ala Belanda itu yang diwujudkan melalui jargon “edukasi, irigasi, emigrasi, dan desentralisasi”.
Melalui rangkaian tulisannya di Nieuwe Arnhemsche Courant (Mei 1908), Ernest mengungkap bahwa politik etis bukanlah jalan keluar dari krisis. Menurutnya, jalan keluar yang sebenarnya adalah pemerintahan Hindia yang mandiri.
Dalam In Search of Southeast Asia: A Modern History (1971), David Joel Steinberg menyebut dekolonisasi mulai jadi “tren” di Asia Tenggara pada awal abad ke-20. Otoritas Amerika Serikat di Filipina, misalnya, telah meningkatkan porsi kursi bagi perwakilan bumiputra di parlemen Filipina pada 1910. Hidia Belanda dengan politik etisnya justru melawan arus itu—dan bahkan baru mendirikan Volksraad pada 1918.
Seturut ukuran itu, kolonialisme Hindia Belanda memang tergolong usang jika dibandingkan dengan kekuatan kolonial lain di Asia Tenggara. Karenanya, pemikiran Ernest tentang pemerintahan mandiri mendapat relevansinya.
Organisasi “kebangkitan nasional” yang muncul pada masa tersebut sebenarnya juga sekedar merespons Politik Etis. Ia nisbi hanya berkutat pada masalah ekonomi dan kebudayaan. Bahkan, Sarekat Islam yang dianggap cukup inklusif secara geobudaya itu pun berakar dari motivasi persaingan ekonomi dalam masyarakat, bukan kesadaran politik.

Menempuh Jalan Politik
Menjadi Inklusif adalah jawaban dari Ernest untuk keluar dari jebakan kultural-ekonomi semacam itu. Sekira 1910, Ernest bergabung dalam Indische Bond yang memperjuangkan kepentingan kaum Indo-Eropa. Dia lantas mengusulkan kepada pengurus organisasi untuk membuka keanggotaan bagi siapa saja yang tinggal di Hindia, tanpa memandang latar etnisnya.
Langkah semacam itu jelas berbeda dari Budi Utomo yang terpaku pada geobudaya Jawa. Kemudian, Ernest membentuk komite reorganisasi yang dia pimpin sendiri untuk mengubah haluan Indische Bond menjadi lebih politis.
Untuk mempropagandakan ide-ide politiknya, Ernest mendirikan jurnal Het Tijdschrif pada September 1911. Dalam edisi Mei 1912, Ernest mencetuskan ide pembentukan partai berasas “pengalaman pahit bersama”. Pemikiran untuk mendirikan sebuah kekuatan politik macam itu adalah cetusan yang paling perdana di Hindia. Gagasan itulah yang kemudian menitis jadi Indische Partij.
Jadi, Sukarno tak salah kala menyebut Ernest sebagai salah satu pencetus kesadaran nasionalisme politik di Indonesia.
Namun, Indische Partij—yang didirikan Ernest bersama Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangkunkusumo—hanya mampu bertahan sekita satu tahun. Pada 1913, Indische Partij digebuk pemerintah kolonial Hindia Belanda dan bubar.
Sepanjang masa hidup singkat itu, Indische Partij berhasil mengumpulkan 7 ribu anggota—terdiri dari 5 ribu orang Indo-Eropa dan2 ribuan bumiputra. Ide Ernest membentuk partai inklusif tidak mendapat simpati dari golongan Belanda totok dan Tionghoa. Pendukung Ernest dari golongan Indo-Eropa pun tersegmentasi hanya pada golongan menengah ke bawah, terutama mereka yang berhaluan sosialis.
Refleksi
Pengalaman politik Ernest itu menghadirkan kepada kita pertanyaan penting: mengapa ide kemandirian politik—yang kemudian meningkat jadi tuntutan kemerdekaan—tampak kurang menarik pada awal abad ke-20?
Perubahan wajah kolonialisme dari eksploitatif menjadi etis memegang peranan kunci di sini. Pada abad ke-19, kolonialisme Eropa jelas terlihat sebagai kekuatan ekspansionis dan eksploitatif. Namun, citra itu perlahan kikis oleh semangat etis yang membuai kawula kolonial dengan harapan kolonialisme bakal berubah ke arah yang lebih baik.
Kritisisme kawula jajahan pun bergeser, dari semula bertitik pada kolonialisme menjadi bertitik pada kebijakan-kebijakan parsial yang tidak menguntungkan. Sikap seperti ini bertahan dalam organisasi non-Marxis hingga negara kolonial Hindia Belanda runtuh pada 1942.
Bahkan, Suwardi Suryaningrat yang dulu radikal kini melunak. Pada 1940, Suwardi menyurati Muhammad Husni Thamrin yang tengah berkonflik dengan pemerintah kolonial. Dalam surat itu Suwardi meminta Thamrin untuk “Mengubur pertentangannya dengan pemerintah [kolonial] dan bergabung dengan blok demokrasi melawan fasisme”—saat itu, Belanda dipandang sebagai blok demokrasi yang melawan Jerman yang fasis (lihat Mohammad Hoesni Thamrin and His Quest for Indonesian Nationhood 1917–1941 susunanBob Hering [1996]).
Pada 28 Agustus 1950—tepat hari ini 71 tahun yang lalu, Ernest wafat. Dia wafat setelah menyaksikan kedaulatan tanah airnya diakui oleh Belanda. Negara inklusif yang dia cita-citakan berhasil didirikan. Tapi, sudahkah negara itu benar-benar menjadi penaung bagi kaum-kaum liyan seperti dirinya?
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id