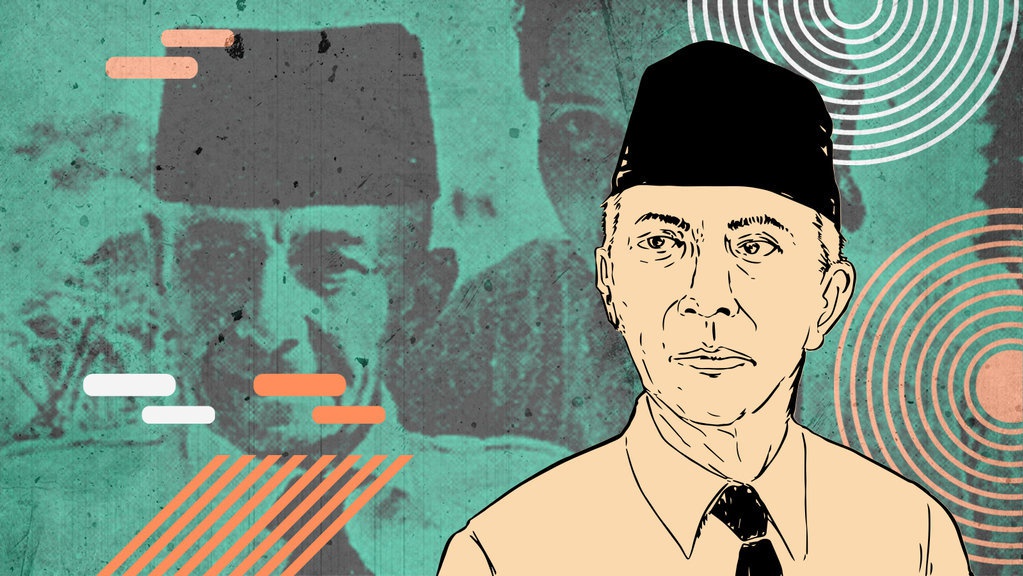tirto.id - Golongan Indo adalah “golongan tanggung” pada masa kolonial. Mereka dianggap lebih rendah dibanding orang Belanda atau Eropa tulen. Tapi mereka tak bisa dianggap lebih rendah daripada warga negara kelas tiga seperti pribumi—yang disebut inlander. Golongan yang disebut inlander adalah golongan tersial. Sementara itu, golongan Belanda atau Eropa tulen adalah yang paling beruntung di Hindia Belanda.
Ernest Francois Eugene Douwes Dekker lahir dalam keadaan sosial macam itu. Meski ibunya punya darah Jawa, yang berarti kebelandaannya tidak murni, dalam status hukum dia masuk golongan orang Eropa.
Dengan status tersebut, Douwes Dekker, yang biasa dipanggil Nes oleh Sukarno, sempat mencicipi pendidikan di sekolah elite Gymnasium Koning Willem III School (HBS KW III) di Salemba.
Orang-orang yang bisa baca-tulis aksara Latin di awal abad ke-20 adalah golongan minoritas. Sementara itu golongan inlander, yang sebagian besar tidak bisa baca-tulis aksara Latin, adalah mayoritas.
Nes yang hidupnya lebih beruntung benci dengan istilah "inlander". Menurutnya, istilah itu diadakan-adakan oleh pejabat Belanda pro-kolonialisme.
“[...] Penduduk Hindia Belanda dibagi dalam dua golongan utama: 'Orang Eropa dan orang Onlander'. Perhatikan 'I' dari Inlander ditulis dengan huruf besar, itu hendak menyatakan bahwa seharusnya akan ada benua atau negeri bernama Inland. Dapatkah kalian menunjukkan kepada saya negeri itu di peta dunia?” kata Nes, seperti dikutip Margono Djojohadikusumo dalam Dr E.F.E. Doues Dekker: Dr Danudirdjo Setia Budi (1975: 31-32).
Lebih lanjut Nes bertanya, “mengapa menurut undang-undang itu saya dimasukkan dalam golongan Eropa, hanya karena saya bernama Douwes Dekker?”
Sebagai orang yang secara hukum dianggap Belanda, ditambah ijazah sekolah KW III, Nes bisa saja hidup nyaman dengan jadi pegawai kolonial yang gajinya lumayan besar. Tapi sejarah Indonesia mencatat Nes sebagai Douwes Dekker yang membela kaum pribumi dalam pergerakan nasional. Atas jasanya itu, dia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional lewat Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 590 tahun 1961 tanggal 9 November 1961.
Inspirator Boedi Oetomo
Di masa kolonial, Nes lebih dari sekadar kaum partikelir (orang-orang yang tidak bekerja kepada pemerintah). Setidaknya, sejak awal abad ke-20, Nes ingin menghapus diskriminasi rasial dan mendorong agar kehidupan orang-orang pribumi lebih baik. Nes merasa wilayah yang kala itu disebut Hindia Belanda sebagai tanah airnya juga.
Keterlibatannya dalam Tiga Serangkai, yang mendirikan Indische Partij (Partai Hindia) pada 1913, adalah bukti bahwa dia merasa tidak berbeda dengan orang Eropa, orang Indo, atau orang pribumi. Lewat koran De Express, menurut Margono Djojohadikusumo, ia mengampanyekan kesetaraan rasial. Semua adalah satu dan seharusnya bekerja bersama-sama.
Gagasan Douwes Dekker melampaui pemikiran banyak orang pada awal abad ke-20. Itulah bentuk kesetiakawanannya kepada semua golongan di Hindia Belanda.
“Saya dilahirkan di sini, mendapat sesuap nasi di sini, dan juga tidak ada yang lebih saya senangi selain dikubur di sini, di bawah pohon palem,” kata Nes seperti dicatat Margono.
Tapi tak semua orang berdarah Belanda punya pemikiran untuk memajukan semua golongan di negeri jajahan. Bahkan orang yang mengaku berdarah asli Indonesia saja belum tentu berpikiran seperti Nes.
Ketika jadi wartawan Bataviasche Nieuwsblad di kota Betawi, Nes tinggal di Jalan Kramat. Di masa-masa ini dia sudah kawin dengan Clara Charlotte Deije. Rumahnya, seperti dicatat Tashadi dalam Dr D.D. Setiabudi (1984: 23), menjadi tempat nongkrong sekaligus perpustakaan bagi beberapa murid School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) atau Sekolah Dokter Jawa yang terletak di Kwitang.
Di antara murid-murid STOVIA itu kemudian mendirikan sebuah organisasi yang terus dikenang dalam sejarah Indonesia: Boedi Oetomo (BO). Organisasi itu didirikan di kampus STOVIA. Tak heran, gedung bekas kampus tersebut kini dinamai Gedung Kebangkitan Nasional.
Namun, sebelum berdiri di situ, gagasan pembentukannya ikut digodok di tempat lain. Seperti dicatat Tashadi, ada yang mengatakan bahwa “jiwa Budi Oetomo itu sesungguhnya terlahir di tempat kediaman Dr EFE Douwes Dekker di Kramat, Jakarta, yang memancar dari tubuh Sutomo, Gunawan Mangunkusumo dan kawan-kawannya pada tanggal 20 Mei 1908” (hlm. 21).
Gunawan Mangunkusumo masih saudara dari dr. Tjipto Mangunkusumo. Belakangan, bersama Nes dan Suwardi Suryaningrat, mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai pendiri Indische Partij (IP).
Suwardi pernah bikin marah pemerintah kolonial karena tulisannya yang berjudul "Als Ik Een Nederlander Was". Artinya kira-kira: Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan itu dimuat di De Express.
Tak hanya Suwardi, Tjipto dan Nes ikut terseret. Pada 1913, mereka bertiga dibuang ke Belanda.
Petualang Sejak Muda
Hidup Nes memang penuh petualangan. Sedari kecil, dia terbiasa hidup berpindah-pindah. Dia tampaknya bangga terlahir di Pulau Jawa. “Saya dilahirkan di kota kecil jawa Timur, Pasuruan, pada 8 Oktober dalam daftar dilahirkan 1879,” akunya ketika mendaftar di Universitas Zurich pada 1913, seperti dikutip dalam Douwes Dekker Sang Inspirator Revolusi (2013: 66).
Pekerjaannya pun gonta-ganti. Seperti dicatat Margono (hlm. 22), setelah cabut dari pekerjaannya di Perkebunan Soember Doeren, di sekitar Gunung Semeru, Nes pindah ke Pabrik Gula Pajarahan di Kraksan (Pasuruan) sebagai laboran. Setelah itu, dia berlayar ke Afrika Selatan untuk jadi sukarelawan Belanda dalam Perang Boer. Nes sempat jadi tawanan pemerintah kolonial Inggris di Pretoria (Afrika Selatan), lalu Colombo (Srilanka).
Pengalaman hidup macam itu membuat dirinya tak merasa berat saat dibuang ke Belanda. Juga belakangan (jelang menyerahnya Hindia Belanda kepada Jepang) ketika jadi orang buangan di Suriname. Pengalaman sebagai tawanan perang Inggris juga membuatnya terbiasa sebagai tahanan politik pemerintah kolonial.
Tak hanya soal tempat tinggal dan pekerjaan, dalam urusan perkawinan Nes juga kerap berpindah dari pelukan wanita satu ke wanita yang lain. Nasib kehidupan perkawinannya kerap dipengaruhi oleh aktivitasnya dalam berpolitik. Perkawinannya dengan Clara Charlotte Deije bubar pada 1912 karena aktivitas politik. Sedangkan pembuangan ke Suriname membuatnya berpisah dengan istri keduanya.
Bukan Ernest Douwes Dekker jika menyerah hanya karena pembuangan. Sepulang dari Belanda, Nes masih bersama kaum pergerakan nasional. Dia bahkan semakin serius. Bikin partai sudah masa lalu yang tak perlu lagi baginya. Nes memilih bergerak di bidang pendidikan. Dia meniti jalan yang juga ditempuh Suwardi Suryaningrat—belakangan dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara—yang mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta.
Nes sempat ikut mengajar di sekolah dasar partikelir milik Nyonya Meyer Elenbasaas di Jalan Kebon Kelapa 17, Bandung dan akhirnya menjadi Direktur MULO. Sekolah yang dikelolanya berubah menjadi Ksatrian Institut pada November 1924.
Ketika mengurus Ksatrian Institut, Nes menemukan seorang pengajar indo bernama Johanna Petronella Mossel. Tak hanya berpenampilan menarik, Johanna juga punya sikap politik yang sama dengan Nes. Mereka kemudian menikah di Kantor Catatan Sipil Bandung.
Menurut catatan Tashadi (hlm. 51-53), Ksatriaan Institut punya beberapa sekolah; mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah dagang, hingga sekolah menengah keguruan. Tak hanya memimpin sekolah, Nes juga menulis buku sejarah untuk siswa sekolah menengah. Selain itu, ia ikut serta bersama beberapa penulis dalam menyusun buku bahasa.
Di tengah kesibukan mengurus Ksatriaan Institut, Nes terus berhubungan dengan orang-orang pergerakan nasional. Kolega pergerakan nasionalnya kali ini lebih muda darinya dan sebagian besar adalah pribumi. Hanya sedikit orang indo.
Kolega Nes paling terkenal tentu saja Mohammad Husni Thamrin, anggota Volksraad (Dewan Rakyat) berdarah Inggris-Betawi. Di tahun-tahun terakhir Hindia Belanda, baik Nes maupun Thamrin dianggap dekat dengan orang-orang Jepang. Tak heran, keduanya jadi tahanan. Thamrin hingga meninggal jadi tahanan rumah. Sementara Nes jadi orang buangan lagi, kali ini ke Suriname. Maka berpisahlah ia dengan Johanna Petronella Mossel.
Nes baru bebas setelah Perang Dunia II berakhir. Beruntungnya, Nes bertemu perempuan indo lagi di Suriname. Namanya Nelly Alberta Kruymel, janda dari Ir. Geertsma dan sudah punya anak pula. Nelly yang masih muda itu yang merawat Nes.

Setia pada Republik
Pada Desember 1946, Nes dan Nelly kembali ke Hindia Belanda, yang sudah bersalin nama menjadi Indonesia.
Kondisinya sudah begitu menyenangkan bagi Nes, karena Republik Indonesia sudah berdiri. Berhubung ibu kota Republik sudah pindah ke Yogyakarta, Nes harus melakukan perjalanan jauh begitu turun dari kapal. Margono mengaku, menantunya, Dora Sigar, ikut membantu Nes menuju Yogyakarta (hlm. 82). Nes berhasil mencapai Yogyakarta meski perjalanannya tidak mudah.
“Selamat datang, Nes,” sambut Sukarno, kawan lama Nes sejak Sukarno masih muda.
Masa di Yogyakarta itu masa menyenangkan baginya. Meski usia semakin senja, sekitar 68 tahun, Nes ingin ikut serta bertempur di pihak Republik Indonesia, bukan Belanda, seperti sebagian darah yang ada dalam tubuhnya.
Seperti dicatat Margono, Nes bilang, “saat gembira bahwa hari tua saya dapat berada kembali diantara saudara-saudara untuk menawarkan jasa-jasa saya pada Republik, kendati pun sebagai prajurit biasa sebab saya adalah penembak jitu” (hlm. 51).
Di Yogyakarta, Nes dan Nelly sempat tinggal di Hotel Garuda. Nes kemudian diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sambil mengajar di Akademi Ilmu Politik. Pada 8 Maret 1947, seperti dicatat dalam Douwes Dekker Sang Inspirator Revolusi, Nes dan Nelly menikah secara Islam di Masjid Agung Yogyakarta (hlm. 150).
Nes disebut-sebut pernah ikut partai Masyumi. Setelah Agresi Militer Belanda 19 Desember 1948, Nes sempat jadi tawanan lagi, tapi kemudian bebas dan tinggal di Bandung. Belakangan, orang-orang mengenal mereka berdua dengan nama Indonesia. Nes sebagai Danudirdja Setiabudi dan Nelly sebagai Harumi Wanasita.
Laki-laki yang merupakan cucu-keponakan dari Eduard Douwes Dekker (1820-1887)—yang mengutuk kolonialisme lewat novel Max Havelaar—ini tutup usia pada 28 Agustus 1950, tepat hari ini 68 tahun lalu. Seperti adik kakeknya, nama Nes disebut dalam sejarah Indonesia sebagai orang-orang yang menentang pemerintah kolonial di zaman berbeda.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id