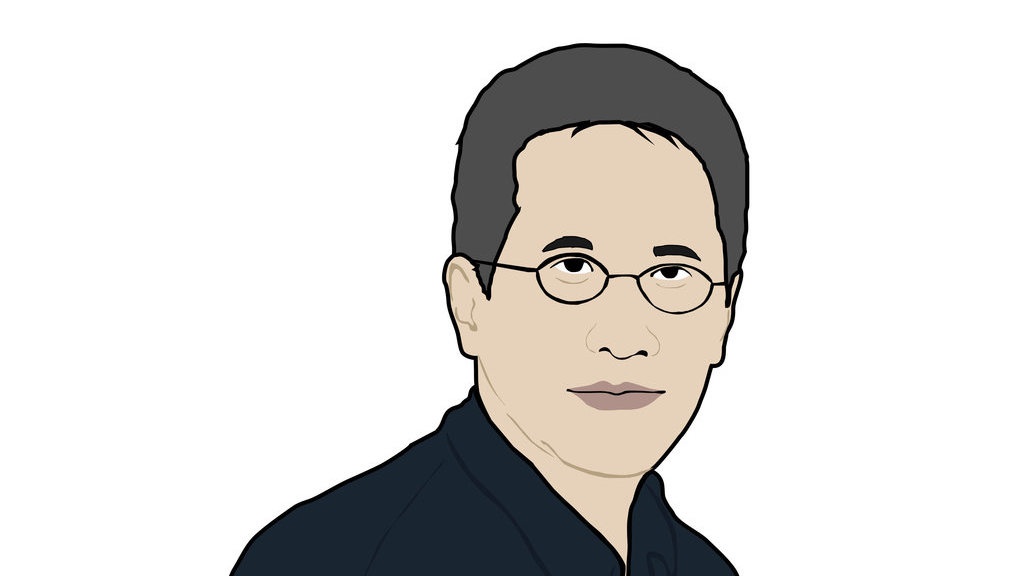tirto.id - Bertahun-tahun sejak abad 18, sebagian besar umat manusia hanya mengenal satu tata kehidupan bersama, yakni kehidupan di bawah kolonialisme Eropa. Karena turun-temurun dihayati sebagai kelaziman, suka-duka kehidupan kolonial diterima sebagai keniscayaan. Tidak terbayang tata kehidupan pada awal abad 20 yang berbeda secara radikal.
Kondisi kehidupan kolonial tak sepenuhnya diterima sebagai musibah seperti yang disarankan oleh propaganda nasionalis dan istilah “penjajahan”. Kehidupan kolonial juga membawa perubahan yang menggiurkan, yakni modernitas; sebuah perubahan terbesar dalam sejarah dunia selama beberapa abad terakhir.
Di Jawa, corak kehidupan kota berubah secara besar-besaran dengan masuknya kereta api, tram, sepeda, mobil, arloji, kalender, sekolah, toko, kantor, pabrik, radio, kamera, bioskop, koran, iklan, novel, dan pelbagai teknologi baru untuk peralatan dapur. Dampaknya sedahsyat gegar budaya akibat meledaknya internet dan media sosial pada peralihan abad 20/21.
Harus diakui, banyak yang menderita selama masa kolonial. Tapi hal yang sama juga dijumpai sesudah masa kolonial. Harus diakui pula, tak semua orang menerima dan membenarkan kolonialisme. Tapi jumlah mereka yang anti-kolonial itu—baik dari kalangan bangsa terjajah maupun penjajah—sangat kecil dibandingkan mayoritas masyarakat jajahan.
Baru sesudah Indonesia merdeka, nama dan wajah para tokoh nasionalis (yang “pribumi”) itu dipasang besar-besaran di buku pelajaran sejarah dan pidato resmi kenegaraan. Juga di pusat-pusat kota sebagai monumen, nama jalan, nama bandara, film, buku biografi, nama lembaga, dan nama gedung.
Semua pemahaman dan bayangan kolonial yang lazim itu mendadak buyar ketika Jepang menaklukkan sejumlah negara kolonial Eropa, termasuk kekuasaan Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Selama tiga tahun (1942-1945), semua yang puluhan tahun tampak baku, niscaya, dan lazim, mendadak luntur. Orang menimbang-ulang kehebatan Eropa. Namun, masa itu berlangsung cuma tiga tahun.
Indonesia Sesudah Merdeka
Tahun 1945, Perang Dunia II berakhir dengan takluknya Jepang di hadapan Sekutu. Sebagian besar penduduk dunia, termasuk mantan penjajah Eropa dan mantan terjajah Asia/Afrika, menduga kehidupan mereka akan kembali menjadi “normal” dengan kembalinya pemerintahan kolonial Eropa; persis kehidupan sebelum Jepang masuk.
Memang sudah ada beberapa tuntutan berakhirnya kolonialisme Eropa, dan harapan kemerdekaan tanah jajahaan. Sedikit demi sedikit orang Eropa menyadari, bahkan bersimpati pada, tuntutan kemerdekaan kaum terjajah. Tetapi semuanya membayangkan bahwa kemerdekaan akan diberikan secara bertahap dari penjajah Eropa ke bangsa terjajah. Itu pun melalui tawar-menawar berkepanjangan. Ratu Belanda dan pemerintahan Hindia Belanda sudah merancang beberapa usulan bentuk dan proses kemerdekaan untuk Indonesia.
Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan Sukarno-Hatta, 17 Agustus 1945, merupakan keajaiban yang tak terbayangkan sebagian besar orang di negeri ini. Apalagi di bagian dunia lain. Bahkan peristiwa itu tak terbayang dalam benak mereka yang menyiapkan dan membacakan teks proklamasi jauh-jauh hari sebelumnya. Semua terjadi mendadak dan tergesa.
Inilah pertama kalinya di dunia ada bangsa terjajah memproklamasikan kemerdekaan secara sepihak tanpa perundingan dengan bangsa lain. Tampaknya tidak ada satu pun pihak yang benar-benar siap menghadapi kenyataan Indonesia merdeka, dan pelbagai implikasinya. Juga pemerintah RI sendiri.
Indonesia kalang kabut ketika Sekutu dan Belanda menolak kemerdekaan itu dan menjawabnya dengan kekuatan militer. Pemerintah RI sendiri belum cukup siap menjalankan roda pemerintahan. Negara yang baru diproklamasikan dalam keadaan porak poranda seusai Perang Dunia dan revolusi sosial pada tahun-tahun sesudahnya dalam kondisi lemah, baik secara fisik maupun hukum dan ekonomi.
Pertikaian internal di kalangan elite politik tak kunjung habis. Kabinet dan perdana menteri silih berganti. Sementara dalam masyarakat terjadi kekerasan, penjarahan, pembunuhan, perkosaan terhadap minoritas Eropa, Indo, Ambon, dan Tionghoa.
Sikap Australia terhadap Kemerdekaan Indonesia
Dunia pun kaget dan bingung menghadapi kenekatan Indonesia yang menyatakan kemerdekaan secara mendadak itu. Tanggapan mereka bermacam-macam. Sebagian besar anggota Sekutu ingin mengembalikan kekuatan kolonial Eropa seperti sebelum pendudukan Jepang.
Australia mengambil sikap paling radikal dan berbeda. Untuk kepentingannya sendiri, Australia menjaga jarak dari mental kolonialisme dan mendukung kemerdekaan RI, sebagai tetangga terdekat.
Australia merupakan negara asing pertama yang mengirimkan utusan ke Jakarta untuk menyambut proklamasi itu. Utusan itu terdiri dari dua orang. Yang pertama seorang dosen ilmu politik bernama Macmahon Ball. Kedua, seorang asisten dosen (tutor) berusia 23 tahun bernama Joe Isaac.
Keduanya berkenalan dengan Sukarno, Hatta, Sjahir dan sejumlah tokoh dalam pemerintahan RI yang baru lahir, dan menyatakan dukungan kepada bayi Republik yang menghadapi ancaman serbuan dari Sekutu.
Sejak itu pemerintahan RI menaruh harapan besar pada dukungan Australia. Selama empat tahun berdarah-darah berikutnya (1946-1949), RI meminta Australia menjadi wakilnya di sejumlah persidangan di PBB untuk menyelamatkan nasib negeri yang telanjur memproklamasikan kemerdekaan. Usaha itu tidak sia-sia. Pengakuan resmi dunia atas kedaulatan RI tercapai pada akhir 1949.
Kesaksian Joe Isaac
Tanggal 29 Maret 2018 merupakan hari yang bahagia untuk saya. Pada hari itu saya berjumpa dan mewawancarai Joe Isaac di rumahnya di Melbourne, atas kebaikan putranya Graeme Isaac. Kisah Joe dalam misi politik mewakili Australia ke Batavia jelas sangat memukau. Tetapi yang tidak kalah mengesankan adalah sosok dan penampilannya sendiri.
Tahun ini Joe berusia 96 tahun. Ia hidup seorang diri di rumahnya yang besar dan asri. Istrinya baru meninggal setahun lalu—setelah 70 tahun mereka hidup mesra. Kemana-mana dia mengemudikan mobil sendiri dan masih aktif terlibat dengan pelbagai kegiatan sosial.
Pendengaran, penglihatan, dan pemikirannya setajam orang sehat pada usia 40-an. Humornya segar. Hanya lututnya agak lemah. Ia butuh alat untuk berjalan.
Saya bertanya, bagaimana ceritanya ia bisa terpilih menemani Macmahon Ball mewakili Australia dalam sebuah misi politik dalam kunjungan ke Batavia?
Ternyata, Indonesia bukan negeri yang asing bagi Joe.
Joe lahir di Penang (Malaya) pada 1922. Ayahnya, yang lahir dan besar di Bagdad, merantau ke jajahan Inggris itu untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tiga tahun kemudian Joe ikut dibawa orangtuanya pindah ke Semarang dan Ungaran (Jawa Tengah). Mereka hidup di sana selama hampir 10 tahun.
Di Jawa Tengah, Joe tumbuh dan dididik di sekolah dasar dan menengah untuk orang Belanda. Salah satu teman sekolahnya adalah Oei Tiong Ham, si raja gula.
“Bahkan pada masa itu ada nama jalan dengan menggunakan nama Oei,” kata Joe.
Di rumah, Joe berbahasa Inggris. Di sekolah, ia berbahasa Belanda. Dalam pergaulan sehari-hari, ia berbahasa Melayu/Indonesia dan Jawa.
Ketika Jepang menyerbu Hindia Belanda dan Malaya, ia pindah ke Australia dan menjadi mahasiswa di Melbourne. Untuk program bergelar Honours, ia menulis skripsi tentang hubungan perdagangan Australia dan Hindia Belanda. Dengan bahasa Belanda yang fasih ia mewawancarai sejumlah narasumber Belanda. Karena latar belakang yang langka inilah Macmahon Ball mengajaknya ikut ke Batavia pada 1945.
Ada sebagian dari kisahnya yang lucu dari pertemuan dengan Sukarno-Hatta-Sjahrir di Batavia. Mereka berbincang dalam bahasa Inggris. Sesekali Sukarno kesulitan menemukan istilah bahasa Inggris, lalu bertanya dalam bahasa Belanda pada rekan di sekitarnya: “Hoe zeg je ...” (“Apa bahasa Inggrisnya ...?”).
Kepada saya, Joe menambahkan sambil tergelak: “Mereka bicara satu sama lain dalam bahasa Belanda, dikiranya saya enggak mengerti!”
Joe mengisahkan pengalamannya di Indonesia 70 tahun lalu dengan lancar dan rinci. Seakan-akan semua itu baru terjadi sebulan lalu. Joe adalah sebutir mutiara dalam sejarah RI dan Australia yang, sayangnya, kini nyaris terlupakan oleh kedua negara yang saling bertetangga ini.
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id