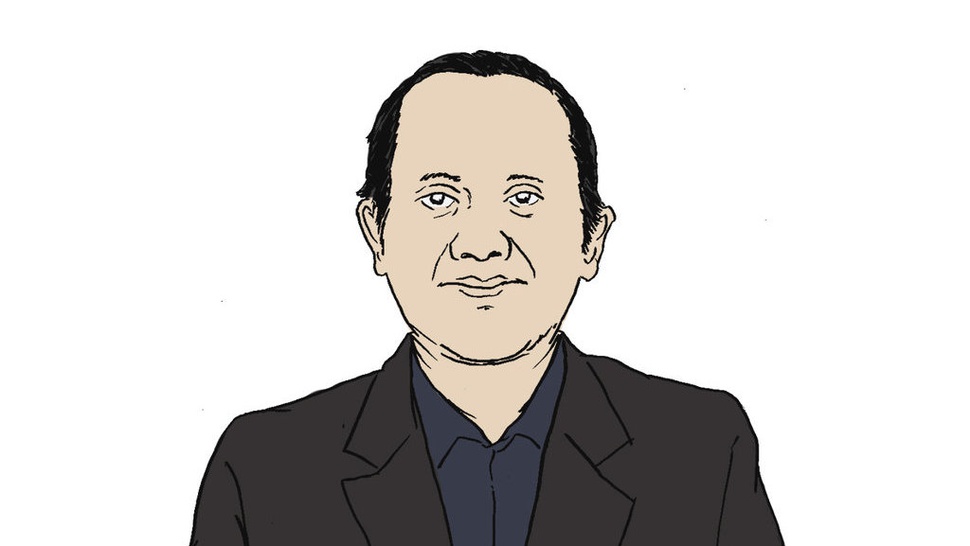tirto.id - "Saya telah berkunjung ke seribu titik lokasi, bertemu masyarakat.... Ada kisah tentang Bapak Najib, seorang nelayan Pantai Pasir Putih di Cilamaya, Karawang. Beliau mengambil pasir untuk ditanam di hutan bakau. Beliau dipersekusi, dikriminalisasi [karena itu]. ” Demikian klaim Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto, Sandiaga Uno dalam debat pertama Pemilihan Presiden Indonesia pada 17 Februari.
Pernyataan Sandiaga dan ceritanya tentang seorang nelayan yang dikriminalisasi secara tidak adil di Karawang langsung memicu keriuhan politik.
Di luar soal benar-tidaknya cerita Sandi, hak-hak nelayan berhasil meraih perhatian publik nasional dalam sebuah forum terkemuka. Jika orang Amerika punya ‘Joe the Plumber’, perwujudan sosok wirausahawan kecil yang merugi akibat tarif pajak yang tinggi, masyarakat Indonesia sekarang memiliki ‘Najib sang Nelayan’, perwakilan dari wong cilik yang menjadi korban dari hukum yang berat sebelah.
Bagi politisi, upaya agar komunitas nelayan mendukung mereka adalah persoalan serius. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan ada hampir satu juta rumah tangga nelayan di Indonesia dan sekitar 2,3 juta nelayan di seluruh nusantara. Meski kuantitasnya terlihat kecil jika dibandingkan dengan total populasi Indonesia, tetapi kelompok ini mewakili seperlima dari total populasi masyarakat pesisir dan memiliki potensi mobilisasi yang kuat. Menjelang pemilihan umum April mendatang, kedua kubu telah berusaha menggalang dukungan dari nelayan.
Ketika menjajaki komunitas nelayan di Jawa Tengah dan Sumatera Utara selama kampanye pemilu 2019, saya menemukan persoalan hak-hak nelayan, yang seringkali dipandang sebagai isu khusus, kini telah menjadi bagian dari wacana politik arus utama. Sayangnya, agensi politik nelayan masih berorientasi pada kebutuhan konsesi jangka pendek, alih-alih pada upaya mendesak perubahan kebijakan yang menguntungkan komunitas nelayan secara keseluruhan.
Dengan karakter organisasi politik yang cenderung lokal dan bersifat ad hoc semata, kelompok nelayan adalah cermin fragmentasi yang berkelanjutan di kalangan masyarakat sipil Indonesia serta keterbatasan peluang kelompok kelas bawah untuk mempengaruhi kontestasi politik.
Hak Nelayan sebagai Masalah Politik
Dalam masa jabatan pertama Jokowi, urusan maritim dan perikanan mulai mendominasi percakapan arus utama tentang politik di Indonesia. Sebagai bagian dari ambisi pembangunan Jokowi, ia membayangkan Indonesia bisa menjadi poros maritim global, yang tak lain adalah pusat utama eksplorasi sumber daya laut dan pesisir.
Ditambah dengan kebijakan nasionalis Menteri Susi, terutama dalam menindak penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, persoalan maritim dan kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan yang rentan secara ekonomi kini tidak pernah absen dari laman berita media Indonesia.
Di sisi lain, tim kampanye Prabowo-Sandi mengajukan proposal kebijakan dengan fokus yang sangat kontras dengan kubu petahana. Dalam manifesto politik Prabowo-Sandi, daftar target yang hendak dicapai tak tangung-tanggung, antara lain: mengurangi kesenjangan antara wilayah pesisir dan pedalaman, meningkatkan anggaran nasional untuk sektor perikanan dan kelautan, menyalurkan lebih banyak skema kredit kepada nelayan, menjamin harga pasar untuk komoditas yang menguntungkan baik nelayan maupun konsumen.
Masalahnya, daftar target janji kampanye yang panjang itu tak disertai paparan tentang cara untuk mewujudkannya.
Di titik ini kita bisa sepakat bahwa persoalan hak nelayan jelas mempengaruhi pemilu 2019. Namun, kebijakan maritim dan perikanan nampaknya akan sama saja, terlepas dari siapa yang berkuasa. Larangan Menteri Susi yang kontroversial tentang penangkapan ikan dengan pukat, misalnya. Sementara para nelayan di pulau-pulau terluar Indonesia menyambut hangat larangan itu, para operator kapal pukat yang berbasis di Jawa mengkritiknya habis-habisan. Akhirnya, Susi menyerah dengan tekanan publik dan mengeluarkan moratorium penundaan larangan tersebut di wilayah Jawa.
Sandiaga Uno turut mengambil kesempatan dalam isu ini. Walaupun belum mengambil sikap yang jelas mengenai kontroversi tersebut, Sandi berjanji untuk mencari solusi tengah yang menguntungkan semua pihak.
Bagaimana Nelayan Terlibat dalam Politik?
Dari kunjungan ke Kendal dan Demak di Jawa Tengah dan Serdang Bedagai di Sumatera Utara, saya menemukan beberapa cara nelayan berpolitik, antara lain menjadi makelar yang menawarkan patronase, beraliansi dengan kandidat lokal yang kooperatif, atau mencalonkan diri dalam pemilihan lokal.
Sebuah cerita dari desa Gempolsewu di kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menggambarkan cara kerja patronase di komunitas nelayan. Saya mendapati kasus klasik di mana seorang tokoh lokal yang menjabat ketua kelompok usaha bersama (KUB) nelayan setempat berperan sebagai perantara antara warga dengan kandidat politik. Nashikin, ketua KUB ini, adalah tokoh kunci yang dapat memelihara (atau memutus) hubungan antara komunitasnya dengan politisi pencari suara.
Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat nasional, komunitas Nashikin diwakili oleh Fadhloli dari partai Nasdem yang pro-Jokowi. "Saya mengapresiasi apa yang telah dia lakukan untuk kami," kata Nashikin. Baginya, Fadhloli adalah jenis politisi langka yang rutin mengunjungi konstituennya dan berjuang untuk mereka—sebagian besar dilakukan dengan melobi pemerintah kabupaten setempat untuk memberikan fasilitas negara bagi para nelayan, seperti jaring ikan. "Ada caleg-caleg yang datang tapi setelah itu lupa (dengan kami). Makanya kami tidak akan memilih mereka lagi," tambahnya.
Hubungan komunitas Nashikin dengan anggota parlemen mereka mencerminkan pola yang jamak terjadi dalam dinamika pemilu lokal di Indonesia, di mana merekrut jaringan lokal dan makelar yang tepat adalah perkara serius.
Komunitas nelayan lainnya menempuh strategi yang berbeda. Aliansi dengan kandidat lokal berfungsi sebagai strategi untuk menagih imbalan yang sejalan dengan kepentingan nelayan. Sugeng, ketua kelompok nelayan lokal lain di Kendal bernama Mina Agung Sejahtera, mengatakan kepada saya bahwa “Pilpres tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah memiliki perwakilan di tingkat lokal.”
Untuk pemilihan legislatif lokal mendatang, Sugeng memberikan dukungannya untuk Mifta Reza Noto Prayitno, seorang anggota parlemen dari partai milik Prabowo, Gerindra, yang memenangkan kursi DPRD dari wilayah Jawa Tengah pada Pileg 2014 lalu. “Karena dia mendukung kepentingan kami. Dia bahkan menggunakan uangnya sendiri untuk mengunjungi kami,” kata Sugeng.
Pendapat serupa dilontarkan Masnu’ah, pemimpin Puspita Bahari, organisasi perempuan yang bekerja di komunitas nelayan di kabupaten Demak. Dia berkata, “Partai politik tidak terlalu penting bagi saya... Sekarang saya lebih melihat kandidatnya.”
Selangkah lebih maju, beberapa nelayan mencalonkan diri dan ikut bertarung di pemilihan lokal. Sulyati, seorang guru dari keluarga nelayan di Gempolsewu, Kendal, mencoba peruntungannya dan maju di pemilihan anggota parlemen daerah pada 2014 dengan tiket dari Gerindra. Meski hampir memenangkan kursi saat itu, dia memutuskan tidak nyaleg tahun ini. “Awalnya saya menyalonkan diri karena dorongan teman-teman saya. Sekarang saya memilih untuk fokus pada kerja-kerja di komunitas saya, ”katanya.
Pemimpin komunitas sekaligus nelayan dari Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara, Sutrisno, juga mencalonkan diri untuk kursi di parlemen tingkat kabupaten, di bawah payung partai PKB yang pro-Jokowi. “Saya pikir penting untuk memiliki seseorang yang dapat menjaga kepentingan kita di tingkat lokal,” ujar Sutrisno.
Lewat aliansi dengan patron politik seperti anggota parlemen, mereka dapat langsung menuai hasil. Sementara, bertarung langsung dalam pemilihan lokal lebih berisiko. Kandidat yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan bisa kalah dan menyurutkan semangat pendukungnya. Namun demikian, Sulyati dan Sutrisno cukup puas dengan pengalaman pemilihan mereka. Walau kalah, pengalaman itu tidak merusak semangat Sulyati.
Sutrisno cukup percaya diri dengan prospeknya untuk 2019. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia sudah memiliki cukup suara untuk memperoleh kursi. Akan tetapi, sebagai aktivis hak-hak nelayan, dia juga membutuhkan dukungan dari para nelayan. Saya bertanya apa yang akan dia lakukan begitu dia terpilih. “Salah satu hal yang akan saya perjuangkan adalah memastikan para nelayan dapat menerima semua subsidi, fasilitas, dan program (yang berhak mereka dapatkan)," jawab Sutrisno. Apa dia terlalu optimis? Kita baru akan mengetahuinya setelah pemilu nanti.
Apa yang Bisa Dipelajari dari Mobilisasi Politik Nelayan?
Para nelayan dan sekutu mereka memiliki pandangan dan strategi berbeda terkait pemilihan. Beberapa mendukung pemerintah, yang lain mendukung oposisi. Banyak yang berpendapat bahwa politik nasional masih penting, tetapi bagi sebagian yang lain, kontestasi lokal justru lebih berperan dalam membentuk kehidupan mereka. Kekuatan gerakan para nelayan terletak pada dua senjata utama: mobilisasi massa dan pemungutan suara.
Konsisten dengan hasil studi akademis tentang gerakan kelas bawah, kekuatan mobilisasi nelayan beserta aksi disruptifnya—mulai dari protes massal hingga penghentian kapal pukat ilegal di laut—kerap berhasil membuat elite menyerah pada tuntutan mereka. Keberhasilan ini biasanya diikuti sejumlah perubahan pada kebijakan lokal perubahan dan penguatan demokrasi lokal.

Namun, di tingkat nasional, para nelayan terbagi-bagi berdasarkan afiliasi organisasi masing-masing. Ada lima serikat nelayan. Empat serikat nelayan adalah serikat independen, yaitu Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), dan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI). Sedangkan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), merupakan organisasi korporatis bentukan Orde Baru untuk menaungi nelayan.
Dinamika pemilu belakangan semakin memperuncing perpecahan ini. “Suara nelayan memang terfragmentasi,” ujar Parid Ridwanuddin, aktivis KIARA, sebuah organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir dan nelayan. "Mendekati pemilihan ini," ia menambahkan, "suara mereka juga terbagi antara Jokowi dan Prabowo." Fragmentasi semacam itu melemahkan kekuatan politik mereka. Walhasil, daya tawar mereka untuk mengajukan alternatif kebijakan nasional di isu kelautan dan perikanan—membatasi ekspansi modal besar di wilayah pesisir atau membendung kekuatan jejaring patronase lokal yang ada—akhirnya pun jadi terbatas.
Namun, di luar keterbatasan mereka, keterlibatan politik nelayan penting untuk penguatan demokrasi di Indonesia. Mereka adalah wujud partisipasi baru dari kelompok kelas bawah dan terpinggirkan. Keterlibatan semacam itu penting untuk mengarahkan kembali debat politik ke masalah nyata, yang berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat. Dengan menjauh dari politik populis yang mengeksploitasi agama dan membicarakan masalah aktual, seperti kesenjangan ekonomi dan konflik antar kelas, politisi mau tak mau dituntut oleh mereka untuk memberikan solusi konkret.
Catatan penulis: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KIARA dan anggota masyarakat desa-desa nelayan di Kendal, Demak, dan Serdang atas bantuan mereka selama kerja lapangan saya.
------------------
Sebelum diterjemahkan oleh Levriana Yustriani, tulisan ini terbit dalam bahasa Inggris di New Mandala dengan judul "Fishing for votes in Indonesia". Penulisnya, Iqra Anugrah, adalah research associate pada Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Jakarta Pusat. Selama Pemilu 2019, ia menjadi New Mandala Indonesia Correspondent Fellow yang menulis isu lingkungan dan sumber daya alam.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.