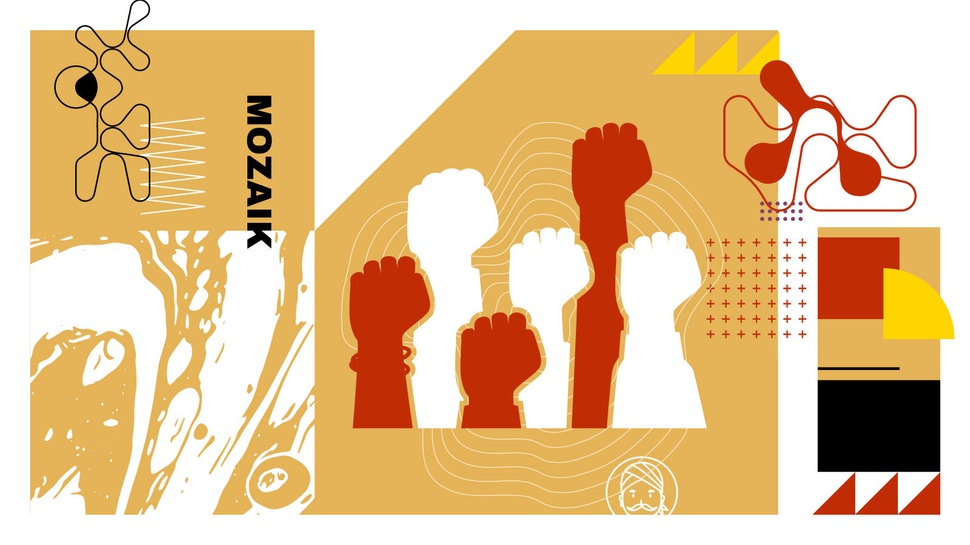tirto.id - Louisa Johanna Theodora “Wieteke” van Dort baru berusia 14 tahun ketika menginjakkan kaki di Belanda untuk pertama kalinya pada akhir 1957. Seniman Belanda kelahiran Surabaya tersebut harus beradaptasi dengan cuaca dan suasana yang serba baru. Tidak ada lagi kehangatan cuaca tropis dan makanan Indonesia yang kaya rasa.
Sebagai anak yang tumbuh di Indonesia, situasi macam itu menyulitkannya. Dia tak terbiasa dengan makanan Negeri Kincir Angin yang menurutnya tak bercita rasa. Bahkan, makanan yang disuguhkan di kapal selama perjalanan dari Indonesia ke Belanda dianggapnya masih lebih baik.
Sampai akhirnya, tiga dekade kemudian, Wieteke mencurahkan kerinduannya terhadap tanah kelahirannya melalui lagu bertajuk Geef Mij Maar Nasi Goreng (Beri Aku Nasi Goreng). Dengan alunan musik keroncong, Wieteke menceritakan nasib masa remajanya yang terdampak politik repatriasi sembari tergiang-ngiang kenangan akan nikmatnya lontong, sate babi, serundeng, bandeng, tahu petis, kue lapis, onde-onde, atau bakpao.
Wieteke adalah satu dari puluhan ribu orang Belanda yang terpaksa angkat kaki dari Indonesia akibat memuncaknya sentimen terhadap orang-orang Belanda pada pertengahan 1950-an. Sentimen anti-Belanda itu adalah buah dari macetnya perundingan terkait status Irian Barat.
Pada Agustus 1957, Indonesia dan beberapa negara pendukungnya berhasil memasukkan pembahasan soal Irian Barat ke agenda Sidang Umum PBB. Keberhasilan ini tentu menjadi pencapaian luar biasa bagi Indonesia. Pasalnya, itu menerbitkan titik cerah dalam masalah yang sudah menggantung sejak 1950.
Menurut Thomas J. Lindblad dalam artikelnya yang terbit di Historiek, persoalan status Irian Barat kemudian bergaung di forum PBB selama beberapa bulan setelahnya. Pihak Indonesia menaruh ekspektasi tinggi bakal diuntungkan oleh menguatnya wacana itu.
Pada Oktober 1957, Presiden Sukarno lantas meluncurkan kampanye Pembebasan Irian Barat di Jakarta. Sebulan kemudian, Sukarno menyuarakan kemungkinan pengambilalihan aset-aset perusahaan Belanda di Indonesia jika Indonesia gagal mendapatkan dukungan internasional terkait konflik Irian Barat.
Kampanye itu kian menghangat oleh menguatnya sentimen anti-Belanda. Suara demonstrasi di jalanan kota semakin santer terdengar. Apapun yang dimiliki orang Belanda menjadi sasaran vandalisme. Seperti yang tampak usai peringatan Sumpah Pemuda di Istana Negara, mana kala beberapa kantor-kantor perusahaan besar Belanda di Jakarta seperti Nationale Handels Bank dan Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) dirisak.
Dinding dan tembok kantor-kantor perusahaan Belanda itu tiba-tiba dipenuhi coretan provokatif. “USIR BELANDA!”, “USIR BELANDA DARI IRIAN BARAT!”, atau “PEMUDA2, PANGGUL SENDJATA REBUT IRIAN BARAT!” adalah kata-kata yang sering muncul. Kendaraan warga Belanda, kios bensin, dan bahkan toko buku seperti Van Dorp dan Kolff pun kena.
Siaran radio pun banyak diisi oleh propaganda anti-Belanda. Di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang, orang Belanda bahkan tidak lagi diperbolehkan masuk ke restoran, bioskop, toko-toko, hingga dilarang mengisi bahan bakar.
Sayangnya, harapan tinggi Indonesia tidak terwujud. Tekanan-tekanan macam itu rupa-rupanya tak mempan juga menyedot perhatian PBB, apa lagi Belanda. Pada 29 November Indonesia gagal memperoleh suara mayoritas di PBB untuk mendesak Belanda berunding.
Mendengar kabar ini, Presiden Sukarno langsung marah besar. Kemarahan tersebut juga diikuti oleh sebagian rakyat Indonesia lainnya dengan menyasar perusahaan-perusahaan Belanda.
Memuncaknya Amarah
Menurut sejarawan M.C Rickfles dalam Sejarah Indonesia Modern (1999, hlm. 394), gagalnya lobi Indonesia di PBB itu memicu terjadinya ledakan radikalisme anti-Belanda.
Dua hari setelah keputusan PBB, Kabinet Djuanda membahas langkah-langkah untuk melawan Belanda. Salah satunya dengan mencabut hak pendaratan pesawat-pesawat KLM. Pemerintah Indonesia juga melarang peredaran surat kabar dan film Belanda. Peristiwa besar terjadi pada 3 Desember 1957, kala serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengan PKI dan PNI melakukan aksi pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda.
Salah satu saksi ketegangan aksi anti-Belanda saat itu ialah Ruurd Koopmans, mantan pegawai KPM Jakarta. Dalam acara TV Andere Tijden, Koopmans mengisahkan tidak ada lagi suasana damai yang menyelimuti gedung KPM sejak hari itu. Di kantornya, banyak terdengar suara teriakan yang sangat lantang dan keras seperti perampokan.
Tidak lama berselang, Koopmans juga diberitahu bahwa bos-bosnya sudah dibebastugaskan dan menyerahkan pekerjaannya kepada staf non-Belanda. Saat itu, dia langsung menyadari kariernya di KPM juga telah berakhir.
Puncak kemarahan terjadi pada 5 Desember 1957—tepat hari ini 64 tahun lalu. Kala itu, Sukarno melalui Departemen Kehakiman secara resmi mengusir 46.000 orang Belanda yang masih bermukim di Indonesia.
Ironisnya, hari itu seharusnya jadi momen perayaan Sinterklas—dengan acara tukar kado dan bernyanyi bersama—di kalangan orang-orang Belanda. Momen yang seharusnya dilambari suka cita itu lantas jadi duka cita. Karenanya, peristiwa ini kelak dikenal sebagai peristiwa Sinterklas Hitam.

Masa-Masa Kelam
Pengumuman Soekarno tersebut menjadi klimaks kepanikan orang-orang Belanda. Mereka berada di posisi sulit: tidak bisa melawan dan berdiam diri lebih lama di kediamannya. Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan angkat kaki dari Indonesia. Banyak orang Belanda yang kemudian mencairkan seluruh tabungannya dan bergegas membeli tiket pesawat untuk keluar dari Indonesia. Tidak sedikit pula yang harus berebut untuk mendapatkan satu tempat di kapal laut.
Kekacauan macam itu tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga menjalar ke seluruh daerah di Indonesia. Di Bandung, misalnya, pengemudi becak tidak mau membawa penumpang orang Belanda. Di Malang dan Surabaya, produk-produk asal Negeri Kincir Angin diboikot dan orang Belanda dilarang masuk toko.
Seorang istri diplomat Belanda bernama Constance Huydecoper, dalam acara Andere Tijden, menuturkan bahwa banyak rekan-rekan Belandanya yang dilanda kepanikan usai Sukarno mengumumkan pengusiran.
“Kawan saya langsung menyembunyikan barang-barang peraknya dan buru-buru menghilang, keluar dari Indonesia. Semua konsulat tutup. Kami semua saling menelepon dan bertanya apa yang terjadi,” tutur Huydecoper.
Narasumber lain, Libert Hol, bahkan mengalami nasib yang lebih buruk. Dia tidak bisa membawa orang tuanya berobat karena rumah sakit menolak pasien orang Belanda.
Hengkang dari Indonesia secara mendadak juga bukanlah pilihan mudah. Mereka yang sudah bertahun-tahun hidup di Indonesia itu buta akan situasi di negeri Belanda. Namun, mereka toh tetap berebut naik kapal-kapal yang disediakan pemerintah Belanda karena terpaksa.
Dengan jumlah puluhan ribu orang, kondisi kapal pengangkut pun langsung penuh sesak. Mereka harus tahan berdesak-desakan selama berhari-hari dalam perjalanan ke Belanda.
Menurut Lindblad, eskodus orang-orang Belanda itu setidaknya berlangsung hingga Agustus 1958. Selama itu, diperkirakan mencapai 33.600 orang Belanda keluar dari Indonesia.
Eksodus itu kemudian juga berdampak pada dinamika ekonomi dalam negeri. Pasalnya, banyak sektor perekonomian Indonesia hingga saat itu dipegang oleh orang Belanda. Ketika mereka pergi, banyak perusahaan jadi kacau karena penggantinya belum tentu cakap. Maka terjadilah salah urus dan ketidakefisienan.
Dalam kasus KPM, misalnya, perebutan perusahaan tersebut membawa konsekuensi serius bagi rakyat Indonesia. Lalu lintas pelayaran yang terhenti memicu perlambatan distribusi bahan pangan dan kemudian membuat harga-harga pangan meningkat di beberapa daerah.
Penulis: Muhammad Fakhriansyah
Editor: Fadrik Aziz Firdausi