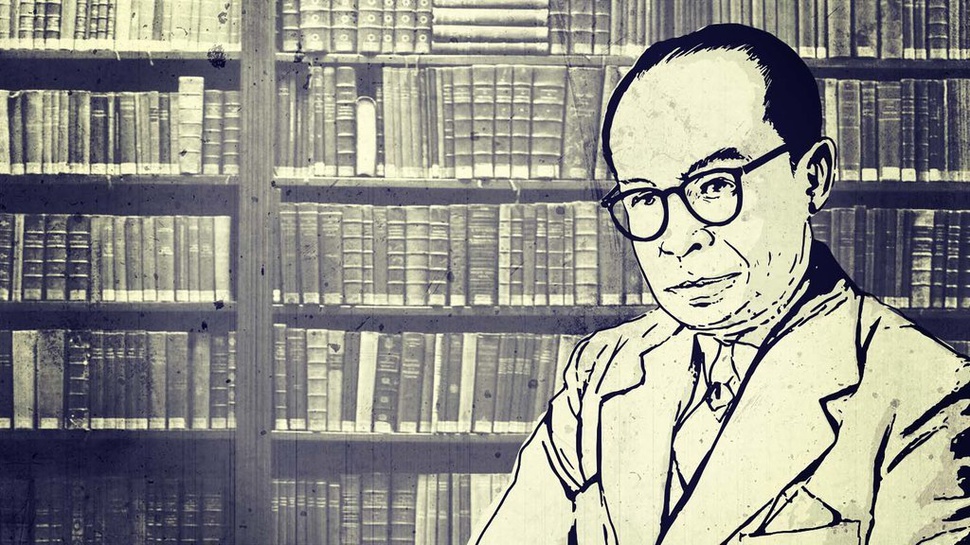tirto.id - Suatu hari di tahun 1960, dalam perjalanan kereta api dari Yogyakarta ke Jakarta, Mohammad Hatta berbincang dengan Pak Wangsa, sekretarisnya, “… sejarah dunia memberi petunjuk bahwa diktator yang bergantung kepada kewibawaan orang-seorang tidak lama umurnya.”
Kisah itu diceritakan Sergius Sutanto dalam Hatta: Aku Datang Karena Sejarah (2013). “Sebab itu pula,” imbuh Hatta, “sistem yang dilahirkan Sukarno tidak akan lebih panjang umurnya dari Sukarno sendiri… Apabila Sukarno tidak ada lagi, maka sistemnya itu akan roboh dengan sendirinya seperti sebuah rumah dari kartu” (hlm. 275-276).
Ramalan Hatta, yang juga terekam dalam tulisan berjudul “Demokrasi Kita” yang dimuat Pandji Masjarakat, itu ternyata terbukti. Kejatuhan Sukarno mulai tampak beberapa warsa berselang, setelah terjadinya insiden berdarah Gerakan 30 September (G30S) 1965.
Dari titik krusial itulah, Bung Karno, yang dulu sangat digdaya, kian tak berdaya. Soeharto yang kemudian menampilkan dirinya sebagai juru selamat mulai menggerus pengaruh sang penyambung lidah rakyat.
Baca juga: Jika Supersemar Palsu, Apakah Orde Baru Tidak Sah?
Orde Lama akhirnya tumbang pada 1968 seiring ditetapkannya Soeharto sebagai Presiden RI yang baru. Dimulai lah upaya sistematis, masif, dan terstruktur untuk merombak semua ajaran, pengaruh, serta apapun yang melekat pada sosok penguasa beserta rezim sebelumnya.
Dan, seperti kata Bung Hatta, segala macam gagasan sekaligus sistem yang dibangun Sukarno ambruk. Sesuatu yang kelak juga dituai Soeharto karena sebab yang sama: kediktatoran.
Mundur Atas Nama Prinsip
Genap satu dekade setelah ditetapkan sebagai Wakil Presiden RI untuk mendampingi Sukarno pada 17 Agustus 1945, Hatta tampaknya mulai tidak nyaman duduk di kursi jabatannya.
Sebelum Pemilu 1955, Hatta menyatakan, apabila parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, maka jabatan wapres akan ia lepaskan. Saat negara memiliki kabinet parlementer, sebut Hatta, sosok kepala negara hanyalah simbol semata. Dengan begitu, peran wakil presiden tidak dibutuhkan lagi.
Pikiran semacam itu sudah menggelayut di benak Hatta sejak lama. Seperti diungkap Wawan Tunggul Alam dalam Demi Bangsaku: Pertentangan Bung Karno vs Bung Hatta (2003), jika tetap menjadi wakil presiden dalam sistem parlementer, Hatta tidak bisa aktif mengurus pemerintahan, sulit berperan langsung membangun negeri (hlm. 252).
Dan ketika parlemen (DPR) dan Konstituante pilihan rakyat akhirnya terbentuk dari hasil Pemilu 1955, Hatta kembali menegaskan tekadnya untuk menanggalkan jabatan wapres. Secara resmi, keinginan itu dituangkan melalui surat tertanggal 20 Juli 1956 yang ditujukan kepada Mr. Sartono selaku Ketua DPR.
Dikutip oleh Deliar Noer dalam Mohammad Hatta: Biografi Politik (1990), Wakil Presiden RI pertama itu menulis, "… setelah DPR yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Segera, setelah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi” (hlm. 482).
Baca juga: Sejarah Monas dan Ironi Cita-cita Bung Karno
Mr. Sartono dan segenap anggota parlemen tampaknya sepakat untuk tidak membalas surat itu, dengan harapan Hatta mengurungkan niatnya. Namun, Hatta rupanya benar-benar serius. Dikirimkanlah surat kedua pada 23 November 1956 dengan isi yang kurang lebih sama. Kali ini, Hatta menegaskan bahwa ia akan benar-benar mundur pada 1 Desember 1956.
DPR kali ini tak kuasa menolak. Maka, dalam sidang pada 30 November 1956, parlemen memberikan persetujuan atas pengunduran diri itu. Hanya sehari berselang, 1 Desember 1956—tepat hari ini 61 tahun lampau—Hatta resmi bukan sebagai Wakil Presiden RI lagi.
Dwitunggal yang Terpenggal
Bukan lantaran persoalan parlementer saja yang membuat Hatta merasa tidak nyaman menjalankan pemerintahan bersama Sukarno. Naga-naganya, Hatta memang sudah tidak sepaham lagi dengan sang presiden dalam beberapa hal yang prinsipil.
Selain ketidaksetujuan Hatta atas tindakan Sukarno yang memasukkan unsur komunis dalam kabinet yang dibentuk 24 Maret 1956, perbedaan pandangan antara dua tokoh ini sebenarnya sudah berlangsung sangat lama, bahkan saat keduanya masih sama-sama berjuang di era pergerakan nasional pada era 1930-an.
Hatta tampaknya tidak terlalu sepakat dengan gagasan persatuan yang digaungkan Sukarno kala itu. Bahkan, pada 1932, Hatta sudah mengkritisi ide Sukarno tersebut.
“Apa yang dikatakan persatuan sebenarnya tidak tak lain dari per-sate-an. Daging kerbau, daging sapi, dan daging kambing, disate jadi satu. Persatuan segala golongan ini sama artinya dengan mengorbankan asas masing-masing,” tukas Hatta dalam tulisannya di surat kabar Daulat Ra’jat (1932).
Baca juga: Beda Sukarno dan Sjahrir tentang Partai Politik

Relasi keduanya memang mengalami pasang-surut. Sempat mereda selama belasan tahun hingga Indonesia merdeka, pertentangan Sukarno-Hatta kembali menyeruak pada November 1945. Saat itu, Sukarno menolak mengesahkan Maklumat No. X yang menjadi pintu masuk sistem multipartai dan demokrasi parlementer.
Sukarno tidak pernah setuju dengan gagasan multipartai karena menurutnya jumlah partai politik sudah seharusnya dibatasi agar mudah dikendalikan—sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan Hatta.
Situasi yang kian memanas itu mencapai puncaknya pada 1956. Seperti dikutip Syamsuddin Haris dalam Demokrasi di Indonesia (1995), Sukarno selaku presiden mencanangkan sistem Demokrasi Terpimpin, dan berseru: “Marilah sekarang kita kubur semua partai!” (hlm. 118).
Hatta tentu saja kecewa. Ia mengecam konsep Demokrasi Terpimpin ala Sukarno sebagai bentuk kediktatoran. Hatta bahkan, seperti dikutip Herbert Feith & Lance Castles dalam Pemikiran Politik Indonesia, 1945 1965 (1988) menyebut Sukarno adalah diktator (hlm. 63).
Itulah fragmen penting yang akhirnya berujung pengunduran diri Hatta dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Baca juga: Cara Legendaris ala Hatta Mengkritik Sukarno
Setelah meninggalkan istana, Hatta mencurahkan waktu dengan mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat di Bandung. Hatta sepenuhnya sadar bahwa Sukarno tidak akan membiarkannya hidup tenang meskipun ia sudah tidak terlibat lagi dalam pusaran kekuasaan. Dan memang itulah yang terjadi.
Setelah 4 tahun menjalani aktivitas di ranah akademis, tugas Hatta mendadak dipungkasi. Hatta paham betul bahwa itu tidak menimpanya begitu saja tanpa campur tangan kekuasaan.
Suatu hari di tahun 1960, dalam perjalanan pulang dengan kereta api dari Yogyakarta menuju Jakarta, seperti dikisahkan Sutanto, Hatta berkata kepada Pak Wangsa, “Tak apalah. Pada prinsipnya, toh saya tidak bisa menjadi perpanjangan tangan kebijakan pemerintah yang kuanggap salah.” (hlm. 276).
“Sampai jumpa wahai segala pepohonan yang telah menghijaukan negeri ini. Sampai jumpa di masa yang lebih arif memandang demokrasi,” lanjutnya lirih.
Penulis: Iswara N Raditya
Editor: Ivan Aulia Ahsan