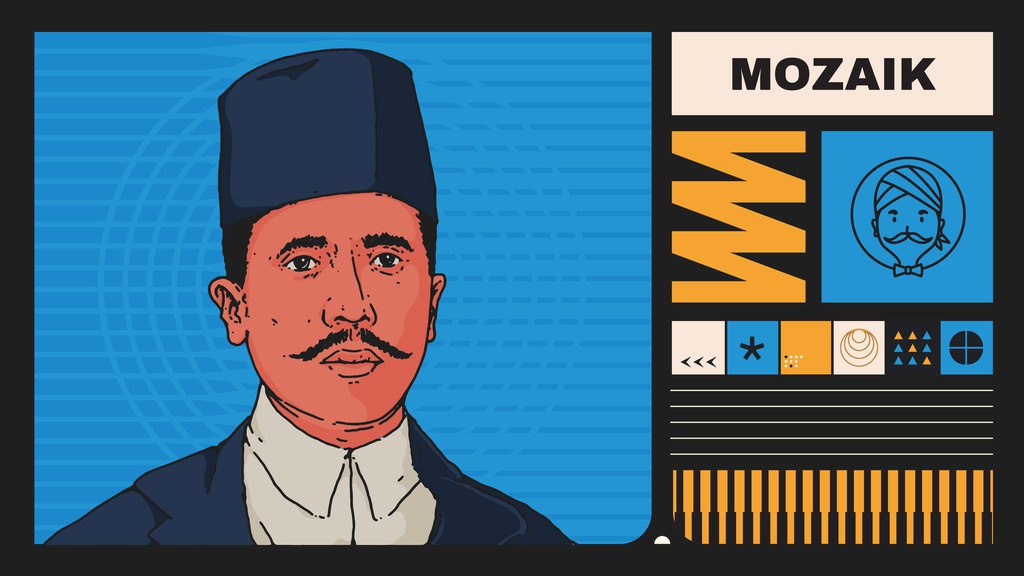tirto.id - Suatu hari, mengenakan kacamata daun pandan buatan kakeknya, Hamka kecil mengaku sebagai mantri cacar kepada sepuluh anak-anak di sekitar rumahnya. Tak ada yang menyangkal, semua menuruti apa yang dikatakannya.
Praktik pun dimulai. Ia mencacar duri jeruk limau ke setiap lengan anak-anak. Sontak, beberapa dari mereka berdarah dan menangis.
Lakonnya sebagai mantri gadungan membuat ayahnya, Haji Rasul, berang dan hendak memukulnya dengan tongkat sebagai hukuman. Tak berani melawan, Hamka hanya menjerit, "ampun Abuya, ampun!"
Beruntung, ada dua orang yang mencegahnya, "dia sudah minta ampun, Engku! Dia sudah minta ampun!"
Pemukulan urung terjadi. Kepada Hamka, ayahnya berkata, "akan engkau ulangi?"
"Ampun Abuya, ampun."
"Sekarang boleh pulang, lekas mandi, jangan kotor bajumu," kata ayahnya seperti ditulis Hamka dalam Kenang-Kenangan Hidup (2018).
Bagi Haji Rasul, kenakalan semacam itu tidak dapat dimaklumi. Ia menghendaki anaknya giat belajar, khususnya mendalami agama Islam, agar kelak dapat menjadi penerusnya sebagai ulama.
Antara Minangkabau dan Makkah
Dalam Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera (1982), Hamka mencatat bahwa ayahnya lahir dengan nama Muhammad Rasul pada 10 Februari 1879 di Jorong Betung Panjang, Nagari Sungai Batang Maninjau, Luhak Agam.
Ia anak ketiga dari tujuh bersaudara. Ayahnya, Syekh Muhammad Amrullah gelar Tuanku Kisai, merupakan cucu dari Syekh Abdullah Arif gelar Tuanku Pariaman--ulama Padri yang memimpin pertahanan di wilayah Matur, Lawang, dan Andalas--sedangkan ibunya bernama Tarwasa.
Ia dikaruniai tujuh anak. Beberapa di antaranya Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), Abdul Wadud Karim Amrullah (Awka), dan Abdul Bari Karim Amrullah, masing-masing lahir dari rahim Syafiyah, Hindun, dan Rafi’ah.
Di kemudian hari, Haji Rasul menjadi mertua dari A. R. Sutan Mansur, tokoh Muhammadiyah dan Masyumi, setelah menikahi putri sulungnya, Fathimah, yang lahir dari istri pertamanya Raihanah.
Dari nama-nama istri tersebut, pernikahan dengan Hindun menjadi yang bertahan paling lama. Namun, saat ia diasingkan ke Sukabumi, Haji Rasul memilih ditemani istrinya yang lain, Dariah.
Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah menempuh sekolah formal, seperti sekolah Raja, yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda. Ia hanya memperoleh pendidikan agama dari ayahnya dan ulama-ulama di Minangkabau dan Makkah.
Saat berusia 7 tahun, ia mulai belajar salat dan puasa. Setelah itu, hingga usia 16 tahun, ia telah menuntaskan pelajaran agama, mulai dari Al-Qur’an, nahwu & saraf, tafsir Jalalain, dan kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi.
Pada 1894, ia pergi ke Makkah dan berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi selama tujuh tahun. Di samping itu, ia juga belajar kepada Syekh Abdullah Jamidin hingga Syekh Yusuf Nabhani yang mengarang kitab Al-Anwarul Muhammadiyah.
Sekembalinya ke tanah Minang, ia mendapat gelar "Tuanku Syekh Nan Mudo". Pengalamannya belajar di Makkah, turut membentuk sikap dan pemikirannya untuk menegakkan kemurnian Islam di Minangkabau dari tradisi adat, sihir, bid’ah, dan tarekat-tarekat yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.
Namun, untuk sementara waktu, hal itu tidak ditentangnya secara terang-terangan. Sebab, bukan perkara mudah baginya, mengingat ayahnya merupakan ulama Naqsyabandiyah--tarekat yang pemahamannya ditentang olehnya.
Menjadi Bagian Kaum Mudo
Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Makkah untuk mengantarkan adiknya menuntut ilmu. Bersamaan dengan itu, ia hendak berguru kembali ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi guna memperdalam ilmunya.
Namun, karena dianggap sudah memiliki ilmu yang cukup, ia justru disuruh untuk mengajar oleh gurunya tersebut.
Beberapa waktu kemudian, ia melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana kebiasaan orang-orang pada masa itu, setelah ibadah haji ia mengganti namanya dari Muhammad Rasul menjadi Haji Abdul Karim. Namun, orang-orang lebih sering memanggilnya dengan nama Haji Rasul.
Pada 1906, ia pulang ke kampung halaman. Kegiatan dakwah dan pengajaran mulai dilakukan, dari kampung hingga kota, di wilayah Padang, Padang Panjang, Matur, dan Maninjau.
Penentangan terhadap segala tradisi adat, perilaku bid’ah, dan tarekat-tarekat yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, tetap menyala. Bahkan, kali ini dilakukannya secara terang-terangan, terutama setelah ayahnya, Tuanku Kisai, wafat pada tahun 1907.
"Pendekatan yang ia lakukan bersifat keras, tanpa maaf dan tanpa kompromi. Tabligh-tablighnya ditandai oleh kecaman dan serangan terhadap segala perbuatan yang tidak disetujuinya," tulis Deliar Noer dalam Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942 (1982).
Seturut Seno dalam Peranan 'Kaum Mudo' dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Minangkabau 1803-1942 (2010, PDF), pada 1910 ia mulai menetap dan mengajar di Sungai Batang Maninjau.
Namanya semakin dikenal luas. Bersama Haji Abdul Ahmad dan Syekh Muhammad Jamil Jambek, mereka dikenal sebagai ulama modernis yang menggagas pembaruan pendidikan Islam di Sumatra Barat.
Bersamaan dengan itu, ulama di Minangkabau terbelah. Haji Rasul dan ulama-ulama yang menghendaki pembaruan dikategorikan sebagai kaum mudo, sedangkan ulama-ulama tradisional dikategorikan sebagai kaum tuo yang berkoalisi dengan kaum adat.
Seturut M. C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2010), dalam perkembangan berikutnya, sebagai bentuk penentangan terhadap ulama reformis, kaum tuo dan kaum adat membentuk organisasi Sarekat Adat Alam Minangkabau yang pro terhadap pemerintah kolonial Belanda.
Memasuki tahun 1911, terbit majalah Al-Moenir yang menjadi corong pembaruan Islam yang digerakkan oleh kaum mudo. Haji Rasul terlibat dalam penerbitan majalah ini sebagai pembantu redaksi.
Majalah ini tidak bertahan lama. Sebab, "percetakan majalah tersebut terbakar habis pada tahun 1916," tulis M. Yuanda Zara dalam Seabad Pers Kebangsaan: Bahasa Bangsa, Tanah Air Bahasa (2007).
Bersamaan dengan itu, Haji Rasul memutuskan pindah ke Padang Panjang dan mengajar di Surau Jembatan Besi. Di bawah pengajarannya, murid-murid didorong untuk berdiskusi, berdebat, dan bereksplorasi terhadap ilmu yang dipelajarinya.
Hal ini dilakukannya guna memantik keberanian pra murid dalam menyampaikan pendapat dan pemikiran, juga "melepaskan kejumudan dan taklid buta terhadap ulama tanpa mengetahui dasar hukumnya," tulis Novita Siswayanti dalam "Haji Abdul Karim Amrullah Ulama Pembaharu Islam di Minangkabau" (Jurnal Dialog Vol. 39, No. 1, Juni 2016, hlm. 33-42).
Menurut Hamka, Haji Rasul sempat melawat ke Malaya untuk memberikan pengajaran. Satu tahun setelah itu, tepatnya pada 1917, ia datang ke Pulau Jawa. Ia menemui beberapa tokoh pergerakan Islam seperti Abdul Muis dan K.H. Ahmad Dahlan.
Ia juga menemui H.O.S. Cokroaminoto. Dalam pertemuan itu, ia diminta untuk terlibat dalam menyebarkan Sarekat Islam di Sumatra Barat. Namun, ia tak menyanggupi permintaan tersebut. Sebab saat itu, ia merasa belum mengerti tentang seluk beluk organisasi politik.
Memasuki tahun 1918, tempat Haji Rasul mengajar, Surau Jembatan Besi, berganti nama menjadi Sumatera Thawalib dan dikenal sebagai lembaga pendidikan agama Islam modern awal di Sumatra Barat.
Setahun kemudian, ia menerbitkan salah satu karya tulisnya berjudul Pertimbangan Adat Lembaga Alam Minangkabau, sebagai kritik terhadap kitab Curai Adat Lembaga Alam Minangkabau karangan salah seorang kaum adat, Datuk Sangguno.
Menurutnya, penjelasan tentang tarikh dan adat dalam kitab yang ditulis Datuk Sangguno penuh dengan dongeng, tidak sesuai dengan kaidah ilmu sejarah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini kemudian menarik perhatian murid-murid Sumatera Thawalib untuk dibahas dalam satu diskusi. Maka, untuk memenuhi permintaan itu, ia memperbanyak Curai Adat Lembaga Alam Minangkabau dengan biaya percetakan dari Sumatera Thawalib.
Mengetahui hal tersebut, Datuk Sangguno menyatakan keberatan dan menggugatnya ke pengadilan di Bukittinggi. Di akhir persidangan, Haji Rasul dinyatakan bersalah dan harus membayar denda sebesar f. 300 karena telah menghina Datuk Sangguno dan melanggar hak izin penerbitan. Sedangkan Sumatera Thawalib didenda f. 400 karena membiayai penerbitan.
Keberatan dengan putusan tersebut, keduanya mengajukan banding. Hasilnya, besaran denda untuk Haji Rasul berkurang, dari f.300 menjadi f. 100. Namun, besaran denda untuk Sumatera Thawalib tidak mengalami perubahan.
Memasuki awal tahun 1920, Haji Rasul bersama Syekh Abdullah Ahmad diangkat menjadi penasihat Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI) yang didirikan atas inisiatif Syekh Abdullah Ahmad.
Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan seluruh ulama dan guru agama di Sumatra Barat guna memajukan pendidikan. Namun, persatuan yang hendak dicapai gagal. Sebab, kaum tuo mendirikan organisasi tandingan bernama "Ittihadul Ulama di bawah pimpinan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli," tulis Seno (2010).
Pada awal tahun 1923, murid Sumatera Thawalib mengalami pembelahan. Masuknya Ahmad Khatib Datuk Batuah dan Natar Zainuddin yang membawa pengaruh komunisme menjadi penyebabnya. Pengaruh Haji Rasul turut mengalami kemunduran.
"Ia sangat kecewa dengan sokongan yang banyak diberikan murid-muridnya kepada kegiatan Datuk Batuah, sedemikian rupa sehingga ia meninggalkan sekolah Thawalib Padang Panjang itu," tulis Deliar Noer (1982).
Mengutip kembali Novita Siswayanti (2016), setelah itu, ia kembali mengajar di Maninjau. Pada tahun 1925, ia melawat ke Yogyakarta dan berkenalan dengan salah satu tokoh Muhammadiyah, Haji Fakhruddin.
Perkenalan itu mendorong rasa ketertarikan dirinya kepada Muhammadiyah. Bersama A.R. Sutan Mansur ia kemudian merintis pendirian Muhammadiyah cabang Minangkabau dan Sendi Anam sebagai lembaga pendidikannya.
Warsa 1926, sebagai penghargaan terhadap jasa-jasanya dalam pergerakan pembaharuan Islam, khususnya di bidang pendidikan, ia bersama Haji Abdullah Ahmad dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dari Al-Azhar, Mesir.

Dalam Pengasingan
Kebijakan pemerintah kolonial Belanda tak luput dari perhatiannya. Ia turut melakukan penentangan terhadap kebijakan-kebijakan kolonial yang dianggapnya menghambat kemajuan, seperti Goeroe Ordonantie dan Wilde Scholen Ordonantie.
Protes yang dilakukannya menjadi tunggangan kaum adat dan kaum tuo untuk mendorong pemerintah kolonial melakukan tindakan terhadap Haji Rasul. Hasilnya, pada tahun 1914, ia ditahan dan diasingkan keluar Sumatra.
Dalam autobiografinya Sumatran Warrior: Mighty Man of Love and Courage (2016), Awka--satu-satunya anak Haji Rasul yang ikut dalam pengasingan--mengisahkan tentang kehidupan ayahnya di Sukabumi.
"Pada tanggal 8 Agustus 1941, saya dan ayah saya, ibu tiri Dariyah, meninggalkan Padang dengan kapal KPM menuju Sukabumi, Jawa Barat, tempat pembuangan politik ayah saya," kenangnya.
Haji Rasul menjadikan rumah pengasingannya di Tjikirai Straat No. 8 sebagai tempat pengajaran agama. Banyak orang mengunjunginya, sekadar untuk berbincang hingga memberi bantuan, salah satunya penulis Aoh K. Hadimadja yang saat itu bekerja di perkebunan teh Parakan Salak.
Pengasingan di Sukabumi berlangsung selama sembilan bulan. Setelah itu, seiring dengan jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang, Haji Rasul bersama anak dan istrinya pindah ke Jakarta dan tinggal di kawasan Tanah Abang, tepatnya di Kebon Kacang IV No. 22.
Beberapa tokoh pergerakan seperti Haji Agus Salim dan M. Natsir kerap mengunjunginya. Ia juga kembali membuka pengajaran agama. Di samping itu, pada tahun 1943, ia diangkat sebagai Penasehat Tinggi oleh pemerintahan militer Jepang dalam rangka menarik simpati ulama.
Meski begitu, masih tersisa sikap penentangan dalam dirinya semasa pendudukan militer Jepang. Ia menentang praktik Seikerei yang mengharuskan dirinya membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang.
Memasuki tahun 1944, kesehatannya menurun. Penyakit asmanya kerap kali kambuh. Setahun berselang, tepatnya pada 2 Juni 1945, ia mengembuskan napas terakhirnya di usianya ke-66 tahun dan dimakamkan di Karet, Jakarta.
Penulis: Andika Yudhistira Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id