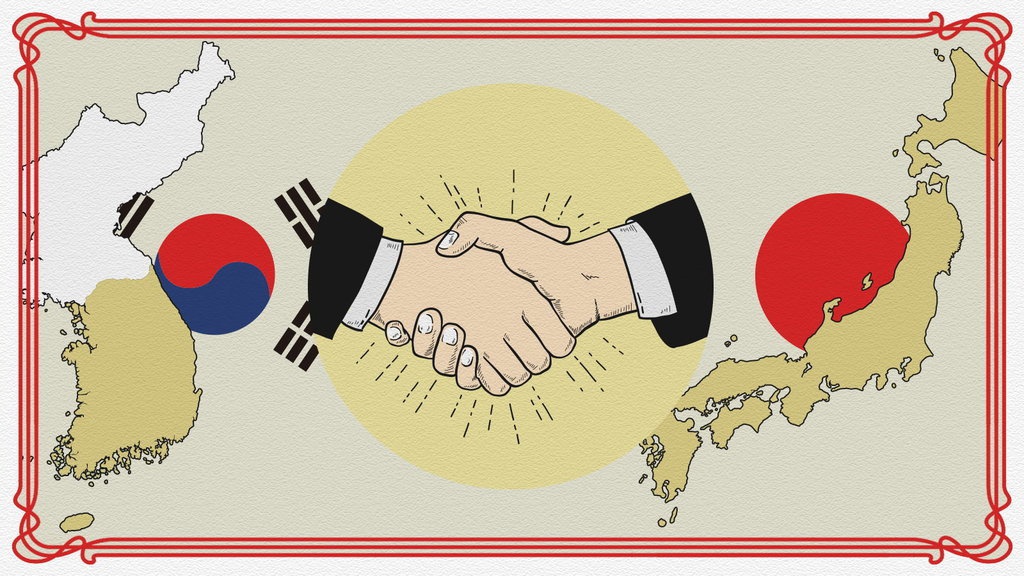tirto.id - Hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan memiliki sejarah yang rumit. Keduanya tercatat beberapa kali terlibat pertempuran dan persaingan sengit. Situasi antagonistik semacam itu pun terjadi pada awal abad ke-20.
Pada dekade pertama abad ke-20, Jepang menandatangani perjanjian aneksasi wilayah Kekaisaran Korea secara sepihak. Perjanjian itu menandai pendudukan Jepang atas Korea. Otoritas pendudukan Jepang lalu menerapkan tindakan-tindakan represif terhadap penduduk Korea: menjadikannya pekerja paksa untuk pembangunan fisik atau keperluan militer, dan menjadikan para wanita sebagai penghibur bagi tentara Jepang.
Represi itu terus berlanjut dan semakin masif dilakukan ketika Jepang melibatkan diri dalam Perang Dunia II (1940-45). Itulah awal dari luka dan kebencian masyarakat Korea—khususnya Korea Selatan—terhadap Jepang.
Pada awal dekade 1950-an, mencuatlah rencana normalisasi hubungan kedua negara. Namun, luka lama akibat kolonialisme Jepang menjadi salah satu penghambatnya. Kedua negara itu kesulitan untuk membangun kembali hubungan diplomatik yang setara.
Sebagai syarat normalisasi hubungan diplomatik itu, Korea Selatan menuntut Jepang untuk bertanggung jawab atas kejahatan perangnya. Korea Selatan bahkan telah menempuh jalur negosiasi internasional.
Usaha Korea Selatan itu gagal karena Jepang enggan mengakui dan meminta maaf atas tindakannya selama periode kolonial. Jepang pun menganggap negosiasi dengan bekas koloni adalah tindakan memalukan.
Kedua negara kesulitan mencari titik temu dan pada akhirnya berpegang teguh pada prinsip yang sama: tidak ingin bernegosiasi. Namun, situasi beku itu berubah sekira 1953, kala Perang Korea—pecah sejak 1950—memasuki fase gencatan senjata.
Dalam konflik itu, Semenanjung Korea terpecah dalam dua kubu ideologi. Korea Utara yang komunis mampu mempertahankan diri dengan dukungan dari Cina dan Uni Soviet. Sementara Korea Selatan bertahan dengan dukungan dari Amerika Serikat.
Korea Selatan bakal berhadapan dengan situasi sulit jika perang berlanjut ketika, di saat bersamaan, tensi politik dengan Jepang memanas. Amerika Serikat pun terdesak kepentingan untuk membendung pengaruh komunisme di Asia. Jika masalah-masalah ini dibiarkan berlarut, Amerika Serikat dan Korea Selatan juga yang bakal rugi.
Alhasil, elit Washington akhirnya menyerukan agar Seoul dan Tokyo menjajaki kembali kemungkinan normalisasi.
Menurut analisis Victor D. Cha dalam “Bridging the Gap: The Strategic Context of the 1965 Korea-Japan Nomarlization Treat” yang dimuat jurnal Korean Studies (Vol. 20, 1996), Amerika Serikat memandang normalisasi hubungan Seoul-Tokyo itu bakal memperkukuh pengaruhnya di Asia-Pasifik. Di sisi lain, Korea Selatan dan Jepang pun sebenarnya juga waswas akan potensi ancaman Perang Dingin.
Untuk menghadapi ancaman Perang Dingin—terutama dari kubu komunis, Korea Selatan mulai memandang perlu bantuan Jepang. Elit politik Korea Selatan paham betul Jepang adalah anak kesayangan Amerika Serikat di Asia. Dengan memperbaiki hubungan dengan Jepang, Korea Selatan juga bakal mengamankan dukungan Amerika Serikat.
Jepang pun setali tiga uang. Kondisi regional tidak lantas melandai begitu saja pasca-Perang Korea. Negeri Matahari Terbit juga musti bersiap menghadapi potensi bahaya yang datang dari Korea Utara dan Cina. Jika kelak Amerika Serikat tidak lagi bisa melindunginya, setidaknya Jepang masih bisa bekerja sama dengan Korea Selatan.
Bantuan Ekonomi Jepang
Memasuki dekade 1960-an, faktor pendorong normalisasi Jepang-Korea Selatan bertambah, yaitu faktor ekonomi. Korea Selatan di bawah Presiden Park Chung-Hee (1962-1979) semakin terbuka untuk menjalin kerja sama ekonomi dengan Jepang.
Menurut peneliti kajian Asia-Pasifik Hyung Gu Lynn dalam artikel “Systemic Lock: The Institutionalization of History in Post-1965 South Korea-Japan Relations” yang dimuat Journal of American-East Asian Relations (Vol. 9, 2000), Presiden Park punya kecenderungan untuk memprioritaskan pengembangan ekonomi Korea Selatan.
Pemerintahannya menyadari betul ketertinggalan negaranya di bidang ini. Karenanya, hubungan diplomatik dengan Jepang juga dipandang sebagai langkah strategis untuk memperbaiki ketertinggalan itu.
Meski demikian, peneliti hubungan internasional Boyu Chen dalam artikel “Decolonizing Japan–South Korea Relations: Hegemony, the Cold War, and the Subaltern State” yang dimuat jurnal Asian Perspective (Vol. 44, 2020) menyebut Korea Selatan sebenarnya berada dalam posisi dilematis saat itu.
Korea Selatan berada di antara dua pilihan sulit: hidup stagnan karena menolak bekerja sama dengan Jepang atas pertimbangan luka sejarah atau melupakan luka masa lalu untuk masa depan bangsa yang lebih cerah. Pada akhirnya, Pemerintah Korea Selatan memilih opsi yang kedua.
Keputusan itu diambil dengan dalih untuk mencapai tiga tujuan, yaitu pembangunan ekonomi, menahan komunisme, dan stabilitas rezim politik. Di sisi lain, Jepang pun merespons baik perubahan sikap Negeri Ginseng itu.
Menurut Boyu Chen, keterbukaan Jepang itu tidak terlepas dari motif membangun citra baik dan bentuk “balas budi” kepada bekas koloninya. Pada saat yang bersamaan, iklim politik Jepang juga sedang menghangat oleh sikap pro-Korea Selatan yang berhembus dari kalangan Partai Demokrat Liberal (LDP). Lain itu, investor-investor Jepang pun semakin tertarik menggarap pasar Korea Selatan yang dinilai cukup menjanjikan.
Alhasil, pada November 1962, Jepang mengucurkan dana sebesar $300 juta ke Korea Selatan. Itu terjadi usai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Jepang Ohira Masayoshi dan Direktur Intelijen Korea Selatan Kim Chong-pil. Dana itu sendiri terbagi dalam dua skema: $200 juta dalam bentuk pinjaman pemerintah jangka panjang dan $100 juta dalam bentuk pinjaman komersial.
Amerika Serikat pun menyambut baik langkah ekonomi yang diambil kedua negara itu. Menurut Victor D. Cha, Amerika Serikat juga diuntungkan oleh langkah Jepang itu. Pasalnya, bantuan ekonomi Jepang itu dapat mengurangi pula beban ekonomi Amerika Serikat.

Normalisasi Setengah Hati
Bantuan ekonomi itu akhirnya sukses membawa Jepang dan Korea Selatan ke fase negosiasi serius. Meski begitu, proses negosiasinya tidak semulus yang dibayangkan. Permasalahan sejarah lagi-lagi muncul menjadi penghambat.
Elite politik Tokyo sadar punya daya tawar yang lebih leluasa karena Seoul membutuhkan bantuan ekonominya. Dengan begitu, Jepang bisa menutup kemungkinan munculnya klausul penyelesaian masalah sejarah kolonialismenya. Jika Seoul tetap ngotot, pada dasarnya mereka sendirilah yang akan kehilangan peluang ekonomi.
Semula Pemerintah Korea Selatan bergeming. Mereka tetap menuntut Jepang membuka pembahasan terkait penyelesaian kejahatan perang yang dilakukannya terhadap rakyat Korea. Namun, daya tawar yang rendah menyulitkan mereka bernegosiasi lebih jauh.
Pada akhirnya, Korea Selatan pun terpaksa menerima persyaratan Jepang. Setelah menempuh negosiasi panjang, Jepang dan Korsel berhasil mencapai kata mufakat pada 22 Juni 1965—tepat hari ini 56 tahun silam. Perwakilan kedua negara itu sepakat menandatangani perjanjian normalisasi hubungan diplomatik yang kemudian dikenal dengan Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea.
Jepang dan Korea Selatan pada intinya menyepakati dua poin utama, yaitu pembangunan hubungan diplomatik resmi dan pembukaan kegiatan ekonomi bersama. Di atas kertas, perjanjian ini menandai awal baru dalam hubungan bilateral kedua negara yang lebih harmonis dan kooperatif.
Namun, untuk mewujudkan persahabatan itu tidak semudah yang dibayangkan. Berpuluh-puluh tahun setelahnya—bahkan hingga kini, perjanjian itu justru mewariskan permasalahan pelik.
Pengarusutamaan ekonomi dan kepentingan Perang Dingin berujung pada pengabaian Jepang atas kejahatan perangnya di masa lalu. Usai perjanjian normalisasi itu, Pemerintah Korea Selatan telah beberapa kali meminta Jepang untuk segera menyelesaikan permasalahan itu dengan menuntut pembayaran kompensasi.
Pada 2019, misalnya, Pengadilan Tinggi Korea Selatan meminta beberapa perusahaan Jepang, termasuk Nippon Steel dan Mitsubishi Heavy Industries, untuk memberikan kompensasi kepada para korban kerja paksa masa penjajahan Jepang (1910-45). Namun, Tokyo mengklaim bahwa perjanjian 1965 telah memberi jawaban pasti terkait permasalahan sejarah itu.
Seoul tentu saja menampik klaim tersebut itu. Pasalnya, memang tidak ada klausul yang memungkinkan pembahasan masalah ini lebih lanjut.
Gara-gara kasus ini, hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan memanas lagi untuk ke sekian kalinya. Perang dagang pun tak terhindarkan dan sentimen anti-Jepang meningkat di Korea Selatan. Bahkan, hasil survei yang dipublikasikan Japan Times (2021) menunjukkan hanya 16,7 persen responden warga Korea Selatan yang merasa bersahabat dengan orang Jepang. Sementara itu, hanya ada 20,2 persen warga Jepang yang mengaku bersahabat dengan Korea Selatan.
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id