tirto.id - Aspirin adalah perjalanan panjang manusia mencari obat untuk rupa-rupa penyakit seperti sakit kepala, nyeri sendi, demam, radang, dan sebagainya. Dengan konsumsi 35 ton per hari di Amerika Serikat saja, seperti dicatat David B. Jack dalam “100 Years of Aspirin”, Lancet, 350 (1997, hlm. 439), pada 1950 aspirin berhasil mencatatkan diri dalam Guinness Book of Records sebagai obat pereda sakit paling laris di dunia. Aspirin kian kondang karena disebut dalam karya-karya penulis masyhur seperti Franz Kafka, Gabriel Garcia Marquez, dan Henry Miller.
Lantas bagaimana aspirin bermula?
Pada pertengahan abad ke-19, Edwin Smith yang terbuang dari keluarganya yang kaya raya di New England, Amerika Serikat, berdagang barang-barang antik di Luxor, Mesir. Ia tiba di Mesir pada 1858 dan segera membangun reputasi sebagai pedagang barang antik. Pengetahuan dan kejelian mata Edwin mengenali barang-barang berharga Mesir, baik yang palsu maupun asli, tiada tandingannya. Ketajaman intuisinya itulah, menurut Diarmuid Jeffreys dalam Aspirin: The Remarkable Story of A Wonder Drug (2004), yang membuatnya memutuskan membeli dua gulungan perkamen kuno yang sudah compang-camping pada 20 Januari 1862.
Dua perkamen kuno itu bertarikh 1534 SM dan ditulis dalam aksara Mesir Pertengahan, tapi isinya jauh lebih tua. Mustapha Agha, sahabat sekaligus saingan Edwin dalam berdagang, mengatakan bahwa dua perkamen papirus itu ditemukan di antara dua kaki mumi di Nekropolis Theban, di tepi barat Sungai Nil. Edwin Smith kemudian menerjemahkan naskah itu.
“Bila Anda memeriksa seseorang dengan luka yang ganjil… dan lukanya meradang [maka di situ ada] konsentrasi panas; pinggiran luka itu memerah dan akibatnya orang itu juga demam… maka Anda harus memberikan ramuan menyejukkan untuk mengeluarkan panasnya… daun-daun dedalu,” demikian bunyi perkamen itu seperti dikutip David B. Jack dalam “100 Years of Aspirin”, Lancet 350 (1997, hlm. 437).
Pohon dedalu (Salix sp.) mengandung salisilat yang telah digunakan sekitar 6.000 tahun lalu di Mesopotamia sebagai obat untuk menyembuhkan luka dan radang. Demikian juga masyarakat di masa peradaban Assyria (4.000 SM) dan Babilonia (605-562 SM) di Irak, mengekstrak kulit batang pohon atau daun dedalu untuk mengobati demam dan radang. Resep dedalu ditemukan para arkeolog pada tablet tanah liat berusia 4.000 tahun dari bangsa Sumeria, yang menjadikannya sebagai resep obat pertama yang tercatat dalam peradaban.
Dedalu masuk dalam ranah pustaka akademik pada abad ke-18, ketika Edward Stone, seorang pendeta dari kota kecil di Oxfordshire, Inggris, memberanikan diri bersurat kepada Presiden Royal Society, George Earl of Macclesfield. Dalam surat bertanggal 25 April 1763 tersebut, Edward menceritakan pengalamannya bereksperimen dengan bubuk dedalu untuk menyembuhkan demam dan nyeri sendi kepada sejumlah orang di kotanya.
Di lembar pertama suratnya, Edward mengutip Doctrine of Signature, gagasan kuno abad ke-16, “Mengingat pohon ini tumbuh subur pada tanah basah atau lembap, di mana penyakit demam kerap terjadi, pepatah lama mengatakan bahwa berbagai penyakit muncul bersama obatnya juga, atau obatnya berada di tempat yang tak jauh dari kemunculan penyakitnya…”
Enam tahun sebelumnya, Edward iseng mengunyah kulit batang pohon dedalu. Rasa pahit yang luar biasa mengingatkannya pada rasa kulit batang pohon kina yang dapat menyembuhkan malaria. Dengan pahit yang sama, Edward menduga bahwa kulit pohon dedalu bisa jadi memiliki khasiat yang sama seperti kina. Ia kemudian mengekstraksi sekantung kulit pohon dedalu dengan mengeringkannya di depan tungku pemanggang roti selama tiga bulan, lalu menumbuknya.
Selama lima tahun, Edward merawat orang-orang sakit di kotanya dengan memberikan ramuan itu dengan dosis sangat kecil, yaitu 1,2 gram yang diulang tiap 4 jam. Sebanyak 50 orang telah sembuh dengan bubuk dedalunya.
Satu abad kemudian, Thomas Maclagan, seorang dokter di Dundee, Skotlandia, juga tampaknya terinspirasi Doctrine of Signature ketika melaporkan hasil uji klinisnya menggunakan salisilat dan asam salisilat sekaligus. Dalam The British Medical Journal edisi 20 Mei 1876, Maclagan membandingkan kemanjuran dan efek samping salisilat dan asam salisilat yang ia berikan kepada 100 pasien radang sendi selama 1,5 tahun. Maclagan menyimpulkan bahwa keduanya mempunyai kemanjuran yang sama, tetapi asam salisilat memiliki efek samping yang tidak mengenakkan, yakni sensasi terbakar di tenggorokan dan iritasi lambung.
Friedrich Bayer & Co.
Pada kurun waktu yang sama di Barmen, Jerman, sebuah pabrik pembuat warna sintesis, Friedrich Bayer & Co. tengah berkembang. Bayer didirikan pada 1 Agustus 1863 oleh seorang pedagang pewarna, Friedrich Bayer, dan ahli pembuat warna sintesis, Johann Friedrich Weskott. Industri pewarna sintetis tumbuh pesat di paruh kedua abad ke-19 serta berdampak besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Perkembangan ini membuat kepala divisi riset Bayer saat itu, Carl Duisberg, mengarahkan riset perusahaan ke penelitian obat. Pada 1896, berdirilah laboratorium Bayer dengan dua divisi, yakni divisi farmasi untuk penemuan obat yang dipimpin oleh Arthur Eichengrün, dan divisi farmakologi untuk pengujian obat, dipimpin oleh Heinrich Dreser.
Proyek pertama laboratorium obat Bayer adalah menciptakan turunan salisilat yang tidak memiliki efek samping seperti asam salisilat, yakni rasa terbakar di tenggorokan, iritasi lambung, mual, bahkan telinga berdenging atau tinnitus. Tugas ini diberikan kepada seorang peneliti muda lulusan Universitas Munich bernama Felix Hoffmann. Ayahnya adalah penderita artritis yang tidak hanya menanggung sakit pada persendian, tetapi juga rasa pahit luar biasa dan iritasi lambung ketika mengonsumsi asam salisilat. Hoffmann muda pun berusaha mengubah struktur kimia asam salisilat sehingga segala efek samping itu lenyap. Pada 10 Agustus 1897, Hoffmann berhasil melakukan asetilasi sehingga mendapatkan asam asetilsalisilat dalam bentuk yang murni dan stabil.
Bayer kemudian mengujicobakan senyawa temuan Hoffmann ini pada hewan--yang merupakan uji coba pertama pada hewan dalam skala industri. Uji coba klinis juga dilakukan pada pasien-pasien di Rumah Sakit Diakonia, Halle, dan membandingkannya dengan asam salisilat. Dalam laporannya, seperti dicatat David B. Jack dalam “100 Years of Aspirin”, Lancet 350 (1997, hlm. 438), Kurt Witthauer, seorang dokter senior yang tadinya skeptis pada obat baru ini menuliskan, “Obat ini tidak pernah gagal mengobati rasa sakit, radang, atau demam, dan tidak menimbulkan efek samping yang tidak menyenangkan pada jantung atau lambung, bahkan pada pasien yang keadaannya parah.”
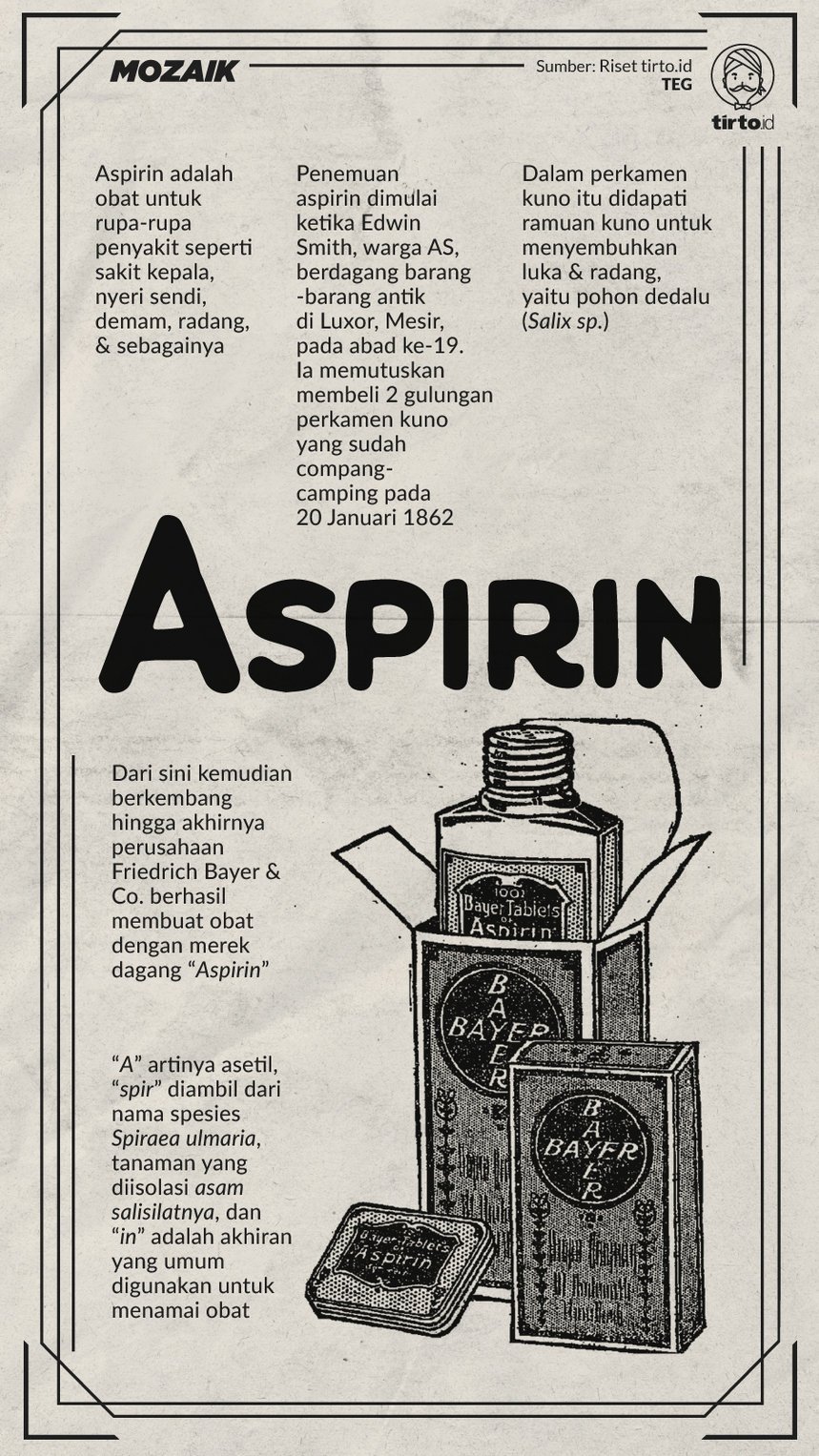
Bayer lantas mendaftarkan obat baru ini dengan merk dagang “Aspirin” pada 1 Februari 1899. “A” artinya asetil, “spir” diambil dari nama spesies Spiraea ulmaria, tanaman yang diisolasi asam salisilatnya, dan “in” adalah akhiran yang umum digunakan untuk menamai obat.
Aspirin mengawali perjalanannya yang gemilang ketika terdaftar secara resmi di Imperial Patent Office di Berlin pada 6 Maret 1899, tepat hari ini 122 tahun silam. Bayer segera mempromosikan obat baru ini kepada lebih dari 30.000 dokter di Jerman yang merupakan kampanye masif pertama dalam industri farmasi. Pada 1904, Bayer mengubah puyer aspirinnya dalam bentuk tablet untuk memastikan ketepatan dosis dan mencegah terjadinya pencampuran obat dengan kandungan lain. Aspirin kemudian dapat dibeli bebas tanpa resep sejak 1915. Hingga hari ini, aspirin tak pernah berhenti menjadi objek penelitian dalam upaya manusia mencari obat baru atau efek baru dari obat yang sudah ada.
Sentimen Anti-Yahudi dalam Sebutir Aspirin
Arthur Eichengrün, kepala divisi farmasi yang menugaskan Felix Hoffmann memodifikasi struktur asam salisilat melaporkan telah melakukan asetilasi asam salisilat sejak April 1897. Pada 1944, di usianya yang ke-76, Eichengrün menulis surat kepada Bayer dari kamp konsentrasi Theresienstadt, Bohemia Utara, terkait eksperimen asam asetilsalisilat itu.
Pada 1949, dalam artikel di jurnal Pharmazie, Eichengrün mengulang isi suratnya, bahwa dirinyalah yang menugaskan asetilasi asam salisilat tersebut untuk menghilangkan efek sampingnya. Secara terperinci Eichengrün menyebutkan bahwa koleganya, Heinrich Dreser, mengabaikan hasil eksperimen asam asetilsalisilat itu selama 18 bulan. Hoffmann sendiri dilaporkan juga mengeluhkan hal ini. Dalam rapat perusahaan, ketika Dresser diminta menguji potensi obat tersebut, Dreser menolak dan memberi komentar, “Ini cuma omong kosong biasa di Berlin. Barang ini tidak ada nilainya.”
Eichengrün kemudian mencobanya sendiri dan meminta Felix Hoffmann melakukan percobaan serupa. Tak berhenti di situ, Eichengrün juga melaporkan hasil temuannya kepada Carl Duisberg, atasan mereka. Dreser kemudian diperintahkan menulis laporan untuk memastikan kredibilitas ilmiah atas obat baru itu. Karena itulah Dreser meneliti lagi potensi asam asetilsalisilat pada 1898 dan melaporkannya pada 1899.
Arthur Eichengrün adalah keturunan Yahudi. Istrinya yang Arya tidak berhasil membuatnya lolos dari kamp konsentrasi dan penghapusan namanya dalam sejarah. Nazi melarang keturunan Yahudi berada dalam posisi-posisi penting di ranah profesional dan ekonomi. Dalam artikelnya tahun 1949, Eichengrün menulis, “Pada 1941, di bagian kimia di dalam Balai Kehormatan Museum Jerman di Munich terdapat sebuah etalase berisi botol kristal putih, dengan tulisan: ‘Aspirin: Penemu Dreser dan Hoffmann’… Tetapi, di gerbang utama museum terdapat sebuah rambu besar yang melarang keturunan non-Arya masuk ke dalam museum. Mereka yang paham akan dapat menafsirkannya.”
Arthur Eichengrün meninggal dunia di Berlin pada 23 Desember 1949, tak lama setelah artikel pengakuannya terbit. Sementara Felix Hoffmann menjalani masa tua dalam kemiskinan karena paten proses asetilasi asam salisilat yang dilakukannya ditolak lantaran tidak dianggap sebagai temuan baru. Sebaliknya, Dreser memilih pensiun muda dalam keadaan kaya raya setelah Bayer berhasil mematenkan produk baru dari proses asetilasi asam salisilat yang pernah disebutnya tak berharga itu.
Editor: Irfan Teguh Pribadi












