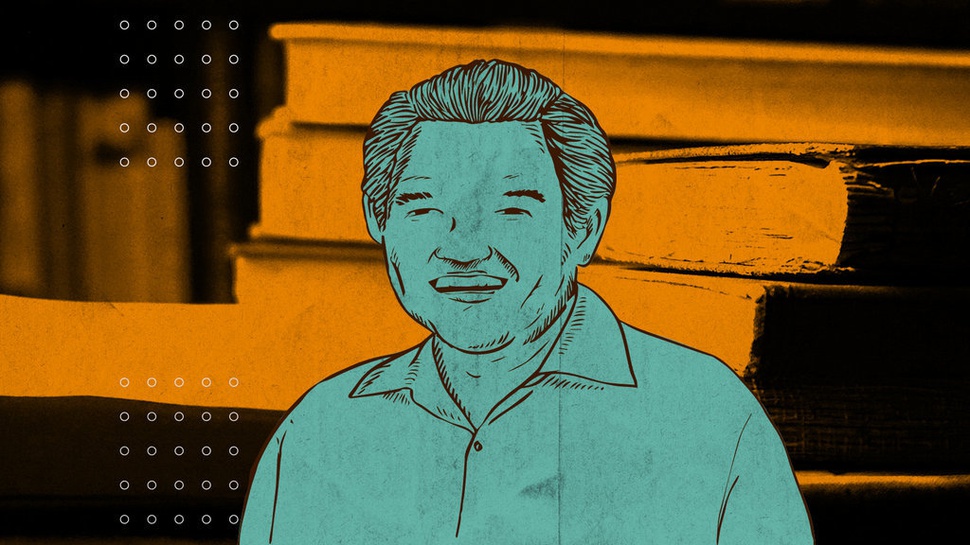tirto.id - Lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) didirikan pada 17 Agustus 1950. Lima belas tahun kemudian, saat arah politik berubah drastis, organisasi onderbouw PKI itu hancur diganyang kekuatan politik baru di gelanggang kebudayaan.
Dua tahun sebelum peristiwa G30S, para seniman yang tak sejalan dengan Lekra membuat Manifes Kebudayaan. Isinya secara implisit menolak jargon “Politik sebagai Panglima” yang digembar-gemborkan Lekra. Bagi para penandatangan Manifes Kebudayaan, humanisme universal menjadi pegangan dan salah satu sektor kebudayaan tidak ditempatkan di atas sektor kebudayaan yang lain.
Orang-orang Lekra kemudian kerap menggunakan akronim "Manikebu" untuk menyebut Manifes Kebudayaan. Akronim ini bernada ejekan, karena diasosiasikan dengan "mani kebo" (sperma kerbau).
Pembersihan terhadap orang-orang komunis dan yang dituduh komunis, selain berjalan dengan kerja-kerja militer yang penuh kekerasan, juga berlangsung di gelanggang kebudayaan secara terorganisasi. Orang-orang Manifes Kebudayaan mempunyai peran besar dalam bidang ini. Wiratmo Soekito dalam harian Merdeka (23/10/1966) seperti dikutip Alexander Supartono dalam Lekra vs Manikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-1965 (2005), menyebut Manifes Kebudayaan sebagai “Kostradnya Kebudayaan”.
Perseteruan antara Lekra yang mengusung realisme sosialis dengan orang-orang Manifes Kebudayaan memang panas saat PKI masih berada dalam lingkaran kekuasaan.
Kelak, perseteruan ini ditulis Taufiq Ismail dan D.S. Moeljanto dalam Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk (1995). Namun, karena dua penulis ini anti-komunis, isi bukunya cuma dokumentasi mentah dan mereka berdua hanya penyunting dari kumpulan kliping koran.
“Taufik Ismail dan DS Moeljanto memberikan arti tertentu dari dokumentasi mentah tersebut dalam penyeleksian dan penyusunan sistematika yang tidak disusun secara kronologis, tidak juga secara sistematis,” tulis Alexander Supartono.
Supartono menambahkan, dengan semangat penyusunan dokumen seperti itu Taufiq Ismail berharap “tabir sejarah pergolakan seni budaya di zaman demokrasi terpimpin tersingkap, sehingga gambaran, paparan suasana dan isi perdebatan kebudayaan tahun-tahun itu bisa muncul.”
Sejumlah catatan tentang sepak terjang Lekra kala mereka menguasai palagan kebudayaan memang kerap disebut-sebut sebagai satu riwayat kezaliman terhadap lawan-lawan politiknya, terutama orang-orang yang pro Manifes Kebudayaan.
Namun, zaman sejatinya pernah berbalik saat PKI dan penumpang gerbong besarnya buru-buru disembelih pasca G30S. Tentu saja Lekra termasuk di dalamnya hingga organisasi itu tumpas, mati selama-lamanya.
Pola kekerasan yang ditimpakan kepada Lekra oleh para budayawan saat rezim berganti ditulis secara gamblang oleh Wijaya Herlambang dalam Kekerasan Budaya Pasca 1965 (2013). Dalam kerja-kerja pembersihan secara budaya itu, sastra menjadi salah satu yang digeledah, diberi wajah baru, dan disampaikan kepada masyarakat.
“Ada banyak sekali produk-produk kebudayaan yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya untuk mempromosikan anti-komunisme, seperti ideologi negara, museum, monumen, diorama, folklor, agama, buku-buku pegangan siswa, materi penataran, film, ideologi kebudayaan dan karya sastra,” tulisnya.
Sejumlah karya sastra tampil dengan langgam seolah-olah bersimpati terhadap orang-orang PKI dan yang dituduh komunis sebagai korban kekerasan. Tapi saat Wijaya Herlambang menyigi beberapa di antaranya, ternyata karya-karya tersebut justru bermakna sebaliknya.
Salah satu karya sastra berupa cerpen yang menohok titik manipulasi kemanusiaan itu adalah karangan Satyagraha Hoerip yang berjudul Pada Titik Kulminasi yang ia tulis pada 1966. Satyagraha adalah salah satu tokoh yang getol menyingkirkan karya-karya pengarang Lekra.
Hal ini salah satunya disinggung Ajip Rosidi dalam suratnya kepada Nh. Dini bertitimangsa 5 Oktober 1982 yang kemudian dihimpun dalam Yang Datang Telanjang (2008). Ajip menulis bahwa setelah peristiwa 1965, ia hendak menerbitkan bunga rampai cerita pendek, tapi penerbit ragu karena di dalamnya terdapat karangan pengarang Lekra. Ajip menolak keinginan penerbit yang hendak membuang karya pengarang Lekra tersebut.
Saat Ajip berkeras dengan pilihannya, H.B. Jassin sudah bersedia mengurangi karya-karya pengarang Lekra dalam Gema Tanah Air yang mula-mula terbit pada 1948 dan Satyagraha Hoerip membuang karya pengarang Lekra dari bunga rampai cerita pendeknya.
Namun di sisi lain, Pada Titik Kulminasi karya Satyagraha Hoerip juga dimasukkan Ajip Rosidi dalam Laut Biru Langit Biru (2013), bunga rampainya yang memuat sejumlah sajak, cerita pendek, penggalan roman, esai, serta kritik sastra.
Cahaya Ilahi sebagai Dalih Pembunuhan
Pada Titik Kulminasi menceritakan tokoh bernama Soes, seorang budayawan anti-komunis yang dihadapkan pada pilihan sulit saat terjadi pembersihan terhadap orang-orang komunis di kampungnya sepanjang 1965-1966. Pasalnya ia harus membunuh Kuslan, orang komunis, yang sekaligus iparnya.
Kawan Soes yang bernama Wimbadi mencoba menepis keraguannya. Menurut Wimbadi, membunuh Kuslan adalah tanggung jawab Soes yang selama ini kerap berpidato menggelorakan perlawanan terhadap komunisme dengan bekal “cahaya Ilahi”.
Wijaya Herlambang dalam Kekerasan Budaya Pasca 1965 (2013) menemukan bahwa frasa “cahaya Ilahi” terdapat dalam naskah penjelasan Manifes Kebudayaan 1963 yang diterbitkan sebagai pernyataan tambahan dokumen tersebut.
“Musuh kami adalah hal-hal yang membelenggu kemanusiaan dan itulah sebabnya kami memegang teguh prinsip bahwa sejahat-jahatnya manusia, mereka masih tetap memancarkan cahaya Ilahi, sehingga kita harus menyelamatkan cahaya Ilahi itu,” tulis Wijaya Herlambang mengutip naskah pernyataan tambahan Manifes Kebudayaan tersebut.
Namun, cahaya Ilahi yang dimaksudkan Wimbadi dalam cerpen karya Satyagraha Hoerip itu justru dalih untuk melaksanakan pembunuhan terhadap Kuslan, ipar Soes.
“Mana itu sinar Ilahi? Yang menurut Mas sendiri harus kita pertahankan dan pancarkan? Tahu: sinar Ilahi bukanlah sekadar kasih sayang yang damai mesra-mesraan! Tapi juga berarti harus berani bertindak apapun demi itu… Sinar Ilahi bukan cuma buat dipikirkan muluk-muluk dan dituliskan berkepanjangan, tapi juga harus disertai tindakan-tindakan tepat dan tegas,” ujar Wimbadi.

Meski pada akhirnya Soes tidak jadi membunuh Kuslan karena pesakitan itu ditangkap kawan-kawan Soes dan diserahkan kepada pihak militer, Pada Titik Kulminasi menyeret pembaca untuk bersimpati kepada Soes sebagai calon pelaku pembunuhan terhadap orang komunis, bukan kepada si korban.
Karya serupa seperti yang dibuat Satyagraha Hoerip bertebaran di Majalah Horison yang didirikan orang-orang pro Manifes Kebudayaan. Pola penceritaan seperti ini, menurut Herlambang, adalah ciri khusus bahasa sastra yang mampu mendeformasi bahasa keseharian sehingga sesuai yang diinginkan si penulis.
Ia menambahkan bahwa di bawah tekanan alat-alat sastra, bahasa keseharian diintensifikasikan, dipadatkan, dibolak-balik, diteleskop, ditenggelamkan, dan dijungkirbalikkan.
“Walaupun kelihatannya tema sentral cerita-cerita ini berhubungan erat denagn konsep humanisme, pada kenyataannya cerita-cerita itu merepresentasikan proses manipulasi atas konsep humanisme itu sendiri,” imbuh Herlambang mengomentari Pada Titik Kulminasi dan sejumlah cerita lainnya.
Setelah getol mengganyang orang-orang Lekra lewat tulisan-tulisannya pada sepenggal episode turbulensi politik, Satyagraha Hoerip masih tetap menulis pada zaman Orde Baru, meski tidak seproduktif dulu. Ia meninggal dunia pada 14 Oktober 1998, tepat hari ini 20 tahun lalu.
Namanya tak bisa dipisahkan sebagai polemicist terdepan dalam melawan wacana kebudayaan Lekra dan PKI.
Editor: Ivan Aulia Ahsan