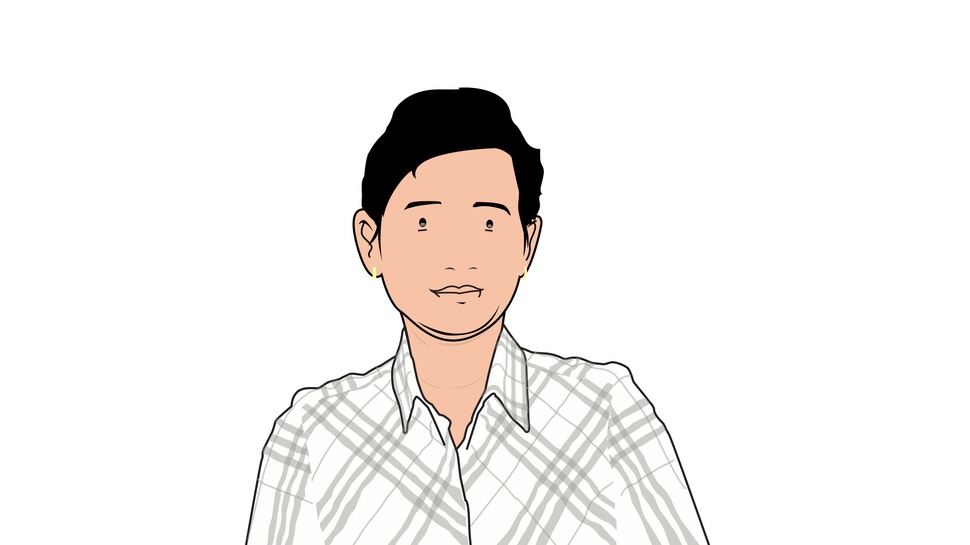tirto.id - Setiap 1 Juni, orang kembali ramai membincangkan Pancasila. Saya pun, lantas teringat pada sebatang pohon sukun dan kisah renungan Soekarno di Ende, kota kecil di Timur Indonesia. Tempat di mana selama empat tahun Soekarno diasingkan, dan di sana pula ia menemukan ide-ide dasar Pancasila.
Saya menjejaknya tiga bulan yang lalu. Menelusuri Ende adalah menapak tilas jejak Soekarno di Pulau Flores: pelabuhan tempat kapalnya pertama kali mendarat, rumah pengasingan, katedral tempat ia sering datang untuk membaca buku dan berdiskusi dengan para pastur sahabatnya, Masjid Ar-Rabithah tempat ia menunaikan salat Jumat bersama warga, serta ke makam ibu Amsi, ibu mertuanya yang wafat di Ende. Tentu saja tak lupa, menyambangi taman lapang di tengah kota yang dinaungi pohon sukun, yang kini disebut Taman Renungan Soekarno.
Februari 1934, kapal yang membawa Soekarno berlabuh di pelabuhan Ende. Ia datang dalam keadaan patah. Empat tahun ditahan di penjara di Sukamiskin, kemudian dibuang ke kota kecil yang sebagian besar penduduknya masih buta huruf. Ia diasingkan dari rakyat yang dicintai. Dijauhkan dari rekan-rekan seperjuangan. Dipisahkan dari kegiatan politik yang selama ini menjadi daya hidupnya.
Soekarno melewati sebuah pergumulan besar. Pelan-pelan ia membangun kembali kekuatan dirinya. Ia berkeliling dan menyapa penduduk: para petani dan nelayan. Berdiskusi dengan para pastur yang dengan ramah membuka pintu perpustakaannya. Ia membaca banyak buku. Ia juga menemu cara untuk berbicara dan menularkan spirit kebangsaan pada penduduk setempat, dengan mengajak mereka berpentas sandiwara. Ada belasan naskah sandiwara ia tulis selama berada di Ende.
Ende adalah kota kecil nan cantik. Sore hari yang berhawa sejuk, saya duduk di bawah rimbun pohon sukun dengan batang-batangnya yang menjulur ke angkasa. Saya menyesap suasana yang begitu magis. Terbayang berpuluh tahun silam, Soekarno duduk sendirian di bawahnya, sambil menatap birunya laut Ende dengan gelombang yang tenang dan perbukitan hijau menjulang. Dalam sendiri, ia berkontemplasi. Di Ende, dengan ragam latar belakang penduduk, yang beragama Islam dan Katolik hidup damai bersama-sama, ia merenungkan nasib bangsa dan cita-cita kemerdekaan yang diimpikannya.
Tentu, Pancasila tak jatuh dari hamparan langit hampa. Benih-benihnya telah tertanam sejak para pemuda mengikrarkan diri “mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia” dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
Pancasila adalah buah kesadaran dari pendiri bangsa ini akan realitas kemajemukan di Indonesia. Ia juga merupakan rangkuman konsensus berbagai kekuatan politik setelah melewati serangkaian proses perdebatan yang alot, serta diobori oleh optimisme menyala-nyala tentang sebuah negara merdeka. Pada 1 Juni 1945, berjarak tujuh tahun dari sejak Soekarno meninggalkan Ende, ia berpidato dalam sidang pertama BPUPKI. Hari itu kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila.
SAYA tumbuh remaja di zaman Orde Baru, ketika Pancasila dipaksa menjadi asas tunggal. Dinarasikan menjadi tafsir berdarah Orde Baru yang membabat habis segala pemikiran yang berbeda. Selama belasan tahun, setiap hari Senin saya mengikuti upacara bendera. Deretan lima sila dan dan pembukaan UUD 45 pun hafal di luar kepala. Sayangnya, ia hadir sebatas hafalan hampa. Saya tak tahu bagaimana mengejanya dalam laku keseharian. Generasi saya, kuyup diguyur dengan rupa-rupa jargon tanpa makna. Tak pernah diajak menyentuh pada pokok-pokok permenungan panjang Soekarno, yang lahir dari rahim dari spirit dan suasana kebatinan bangsanya.
Pada zaman Orde Baru, 1 Juni bahkan dilarang untuk diperingati. Yang dipaksakan hadir adalah narasi Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober, yang penuh simbol berdarah-darah paska konflik politik besar pada 30 September 1965. Pancasila yang humanis dan menjunjung tinggi keragaman pun beralih menjadi alat Orde Baru untuk menyeragamkan segalanya, dari ide hingga organisasi.
Hari ini, sebuah tantangan baru menghadang: Pancasila digotong-gotong oleh kelompok intoleran untuk meniupkan kembali hantu kengerian atas nama komunisme. Kita begitu mudah menghardik dan menghakimi keyakinan orang lain. Kita dikoyak-koyak untuk saling memusuhi atas beda keyakinan dan ideologi. Kita marah ketika biduan dangdut Zaskia Gotik lupa sila-sila Pancasila, tapi kita tak bereaksi serupa ketika kelompok intoleran secara sengaja merubuhkan rumah ibadah orang lain. Isu anti komunisme kembali dihidup-hidupkan. Rakyat dibuat tenggelam dalam ketakutan terhadap perbedaan ide dan keyakinan.
Dahulu, Soekarno menggagas Pancasila untuk merekatkan jarak, mengakui kebhinekaan, merangkumnya dalam satu tekad dan cita-cita kebangsaan. Kini, orang-orang menebalkan jarak. Membuat sekat-sekat pembeda, seakan lupa bahwa kita berada di bawah atap rumah yang sama: Pancasila.
Saat menuliskan ini, sayup-sayup terdengar lagu Pancasila Rumah Kita yang dilantunkan oleh Franky Sahilatua:
Pancasila rumah kita
Rumah untuk kita semua
Nilai dasar indonesia
Rumah kita selamanya
Pelan-pelan air mata saya menitik. Ada segumpal rindu bergolak. Rindu pulang ke rumah besar, di mana semua orang merasa aman bernaung di dalamnya. Ketika semua penghuninya bisa beribadah tanpa rasa takut rumah ibadahnya akan dibakar. Ketika kita semua bisa menghirup hawa segar kebebasan berpikir dan berdiskusi tanpa ancaman dibubarkan dan dituding komunis dan pengkhianat bangsa.
Puluhan tahun berjarak dari sejak digagasnya Pancasila, rasanya kita harus merenungkan kembali, tentang nasib rumah besar kita. Saya yakin, kita sama-sama merindukan damai bernaung di dalamnya. Rumah besar Pancasila, dengan konstitusi sebagai pagarnya.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.