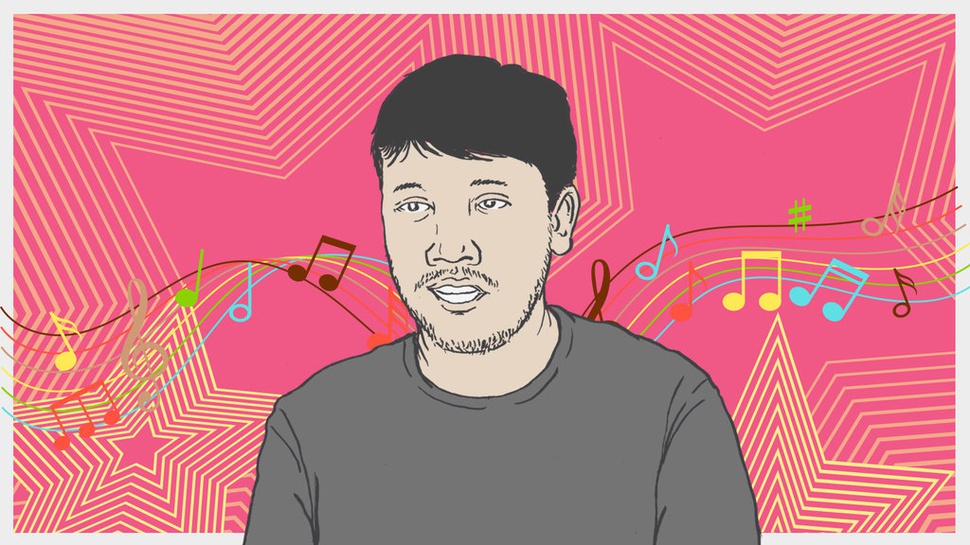tirto.id - Datang, bersenang-senang, dan menyiapkan lagi kegembiraan untuk tahun depan. Kira-kira begitulah pesan Kiki Aulia Ucup kepada calon penonton yang hendak datang ke Synchronize Festival akhir pekan nanti. Ucup, demikian ia akrab disapa, merupakan Direktur Program festival tersebut. Tugasnya, salah satunya, adalah melakukan kurasi terhadap band-band penampil di Synchronize.
Dalam beberapa tahun belakangan, Synchronize menjadi acara yang ditunggu kehadirannya. Pasalnya, sejak awal diadakan, Synchronize bisa dibilang mendobrak segala konvensi festival musik lokal pada umumnya: dari mengandalkan musisi dalam negeri hingga menghadirkan kembali nostalgia ke hadapan penonton.
Untuk yang disebut terakhir tersebut bahkan menciptakan euforia tersendiri di tengah anak-anak muda. Berkat Synchronize, lahirlah sebuah pemandangan yang jarang dijumpai: lautan massa menikmati secara paripurna nyanyian Rhoma Irama hingga Nasida Ria.
Ditemui di kantor Demajors di bilangan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Ucup berbicara tentang banyak hal kepada Tirto, mulai dari Soneta sampai apa yang harus dilakukan agar festival musik bisa berlangsung lama. Berikut petikannya.
Synchronize Festival sudah punya signature sebagai festival musik yang mengedepankan musisi-musisi lokal. Bila disempitkan lagi cakupannya, Synchronize juga berani mengundang musisi-musisi lawas sampai yang dianggap ‘norak.’ Apa tujuannya?
Sebetulnya tujuan utama Synchronize hadir itu adalah meng-capture industri musik nasional. Artinya, musik dalam negeri secara keseluruhan. Untuk itulah kita berupaya memfasilitasi semuanya, termasuk musik-musik yang dianggap ‘norak’ tadi. Bahkan, itu jadi semacam karakternya Synchronize: mengundang mereka yang sudah seperti mitos.
Ini juga enggak bisa dilepaskan dari fenomena yang ada. Sekarang, [rodanya] lagi berputar. Yang dulu dianggap ‘bawah,’ sekarang jadi sesuatu yang ‘keren.’ Sementara yang dianggap ‘keren,’ seperti EDM [Electronic Dance Music], malah jadi cheesy. Gue, sebagai Direktur Program, harus bisa membaca fenomena itu.
Setiap tahun, kita berusaha selalu menghadirkan musisi-musisi lawas dalam rentang tahun yang jelas. Misalnya, musisi-musisi 1960-an atau 1970-an. Rentang tahunnya terbayang. Tahun ini saja, ambil contoh, kita berusaha ‘menghadirkan kembali’ Chrisye. Mungkin gue atau elo tahu siapa itu Chrisye. Tapi, belum tentu dengan anak-anak muda zaman sekarang. Inilah yang kemudian ingin kita lakukan: mengedukasi kepada penonton tentang apa yang terjadi dalam industri musik lokal.
Ada kesulitan tidak ketika mengundang para musisi veteran seperti, katakanlah, Rhoma Irama dan Soneta? Mengingat ada gap generasi yang cukup lebar, ya.
Musisi-musisi lama biasanya cuek karena mereka beranggapan sudah manggung ribuan kali. Susahnya adalah bagaimana kita menginformasikan Synchronize kepada mereka. Karena mereka sendiri kadang enggak yakin apakah nanti banyak yang nonton atau enggak. Kayak Rhoma [Irama] kemarin itu enggak percaya diri dengan potensi antusiasme dari penonton. Sama dengan Ebiet [G. Ade] yang kaget ketika yang nonton show-nya banyak.
Mengundang mereka tampil ke Synchronize enggak gampang. Pendekatannya adalah bukan, ‘Eh, tanggal segini kosong enggak?’ Bukan seperti itu. Tapi, lebih ke pendekatan yang personal. ‘Eh, Synchronize mau ada lagi ini. Kira-kira konsepnya begini, begitu.’ Jadi, kita datang ke mereka tidak dengan tangan kosong. Pendekatan bukan sekadar telepon, tapi juga harus secara personal. Kita datang sebagai temen, bukan semata pelaku bisnis.
Festival di Indonesia selalu identik dengan sponsor rokok. Ada anggapan, kalau ingin bikin festival yang besar, maka harus cari sponsor rokok. Sekarang bagaimana kondisinya? Apakah sebuah festival bisa mandiri tanpa rokok?
Jawabannya bisa banget. Banyak festival di Indonesia yang sudah bisa berjalan tanpa kehadiran [sponsor] rokok. Jazz Gunung [festival jazz di kaki Pegunungan Bromo yang diinisiasi oleh Butet Kertaradjasa dan Djaduk Ferianto], misalnya.
Sebetulnya, Synchronize sendiri juga ada sponsor dari rokok. Cuma, porsinya enggak besar dan enggak jadi sponsor utama. Sejak awal, kita ingin festival ini bisa berjalan tanpa batasan umur—sesuatu yang sulit terealisasi bila mengundang rokok sebagai sponsor.
Lagi pula, bila dilihat dengan baik, ada banyak peluang dari sponsor non-rokok karena industri sponsorhip-nya kebetulan juga sedang berkembang. Mulai dari e-commerce hingg telco [telecommunication]. Kalau elo tadi tanya bisa enggak [festival musik] jalan tanpa rokok, ya, jawabannya bisa. Asalkan perhitungan bisnis dan kecakapan untuk menangkap peluang sponsor yang lain itu jelas.
Kita lihat aja pensi [pentas seni] di SMA-SMA itu. Pensi, kan, bisa dibilang cikal bakal festival. All genre. Mereka bisa, tuh, berkembang tanpa rokok. Bahkan, secara kolektif. Seharusnya kita, yang lebih ‘dewasa,’ juga bisa berpikir seperti mereka.
Exposure yang dihasilkan Synchronize tidak bisa dipungkiri cukup besar. Adakah efek positif yang didapatkan band-band penampil dari situ? Misalnya soal jumlah streaming mereka.
Kalau untuk menghitung dampak digital, belum ada perhitungan yang dilakukan secara formal. Tapi, secara umum, gue yakin ada [dampaknya]. Jamrud, misalnya. After Synchronize, mereka jadi langganan festival-festival anak muda. Itu juga termasuk dampak. Jadi, ada expand market dari band-band ini.
Karena bagaimanapun, ketika band-band ini berupaya tampil total dalam Synchronize, akan ada dampak yang mereka peroleh. Karena penonton [Synchronize] sendiri juga bermacam-macam. Gue yakin ada dampaknya.
Butuh sampai berapa penyelenggaraan bagi Synchronize agar balik modal?
Sebetulnya di tahun kedua itu [finansial] udah baik. Jarang banget ada festival berskala nasional yang di tahun kedua [keuangannya] udah berstatus biru. Ini di luar prediksi kita juga. Mungkin karena saat itu yang ditawarkan Synchronize adalah sesuatu yang baru, yang fresh, di tengah kebosanan terhadap line-up internasional.
Kuncinya adalah bahwa festival harus bisa ngasi vibe yang seru. Ini bukan perkara siapa yang tampil. Tapi, lebih ke bagaimana festival itu bisa jadi ruang selebrasi bagi para penonton. Lebih ke situ, sih. Dan ini yang sedang kita bangun. Syukur, hasilnya sudah kelihatan. Sebelum announce soal line-up kemarin, tiket laku terjual sekitar tujuh ribu. Ini bukti bahwa orang-orang yakin dan percaya kredibilitas Synchronize.
Ada kemungkinan untuk mengundang penampil internasional?
Kemungkinan ke sana [tetap] ada.
Apakah tidak berpotensi mengurangi identitas Synchronize itu sendiri karena selama ini publik mengenal Synchronize sebagai festival yang lokalitasnya sangat terasa kuat?
Ini bakal jadi hal yang tricky, sih, sebetulnya. Analoginya seperti main musik. Orang akan kaget ketika yang dulunya main pop banget, tiba-tiba berubah haluan ke subgenre. Tapi, pada akhirnya, ini soal bagaimana kita ngegambar festival itu. Gimana caranya kita mempertahankan karakter yang udah dibuat, dan yang paling penting enggak sampai bikin penonton kaget.
Inilah pentingnya konsep dalam sebuah festival musik. Kayak misalnya aja, tahun ini, kita menghadirkan lagi Wali, Radja, dan Andika [Kangen Band] buat ‘main’ di Synchronize. Orang-orang bakal bilang, ‘Anjing, ga sabar ternyata nunggu mereka main.’ Sebisa mungkin, sekalipun nanti pada akhirnya ada line-up dari luar yang diundang, kita akan tetap menjadikan musisi lokal berjaya di rumahnya sendiri.
Festival musik di Indonesia punya masalah akut berupa line-up yang itu-itu saja. Regerenasi seperti berhenti.
Kalau mau bilang sebenarnya Synchronize juga terjebak di lingkaran itu. Tapi, cara untuk menyiasati masalah ini adalah bahwa pihak festival harus berani main konsep. Synchronize memang banyak banget band yang main, namun kita juga ngasih space untuk, misalnya, band-band emo maupun Melayu.
Ini yang kemudian jadi tantangan festival-festival di Indonesia. Bagaimana mereka bisa lepas dari jebakan penampil utama. Karena pada dasarnya festival itu bukan ajang sekadar comot [band] dari sana dan sini untuk dibentuk jadi sebuah kesatuan. Festival juga bicara soal gimana cara elo untuk bikin program yang menarik dan sebagainya.
Kultur kita sudah menuju ke arah sana?
Gue rasa akan menuju ke sana. Berdasarkan pengamatan gue ke tiga festival yang gede macam We The Fest, Soundrenaline, dan Synchronize sendiri, kultur itu udah mulai kebentuk. Di We The Fest, misalnya, orang dateng ke sana bukan cuma lagi pengen lihat band-band asing tapi juga pengen memenuhi kebutuhan lifestyle mereka. Ini balik lagi ke gimana caranya sebuah festival itu bisa menawarkan sesuatu yang berbeda kepada para penontonnya.
Untuk sebuah festival yang besar, harga tiket Synchronize tergolong murah, atau mungkin tepatnya terjangkau. Apakah memang sesuai dengan kalkulasi finansialnya?
Synchronize memasang tiket yang “murah” sebetulnya tidak sedang bertujuan untuk datengin banyak orang. Ini karena hitung-hitungannya udah possible aja di harga segitu. Tapi, jika boleh bilang, tiket kita itu tergolong mahal untuk pasar penonton Synchronize yang kebanyakan diisi oleh anak-anak SMA sampai mahasiswa. Di awal itu, secara finansial Synchronize bisa dibilang gagal. Karena kita emang fokus ngebangun antusiasme terlebih dahulu.
Bagaimana cara membentuk penonton yang loyal?
Kuncinya ada di vibes. Jadi, ketika elo dateng ke festival musik itu ada hal positif yang bisa dibawa pulang dan jadi bekal untuk nonton lagi di tahun depan. Salah satunya adalah alur pengisi acara. Ini penting banget. Karena festival musik harus bisa bikin mood orang jadi happy ending, bukan malah bikin tambah pusing.
Di tahun awal, secara finansial Synchronize belum memenuhi target. Namun, di waktu bersamaan, berhasil dalam hal awareness. Festival, sekali lagi, bukan ajang berkumpulnya band-band besar semata. Banyak nama besar bukan jaminan. Festival, yang terpenting, harus bisa jadi wadah maupun ruang untuk selebrasi dan bukan malah terus mengikuti permintaan pasar.
Editor: Windu Jusuf