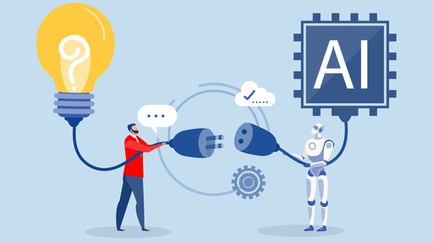tirto.id - Suara mesin kapal menderu di balik tanggul laut. Sore itu anak-anak berlarian di hadapan para orang tuanya yang duduk di bangku plastik. Tetua pria bersarung; yang perempuan berkerudung. Mereka, warga Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, seolah tak peduli terik menghujam kulit hingga peluh menumpuk di aspal.
Saya menemui Mariyah, 49 tahun, ibu rumah tangga bersuamikan nelayan bernama Udi. Angin laut mulai terasa mendekat, persis saya yang menghampirinya untuk duduk bersebelahan. Sumuk belum hilang. Sebagai perempuan yang terlibat dalam dalam sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, peran Mariyah tak kalah penting, meski ia tak turut menjaring ikan di tengah laut.
Sebelum Udi melaut, Mariyah akan menyiapkan keperluan si suami seperti makan-minum. Ibaratnya, jika tak ada sang istri, Udi bisa saja kerepotan menyiapkan semuanya seorang diri. Peran perempuan seringkali diabaikan dan kurang terdokumentasikan dengan baik perihal efek dari perubahan iklim.
Naiknya permukaan air laut dan tingginya ombak membuat nelayan sulit untuk menangkap ikan, lalu ada pencemaran limbah pabrik dan rumah tangga yang juga berkontribusi mencemarkan laut.
Perubahan iklim yang mengakibatkan kemarau berkepanjangan, bencana alam, peningkatan permukaan air laut dan ombak yang besar menyebabkan turunnya hasil tangkapan nelayan. Di laut kawasan Cilincing, pernah ada limbah pabrik yang mengotori laut yang mengakibatkan ikan-ikan di situ pun mati mengambang. Belum lagi perkara permukaan air laut dan tingginya ombak kawasan Cilincing pun berpengaruh.
Mariyah, yang segera mengenakan kerudungnya sebelum kami bercakap, mengaku hal-hal perubahan iklim berdampak kepada keluarganya.
Dia mengeluarkan Rp600-700 ribu untuk modal sekali perjalanan, sementara hasil penjualan ikan Rp800 ribu hingga Rp1 juta. Malah bisa remis alias sama saja modal dan untung. Keluarga ini memiliki kapal bermesin tiga, bila ditambah dengan solar dan kebutuhan lainnya maka modal sekali jalan bisa Rp3 juta untuk dua-tiga hari melaut.
“Banyak kerugiannya, besar pengeluaran. Buat solar, bekal makan, rokok,” kata Mariyah, Jumat (27/10/2023). Mariyah, sebagai pengelola keuangan keluarga, harus memutar otak agar kebutuhan bulan tersebut terpenuhi. “Kalau pendapatan kurang, ya, kami mengutang di warung.”
Ketika saya tanya apakah hasil tangkapan saat ini berbeda dengan lima atau sepuluh tahun lalu? Mariyah menegaskan, “Lebih sedikit, sih, kalau sekarang.”
Bahkan Udi bisa putar balik kapal jika ombak menjadi lawan. “Kalau cuaca baik, kadang dapat (untung) lebih (banyak ketimbang modal). Kalau ombak (tinggi), balik lagi (bersandar).”
Apa yang dialami Mariyah juga dipotret dalam sebuah studi. Persepsi peran perempuan sebagai penanggung jawab pemenuhan kebutuhan dan belanja keluarga, membuat banyak perempuan, terutama ibu rumah tangga yang terjebak dalam utang.
Hal ini lantaran perempuan di permukiman nelayan di Jakarta Utara tidak banyak yang memiliki rekening bank sehingga rentan terlilit utang dari koperasi, lintah darat, atau kredit keliling yang mengenakan bunga tinggi.

Nelayan Perempuan Alami KDRT
Dua hari berikutnya saya berjanji temu dengan Yulmaini, 44 tahun, di kediamannya di Kamal Muara, masih termasuk area utara Ibu Kota. Rumahnya sekira 50 meter dari “Gedung Biru” ke arah tanggul. Lagu dangdut terdengar dari dalam kiosnya. Yulmaini kerap dipanggil Ayu, memiliki lima anak (tiga tinggal bersamanya dan Frans, suaminya; dua lainnya di Padang).
Anak-anaknya bersekolah, kecuali si bungsu yang masih berusia 4 tahun –ia asyik bermain sendirian. Tak hanya mengurus kiosnya, Ayu kadang turut melaut atau membawa tamu menuju pulau di Kepulauan Seribu.
Biasanya ia pergi melaut sekitar pukul 6 pagi, sekira empat jam kemudian ia kembali ke rumah. Begitu juga suaminya, kadang melaut dan membawa hasil tangkap. Tapi tentu saja hasil tangkapannya tak melulu banyak, paling 6-7 kilogram. Jika dijual per kilogram seharga Rp35 ribu.
Ayu dan Frans menjalani pernikahan selama 13 tahun, tapi hampir setiap hari ia kerap mendapatkan kekerasan dari suaminya. Anak-anak pun jadi saksi perlakuan si bapak.
“Ngoceh sedikit, pukul. Kurang duit, pukul. Memang apa kurangku sebagai perempuan? Aku yang menafkahi semua. Kalau aku tak ke laut, dia ngoceh-ngoceh lagi,” ucap Ayu, suaranya bergetar.
Si suami bakal curiga dan bertanya apa yang Ayu kerjakan di rumah bila tak melaut, apalagi jika Ayu tengah menemani calon tamu yang ingin menggunakan jasanya untuk keliling pulau.
Memang Frans tak pernah menendang Ayu, tapi malah melemparnya dengan balok. Suatu petang ketika Ayu tengah salat magrib, suaminya membawa pisau dan hendak menikamnya.
“Beruntung anak perempuanku menghalanginya. Kalau tak ada anakku, aku mati.”
Hikmat, bukan nama sebenarnya, tetangga Ayu, pun membenarkan bahwa kekerasan sering dilakukan Frans. “Kalau marah-marah, dia (Frans) sering lempar perabotan, kadang main tangan juga. Ayu sudah lelah diperlakukan begitu,” kata dia. Tetangga-tetangga risih, pernah mencoba mengusir Frans tapi gagal.
Ayu beberapa kali lapor kepada polisi tentang kekerasan yang dialaminya. Polisi menindaklanjuti pengaduan itu dengan menyambangi rumah Ayu untuk bertemu Frans, sialnya Frans sering kabur selama beberapa hari agar tak ditangkap. Berkali-kali Ayu ingin pisah dari suaminya, namun tak berhasil pula.
Hasil tangkapan yang berkurang karena perubahan iklim bisa berdampak serius hingga ke atap rumah. Bukan soal lauk peneman nasi, tapi bagaimana suami memperlakukan istri.

Krisis Iklim Picu Kekerasan
Dalam laporanDampak Perubahan Iklim terhadap Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia, perubahan iklim saat ini berperan dalam memperparah krisis kemanusiaan dengan berinteraksi dengan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bahaya terkait iklim.
Perubahan iklim berdampak negatif secara signifikan pada ekosistem, sektor-sektor mata pencaharian, dan interaksi sosial di masyarakat. Laporan ini menyatakan bahwa perubahan tersebut dapat menyebabkan meningkatnya kejadian kekerasan berbasis gender, termasuk tindakan kekerasan fisik, seksual, dan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
Kejadian kekerasan berbasis gender terkait peristiwa cuaca ekstrem diprediksi akan meningkat seiring dengan pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
Ketua Program UN Women Indonesia Dwi Yuliawati Faiz berkata fenomena kekerasan berbasis gender di Indonesia memang sudah ada. Pihaknya juga melakukan survei setiap tahun dan hasilnya satu dari empat perempuan mengalami kekerasan. Perihal perubahan iklim dan dampaknya terhadap kekerasan berbasis gender, salah satu cara melihatnya yakni melalui kerentanan (vulnerability).
“Ketika ada perubahan iklim, maka perempuan lebih rentan terhadap berbagai jenis kekerasan; yang juga menjadi titik kritis dari perubahan iklim dan juga aksi perubahan iklim adalah sumber daya dan juga akses ekonomi. Ini yang kerap jarang disorot,” ujar Dwi, Rabu (25/10/2023). Maka yang terjadi adalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan jadi berlapis.
Dwi mencontohkan perihal dimensi fenomena kelautan. Biasanya yang melaut adalah laki-laki, lalu mereka pulang dan hasil tangkapan dijual atau diproses oleh perempuan. Perubahan iklim menyebabkan melaut itu semakin jauh ikannya semakin sedikit. Maka pendapatan rumah tangga secara keseluruhan juga sedikit.
“Ketika ada penurunan pendapatan, kesulitan ekonomi pada sebuah rumah tangga, perempuan yang menjadi korban,” kata dia.
Makanan maupun produk-produk hasil kelautan yang diproses dan disiapkan oleh perempuan tentu bakal menurun juga. Hal ini yang menyebabkan perempuan menerima kekerasan.
Publik mesti paham bahwa sejak awal situasi memang tidak setara dan perubahan iklim yang membuat perempuan semakin rentan. Bukan berarti perubahan iklim lantas membuat laki-laki memukuli perempuan, namun nyatanya ketidaksetaraan itu memang ada.
Indeks ketimpangan gender Indonesia pada tahun 2021 menempati peringkat 110 dari 170 negara. Sejak 2019, peringkat GII Indonesia berhasil naik 11 peringkat.
Merujuk Indeks Kesenjangan Gender yang dirilis oleh World Economic Forum, beberapa komponen ketimpangan gender pun masih berada di bawah rata-rata global di tahun 2022. Indonesia memiliki Gender Gap Index sebesar 0,697 dan menempati peringkat 92 dari 146 negara.
Sementara, data tahunan yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2016 dan Komnas Perempuan sejak tahun 2001, menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan.
Data yang terkumpul ini berasal dari laporan kasus kekerasan yang dilaporkan kepada berbagai lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, rumah sakit, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Hasil temuan mereka mencatat bahwa setiap tahun kekerasan terhadap perempuan jauh lebih sering terjadi daripada kekerasan terhadap laki-laki. Data ini juga menunjukkan bahwa jumlah kasus dan jumlah korban kekerasan paling tinggi terjadi dalam konteks rumah tangga atau dalam ranah personal, yakni mayoritas kasus tersebut merupakan kekerasan seksual.
Sementara itu, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, Eni Widiyanti, berujar meski tidak menjadi dampak langsung dan dianggap sebagai dampak turunan, tapi perubahan iklim selalu berujung pada kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan.
Ada empat sektor spesifik yang dianalisis, yakni ketahanan pangan, industri ekstraktif, kelautan-perikanan, dan perhutanan sosial. Merujuk kepada Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, secara umum angka kekerasan terhadap perempuan menurun dibandingkan hasil SPHPN tahun 2016.
Hasil SPHPN 2021 menunjukkan 1 dari 4 (26,1 persen) perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan selama hidupnya, dan 1 dari 11 (8,7 persen) perempuan mengalami kekerasan pada kurun waktu setahun terakhir.
Kekerasan terhadap perempuan di daerah perkotaan sedikit lebih besar dibandingkan di pedesaan, baik untuk pengalaman seumur hidup maupun setahun terakhir. Lantas ada 1 dari 9 (11,3 persen) perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan selama hidupnya. Untuk kekerasan fisik ada 1 dari 13 (8,2 persen) perempuan yang pernah mengalami, dan 1 dari 18 (5,7 persen) perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan seksual oleh pasangan selama hidupnya.
Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami/pasangan yang terbanyak dialami adalah pembatasan perilaku (PP) - 30,9 persen untuk waktu selama hidup dan 22,0 persen setahun terakhir. SPHPN 2021 memaparkan hasil kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh orang lain atau bukan pasangan, dan ternyata 1 dari 5 (20,0 persen) perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh bukan pasangan selama hidupnya, dan 1 dari 17 (6,0 persen) perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh bukan pasangan selama setahun terakhir.
Berdasar pengalaman kekerasan ini, 1 dari 7 (15,4 persen) perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan seksual oleh bukan pasangan selama hidupnya, dan 1 dari 20 (5,2 persen) mengalami kekerasan seksual oleh selain pasangan setahun terakhir.
Contoh lain bagaimana krisis iklim berdampak pada kekerasan berbasis gender, dalam hal ini kekerasan seksual adalah kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Desa Pasar Seluma, Bengkulu.
Satreskrim Polres Seluma menetapkan MZ, karyawan Tambang Pasir Besi PT Faminglevto Bakti Abadi, sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual nonverbal, Juni 2023. Ia ditetapkan tersangka atas laporan lima korban yani kaum ibu Desa Pasar Seluma.
Melansir Antara, para ibu saat itu tengah berorasi di depan pintu masuk perusahaan tambang Pasir Besi mendapat pelecehan dari salah satu karyawan tambang besi. Kehadiran tambang ini memicu konflik horizontal dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat, khususnya perempuan.
Selain itu, faktor yang paling banyak sebagai pemicu kekerasan terhadap perempuan adalah faktor ekonomi (30,7 persen). Masalah pekerjaan yang dialami oleh suami maupun istri juga disebut sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya kekerasan.
“Artinya dengan perubahan iklim, seperti kekeringan berkepanjangan di Nusa Tenggara Timur, perempuan yang di sektor pertanian saja berperan untuk ketahanan pangan,” ucap Eni, Rabu (25/10/2023, kepada Tirto.
Ia mencontohkan, ketika akses kepada bahan makanan semakin langka karena gagal panen akibat kekeringan, otomatis rasa aman si perempuan bisa terdampak.
Perempuan itu, lanjut Eni, akan mengakses makanan yang sedikit, lalu mengutamakan makanan itu kepada anak dan suaminya, sementara dia sendiri akan mengonsumsi lebih sedikit.
“Akibatnya apa? Untuk perempuan yang hamil dan menyusui, gizinya jadi berkurang dan anak berpotensi stunting. Kaitannya dengan rasa aman, artinya perempuan jadi korban kekerasan dan lahir praktik-praktik lain seperti perempuan menikah dalam usia anak.
Inilah yang menurut Eni, menjadi awal dari lingkaran setan kemiskinan yang tidak berujung. Perempuan dinikahkan pada usia anak, hamil masih di usia anak-anak, lalu melahirkan, tentunya secara fisik dan mental mereka tidak siap.
“Akan menjadi seperti itu lagi nanti. Dia akan miskin juga nanti ketika dewasa. Begitu terus, ya. Itu cerita ketika ada perubahan iklim,” jelas Eni.
Contoh lain adalah sektor perikanan dan kelautan. Tidak hanya lelaki yang menjadi nelayan, tapi perempuan pun ada. Pengakuan negara ini terhadap nelayan perempuan itu kurang. Buktinya seperti nelayan perempuan yang tak memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka).
“Itu yang kemudian kami perjuangkan. Hubungan dengan kekerasan berbasis gender ini? Ternyata ada diskriminasi terhadap perempuan. Segala macam yang disediakan pemerintah, perempuan menjadi tidak bisa mengakses,” sambung Eni.
Dampak krisis iklim terhadap meningkatnya kekerasan, terutama yang berbasis gender, juga dapat dilihat pada studi kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim. Nyatanya, wilayah yang lebih rentan terhadap perubahan iklim berbanding lurus dengan peningkatan kasus kekerasan di wilayah tersebut.
Studi kasus penelitian ini dilakukan di dua wilayah terpilih yang mewakili daerah pedesaan (rural) dan juga perkotaan (urban) pada level subnasional. Sumba Timur dipilih mewakili wilayah perdesaan, sedangkan Jakarta Utara mewakili daerah perkotaan.
Berdasar laporan ini, dari 350 wilayah urban di tujuh negara ASEAN, termasuk Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Indonesia, tujuh area di DKI Jakarta termasuk dalam 10 kota teratas yang rentan terhadap perubahan iklim (Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Barat). Kemudian, turunnya permukaan pesisir Jakarta yang menyebabkan abrasi dan banjir meningkat tiap tahunnya.
Sementara di Sumba Timur termasuk dalam kabupaten prioritas dalam program resiliensi perubahan iklim. Lalu pada tahun 2022 mengalami kekeringan ekstrem dengan 215 hari tanpa hujan.
Pada tahun 2021 mengalami musim kemarau dengan 205 hari tanpa hujan dan (tidak terdokumentasikan) 259 hari tanpa hujan. Risiko banjir dan kekeringan berada pada kategori sangat tinggi (skor 7.) dan wilayah ini termasuk kategori penduduk termiskin di NTT (BPS 2022).
Lalu berdasar laporan serupa, periode Januari-November 2022, Komnas Perempuan menerima laporan 3014 kasus kekerasan berbasis gender dengan perempuan sebagai korban, 860 di antaranya merupakan kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik dan 899 di ranah personal.
Di level provinsi, laporan mengenai kekerasan berbasis gender di DKI Jakarta menempati peringkat 5 besar di Indonesia, dengan Jakarta Utara merupakan salah satu wilayah dengan angka kekerasan berbasis gender tertinggi di Indonesia.
Sedangkan di Sumba Timur pada tahun 2022 tercatat 84 kasus kekerasan berbasis gender di Sumba Timur, angka ini merupakan angka tertinggi jika dibandingkan dengan empat kabupaten lain di Pulau Sumba (SIMFONI-PPA); Perempuan memutuskan untuk bekerja sebagai imigran ilegal karena adanya kemarau yang berkepanjangan dan kekurangan pangan.

Pengarusutamaan Gender Jadi Solusi
Elisabeth Sidabutar, Humanitarian Analyst UNFPA Indonesia menyebut alasan pihaknya memberikan perhatian lebih dalam kasus ini agar bisa mengintegrasikan gender dalam adaptasi lingkungan dan juga mitigasi lingkungan, khususnya berkorelasi dengan kebencanaan yang bisa mengganda. Apalagi dari Sabang sampai Merauke daerah Indonesia termasuk 97 persen daerah rawan bencana.
Adanya perubahan iklim yang mengarah ke krisis lingkungan sekarang ini bakal mempercepat atau menggandakan jumlah respons kemanusiaan atau penanganan bencana yang ada.
“Ini menjadi kekhawatiran kami. Situasi normal saja ada masalah ketimpangan kuasa-relasi antara perempuan dan laki-laki di Indonesia. Kita daerah patriarki, ya, bermasalah,” kata Elisabeth kepada Tirto.
UNFPA ingin bergerak cepat dalam memitigasi krisis lingkungan dan kesiapsiagaan kebencanaan. “Dengan memitigasi kesiapsiagaan bencana, dengan begitu kami mengurangi risiko-risiko kerentanan terhadap kelompok rentan.”
Secara keseluruhan semua upaya untuk meminimalisasi dampak negatif perubahan iklim harus sejalan dengan upaya-upaya lain seperti pengentasan kekerasan perempuan.
“Punya perspektif gender dan mempertimbangkan kerentanan adalah cara baik untuk berbisnis dalam aksi iklim,” ujar Dwi dari UN Women Indonesia.
Masalah yang terjalin dalam sektor rumah tangga disebabkan oleh norma dan peran gender perempuan, maka yang perlu dilakukan saat ini adalah fokus bagaimana publik menghapus norma-norma tersebut.
Project Manager Saraswati, Rini Astriani Fauziah, berpendapat serupa. Dalam perkara krisis iklim yang berdampak kepada kekerasan berbasis gender, ada banyak faktor hambatan yang dikaitkan dengan norma sosial. Rini bilang pihaknya tak hanya melihat dari tingkatan yang memiliki opsi banyak (akses kesehatan, pendidikan dan lain dengan mudah), tapi juga dalam ranah ekonomi atau faktor penentu lain.
Lantas bagaimana jika kebiasaan adat atau norma sosial suatu daerah jadi penghambat perubahan? "Dilihat konteks per konteks. Karena sosial dan budaya satu daerah dengan daerah lain punya keunikan masing-masing, tapi memang (mengubah) itu sesuatu yang tidak gampang," ujar Rini.
Apalagi jika hambatan itu bernuansa membenarkan 'atas nama budaya'.
Hal lain yang tak kalah penting adalah regulasi. Di Indonesia telah banyak aturan dan kebijakan. Lantas bagaimana agar lintas sektor pemerintah bisa mengoptimalkan regulasi yang telah ada?
“Sebenarnya yang bisa dilakukan adalah mengintegrasikan kebijakan yang sudah ada, melaksanakan dengan baik dan memonitornya. Itu saja PR-nya, tidak usah ditambah lagi (aturan baru),” tutur Dwi.
Senada, Rini pun menegaskan pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan baru perihal kasus-kasus karena iklim ini, namun bisa memaksimalkan aturan yang ada.
Koordinasi antarlembaga pun jadi penting, agar tak menjadi masalah baru. "Kendalanya, kalau bisa dibilang ego masing-masing kebutuhan dari sektor tersebut. Bagaimana mereka ingin menjadikan apa yang menjadi prioritas, karena prioritas balik lagi kepada anggaran, kepada bagaimana mereka melakukan pelaporan. Ketika hal-hal itu tidak bertemu di satu titik, maka itu akan jadi susah," terang Rini.
Lalu belum ada sinkronisasi yang tepat untuk menyamakan regulasi negara dan nilai adat. Tapi ada kendala lain seperti memetakan semua itu menjadi satu. Lantaran pemetaan itu bersifat kontekstual dan kebudayaan tiap daerah berbeda, itu menjadi tantangan tersendiri. "Hambatannya adalah apakah kita punya sumber daya, mungkin orang atau dana untuk melakukan itu?"
Rini juga menegaskan bahwa tak hanya perempuan yang mendapatkan edukasi demi kepentingan dirinya, namun pelibatan laki-laki pun wajib disertakan. Agar bisa mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan, tidak ada kesenjangan dan celah, serta perempuan bisa menyuarakan pendapatnya tanpa merasa posisinya lebih rendah ketimbang pria. Semua ini bukan soal siapa yang mendahului siapa, tapi setara dalam kebutuhan.
Di sisi lain, negara juga perlu memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Misalnya, mengikutsertakan partisipasi perempuan dan komunitas dalam penanganan perubahan iklim atau pemanfaatan lahan.
Tata kelola pemerintahan yang baik jika bisa diimplementasikan maksimal, maka isu-isu tersebut tak perlu muncul. “Ini tata kelola pemerintah dan itu harus netral dari kepentingan politik,” ujar Dwi.
Sementara itu, Eni menyebut Kementerian PPA tak mungkin bekerja sendiri untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Ada dua solusi paling mendasar guna memperkecil kesenjangan.
Pertama, pengarusutamaan gender. Eni menegaskan semua program di kementerian apa pun semuanya harus diwarnai dengan program yang responsif terhadap gender. Dua, perlindungan perempuan. Dengan cara menerapkan program yang sistematis dan berkelanjutan, serta memenuhi hak-hak perempuan.
UNFPA menyebut adanya kolaborasi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk bisa memaksimalkan rencana ini. Hasilnya nanti bisa saja berupa peta panduan yang kemudian diperkuat oleh banyak pihak guna memastikan partisipasi perempuan di dalam perencanaan atau penanganan kebencanaan.
Editor: Restu Diantina Putri
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id