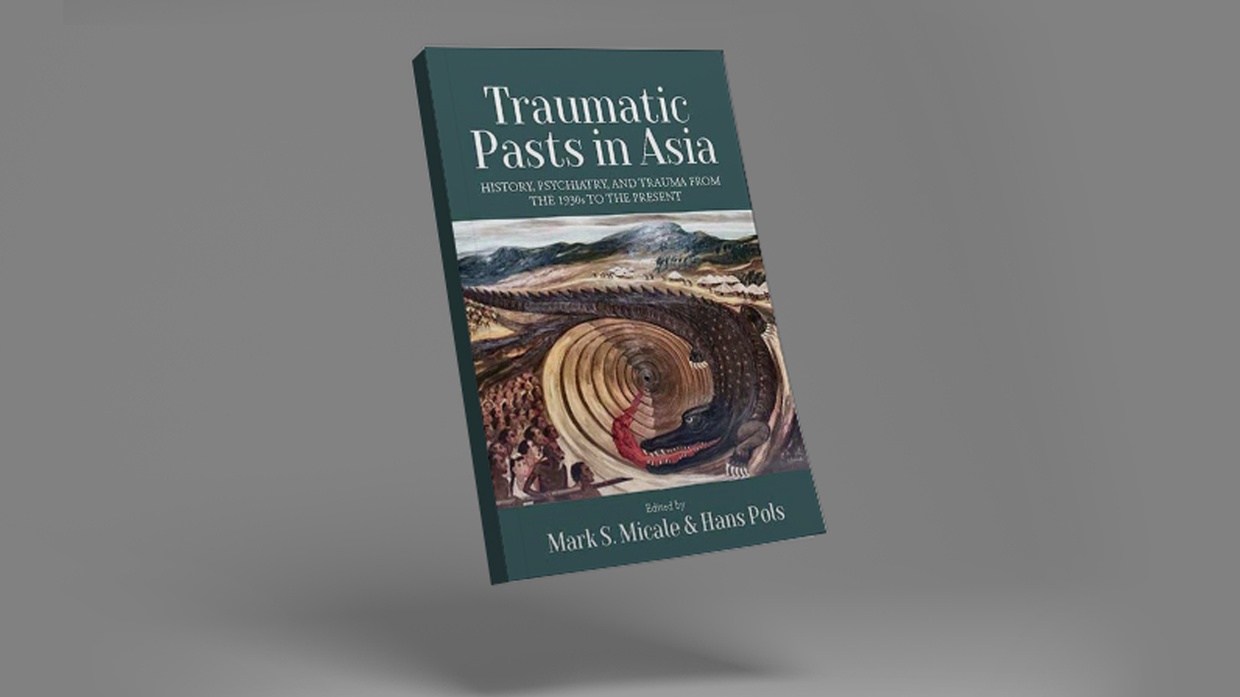tirto.id - “Kami meninggalkan [Blitar Selatan] dengan hati tak menentu… karena beberapa dari kami mesti meninggalkan anak, di tengah medan perang yang suram. Bagaimana seseorang dapat melarikan diri dengan mudah bila membawa serta anak-anak? Jadi Bu C, E, dan G harus menitipkan anak-anaknya kepada orang lain. Bu C meninggalkan anak lelakinya yang berumur 6 tahun, Bu G meninggalkan putrinya yang berumur 5 tahun, sedangkan Bu E menitipkan dua anak, satu masih menyusu dan seorang lagi anak perempuan berusia 5 tahun… Tak satu pun dari anak-anak ini ditemukan kembali oleh orang tuanya.”
Itulah penggalan surat Pudji Aswati, seorang tahanan politik anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), kepada Patricia Cleveland-Peck, seorang penulis cerita anak dari Sussex Timur, Inggris. Surat itu kemungkinan ditulis pada 1984 atau sesudahnya, ketika Pudji berhasil menemukan cara menyelundupkan surat keluar tanpa harus menghadapi sensor sipir penjara.
Surat itu kemudian dikutip oleh Vannessa Hearman dalam “Psychological Trauma and Suffering In Long Distance Friendships Involving Political Prisoners in Indonesia” yang menjadi bagian dari bunga rampai Traumatic Pasts in Asia: History, Psychiatry, and Trauma from the 1930s to the Present. Bunga rampai itu dieditori oleh Mark S. Micale dan Hans Pols dan terbit pada September 2021 lalu.
Surat-menyurat antara seorang tapol dan seorang perempuan kelas menengah di sebuah negara maju itu bukanlah korespondensi biasa. Surat-menyurat itu adalah bagian dari sebuah gerakan politik.
Pada awal 1970-an, kaum Quaker Inggris dan Amnesty International menggagas sebuah kampanye masif yang menghubungkan para anggota dua organisasi ini dengan para tahanan politik di negara-negara kawasan Selatan. Kaum Quaker kemudian membuat kampanye sendiri, yaitu “Prisoner Befriending Scheme” yang kegiatannya juga berkirim surat dan kartu kepada para tahanan politik di Chili, Argentina, Uni Soviet, dan Indonesia.
Patricia Cleveland-Peck dan Pudji Aswati adalah salah satu pasangan kawan pena yang terhubung melalui gerakan ini.
Kala masih aktif di Gerwani, Pudji mengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah menengah atas untuk komunitas Tionghoa. Dia juga rutin menulis artikel di nawala-nawala organisasi gerakan perempuan internasional. Suaminya, Gatot Lestario, juga seorang guru dan pengurus Partai Komunis Indonesia (PKI) Surabaya pada 1950-an.
Kemudian meletuslah Gerakan 30 September (G30S) 1965. Setelah peristiwa ini, militer mengumumkan lewat siaran radio bahwa PKI melalui G30S, berniat mencetuskan pemberontakan nasional. Dengan dalih memulihkan kembali ketertiban dan keamanan negara, militer melancarkan operasi pembersihan terhadap orang-orang komunis dan siapa pun yang dianggap terkait dengan PKI beserta organisasi-organisasi afiliasinya.
Pada 2010, Jess Melvin menemukan 3.000 halaman dokumen militer Indonesia yang mengkonfirmasi bahwa operasi penumpasan tersebut dilancarkan untuk menghancurkan PKI sebagai lawan politik militer (Melvin, Jess, The Army and The Indonesian Genocide. Mechanics of Mass Murder, 2018, hlm. 2-3, 301).
Pogrom yang dipimpin Jenderal Soeharto itu meluas di seluruh wilayah Indonesia sejak awal Oktober 1965 hingga sekitar Maret 1966. Beberapa sumber sejarah mencatat setidaknya 500.000 hingga 1 juta orang tewas dalam kampanye pembersihan itu. Salah satu provinsi yang mengalami pembantaian paling mengerikan adalah Jawa Timur, tempat Pudji dan Gatot tinggal.
Ketika Soeharto pegang kendali kekuasaan pada Maret 1966, operasi pengganyangan kelompok kiri semakin intensif. Pada awal 1967, Pudji dan Gatot menyingkir ke Blitar Selatan untuk menghindari perburuan militer sekaligus membangun kembali kekuatan partai di wilayah pedesaan.
Fase pelarian itu berlangsung selama tiga tahun. Hingga akhirnya pada 28 Juni 1968, Pudji tertangkap dalam Operasi Trisula—operasi militer besar-besaran melibatkan 5.000 personel tentara sepanjang Juni-September 1968.
Pudji kemudian dikirim ke penjara perempuan di Malang dan baru dibebaskan pada 1989. Segala jenis siksaan, kelaparan, dan kekurangan dialami Pudji dan para tahanan politik perempuan lainnya, menciptakan trauma berlapis.
Meski begitu, tak sekalipun Pudji menyebutkan kata “trauma” dalam 150 lembar surat Pudji kepada Cleveland-Peck yang dikumpulkan Vannessa Hearman. Padahal, sepanjang 3 tahun pelarian dan berlanjut 21 tahun di dalam penjara, Pudji mengalami penderitaan yang kompleks.
Dalam rentang derita yang panjang, Pudji masih juga harus berpisah dengan kedua anaknya setelah rumahnya dibakar massa. Pukulan terberat Pudji adalah menerima berita bahwa Gatot tertangkap dalam pelarian ke Jakarta pada Januari 1969 dan dieksekusi mati pada Juli 1985.
Tak juga dia ceritakan bagaimana dirinya diperkosa beramai-ramai oleh tujuh anggota hansip kala baru saja masuk tahanan. Teman-temannya sesama tapol pun baru berani menceritakan pemerkosaan itu kepada jurnalis pada 2012.
Sensor ketat untuk surat-menyurat berkontribusi dalam keengganan Pudji menceritakan detail penderitaan yang dialaminya. Selain itu, mengingat dan menceritakan penderitaan sendiri kepada orang lain memang bukan perkara gampang bagi korban.
Maka Pudji dan Cleveland-Peck membangun persahabatan mereka dengan cerita keseharian dan hobi. Mereka membahas hobi merajut, buku, dan keluarga. Kisah ringan keseharian, menurut Janet Maybin yang dikutip dalam buku ini, merupakan kegiatan yang bersifat terapi, selain surat-menyurat itu sendiri.

Micale dan Pols juga menjelaskan kemungkinan lain terkait absennya kata “trauma” dalam surat-surat Pudji. Di bagian Pendahuluan, Pols dan Micale menyebut badan-badan bantuan internasional yang bekerja di Asia menggunakan konsep psikiatri Barat dalam menangani kejadian-kejadian traumatis. Namun, konsep dan penanganan fenomena kejiwaan ala Barat itu tidak selalu selaras dengan pendekatan-pendekatan lokal yang dipakai untuk menangani bencana alam, trauma, dan gangguan sosial besar. Padahal, Tafsiran atas trauma dan bagaimana dampaknya pada setiap individu tentunya sangat beragam sesuai dengan latar budaya penyintas.
Buku Traumatic Pasts in Asia: History, Psychiatry, and Trauma from the 1930s to the Present ini menghimpun 12 studi kasus sejarah dan antropologi dari berbagai negara di Asia dalam rentang waktu 1930-an hingga kini. Pols dan Micale mengumpulkannya untuk mengetahui bagaimana individu dan komunitas menanggapi bencana serta bagaimana strategi bertahan yang dilakukan oleh korban dan penyintas.
Beberapa bab dalam buku ini menjajaki bagaimana ilmu kedokteran, psikologi, dan psikiatri memainkan peran dalam upaya memahami dan menangani pengalaman-pengalaman traumatis serta interaksinya dengan pendekatan lokal.
Selain kisah Pudji di Bab 6 yang ditulis oleh Vannessa Hearman, Dyah Pitaloka dan Mohan J. Dutta menuliskan “Performing Songs as Healing the Trauma of the 1965 Anti-Communist Killings in Indonesia” di Bab 9.
Studi Pitaloka dan Dutta itu mengetengahkan kelompok paduan suara Dialita yang anggotanya terdiri dari para korban, penyintas, atau kerabat korban. Lagu-lagu dari penjara perempuan yang pernah terkubur dan dibungkam, akhirnya berhasil meraih pendengar-pendengar muda pada awal 2000-an. Album pertama meraka, Dunia Milik Kita, bahkan diluncurkan di Beringin Soekarno di kompleks kampus Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, pada Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2016.
Selain dari Indonesia, Traumatic Pasts in Asia juga menghadirkan kisah-kisah para korban dan penyintas bom atom Hiroshima dan Nagasaki, Perang Korea, Perang Asia-Pasifik, Kamboja Pasca-Khmer Merah, gerakan demokrasi di Burma, perebutan wilayah Kashmir, hingga kisah korban gempa bumi di Taiwan pada 1935.
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id