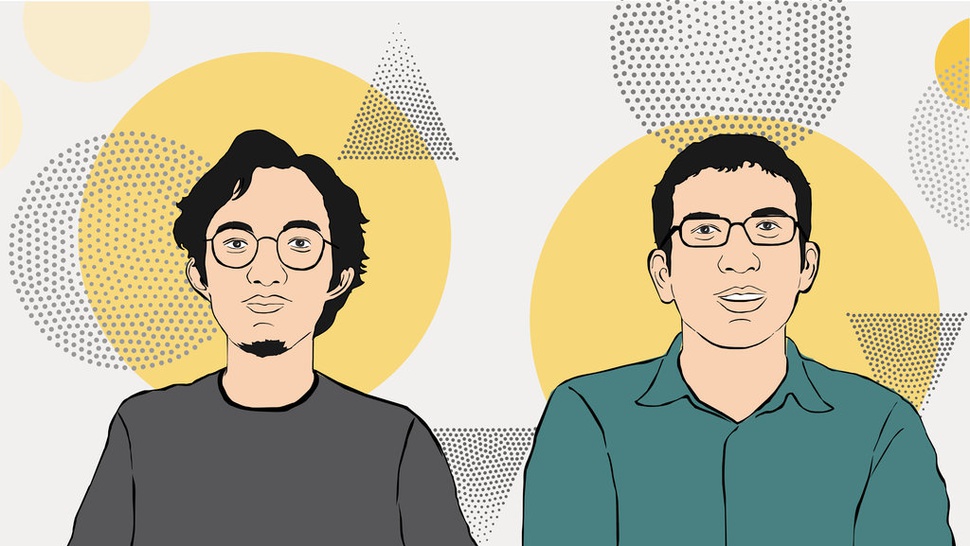tirto.id - Mengapa sinetron Indonesia, yang menurunkan kualitasnya, tetap laris manis dan menjaring banyak penonton? Jalan cerita yang tak masuk akal dan akting yang buruk tetap disukai penonton.
Melongok informasi dari akun Rating Program Televisi Indonesia per 28 April 2017, pemuncak daftar acara dengan rating tertinggi adalah sinetron Dunia Terbalik, dan 10 dari 15 acara televisi itu adalah sinetron.
Kami berbincang dengan Yovantra Arief dan Muhamad Heychael, dua peneliti dari pusat studi media dan komunikasi Remotivi, untuk mendiskusikan tentang kualitas sinetron dan lingkaran setan, perebutan kue iklan di televisi, serta perlunya turut campur negara dalam tayangan televisi.
Sebenarnya mana yang lebih tepat: sinetron jelek ada karena yang nonton masih ada, ataukah selera penonton memang kurang bagus sehingga sinetron jelek terus diproduksi?
Yovantra: Menurut saya, karena sinetron "jelek" terus diproduksi. Persoalannya sebenarnya ada di bagian "standar baik-buruk sinetron" itu datangnya dari mana? KPI punya standar P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran), dan stasiun televisi punya rating. P3SPS itu, kan, hukum positif, dan seringkali kagok kalau mau mengukur konten TV berdasarkan nilai "publik" yang ia kandung. Sederhananya, Anda bisa lihat pasal-pasal soal seksualitas. Isinya larangan atas tindakan yang mengarah pada seks dan pembatasan tubuh perempuan: enggak boleh kelihatan bokong, belahan dada, dan seterusnya. Memang perempuan sering diobjektivikasi lewat gambar, tapi kan bukan itu saja.
Dalam pasal soal perlindungan perempuan, yang ada itu hanya mengatur konten jurnalistik: soal harus menyamarkan identitas untuk korban pemerkosaan. Lalu bagaimana kita mau bicara soal proyek kesetaraan gender? Tentu enggak bisa lewat produk hukum positif macam ini karena bisa berabe kalau ada pasal, misalnya, "Semua penulis naskah sudah harus khatam Second Sex-nya (filsuf feminis) de Beauvoir".
Soal isu kesetaraan gender atau keberagaman, misalnya, itu bisa dicapai melalui kebijakan programatik. Strateginya bisa macam-macam, tapi sejauh yang saya tahu, KPI tidak punya itu. KPI punya sekolah P3SPS. Tapi, ya, isinya soal hal teknis itu tadi: gambar macam apa, adegan macam apa, yang enggak boleh kelihatan.
Padahal yang tidak dimiliki pekerja TV adalah perspektif dan imajinasi soal menghadirkan gender secara setara di TV. Belum lagi soal efektivitas, karena turn-over pekerja TV cukup tinggi. Wartawan TV rotasinya cepat, dan tiap tahun ada orang baru. KPI pernah mengeluh soal ini. Jadi sebenarnya perspektif ini mesti dikenal sejak dari sekolahan atau perusahaan TV punya pendidikan perspektif juga. Kalau infrastruktur semacam ini sudah ada, KPI bisa memberlakukan aturan yang lebih progresif yang bukan cuma soal teknis.
Soal rating, sebagaimana sekarang ramai diperdebatkan, itu sebenarnya problem turunan. Memang ada masalah representasi, metode pengambilan data, sampai kecurigaan bahwa rating bisa dibeli. Tapi kalau pun sistem rating sudah sempurna, saya enggak yakin sinetron bakal membaik.
Rating, kan, mau enggak mau soal bisnis. Jadi yang disurvei itu hanya kota yang jadi target market pengiklan saja, enggak merepresentasikan Indonesia. Akar masalahnya itu ada di infrastruktur sebenarnya.
Sejak TV swasta mulai muncul tahun 1990-an, saingannya itu masalah wilayah siar. Siapa yang siarannya paling besar, dia yang menang. Nah, kalau sudah ada 10 stasiun TV bersiaran nasional kayak sekarang, saingannya ya antara mereka sendiri. Kita tidak punya banyak pilihan karena sinetron mereka, kan, kualitasnya sama semua. Prinsip penonton Indonesia akhirnya, kan: "Ya adanya itu, mau gimana lagi?"
TV besar itu sudah ada di semacam comfort zone. Dengan produksi sinetron seperti itu saja sudah dapat untung, ngapain ningkatin kualitas? Lalu, kalaupun ada TV lokal yang mau bikin sinetron yang kualitasnya lebih bagus, sebagus apa pun penontonnya di wilayah lokal, dia enggak bakal bisa nyaingin raksasa-raksasa ini kecuali dimodalin orang-orang kaya Hary Tanoesoedibjo.
Tantangannya itu bagaimana kita tidak lagi menjadikan infrastruktur sebagai domain persaingan (karena TV lokal pasti kalah banyak, dan TV raksasa itu pasti menang karena jangkaunnya nasional dan pengiklan pengin jangkauan itu). Melainkan lebih pada persaingan di wilayah konten. Kalau sudah di konten, TV dipaksa ningkatin production value. Jadi TV mesti ngurangin durasi tayang sinetron supaya produknya lebih baik dan diminati orang. Sekarang, kan, enggak.
Dalam hitungan kami, umumnya satu sutradara memproduksi 1 menit sinetron dalam 8-12 menit. Dalam 1 minggu, 1 penulis naskah mesti nulis 1 jam tayangan, terus-terusan. Gimana mau ngimpi bikin Game of Thrones?
Ini baru dua standar kualitas. Belum lagi kalau kita bicara soal masyarakat umum: ada yang bilang nasionalisme-lah, moralitas-lah, perjuangan kelas-lah, yang tidak terlalu mendesak kita bicarakan sekarang.
(Baca: 'Tukang Bubur Naik Haji' > 'Game of Thrones')
Apakah ada pengaruh, misalnya, dari anggapan kita kekurangan penulis naskah sinetron?
Heychael: Aku kira bukan di situ, ya. Aku juga punya teman yang kebetulan menulis naskah TV. Awal-awal dia bikin ceritanya cukup ideal, kan. Lalu oleh produser minta diedit karena banyak tempat. Kalau terlalu banyak tempat, katanya nanti biaya produksinya membengkak. Nah, artinya ada penulisan naskah, lalu produksi itu mengikuti bujet sebenarnya. Ini yang menjadi pekerjaan rumah, karena bujet sedikit kemudian sulit untuk berkreativitas. Akhirnya tempatnya rumah, taman dan paling sama café. Nah sekreatif bagaimana pun kalau dibatasi dengan bujet, kukira akan sulit.
Bagaimana asumsi bahwa selera penonton memang tertarik dengan kualitas buruk, mengikuti tren dari tayangan stasiun TV pesaing?
Heychael: Ada beberapa hal yang sebetulnya menolak asumsi itu. Kita ambil contoh sinetron Para Pencari Tuhan. Meski dinilai banyak kekurangan, kalau kita lihat sinetron yang sekarang lagi tren, saya kira kualitasnya jauh dari Para Pencari Tuhan, yang masih punya ide cerita, ada karakter yang kuat. Nah ia pernah mendapatkan rating nomor satu saat bulan puasa.
Artinya, sebenarnya, kalau ada sinetron yang bagus dan relevan, dekat dengan kehidupan sehari-hari, masyarakat mau kok. Persoalannya, masyarakat dibiasakan dengan sinetron yang kita sebut "buruk" itu, loh. Dan akhirnya seleranya terbentuk. Buktinya kita dulu menikmati Si Doel Anak Sekolahan, kita menikmati Keluarga Cemara, artinya masyarakat sebenarnya siap dengan konten yang bagus.
Tahun 2015, KPI melansir survei tentang tayangan dengan indeks rendah. Sinetron termasuk yang punya indeks terendah. Siapa yang layak bertanggung jawab, anggaplah begitu, atas temuan KPI ini?
Yovantra: KPI itu niatnya bikin tiap tahun. Paling baru itu November-Desember 2016. Niatnya sih rating alternatif. Sebenarnya, banyak yang bertanggungjawab karena ini industri yang melibatkan pelbagai institusi sosial.
Perusahaan TV dan PH itu yang secara langsung bertanggung jawab karena mereka yang memproduksi. Negara, terutama yang secara langsung ngurusin TV, seperti Komisi I DPR, Kominfo, dan KPI. Mereka yang bikin dan ngawal aturan main. Mereka juga yang idealnya bikin program literasi media pada publik.
Sejak kapan sinetron bersinonim dengan kualitas buruk?
Yovantra: Sejak produksi stripping mulai sering dipraktikkan. Sinetron Tersanjung itu potret paling bagus. Pada 1998, dia cuma tayang Jumat jam 8 malam, kalau tidak salah ingat. Lalu seminggu 2 kali, terus sampai 2005, sebelum tamat, tayang hampir tiap hari. Dari tokoh Indah dimainin oleh Lulu Tobing, Jihan Fahira, sampai Ayu Azhari.
Sebenarnya menarik untuk menggali secara historis kenapa industri kita akhirnya ada di jalur ini, tapi kami belum kesampaian juga melakukan penelitian.
Dugaan saya, hal ini berhubungan dengan ekspansi infrastruktur penyiaran. Sampai 1990-an, televisi swasta siarannya masih terbatas di kota-kota tertentu dan membidik pasar kelas menengah ke atas. Sumberdaya profesional masih sangat terbatas sehingga tidak kuat produksi terlalu banyak. Ditambah lagi, TVRI masih cukup dominan dalam membentuk selera massa.
Dari arsip-arsip koran yang saya baca, sinetron TVRI masih sering merajai peringkat pertama dalam survei SRI (sekarang Nielsen). Setelah Orde Baru tumbang, TVRI mulai menurun daya saingnya. TV swasta makin luas wilayah siarnya, dan makin banyak sekolah yang meluluskan calon pekerja TV. Tahun 2005 mungkin puncak dari booming TV bersiaran nasional karena Kominfo memberi izin untuk 5 stasiun TV sekaligus waktu itu.
Masuk tahun 2010, 10 TV itu sudah berkuasa, hegemoni yang enggak ada yang nantang. "Formula" sinetron pun sudah ditemukan karena teknologi rating sudah bisa real-time, jadi ketahuan bagian mana dari sinetron yang banyak ditonton, tokoh mana yang lagi populer. Dan yang terjadi setelah itu, ya, pasar bekerja, yang permintaannya besar (terbukti dari rating). Itu dapat jam tayang paling banyak.
Tapi yang perlu diingat, "pasar" di sini bahkan enggak memenuhi ideal dari orang liberal, karena diciptakan oleh oligarki besar yang menguasai infrastruktur penyiaran nasional. (Lihat infografik Remotivi mengenai peta siar televisi Indonesia)
Remotivi pernah melakukan penelitian tentang demografi penonton sinetron?
Yovantra: Belum. Data Nielsen, meskipun punya bias urban, masih merupakan acuan paling baik di Indonesia.
Heychael: Kalau realitasnya sulit kita bayangkan. Tetapi kalau kita mengacu ke datanya Nielsen, semua rating ukurannya Nielsen. Nah, Nielsen ini sistemnya mengambil sampel di sebelas kota, sebelas kota itu 50 persennya Jakarta. Jadi 50 persennya lagi ada di 10 kota yang lain. Yang kedua, sampel paling besar adalah kelas C, menengah ke bawah atau menengah. Berarti bisa kita bayangkan, kalau seperti itu, berarti porsi penonton sinetron terbesar pun adalah menengah ke bawah.
Akhirnya, itu dijadikan alibi: "Oh, kita bukan tidak mau memproduksi tayangan bagus. Tapi karena penontonnya kelas C." Makanya yang dikenal "penonton" (dalam tanda petik) itu adalah tayangan-tayangan seperti Si Boy Anak Jalanan, misalkan.
Ini saya kira lempar tanggung jawab. Ketika Anda menghadirkan Para Pencari Tuhan itu juga dimakan (ditonton). Jangan salahkan penonton dan cara pandang seperti ini. Sangat bias. Seolah-olah kelas menengah ke bawah itu adalah orang-orang yang tidak punya selera dan orang-orang yang punya selera itu kelas menengah ke atas. Jadi tidak begitu cara berpikirnya karena fakta-fakta menunjukkan, tayangan yang bagus kalau juga diberikan kesempatan, itu bisa diterima.
Persoalan di TV, kalau ada tayangan bagus, baru tayang tiga episode, tidak naik ratingnya, langsung dibunuh, tidak diteruskan. Para pemilik stasiun TV inginnya langsung: ini disukai enggak, ini ratingnya naik enggak? Begitu, kan.
Saya melihatnya dalam sistem ekonomi-politiknya, industri televisi kita, tidak sehat.
Sebenarnya KPI punya peran menginstruksi, salah satunya lewat regulasi. Misalnya sanksi-sanksi yang lain untuk tayangan-tayangan yang tidak bermutu. Ini belum dimainkan maksimal oleh KPI sehingga stasiun TV tidak perlu memperbaiki diri.
Apakah ada kasus sinetron yang dihentikan tayang karena aduan masyarakat?
Yovantra: Sejauh yang kami amati, belum ada. Lagi pula, tidak ada yang bisa memberhentikan program TV. Di aturannya sih, KPI, melalui persetujuan Kominfo, bisa. Tapi mekanismenya tidak terlalu jelas dan tidak pernah dipakai. Yang bisa menghentikan program cuma TV dan itu hanya terjadi karena sudah tidak menguntungkan.
Paling banter penghentian sementara. Seingat saya Ganteng-Ganteng Serigala pernah tiga kali melanggar berturut-turut. Tidak begitu jelas apakah itu karena desakan masyarakat. Tapi memang banyak yang protes kala itu.
Tim riset Tirto mengumpulkan jadwal televisi 5-11 Mei 2017. Di masa jam tayang utama, kebanyakan adalah sinetron. Indikasi sinetron memang mesin uang terbesar bagi industri televisi?
Yovantra: Yap! Setahu saya, fenomena ini sudah terjadi sejak tahun 1990-an. Zaman itu Kompas sering meliput hasil rating SRI tiap minggu, dan yang memuncaki tangga rating, ya, sinetron.
Apa yang bisa dilakukan agar kualitas sinetron membaik?
Yovantra: Kuncinya sebenarnya meningkatkan production value tiap episode, dan konsekuensinya menyudahi praktik stripping. Dinamika di PH sendiri sebenarnya sangat berpengaruh.
Semakin ke sini, kan, integrasi horisontal TV makin kuat. PH besar banyak diakuisisi perusahaan TV atau sebuah grup bikin PH sendiri macam MNC. Ini sangat kontras dari awal industri ini terbentuk: PH produksi lalu dijual ke TV. Sekarang memang lebih menguntungkan TV karena kontrol produksinya lebih mudah dan cost-nya bisa lebih ditekan. Ini jadi tantangan tersendiri.
Tentu ini bukan obat mujarab yang langsung bikin sinetron kita keren. Pekerjanya juga mesti dididik, baik itu masalah teknik sinematografi dan teknik penceritaan, juga masalah perspektif dan isu sosial yang bisa diangkat. Tapi itu tahap yang lebih advanced, karena percuma kalau tim kreatifnya keren tapi kondisi kerjanya tidak memungkinkan itu. Kalau production value bisa ditingkatkan, eksperimen dan persaingan kualitas antar sinetron akan mungkin terjadi.
Heychael: Yang pertama adalah moratorium perizinan. Yang kedua, pemerintah harus menyusun syarat pendirian televisi. Nah, selama ini syarat itu hanya syarat teknis. Menurut saya, harusnya ada syarat modal: Kalau kamu tidak kuat bikin TV, tidak boleh bikin produksi sembarang.
Selain itu, misalnya KPI, daripada melakukan survei kualitas siaran yang enggak penting itu, mendingan mereka melakukan riset misalnya: Sekarang ini ada berapa rumah produksi di Indonesia? Lalu mereka melayani TV itu, per rumah produksi itu berapa. Itu untuk menghitung, apakah rumah produksi kita kurang sehingga harus ditopang stripping?
Kalau pola stripping ini masih berjalan, masih menjadi masalah. Pertanyaannya kenapa sih orang stripping? Kenapa dulu enggak stripping? Apakah rumah produksinya berlebihan atau bagaimana?
Pertama-tama, sebelum kita mengambil keputusan, yang dibutuhkan mengurangi masalah ini. Masalah stripping sendiri belum tuntas.
Yang kita tahu baru di level perizinan. Tetapi di level industrinya bagaimana? Relasi pengiklan dengan stasiun televisi, misalnya. Nah, kalau ini sudah bisa dijelaskan dengan riset yang baik, maka kita bisa merumuskan intervensi. (Lihat infografik Remotivi mengenai balada industri sinetron kejar tayang)
Bagaimana peran pemerintah mengatasi problem tayangan televisi?
Yovantra: Pemerintah bisa menyiasati struktur industri supaya memungkinkan buat bikin sinetron yang berkualitas. Masalah, hegemoni TV besar ini, kan, problem lama dan berhubungan masalah-masalah lain. Kalau konsentrasi dipecah, pasti berimbas juga pada sinetron.
Misalnya, sistem jaringan dilakukan dengan benar, dan siaran nasional dibatasi sekian jam, sisanya harus siaran lokal. Siaran nasional hanya bisa sekian persen dari total prime time. Dengan batasan-batasan waktu seperti itu, durasi sinetron prime time mau tidak mau dipadatkan, jadi investasinya bukan di soal memanjangkan durasi tapi meningkatkan narasi buat bersaing sama sinetron lain.
Selain itu, kesejahteraan pekerja TV pun enggak pernah jadi perhatian negara.
Misalnya, dalam hitungan kami, pemain anak yang 13 tahun itu bisa kerja 8-13 jam sehari, apalagi kru produksi yang sudah dewasa? Ini perlindungan kerjanya gimana? Kalau standar jam kerja dibikin manusiawi, pilihan TV itu antara nambah orang buat produksi stripping (yang kurang menguntungkan), atau ngurangin jumlah produksi. Strateginya bisa diulik lagi lebih dalam dan kalau negara niat (Bekraf tu ngapain aja sih? Kayaknya sadar pun enggak, deh), tinggal bikin riset, datengin ahli, bikin regulasi. (Baca wawancara Remotivi: "Ada Eksploitasi Anak dalam Sinetron Televisi)
Heychael: Apabila kenyataannya kita kurang rumah produksi, pemerintah bisa membuat insentif ke pengusaha yang mau masuk ke rumah produksi. Nah, yang sekarang terjadi, pemerintah tahu saja tidak. Bahkan KPI sejak periode lalu salah sasaran dengan bikin malah indeks survei siaran. Itu tidak banyak berguna. Alih-alih seharusnya kita memahami realitas industri (televisi) kita.
Penulis: Arbi Sumandoyo & Nuran Wibisono
Editor: Fahri Salam