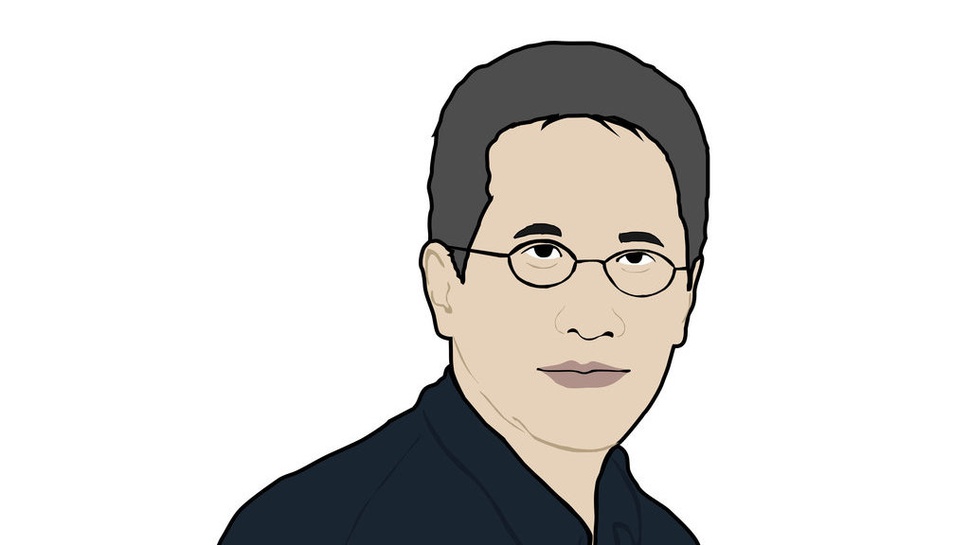tirto.id - Hari ini Indonesia tiba di sebuah persimpangan jalan seiring ketegangan menajam antara dua kiblat moralitas dan politik (tetapi dalam banyak kubu): kebangsaan dan keagamaan. Situasi itu terungkap secara gamblang dalam istilah dan semboyan yang dipakai dalam debat publik.
Misalnya “Islam Nusantara” dan sosok lawannya yang secara tersirat atau tersurat dianggap kurang atau tidak Nusantara. Pancasila, kemajemukan tersirat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan “NKRI” juga dijadikan senjata yang dikerahkan untuk menanggapi kekerasan yang dengan klaim agama. Contoh mutakhirnya: bom bunuh-diri di dekat gedung Sarinah (Jakarta, 2016), vihara di Tanjung Balai (2016), gereja (Surabaya, 2018). Wacana nasionalis juga tampil sebagai tanggapan terhadap laporan penelitian yang menunjuk pada merosotnya toleransi antar golongan (SARA) di lingkungan sekolah, keluarga, hingga debat politik sejak pilres 2014, disusul pilgub DKI (2017) hingga menjelang pilpres 2019.
Catatan ini adalah ajakan untuk memahami peta persoalan secara lebih jernih dengan mengambil jarak sejenak dari rangkaian kasus-per-kasus pertikaian. Dengan berjarak dari kasus mikro dan individu yang terlibat, semoga masalah makro yang dihadapi Indonesia bisa diamati dengan wawasan lebih luas dan bijak.
Duduk Persoalan
Dari mana datangnya ketegangan antara kiblat “kebangsaan” dan “keagamaan” masa kini? Kedua kiblat mempunyai tempat terhormat dalam Pancasila. Bukan baru sekali ini ketegangan di antara mereka mengemuka. Tapi mengapa sekarang ia berkobar (lagi) dan berkepanjangan dalam sosoknya yang mutakhir?
Uraian di bawah ini merupakan sebuah usaha awal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan ada pencerahan yang lebih baik dari mereka yang lebih paham dari penulis.
Ringkasnya, jawaban saya terdiri dari tiga pokok. Pertama, martabat dan kewibawaan nasionalisme mengalami krisis di tingkat global. Kedua, walaupun nasionalisme masih sangat dihormati di Indonesia, kebangsaan di tanah air ini menderita cacat. Sangat berbeda dari semangat kebangsaan di awal abad 20.
Ketiga, kebangkitan Islam di luar bidang keagamaan di Indonesia dalam tiga dekade terakhir menanjak secara dramatis. Ini wajar dan sudah waktunya terjadi. Terlalu lama agama mayoritas ini ditindas dan kaumnya disisihkan di Indonesia. Namun sekali meluap, gelombang kejayaan ini tidak dikendalikan satu pihak, tak mudah diatur, atau dibendung oleh siapapun.
Nasionalisme: Krisis Global dan Cacat Lokal
Dalam bentangan sejarah manusia, nasionalisme relatif berusia muda. Bangsa (dalam pengertian modern seperti yang kita kenal saat ini) baru hadir sekitar dua ratus tahun belakangan.
Pada awal kebangkitannya, kebangsaan diyakini oleh para pendukungnya sebagai sesuatu yang mulia, wajar, terhormat dan berlaku secara adil untuk semua di muka bumi ini. Juga di Indonesia—ingat bunyi Mukadimah UUD 1945. Nasionalisme ini pada awalnya sekaligus berwatak inter-nasional-isme.
Seperti kata ilmuwan politik Benedict Anderson, sedemikian hebatnya gagasan kebangsaan itu, sampai-sampai jutaan pengikutnya (kaum nasionalis) di dunia siap mati demi gagasan tersebut. Mereka bukannya siap membunuh, melainkan berkorban nyawa, demi terwujudnya bangsa-bangsa di dunia.
Gagasan kebangsaan awal itu kini telah mengalami krisis di mana-mana. Banyak sekali penyebab dan prosesnya. Yang jelas, banyak warga bangsa-bangsa di dunia kehilangan kepercayaan pada janji-janji indah kebangsaan. Dalam budaya pop dan gerakan sosial, syair lagu “Imagine” John Lennon mewakili suara generasi muda yang tidak lagi peduli atau percaya pada nilai-nilai kebangsaan.
Berbagai bangsa besar di dunia mengalami krisis nasionalisme, sekaligus krisis moral dan politik lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain: agama, keluarga, partai politik, lembaga pendidikan, teknologi dan sebagainya. Dalam krisis berat ini, warganya meraba-raba, atau merumuskan identitas sosial alternatif. Bentuk dan hasilnya bermacam-macam.
Di Indonesia situasinya berbeda. Seperti di banyak negara bekas terjajah lainnya, khususnya yang mencapai kemerdekaan lewat revolusi berdarah-darah, kebangsaan masih dimuliakan. Juga berbeda di Barat, kebangkitan Islam di Indonesia justru sedang mencapai titik kejayaan yang belum pernah terjadi di negeri ini.
Sayangnya, kebangsaan yang dimuliakan di Indonesia menderita cacat berat. Pada awalnya gagasan kebangsaan di kalangan cendekiawan Indonesia bersifat kosmopolitan, modern, progresif dan lintas-SARA, seperti halnya di banyak bagian dunia lain. Namun, sejak Republik Indonesia merdeka, kebangsaan justru dihayati secara sempit. Dikaitkan dengan primordialisme kesukuan, melahirkan gagasan pribumisasi, dan elitisme Jawa-sentris.
Bangsa tidak lagi dipahami sebagai sebuah cita-cita dan kerja kolektif menciptakan kehidupan bersama yang majemuk, adil, dan beradab bagi semua. Hari ini bangsa dianggap semacam warisan dari nenek moyang. Sebagian warga merasa punya hak-waris istimewa, melebihi hak warga lain yang sebetulnya masih sebangsa.
Walau bertentangan dengan gagasan awal nasionalisme seabad lalu, nasionalisme cacat primordial di Indonesia bertumbuh subur. Ia subur karena dirawat dengan baik oleh sebagian kelompok elit yang diuntungkan oleh gagasan tersebut.
Gagasan nasional-primodial itu jelas anti-kemajemukan. Ironisnya, ia seringkali diserukan dalam wacana publik sebagai semboyan kemajemukan, dan diajukan sebagai lawan dari fundamentalisme keagamaan yang dituduh tidak toleran.
Untuk menghadapi berbagai tantangan zaman, Indonesia tidak bisa terus-menerus mengandalkan gagasan kebangsaan yang cacat. Indonesia perlu menyegarkan kembali gagasan kebangsaan, dengan mengenal dan merayakan gagasan kebangsaan satu abad lampau.
Masa Emas Keagamaan
Masyarakat Indonesia sangat kuat beragama selama berabad-abad. Datangnya kolonialisme Belanda telah membatasi wilayah gerak keagamaan, khususnya gagasan dan kegiatan politik yang didasarkan pada agama.
Kondisi itu berubah sedikit pada tahun-tahun awal kemerdekaan RI. Organisasi sosial, budaya, dan politik dengan afiliasi keagamaan mendapat ruang lebar. Tapi tidak sendirian. Mereka bersaing dengan berbagai organisasi dan partai politik sekuler.
Semua itu berakhir sejak bangkitnya pemerintahan Orde Baru (1966). Komunis dan sosialis dihancur-leburkan. Islam menjadi satu-satunya kekuatan alternatif besar terhadap pemerintahan militer-teknokratik Orde Baru. Setelah Komunis, giliran Islam menjadi sasaran penindasan Orde Baru. Baru pada tahun 1990 keadaan berubah. Untuk mengatasi perpecahan dalam pemerintahannya, Presiden Suharto berusaha menyelamatkan kekuasaan dengan merangkul berbagai kelompok dan tokoh Islam.
Orde Baru tidak terselamatkan, Suharto jatuh. Tetapi keran Islamisasi yang dibuka Suharto menjadi gelombang besar yang tidak tertandingi. Islamnya satu, tapi komunitas muslim tidak tunggal dan seragam. Di sela-sela keragaman itulah, hadir ketegangan antara yang disebut “Nusantara” dan yang dianggap bukan atau kurang.
Di tengah kemeriahan Islamisasi kehidupan bangsa masa kini, berbagai ragam kelompok dan kegiatan Islami bersaing keras. Nasionalisme Indonesia tampak kedodoran memberikan tanggapan, bukan saja karena sudah lama menderita cacat berat, tetapi juga karena tidak didukung oleh kejayaan nasionalisme tingkat global yang sedang menderita krisis.
Sebaliknya, dinamika politik global pasca-Perang Dingin memberikan angin baru pada sebagian negara dengan mayoritas muslim. Dengan bentuk dan arah berbeda-beda, Islami Indonesia mendapat siraman dukungan globalnya. Masalahnya, seperti telah disinggung di atas, pertikaian utama kaum muslim terjadi dengan sesama muslim. Tidak sedikit dari mereka yang masih menyimpan kesetiaan pada gagasan nasionalistik.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.