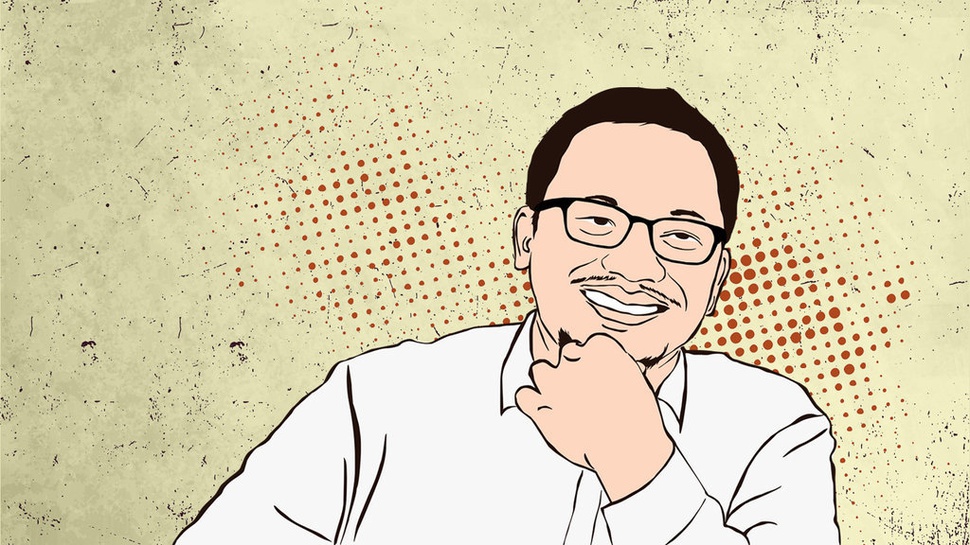tirto.id - Dua dari lima anak pasangan suami-istri, Amien Rais dan Kusnariyati Sri Rahayu, berkarier sebagai politisi. Ahmad Hanafi Rais Wiryosudarmo, si sulung yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2014-2019, adalah salah satunya.
Meski secara resmi menyandang jabatan politik sejak 2014, persentuhan laki-laki yang akrab disapa Hanafi tersebut dengan dunia politik dimulai jauh sebelum itu.
Hanafi menimba ilmu di jurusan Hubungan Internasional (HI) Universitas Gajah Mada (UGM). Selepas itu, dia melanjutkan studi magister kebijakan publik di National University of Singapore (NUS), Singapura. Setelah itu Hanafi pun menjadi dosen di HI UGM.
Pada 2011, Hanafi mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Yogyakarta didampingi Tri Harjun Ismaji. Saat itu, Hanafi-Tri kalah. Paslon yang diusung koalisi PPP, Demokrat, PAN, dan Gerindra itu hanya mendapat 84.122 suara atau setara 42 persen total suara sah.
"Saya enggak baperan ini. Artinya kalau Pilwalkot kalah, ya, udah selesai. Begitu juga kalau menang. The most democratic game itu, ya, lewat pilkada," ujar Hanafi kepada Tirto.
Tiga tahun kemudian, Hanafi banting setir, dari mengincar jabatan eksekutif ke legislatif. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Hanafi terpilih sebagai anggota DPR mewakili Partai Amanat Nasional (PAN) untuk daerah pemilihan (Dapil) Yogyakarta dengan bekal sebesar 197.915 suara.
Ada anggapan seluruh karier Hanafi dibukakan oleh ayahnya, Amien Rais. Sebelum mendirikan PAN pada 1998, Amien adalah pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM -- di sana pula Hanafi sempat mengajar. Kemudian, dia dikenal sebagai tokoh reformasi dan menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1999-2004 -- dan menjadi wakil rakyat pula Hanafi pada akhirnya.
Bagaimana tanggapan Hanafi mengenai anggapan tersebut? Dalam wawancara bersama Zen RS, Ivan Aulia Ahsan, dan Husein Abdulsalam, laki-laki kelahiran Chicago, 9 Oktober 1979 itu bercerita banyak hal, mulai dari pandangannya soal sang ayah, perjalanan karier politiknya, hingga hubungan internasional Indonesia yang menurutnya perlu dibenahi.
Yang mendorong terjun ke politik ini bapak atau dorongan lebih kuat dari internal sendiri?
Lebih yang kedua. Kalau Bapak ke saya dan keempat adik saya tidak pernah mengarahkan nanti kamu harus sekolah jurusan ini atau setelah lulus kerja ini atau jadi apa. Saya ingat pesan Bapak atau ibu ketika kami sekolah pokoknya cuma dimodali ilmu. Terserah mau dipakai apa.
Mungkin juga karena sejak awal saya tertarik untuk mengikuti Bapak. Kemudian saya beberapa kali minta ikut, misalnya pas di Kaliurang, Yogyakarta, di acara Muhammadiyah. Atau pas di Surabaya pernah ikut Bapak mengisi ceramah di acara Pemprov (Pemerintah provinsi). Juga di Jakarta beberapa kali.
Anda mulai kuliah pada 1997, ya?
Saya masuk 1995.
Pada kisaran itu, Pak Amien agak menyengat pemerintahan lewat kolom-kolomnya di Republika. Anda mungkin sudah cukup dewasa untuk membaca tulisan-tulisan itu atau mendengar omongan orang-orang tentang Bapak. Sering juga saat orang-orang membicarakan Pak Amien, padahal Anda ada di situ.
Seringlah kalau itu. Saya lebih suka begitu. Biar orang-orang ngomongin Pak Amien tanpa tahu saya. Saya lebih senang orang membicarakan Pak Amien apa adanya. Kalau tahu, biasanya sungkan atau tidak enak.
Masuk Fisipol bukan atas dorongan Bapak?
Sama sekali enggak. Saya muncul minat masuk HI (Hubungan Internasional) itu karena saya pikir HI bergelut dengan diplomasi, dunia internasional, dan bahasa asing. Ada prestise. Jadi, saya masuk HI aja, deh. Lagi pula passing grade-nya cukup tinggi di Fisipol. Keinginan masuk HI karena alasan-alasan itu saja, bukan karena harus mengikuti Pak Amien.
Dan, Pak Amien pun membiarkan saya. Putusan untuk maju Pilwalkot, misalnya. Pak Amien bilang, "Ya sudah kamu sudah dewasa, kamu putuskan. Kalau hatimu mantap maju, ya maju."
Enggak ada tawaran dari Bapak, ya? Misalnya, "Eh kamu kenapa nggak maju di Yogya?"
Enggak pernah. Saya merasa begini saja: karena eksposure-ku ke aktivitas Bapak itu mungkin banyak. Saya tahu sejak kecil Bapak ngapain. Mungkin minat [ke politik] itu muncul entah secara tidak sadar ke arah sana.
Kalau anak laki-laki, kan, kadang menampik dianggap "mbuntuti bapake". Kan, ada anak laki-laki yang menolak seperti itu. Relasi bapak dan anak [laki-laki] kadang tidak mulus-mulus saja. Ada enggak dorongan Anda untuk tidak seperti Bapak?
Kalau orang mengecap Hanafi cuma mengikuti bapaknya atau cuma mbuntut, yang saya rasakan: jalan apapun yang saya ambil, orang akan [tetap] melabeli seperti itu. Secara biologis saya ini [memang] anaknya Amien Rais. Dari proses itu saya belajar agar omongan orang cukup didengarkan. Enggak semua harus dijalankan.
Waktu awal-awal, misalnya, saat masuk Sospol, kebanyakan temanku masuk ekonomi. Saya masuk Sospol karena kalau di rumah itu saya sering baca bukunya Pak Amien soal politik, revolusi Iran, dan segala macam sehingga saya lebih banyak terpapar hal-hal seperti itu. Jadi saya lebih banyak tahu politik.
Nah, pas lulus Sospol pun minatnya tidak langsung ke politik [praktis]. Waktu itu pilihannya dua: mau jadi wartawan atau dosen. Menurutku dua hal itu sangat berdekatan, dunia intelektual begitulah. Kemudian saya pilih jadi dosen.
Itu pun bukan karena Pak Amien dulunya dosen, tapi karena saya sudah nyaman di kampus. Dulunya saya terlibat di Persma (Pers Mahasiswa) Fisipol UGM Sintesa. Saya jadi PU (Pemimpin Umum). Saya merasa yang paling dekat itu, ya, kampus.
Saya sempat jadi asdos (asisten dosen). Lalu, tahun 2006, saya jadi dosen. Kuliah S2 selama 2 tahun kemudian balik lagi mau meneruskan kuliah S3.
Saya pikir kalau di kampus terus sepertinya dinamikanya kurang seru. Akhirnya saya putuskan untuk mencalonkan walikota waktu itu karena ilmu ada dan selama ini saya juga berkawan dengan teman-teman di PAN. Walaupun bukan struktur, tapi kan banyak bicara dengan mereka. “Kenapa enggak maju untuk eksekutif,” saya pikir.
Ada hampir satu dekade, mulai dari mengajar sampai mencalonkan walikota. Ada enggak, sih, ajakan untuk terjun ke politik saat itu?
Pernah. Waktu saya masih kuliah di Singapura. Waktu itu Ketua Umum PAN, Mas Sutrisno Bachir.
Kebetulan ada teman yang menjadi anggota DPR di zamannya Mas Tris main ke Singapura bertemu saya. Terus saya didorong untuk maju (Pileg 2009) DPR. Saya selesai kuliah kira-kira 2008. Saya ditawarkan maju dari (dapil) di Sumbar (Sumatera Barat) karena suara PAN, kan, bagus di sana.
Waktu itu, saya pikir harus bergelar doktor kalau mau terjun ke politik. Lebih sempurna kalau sudah doktor. Tawaran itu saya tolak. Jadi, 2009 saya masih di kampus sampai 2013. Berangkatku memang dari kampus, dunia intelektual, jadi masuk ke politik langsung waktu 2013 pencalegan ya dengan modal itu.
Melihat ke depan, yang paling dibayangkan di benak Anda itu apa? Sampeyan ini pengen jadi apa?
Kalau jabatan, saya tidak membayangkan mau jadi menteri, presiden, atau anggota DPR. Tapi bahwa saya sudah memilih terjun ke politik, ya, jalani saja. Politik itu bukan pekerjaan, tapi panggilan. Ada banyak misi, baik oleh partai maupun Pak Amien, yang belum selesai yang coba diteruskan. (Proses ini) mau mengantar saya ke mana, saya tidak punya target.
Dari Piwalkot ke pendaftaran caleg, Anda sudah tidak mengajar lagi?
Oh, mengajar. Cutinya saya cabut.
Tapi waktu mendaftar sebagai caleg dengan sendirinya mengajukan pengunduran diri. Jadi terakhir mengajar itu akhir 2013, ya?
Iya, akhir 2013.
Bicara soal Pilwalkot, apa yang Anda catat dari kekalahan itu?
Mobilisasi dukungan di lapangan, di level massa. Mobilisasi itu membutuhkan isu yang kuat. Waktu itu, isu yang saya angkat pembangunan kota. Tapi dilawan dengan isu yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan kota sama sekali.
Key message lawannya itu apa?
Isu pro-penetapan. Waktu itu Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta sedang didorong untuk disahkan.
Itu isu konkret ya?
Malah bukan konkret menurut saya. Kalau konkret malah isu pembangunan karena kami mengangkat isu penataan kota, parkir, taman, dan kartu jaminan kesehatan, dan lain sebagainya.
Isu identitas yang dipakai lawan?
Justru yang muncul isu identitas karena menjadi sentimen primordial orang Yogyakarta; karena wong Jogja harus pro-penetapan. Saya pikir semangat Undang-Undang Keistimewaan sah-sah saja, tapi kemudian itu jadi komoditas politik. Saya pikir memobilisasi dukungan dengan isu politik yang lebih masif itu lebih efektif.
Anda menyadari itu setelah semuanya berjalan atau sejak awal sudah menyadari lawan pakai key-message soal pro-penetapan itu?
Itu munculnya terakhir-terakhir aja. Awal 2011. Itu di tengah proses politik.
Di Pilwalkot, suara yang Anda peroleh tidak sampai 90 ribu. Kira-kira satu tahun kemudian, Anda hampir 200 ribu suara di Pileg. Loncat jauh. Apa kiat Anda?
Saya senang pertanyaan ini. Nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya, kuncinya belajar dari pengalaman kekalahan.
Ternyata isu yang berkaitan dengan kedaerahan ini kuat, maka sejak 2011 bahkan sampai sekarang, saya lebih mendorong memajukan budaya lokal Yogya, berpartner dengan seniman lokal di sana untuk rutin setiap Senin punya acara bareng-bareng. Ada tembang mocopatan, ada lawakannya, yang ending-nya adalah nasihat.
Key-message yang mau disampaikan adalah Hanafi ini anak muda asli Yogya yang paham tentang budaya lokalnya sehingga orang Yogya melihat Hanafi bukan sebagai orang kampus yang jauh dari hingar-bingar rakyat; karena saya dari dulu mencoba untuk konsisten memelihara budaya lokal itu. Sampai sekarang saya masih melakukan itu.
Waktu itu berapa orang tim inti Anda di Pilwalkot dan Pileg?
Tim inti tiga orang. Kalau Piwalkot tiga orang: 1 orang mengurusi jadwal, 1 orang bendahara, dan 1 think-tank untuk diajak bicara. Untuk Pileg jumlahnya sama, tapi orangnya berbeda, meski masih sama teman dan orang Yogya juga.
Persoalan politik identitas ini ngeri-ngeri sedap. Akhir-akhir ini isu juga menguat. Terkait polarisasi di Indonesia sekarang, jalan tengahnya apa sih antara problem konkret dan lekatnya isu identitas?
Saya melihatnya politik identitas laku kalau ada problem material yang tidak selesai. Sekarang, tuh, lagi populer, istilahnya, gelombang kanan. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Yunani. Juga Singapura yang anti-ekspatriat.
Nah, sebenarnya ini adalah masalah material yang tidak selesai. Artinya ada keterdesakan ekonomi, ada kegelisahan terkait kesejahteraan yang makin menurun daya belinya sehingga mereka butuh saluran untuk mengekspresikan ini dalam bentuk apa. Kemudian tiba Pemilu, isu identitas dianggap yang paling efektif menyampaikan kegelisahan dan keresahan ini. Jadi, munculnya populisme kanan, dalam hal ini, yang ngetren akhir-akhir ini, karena problem ekonomi yang tidak selesai.
Kira-kira hanya suprastruktur, ya?
Bahasanya Marxisme seperti itu.
Dalam kasus Jogja 2013, problem material itu apa? Kenapa poltik identitas mengenai keistimewaan Yogya itu bergaung?
Yogya ini gini ratio paling tinggi. Dan itu sampai sekarang. Saya punya hipotesis ketika ini tidak diselesaikan atau sengaja tidak diselesaikan, maka akan mudah sekali untuk dimobilisasi dengan isu identitas. Apakah isu primordial atau isu lain. Kepala daerah mestinya menyelesaikan isu itu karena memang hak dasar setiap warga negara soal akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Saya kira kalau orang perutnya kenyang, dia akan menjalankan agamanya dengan baik. Dia akan menjalani undang-undang dengan baik. Tapi, kalau lapar, angry men are hungry men, orang lapar cenderung marah, kan? Salurannya bisa macam-macam.
Jadi, Anda melihat menguatnya politik identitas jawabannya bukan hanya dengan kampanye kebinekaan, ya?
Nggak. Kampanye kebinekaan itu salah kaprah. Yang dialamatkan di situ adalah masalah ekonomi: listrik naik, daya beli turun, gas naik, harga sembako naik. Orang semakin susah dan tidak punya saluran. Kemudian, ndilalahnya ada ideologi kanan. Kalau dulu mungkin kiri yang laku, kalau sekarang kanan yang laku.
Itu yang terjadi. Jadi, jangan menyalahkan agama atau identitas apa pun. Selesaikan masalah ekonomi itu. Menurut saya, negara mestinya lebih aware bahwa ada problem mendasar material: ekonomi, pendidikan, kesehatan yang seharusnya diselesaikan. Walaupun tidak bisa langsung selesai, tapi harus ada bentuk konkretnya.
Itu seperti Abu Nawas kehilangan jejak kucing dalam rumah tetapi karena gelap dia mencarinya di jalan raya karena lebih terang.
Awalnya ditawari di Sumbar. Kenapa pilihannya tetap nyaleg di Yogya?
Saya nggak baperan ini. Artinya kalau Pilwalkot kalah, ya, udah selesai. Saya menghadiri pengumuman hasil terakhir di KPUD, menghadiri acara KPUD di Balaikota, hadir sendiri untuk menerima kekalahan, dan datang saat pelantikan. Saya belajar, kalau dalam politik itu kita fair aja. Kalau memang sudah kalah, ya selesai di situ. Jangan diseret ke game yang lain. Begitu juga kalau menang. The most democratic game itu, ya, lewat pilkada.
Ketika saya memutuskan maju Pileg di Yogya, itu bukan karena saya kalah, terus merasa penasaran.
Di Yogya kebetulan incumbent-nya, Pak Totok, pindah dapil. Beliau sudah dua periode, kemudian pindah ke asalnya di daerah Malang yang kebetulan di periode kemarin PAN tidak mendapatkan kursi. Dengan begitu, ada kekosongan tokoh PAN. Saya mengajukan bagaimana kalau saya saja di dapil Yogya. DPP menyetujui. Kalau di Sumbar sudah ada incumbent, jadi saya menghormati.
Akhirnya saya maju lewat dapil Yogya dengan harapan waktu itu PAN bisa meraih dua kursi. PAN meraih dua kursi saat 1999. Kemudian, pada 2004, PAN meraih dua kursi. Lalu, hilang saat 2009. Saat 2014 kemarin kami harapkan bisa 2 kursi, tapi ternyata masih kurang 20 ribu suara.
Ketika diputuskan lolos ke Senayan, Anda membayangkan bekerja di Komisi I DPR?
Iya. Disetujui oleh fraksi PAN.
Terkait pengalaman legislator di DPR, kan, biasa, tuh, tiap kelompok punya jagoannya masing-masing. Sepengalaman Anda, siapa orang seperti itu di Komisi I DPR?
Dulu di Golkar ada mas Tantowi Yahya. Saya suka gayanya. Walaupun dikenal artis, tapi dia update dengan urusan luar negeri. Artikulasinya juga bagus.
Komisi I itu, kan, komisi yang paling dekat suasanya dengan kampus. Benar, enggak?
Mungkin karena Komisi I urusannya non-teknis, ya. Misalnya, komisi IV, V, VIII itu kan membahas teknis seperti pertanian, infrastruktur, perdagangan, dan industri.
Komisi I itu negarawanlah. Mikir negaranya beneran, bukan cuma teknisnya. Dia mikir konstitusinya, urusan globalnya, kepentingan dan kedaulatan nasional. Frame orang-orang Komisi I seperti itu, meski beda-beda partai.
Ketika pertama kali masuk ke Senayan, hal pertama yang Anda lakukan apa?
Masuk di Senayan, saya perkenalan degan seluruh teman-temen di komisi. Kemudian, saya berkenalan dengan semua mitra. Kami di Komisi I punya 15 mitra. Dan, saya mempelajari kultur di komisi ini seperti apa.
Saya temukan kultur kerja di sana berbeda jauh dari kampus. Kalau di kampus kami sesama dosen saling berbagi informasi. Kalau di politik, berbagi informasi ini tergantung kedekatan atau kesempatan, apa bisa punya proyek bareng atau kerja sama antar parti atau dapil.
Tapi, di sisi lain, saya pun belajar ilmu negosiasi menjadi ilmu utama di parlemen. Kalau di kampus ini, kan, ilmu teori. Kalau di DPR, ini ilmu negosiasinya: antara Komisi I dengan pemerintah, antara satu partai dengan partai lain dalam komisi, atau antar anggota partai dalam komisi. Di sospol pernah belajar itu. Ada mata kuliah "Negosiasi dan Resolusi Konflik". Itu populer di kampus.
Salah satu fungsi DPR, kan, membuat Undang-undang. Anda punya target satu Undang-Undang untuk dikejar?
Sejak awal saya ingin mendorong ada undang-undang perjanjian internasional yang lebih up-to-date.
Dari yang saya pelajari selama ini, pertimbangan membuat perjanjian internasional tidak hanya negara dan negara saja, tapi juga dengan aktor non-negara. Bisa dengan perusahaan yang pengaruh modalnya lebih dari kekuasaan negara bahkan individu.
Melihat itu, semestinya undang-undang perjanjian internasional di Indonesia berubah. Tapi, sampai sekarang belum berhasil. Sekarang sudah ada undang-undang perjanjian internasional tahun 1999. Itu out-of-date. Ya, itu tadi alasannya.
Dengan itu, masalahnya kita nanti bisa sering tidak punya bargaining position. Banyak case yang kita selalu kalah dalam perundingan internasional, maju dalam litigasi di forum internasional, misalnya di WTO, atau membuat perjanjian internasional secara bilateral tapi kita dalam poisisi yang less powerfull.
Misalnya, di periode kemarin kita buat perjanjian Defence Cooperation Agreement dengan Singapura. Isinya tidak menguntungkan Indonesia karena pertimbangannya hanya soal kepentingan nasional kedua negara. Padahal di sana ada kepentingan investor industri pertahanan.
Itu problem kelemahan regulasi atau memang keterampilan diplomat Indonesia yang kurang, atau memang negara Indonesia yang powerless?
Powerless, sih, tidak. Indonesia punya potensi militer yang cukup bagus di kawasan Asia Tenggara. Saya kira jumlah prajurit juga yang paling banyak di Asia Tenggara. Selama ini Indonesia juga punya sejarah diplomat hebat. Ada Djuanda yang melahirkan undang-undang UNCLOS. Keterampilan diplomat, dalam bacaan kami anggota parlemen, mestinya lebih bisa di-upgrade.
Loh Anda ini, kan, dosennya para [calon] diplomat itu?
Kalau bicara keterampilan diplomatik, sih, soal skill-nya saja. Itu lebih banyak inovasi, tidak cuma teori. Teori memang ada, tapi temuan lapangan harus tetap update dan biasanya apa yang berangkat dari dunia swasta lebih cepat update. Saya kira Kemenlu perlu melakukan kombinasi dari kampus, swasta, dan dunia diplomatnya tersendiri.
Dalam melakukan negosiasi memang dilakukan tertutup, tapi kita bisa melihat hasilnya, kira-kira kita untung apa tidak.
Soal batas wilayah Indonesia dengan Singapura saya kira masih menyisakan permasalahan?
Memang ada. Kalau soal batas wilayah laut dengan Singapura itu tinggal satu titik di sebelah timur Singapura dan Batam yang belum selesai karena mesti melibatkan Malaysia. Jadi perundingannya tripartit. Yang ke barat, sudah selesai.
Itu krusial. Sebagai negara merdeka maka batas wilayah darat, laut, dan udara juga harus jelas. Itu terkait hak ekonomi, wilayah, dan lintas manusia.
Kalau soal clearing house di Papua, apa pandangan Anda?
Kami kalau raker (rapat kerja) dengan Menlu (Menteri Luar Negeri), Menhan (Menteri Pertahanan), dan BIN (Badan Interlijen Nasional), itu memang jadi salah satu titik atau pintu supaya warga asing tidak menyebarkan abuse of information tentang Papua. Kami melihat cara OPM, Benny Wenda cs., menggalang dukungan lewat informasi palsu. Dan, ini mesti dibendung, tentu, dengan kontra-diplomasi publik yang lebih efektif.
Tapi karena Presiden sudah mengatakan dibuka bebas orang asing masuk ke Papua. Di sisi lain, ada clearing house yang dibentuk bersama oleh pemerintah untuk menyeleksi bahwa yang keluar-masuk itu yang valid, bukan untuk menyebarkan propaganda atau misinformasi. Dalam konteks itu, mestinya ada laporan yang rutin.
Sampai sekarang, kalau kami cek ke daerah-daerah, soal bebas visa misalnya, termasuk di Papua, sumber daya Indonesia sendiri untuk melakukan pengawasan kurang. Jadi antara keinginan dan resource agak jauh.
Langkah pak Jokowi mendatangi banyak negara pasifik adalah langkah yang benar dari sisi diplomatik?
Itu tepat menurutku. Negara-negara pasifik selatan ini memang kecil tapi mereka punya satu suara yang sama dengan Indonesia, Cina, atau Amerika Serikat di PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Jadi, jangan diremehkan. Justru menjadi tetangga dan dekat harusnya jadi prioritas.
Sama seperti ASEAN yang juga jangan ditinggalkan. Presiden tampak lebh prefer untuk melakukan diplomasi bilateral daripada dengan ASEAN yang multi-lateral.
Saya pikir negara-negara Pasifik Selatan ini kalau digandeng lebih intensif akan menguntungkan kepentingan nasional, terutama Papua. Mestinya itu dikerjakan secara serius, tidak sekadar gimmick.
Misalnya begini. Mereka menganggap Melanesia itu milik mereka. Padahal, kalau dilihat dari sejarahnya, pusat Melanesia ini ada di Indonesia, terutama di Maluku. Di NTT juga kuat. Saya pikir mengapa ini tidak jadi proyek bersama dengan negara Pasifik Selatan bahwa identitas Melanesia itu milik bersama.
Kami pernah mengusulkan itu kepada pemerintah. Tapi, tindak lanjutnya kami belum melihat secara konkret.
Soal kualitas diplomat. Sempat ramai jadi bahan perbincangan mengenai dua diplomat muda Indonesia yang membela Papua dengan argumentasi yang seolah mereka tidak membaca apapun mengenai situasi di Papua. Menurut Anda bagaimana?
Iya. Pertama, diplomat muda itu ketika membuat statement resmi atas nama negara pasti juga atas endorsement Kemenlu. Jadi, dia tidak membuat opininya sendiri. Artinya ketika pesan itu disampaikan Kemenlu lewat dua diplomat muda, pesannya kira-kira setimpal dengan cara negara-negara lain yang mencoba mengusik kemerdekaan Papua.
Informasi yang mereka (OPM) sebarkan saja itu tidak berdasarkan fakta yang objektif, bahkan berdasarkan hoaks dan informasi palsu. Karena itu, Kemenlu menyatakan jangan terlalu masuk ke dalam game mereka sehingga yang kami bahasakan itu yang lebih ringan atau lebih gampang dipahami. Saya pikir kalau seperti itu.
Berikutnya soal Timur Tengah. Bagaimana Anda melihat hubungan Indonesia dengan Timur Tengah?
Timur Tengah sedang berubah drastis. Iran menjadi negara yang cukup kuat, mengimbangi Arab Saudi di Timur Tengah. Di berbagai macam konflik Iran cukup menunjukkan kekuatannya, di Yaman, Suriah, Libanon, Sementara itu, Arab Saudi yang selama ini menjadi barometer kekuatan politik di Timur Tengah, sedang mengalami perubahan yang tidak gampang secara domestik maupun kawasan.
Saya pikir Indonesia sekarang ini semestinya bisa mengambil posisi sebagai negara Muslim terbesar dengan memainkan diplomasi ala Islam: bahwa dua kekuatan besar yang berpengaruh, baik itu Iran dengan kawan-kawannya atau Arab Saudi dengan kawan-kawannya, bisa lebih unified. Dari situ, ketika menghadapi masalah Israel, terorisme, atau Amerika Serikat yang cenderung tidak pasti sekarang ini, ayunan diplomatiknya bisa lebih berbobot.
Anda masih tetap concern ke Timur Tengah?
Kalau minat, jika tidak Timur Tengah ya Asia.
Masih membaca buku?
Saya membaca, tapi ebook.
Penulis: Husein Abdulsalam
Editor: Zen RS