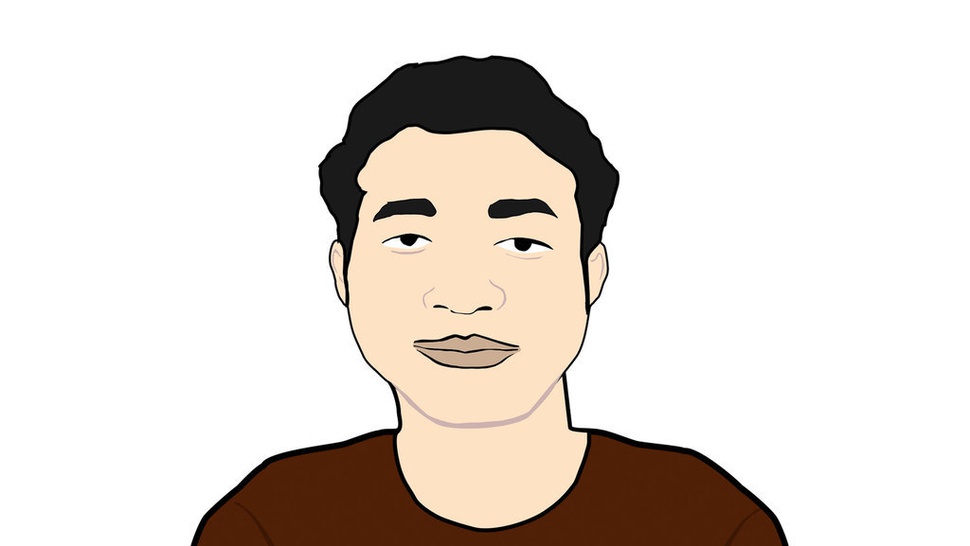tirto.id - Anggapan umum bahwa partai politik (parpol) hanyalah kendaraan "rental" dalam pemilihan semakin terbukti. Menjelang masa kampanye, parpol sibuk melihat ke luar menyaring daftar tokoh yang bakal diusung. Dari latar belakang mana tidak soal, yang penting daya tarung elektabilitasnya (peluang kandidat untuk dipilih).
Di daerah-daerah bernilai strategis, calon non-kader makin jadi andalan. Di Jawa Timur, misalnya, gabungan partai mengusung pasangan calon (paslon) tokoh masyarakat, petahana, dan keluarga elite. Kondisi yang mirip terjadi di Sulawesi Selatan. Di Sumatera Utara, daftar calon didominasi pengusaha dan militer. Hampir seluruh daerah, provinsi dan kabupaten/kota, calon non-kader lebih mewarnai perhelatan politik.
Hal yang menarik, kalangan TNI/Polri dan pegawai negeri (PNS/ASN) adalah figur paling banyak disorot. Karakter kelembagaan mereka memang paling berpengaruh terhadap modal dan jejaring. Selama masa kerjanya mereka mengakumulasi modal sosial dan kultural, plus jejaring modal ekonominya.
Jumlah figurnya pun meningkat. Pada Pilkada 2015, 18 persen kandidat berasal dari TNI/Polri. Peningkatan tajam di Pilkada 2018, tokoh TNI/Polri jumlahnya mencapai 30 persen. Sisanya, mayoritas tokoh masyarakat dan pengusaha bukan kader partai namun dekat dengan partai
Klise berikutnya adalah anggapan bahwa partai defisit kader. Kondisi ini tidak saja terjadi di parpol kecil. Parpol menengah dan besar kondisinya sama.
Lalu, kenapa partai tidak percaya diri mengusung kader sendiri?
Menuju Elektabilitas
Sebelum menjawab itu, perlu dipahami pentingnya mengusung kader internal partai. Secara internal parpol memperjuangkan tujuan-tujuan tertentu. Kemudian, publik mengenal parpol dari politik eksternalnya, yaitu rekam kerja para anggotanya yang tersebar di berbagai jabatan publik. Politik internal dan eksternal melahirkan “platform partai”. Platform partai dapat dilihat dan dirasakan publik, bukan sekadar lewat sosialisasi.
Jika parpol terus-menerus mengusung tokoh “siap pakai”, akan muncul gap antara politik internal dan eksternal partai. Karena tidak berproses di dalam partai, figur non-kader yang menjadi pejabat hampir pasti akan mengambil kebijakan berdasar nilai, tujuan, dan cara berbeda. Kesalahan figur non-kader tidak bisa ditimpakan ke parpol karena dia bukan kader. Sebaliknya, prestasinya sebagai pengambil kebijakan pun bukan kegemilangan partai.
Terpisahnya politik internal dan eksternal berdampak gerak politik jadi lebih elitis dan mengikis tradisi pertanggungjawaban politik. Akhirnya, parpol semakin merasa nyaman bermain dalam pembagian sumber daya di tingkat elite dan kebijakan strategis. Publik pun semakin sulit mengidentifikasi rekam kerja partai. Masalah ini berjalan seperti siklus yang mengaburkan platform partai. Padahal tanpa jelasnya platform, apa yang bisa diharap dari parpol?
Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan diri parpol mengusung kadernya sendiri. Pertama, rendahnya popularitas kader. Namun, rendahnya popularitas bukan salah kader alih-alih partai yang tidak mengelola dan mendistribusikan jejaring politiknya untuk diolah kader. Regenerasi kedekatan dengan masyarakat (public engagement) sebagai dasar popularitas pun lemah karena parpol lebih suka bermain di tataran elite, misalnya dalam perdebatan APBN/APBD belaka.
Kedua, rekam kerja positif (reputasi) parpol yang tidak dirasakan masyarakat. Mayoritas survei menempatkan parpol di urutan terendah kepercayaan publik. Masalah keberpihakan dan korupsi adalah isu utama yang menurunkan citra parpol secara serius. Sejauh ini, kita belum melihat parpol atau tokohnya yang konsisten mendorong perubahan nyata. Publik malah menyaksikan daftar panjang skandal korupsi.
Popularitas dan reputasi adalah pondasi melambungnya “nama merek” (brand name) parpol, sebagaimana diutarakan John Aldrich, yang mempengaruhi nilai kemenangan dalam pemilihan. “Nama merek” adalah modal politik yang sifatnya akumulatif. Jika parpol sudah punya “nama merek”, kapan pun diadakan pemilihan ia akan berpeluang menang.
Buruknya “nama merek” tidak hanya berimbas pada ditariknya figur non-kader dalam pemilihan. Terus-menerus dipajangnya tokoh besar masa lampau (pendiri negara atau tokoh bangsa) dalam kampanye adalah bukti sedikitnya tokoh yang diakui masyarakat. Parpol tidak menyebarkan gagasan tentang problem publik dan solusi kolektif kekinian. Kelangkaan gagasan politik ini menjelaskan mengapa parpol enggan beradu program dalam kampanye.
Ada paradigm shift (pergeseran cara pikir) di mana parpol lebih mementingkan kemenangan daripada kokohnya platform. Dengan logika kepraktisan, parpol memilih menguatkan “mesin” politiknya dalam masa kampanye.
Parpol tampak cekatan dalam lobi-lobi politik dan kampanye. Namun bagi para calon non-kader, parpol tidak lebih dari mesin yang bisa mengkonversi popularitas dan reputasinya menjadi suara. Artinya, parpol mana pun tidak masalah. Hal yang sama buat parpol, calon non-kader hanyalah cara praktis mengkapling “saham” untuk politik pemerintahan kelak.
Karena yang dipakai adalah pragmatisme, tidak jarang praktiknya melampaui ideologi partai. Parpol berideologi dan berplaftorm agama, enteng saja beraliansi dengan parpol non-agama atau agama lain. Pun dengan fakta bahwa terdapat 12 daerah Pilkada 2018 yang bercalon tunggal. Alih-alih jadi masalah keberanian parpol memunculkan sosok politik baru, dalam rasionalitas parpol hari ini langkah tersebut adalah pilihan yang lebih efisien.
Problem Etika
Tatanan yang terlihat hari ini menampilkan paradoks. Parpol yang semestinya mengokohkan platform justru sibuk menggaet tokoh luar, sementara politisi yang semestinya menampilkan nilai yang diyakininya, harus mau disetir arahan politik parpol pengusung.
Dari sudut pandang etika, paradoks tersebut jadi lebih problematik. Pepatah mengatakan bahwa politik adalah tangan yang kotor jika bekerja tanpa etika. Dalam The Controversy over Dirty Hands in Politics (Paul dan David, 2000) dikatakan bahwa jika politik tidak berjalan dengan etika, maka ia akan bebas menyalahi sesuatu karena semua dianggap benar. Kepraktisan dan proses politik yang serba instan mencerminkan gambaran politik tanpa etika, yang menganggap kemenangan dalam pemilihan adalah segalanya. Padahal alasan kepraktisan yang berdampak menipisnya platform parpol dan pengulangan tradisi politik minus pertanggungjawaban ini jelas merusak secara berkelanjutan.
Mutualisme kepentingan antara calon non-kader yang ingin jabatan dan parpol yang kekurangan kader bukan sebatas problem teknis. Ini adalah problem etika dalam sistem kepartaian kita. Publik tidak disuguhi pilihan selain daftar calon dengan gebyar popularitas dan kemenarikannya. Hal-hal non-substansial inilah yang disebut political gimmick—dan sayangnya hanya ini yang tersisa buat dipilih. Ketegasan, bersih korupsi, agamis, atau usia mudanya adalah contoh political gimmick yang sering dipasarkan dalam kampanye.
Agaknya, baik parpol maupun publiknya sudah saatnya belajar bahwa ujung dari politik adalah tanggungjawab. Sehingga dalam prosesnya pun perlu pertimbangan etika. Model kerja parpol akan selalu diperhatikan sebagai panutan publik. Maka, segala proses membangun popularitas dan reputasi mestinya dilalui dengan kesabaran. Jangan melulu melihat politik sekadar fase pergantian personel jabatan!
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.