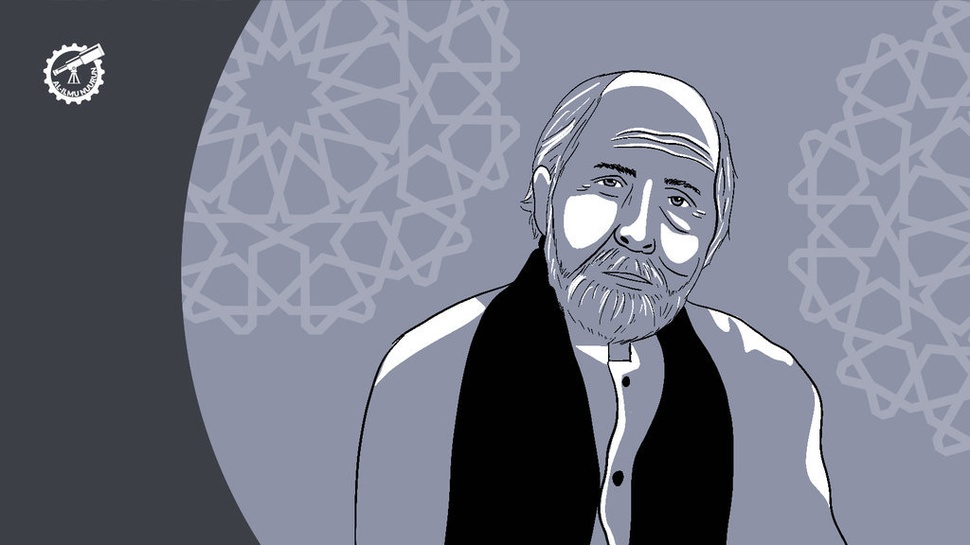tirto.id - "Ketika saya kuliah tahun kedua di Institut Teknologi Massachusset (MIT), Boston, saya mengalami krisis spiritual. Nilai fisika saya padahal yang terbaik sekelas. Guru saya punya harapan besar supaya saya menjadi fisikawan hebat di dunia. Tapi saya sadar, spiritualitas kosong. Tuhan tak hadir. Saya sembahyang, menjadi fisikawan muslim yang baik. Tapi bukan itu yang saya cari.
Akhirnya, saya memutuskan mempelajari filsafat untuk tingkat lanjut. Yang terpenting ialah rasa rendah diri (inferiority complex) saya di hadapan Barat sirna. Saya menjadi percaya diri justru di jalan pandangan dunia tradisional. Saya menelusuri bagaimana pengembaraan hidup dan pemikiran manusia, lelaki dan perempuan, selama ribuan tahun. Lalu saya belajar tradisi Hindu, Cina, Islam, dan saya menghabiskan masa muda saya di Iran belajar tradisi Arab, Persia, dan lainnya. Dan saya kembali pada perbendaharaan spiritual yang ada di dalam diri saya."
Seyyed Hossein Nasr, filsuf muslim berpengaruh dari Iran, mengungkapkan pengalaman pribadi tersebut kepada saya dalam sebuah wawancara pada 1 Desember 2018. Ia masih berkantor, meski sudah pensiun lama, di lantai atas gedung perpustakaan Universitas George Washington, Washington DC. Di kampus inilah Nasr lama berkarier di Barat, setelah pindah dari Universitas Temple, karena eksil akibat Revolusi Islam Iran 1979.
Pada 1980-1981 ia terpilih memberi rangkaian kuliah Gifford Lectures paling bergengsi di Skotlandia dengan judul "Knowledge and the Sacred". Ia adalah muslim pertama sekaligus sarjana non-Barat pertama yang menerima penghargaan itu.
Spiritualitas adalah Kunci
Penelaah filsafat Islam dari Perancis, Henri Corbin (m. 1978), pernah menjadi guru penting di lingkaran intelektual beken di Teheran. Dari artikel saya sebelumnya soal 'Abd al-Rahman Badawi, kita tahu Corbin juga membaca filsafat Heidegger di forum filsafat Alexander Koyré. Bukan kebetulan jika Badawi pernah menjadi profesor tamu di Teheran karena jaringan yang sama ini. Selain meneliti tradisi filsafat Persia, Corbin juga mentransmisikan gagasan Heidegger ke Iran pada 1950-an dan ikut meramaikan mazhab Tradisionalisme. Pada masa ini Nasr sudah mulai mengajar di Universitas Teheran saat ia masih mahasiswa doktoral.
Ketika masih menulis disertasi dalam bidang filsafat sains, ia mulai menggali banyak tradisi esoterisme Syiah dari ulama tradisional. Kehadiran Corbin ikut memperkaya apa yang ia pelajari. Selain tumbuh sebagai intelektual terpandang di Iran, karier Nasr terus melejit dan diangkat sebagai sekretaris pribadi Ratu Farah Pahlavi. Pada 1974 sang ratu menunjuk Nasr untuk mengepalai Akademi Filsafat Kerajaan Iran (Anjoman-e Shahanshahi-ye Falsafah-ye Iran) yang mengembangkan mazhab Tradisionalisme dan tempat berkumpul para filsuf muslim dan pengkaji Islam ternama. Akademi ini menjadi rujukan internasional dan tetap dipertahankan ketika revolusi bergulir karena aset material dan intelektualnya yang luar biasa.
Selain Nasr ada dua intelektual menonjol dalam sirkuit pengetahuan melalui Corbin ini. Mereka adalah Ahmad Fardid (m. 1994) dan Daryush Shayegan (m. 2018). Mereka membaca Heidegger dan filsafat Barat kendati tidak seratus persen menyetujui. Fardid lalu menjadi salah satu ideolog terkemuka semasa Republik Islam dan penemu asli istilah anti-Barat semasa Shah Reza Pahlevi yang dipopulerkan Jalal Al-e Ahmad: gharbzadegi (westoksifikasi). Sementara itu Nasr dan Shayegan memutuskan menjadi eksil.
Shayeghan, seorang filsuf yang juga penting ditelaah, keluar dari mazhab Tradisionalisme dan lalu lebih banyak mengkaji soal filsafat perbandingan Islam-Hindu. Shayegan juga pencetus gagasan filosofis soal dialog peradaban jauh sebelum Presiden Khatami mengemukakannya pada 1990-an untuk melawan wacana benturan peradaban dari Samuel Huntington. Nasr tetap berdiri teguh pada kaki Tradisionalisme dan menjadi orang penting dalam lingkaran intelektual dan imperial shah terakhir.
Tradisionalisme yang disebut di atas berakar dari filsafat perenial yang menganggap ada kebijaksanaan abadi yang bersifat primordial dan universal serta menjadi titik temu bagi semua agama besar. Setelah dikembangkan pemikir seperti René Guénon, Ananda Coomaraswamy, dan Fitjof Schuon, mazhab ini menjadi tersebar hingga abad ini yang perkembangannya terus menarik minat ilmuwan Barat. Salah satunya adalah sejarawan Inggris Mark Sedgwick.
Nasr sendiri menjadi salah satu mursyid penting dalam tarekat Maryamiyyah yang didirikan Schuon, yang visinya tampak dalam judul buku yang terkenal dalam pemikiran pluralisme Indonesia, The Transcendent Unity of Religions (1948). Nasr beberapa kali menulis Ya Maryam, 'alaiki al-salam dalam beberapa bukunya untuk membuktikan Bunda Maria (Maryam) sebagai wasilah dalam tarekat yang asalnya dari persaudaraan Shadhiliyah tersebut. Sebuah wasilah sufistik yang jarang ada.
Kata ‘tradisi’ seperti ia sering tekankan dalam wawancara lumayan panjang menjadi penting untuk dikembangkan dalam peradaban muslim modern. Yang utama, menurutnya, ialah umat Islam harus menemukan kembali diri mereka secara intelektual dan spiritual. Menemukan kembali tradisi dan warisan kebudayaan—kembali ke Al-Qur'an, hadis, perjalanan peradaban beserta mazhab filsafat dan pemikirannya—penting dilakukan untuk membangkitkan kebanggaan pada tubuh umat.
“Sering saya tekankan pada mahasiswa saya,” kata Nasr, “dulu orang Eropa Latin menerjemahkan ratusan buku dari bahasa Arab untuk belajar matematika dan astronomi sebagai seorang Katolik berbahasa Latin. Kita pernah juga mulai abad ke-19. Orang Persia atau Indonesia, misalnya, menerjemahkan Bergson atau Descartes, tapi tidak melihat dari perspektif pemikir Persia atau Indonesia.”
Apalagi ia menyebut penjajahan muncul secara intelektual bahkan hingga era pascakolonial. India-Pakistan terjajah, filsafat dan iklim pengetahuannya ikut Inggris. Aljazair ikut Perancis. Demikian halnya dengan Indonesia. Ia menambahkan, bahkan Cina yang agung juga secara intelektual masih belum bangkit. Ini yang kemudian menyebabkan modernisasi menjadi hegemoni cara pandang Barat dalam dunia muslim. Dalam penalaran Nasr, kita jangan kehilangan jati diri sebagai orang Timur juga sebagai umat beragama. Dalam hal yang kasat mata, Nasr bilang, “Polusi dan krisis lingkungan di Karachi, Teheran, dan Jakarta ini adalah polusi dari Barat, mereka mengadopsi industrialisasi Barat tanpa filter. Ini sayang sekali.”
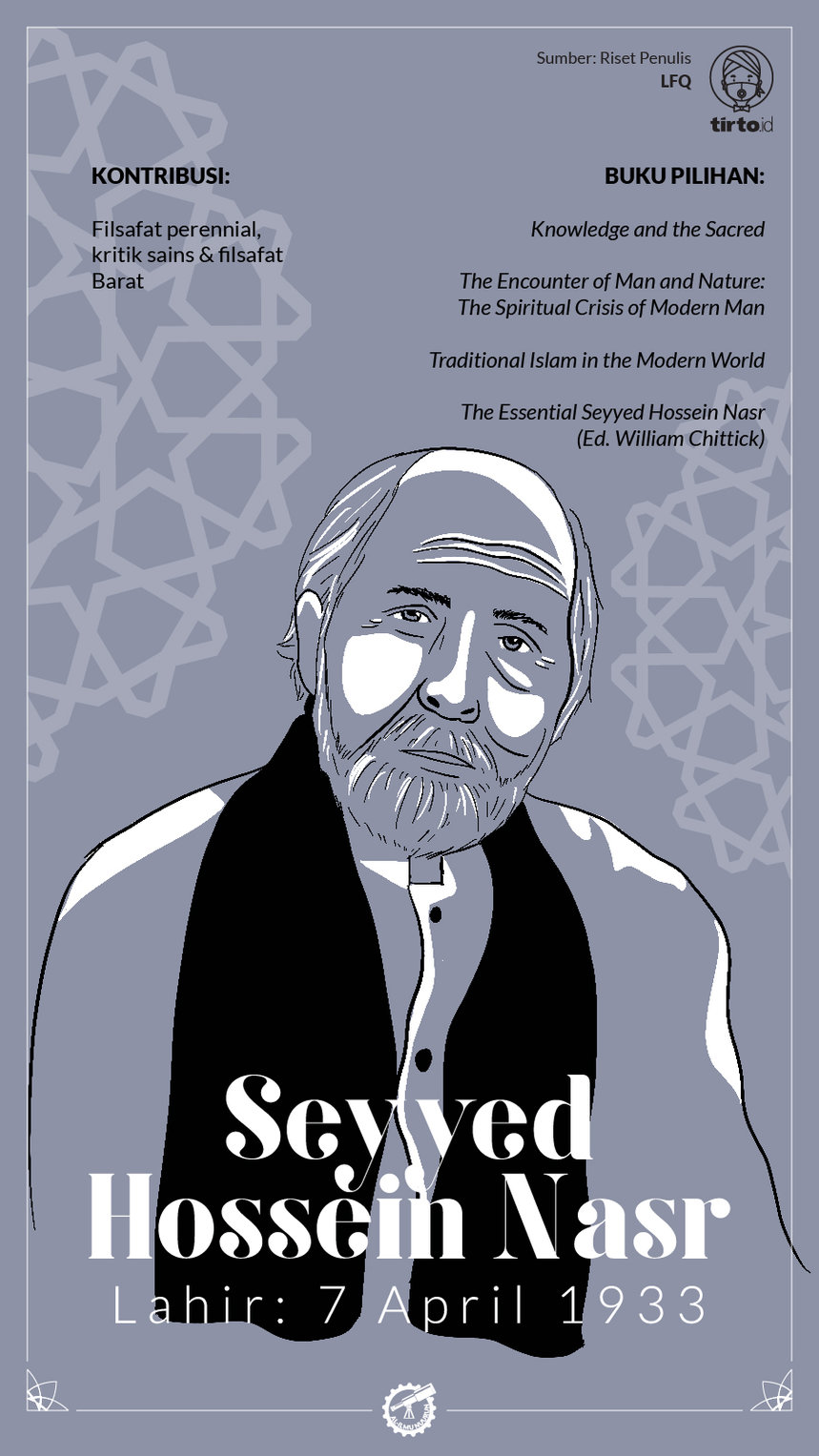
Setengah Abad Mengutuk Modernitas Barat
Ada banyak yang belajar langsung kepadanya, meskipun dari Iran tidak kelihatan. Barangkali karena pengaruh revolusi Islam yang menganggap Nasr dan lainnya sebagai orang-orang tersingkir. Di abad yang ia akui semakin sulit dan bahaya ini, khususnya karena krisis modernitas Barat yang mematikan spiritualitas, ia mengajak generasi saat itu bukan menunggu hingga dua ratus tahun. Memiliki kembali tradisi Islam tidak bisa ditawar lagi, sambil menggenggam sikap hakulyakin sebagai penawar inferiority complex.
Baginya, kebangkitan ialah sekaligus tumbuhnya mentalitas dan intelektual yang bukan dipaksakan alam pikiran modern dari Barat. Untuk menghidupkan kembali tradisi filsafat Islam, ia menyebut nama yang perlu ditiru: al-Farabi, Ibnu Sina, Suhrawardi, Mulla Sadra, Ibnu Khaldun, dan seterusnya.
Tidak berhenti di sini, Nasr memberi petunjuk guna memahami tantangan dunia modern untuk mengetahui pemikiran Barat. Menurutnya, tantangan muslim bukan datang dari Cina, tetapi dari Barat. Secara intelektual, apa yang kini ada di Cina datang dari Barat. Ini termasuk kapitalisme dan sosialisme yang basisnya materialisme. Namun, memahami ini perlu dibuka melalui cara pandang Islam, bukan dengan menyalin filsafat Barat dengan nama Pakistan atau istilah Arab.
Setelah menguasai keduanya, saran Nasr ialah mereformulasi dan membahasakan kembali filsafat Islam ke dalam bahasa terkini. Di dalamnya termasuk menyediakan jawaban untuk pertanyaan yang tidak relevan di masa lalu seperti lingkungan atau tantangan mekanika kuantum.
Nasr lalu membuat analogi. Katanya, “Anda belajar dari perspektif Anda. Anda melihatku dari sudut pandang mata anda. Anda tidak melihatku dari perspektif pintu di belakangku. Ini sama secara intelektual. Muslim harus belajar untuk melihat Barat dari perspektif Islam, bukan dari perspektif Barat. Sehingga kita tidak terbaratkan.”
Lima puluh tahun Nasr mengutuk materialisme Barat yang kini banyak diadopsi dalam modernisasi, termasuk dalam program integrasi Islam dan sains Barat yang disuarakan dunia muslim. Pada abad ke-19 ulama lebih banyak mengutuk sains dan mengenyahkannya, padahal mereka mengetahui ilmu keislaman, filsafat alam dalam Islam, dan kedalaman kosmologis yang bisa digunakan untuk mencari jawaban hakiki. Kecenderungan umumnya kini umat Islam memiliki pandangan dunia yang sangat berbeda: terlalu mekanistik dan materialistik. Integrasi Islam dan sains modern belum tentu menyelesaikan akar persolan: krisis spiritualitas.
Seperti diakuinya sendiri, jika ia tak memiliki ijazah MIT dan Harvard, kritik atas materialisme Barat yang ia lontarkan dengan berjilid-jilid buku tak akan mendapat gaung yang luas. Pemikirannya baik dalam mazhab tradisionalisme maupun bacaannya atas filsafat Islam, seni, sastra, teknologi, dan topik lainnya banyak mendapat gaung di seluruh dunia, Islam dan Barat.
Buku The Study Quran: A New Translation and Commentary (2015) yang disunting Nasr menuai pujian sebagai terbosan penting yang memadukan pelbagai tafsir metafisik spiritual, teologis, dan hukum. Perennialisme-nya menjadi payung besar, termasuk ketika ia membaca filsafat Islam—sesuatu yang tidak selalui disetujui sehimpun ilmuwan di Barat. Contohnya, penafsiran yang ia kembangkan bersama Corbin tentang mazhab filsafat Isfahan atau maktab-e falsafi-ye Esfahan, yang menyiratkan ada esensi budaya Persia dan sekelumit penjelasannya mendapat kritik baik di dalam tradisi intelektual Syiah sendiri maupun orientalisme Barat.
Muridnya banyak tersebar. Kita hitung beberapa. Di Turki, murid didiknya langsung, İbrahim Kalın, ialah seorang filsuf yang menjadi jubir dan penasihat khusus Presiden Erdoğan. Di Indonesia, yang paling kentara, ada Mulyadhi Kartanegara dan forum filsafat di Paramadina yang diampu Budhy Munawar Rahman serta lingkaran studi Syiah. Juga ada pula Wahyuddin Halim, seorang sarjana-pemikir yang penting di Makassar. Kita tidak tahu seberapa kuat jaringan tarekat Maryamiyyah-nya.
==========
Redaksi Tirto kembali menampilkan rubrik khusus Ramadan "Al-Ilmu Nuurun". Tema tahun ini adalah para cendekiawan muslim global abad ke-20 dan ke-21. Kami memilih 33 tokoh untuk diulas pemikiran dan kontribusi mereka terhadap peradaban Islam kontemporer. Rubrik ini diampu kontributor Zacky Khairul Umam selama satu bulan penuh.
Zacky Khairul Umam adalah alumnus Program Studi Arab FIB UI dan kandidat doktor sejarah Islam di Freie Universität Berlin. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Islam di Madinah abad ke-17. Ia pernah bekerja sebagai peneliti tamu pada École française d'Extrême-Orient (EFEO) Jakarta 2019-2020.
Editor: Ivan Aulia Ahsan