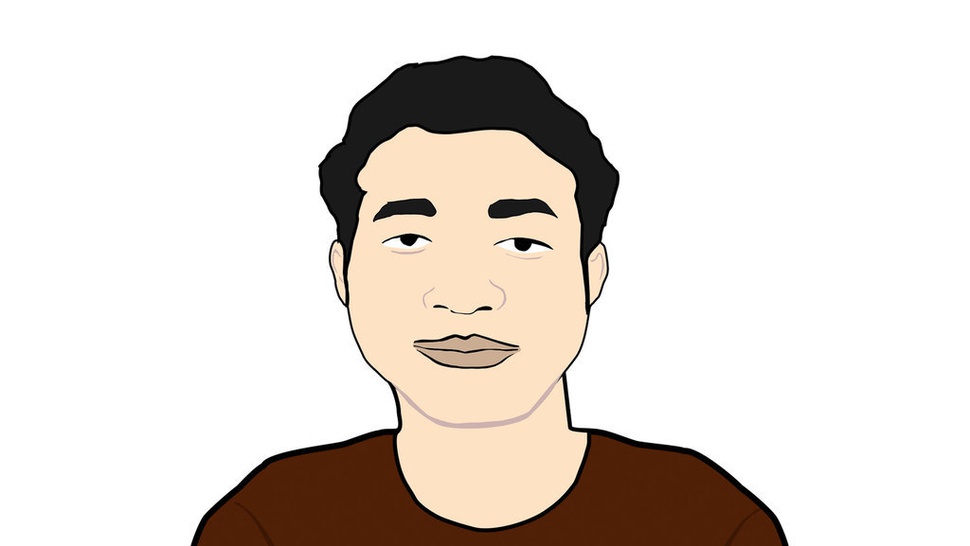tirto.id - Per 1 Juli, Bank Dunia resmi mengumumkan status Indonesia di kategori berpendapatan menengah-atas. Walaupun ada keterangan Bank Dunia dalam dokumennya (“… do not yet reflect the impact of COVID-19”) atau belum mencakup dampak krisis akibat pandemi, status ini cukup memberi angin positif bagi Indonesia.
Naik kelasnya status bisa diartikan laju perekonomian yang telah diakui. Kini Indonesia dihadapkan pada tantangan daya saing. Gengsi yang didapat dari status baru, lazim berpotensi memperkecil akses fasilitas afirmatif (penguatan). Negara menengah-atas diyakini telah mampu bersaing lebih kompetitif.
Middle Income Trap
Gross National Income (GNI) Indonesia naik dari 3.840 USD (2018) menjadi USD 4.050 per kapita (2019). Tetapi, yang belum banyak dipahami adalah GNI Indonesia masih jauh di bawah rata-rata GNI negara-negara di kelasnya (upper-middle), yaitu USD 9.074. Bahkan, masih di bawah rata-rata negara di bawahnya (middle income), yaitu USD 5.598.
Memang, ada keuntungan-keuntungan status baru. Kesan positif ketahanan ekonomi akan berimbas potensi investasi. Jika dibarengi intervensi struktural, kesan positif berpeluang menemukan momentum dorongan daya saing di tingkat global.
Sayangnya, status baru bisa mejadi pedang bermata dua kalau hanya mandek terpukau gengsi. Kategorisasi upper-middle tak jarang berimplikasi hambatan akses fasilitas-fasilitas lama, seperti kesepakatan dagang (bea masuk produk atau pembiayaan ekspor-impor) dan keringanan bunga pinjaman. Maka, sudah saatnya pemerintah punya rumusan visioner membenahi struktur ekonomi Indonesia.
Keunggulan daya saing antarnegara punya sekian variasi yang tercakup dalam keunggulan teknologi, modal, alam, dan pasar. Keunggulan teknologi dan modal biasanya dimiliki negara-negara maju (high income country) dengan telah lamanya mereka menguasai keduanya. Sedangkan bagi kebanyakan negara berpenghasilan menengah (middle income country), sumber daya alam dan pasar adalah keunggulan yang mampu dijual sebagai “daya saing”.
Jebakan pendapatan menengah (middle income trap) pun menjadi momok banyak negara seiring harapan besar membenahi industrinya. Brazil dan Afrika Selatan adalah contoh yang sering dilihat. Setelah beberapa dekade, mereka masih kesulitan mentransformasi sistem ekonominya. Industri padat karya berupah murahnya tak kunjung berkembang menuju model industri modern.
GNI per kapita Brazil anjlok dari USD 12.790 (2013), menjadi USD 8.700 (2017). Sementara GNI Afrika Selatan dari USD 7.570 (2012) menjadi USD 5.410 (2017). Lemahnya transformasi, variasi, dan reaplikasi adalah fenomena kegagalan industri banyak negara (Amsden dan Chang, 2003). Akibatnya, banyak tenaga terampil diimpor dari luar. Pembangunan tidak merata pun membuat maraknya urbanisasi yang memperparah ketimpangan daerah. Ketidaksiapan menata industrialisasi mengakibatkan negara hanya jadi lokasi pasar global, bukan produksi.
Berubahnya status Indonesia akan lebih baik dilihat sebagai momentum milestone arah perekonomian. Ketika muncul sekian tantangan seiring status baru, maka inilah saatnya mempersiapkan industrialisasi yang serius.
Melompat Perlu Fokus
Melihat ke depan, keunggulan tenaga kerja murah di Indonesia jelas akan tersaingi negara menengah-bawah. Sementara untuk bersaing dengan negara maju, Indonesia masih harus memperbaiki prasyarat industrialisasinya terlebih dulu, alih-alih mengungguli aspek teknologi dan modal.
Pengalaman India dengan GNI per kapita USD 2.130 (lower-middle income country) mampu membuktikan sebagai salah satu negara yang disegani dalam perekonomiannya. Sejak 2014, India menjadi “world’s fastest growing major economy” dengan menggabungkan dua strategi: investasi untuk menyerap tenaga kerja, dan daya saing sektor jasa. Tenaga kerja diserap pada agrikultur, manufaktur, dan konstruksi yang dipercepat dengan responsivitas mendatangkan investasi. Sedangkan, sektor layanan (jasa) berbasis teknologi informasi dipilih India sebagai keunggulan daya saingnya.
Sebagaimana ambisi India terhadap layanan teknologi informasi, China mengekspansi perekonomian lewat produk pabrikannya. Lebih dari 40 persen pendapatan domestik berasal dari perindustrian, memanfaatkan berlimpahnya tenaga kerja.
Ada kesamaan pola yang diterapkan India dan China menggeber industrialisasi nasional. Pertama, pemanfaatan kondisi yang ada (existing condition). Besarnya jumlah penduduk disulap jadi tenaga kerja terampil. Sedangkan sektor agrikulturnya diintegrasi dan dimodernisasi. Kedua, fokus penguatan sektor strategis yang berdampak multiplier. Kini sulit menyaingi murahnya layanan teknologi India dan produk pabrikan China.
Lantas bagaimana Indonesia menjajaki tantangan ini ke depan? Sebagai negara berpopulasi terbesar keempat, Indonesia jelas punya potensi menjadi salah satu major economycountry. Menjajaki milestone perubahan, pekerjaan rumah terbesar kini adalah bagaimana 'menyulap' existing condition nasional dalam desain visi jangka panjang.
Pertama, menghadirkan investasi yang selaras visi nasional adalah enabler perekonomian yang penting. Prinsipnya, investasi harus bisa mendongkrak penyerapan tenaga kerja dan transfer pengetahuan.
Hal yang mesti dicatat adalah proteksi pada sumber ekstraktif (tambang, laut, hutan, dan sejenisnya), terutama yang tanpa proses nilai tambah di dalam negeri. Berbagai negara maju pun menerapkan kebijakan proteksionisme pada sektor alamnya. Tantangan daya saing selalu ada pada kreativitas “menciptakan produk”, bukan “menjual isi rumah”.
Kedua, memenuhi prasyarat industrialisasi. Dalam konteks Indonesia, masih dibutuhkan pembenahan pendidikan untuk mentransformasi penduduknya menjadi tenaga kerja terampil. Hal ini bisa dijembatani dengan menyeriusi kembali kebijakan vokasi yang sejak tahun lalu sudah direncanakan sebagai program prioritas nasional.
Selain soal SDM, memperkuat konektivitas antarwilayah adalah hal yang tidak bisa ditawar mengingat karakteristik kewilayahan Indonesia. Ketimpangan daerah dan akumulasi modal selalu akan jadi problem klasik ketika bicara struktur perekonomian nasional.
Terakhir, langkah di atas (investasi sekaligus penyiapan prasyarat industri) tidak akan menemukan tujuannya tanpa penentuan arah keunggulan daya saing nasional. Dalam banyak kesempatan, Presiden Joko Widodo menyebut pariwisata sebagai keunggulan komparatif Indonesia. Seandainya memang itu yang dijadikan fokus, maka perlu ada penyesuaian pada struktur kebijakan nasional hingga daerah yang membuat wisata Indonesia bisa mendatangkan devisa; bukan hanya dibuat untuk wisatawan domestik. Demikian juga dengan dukungan kepada para pelaku usaha (korporasi dan UMKM) serta perusahaan negara di sektor terkait.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.