tirto.id - Membahas David Bowie tentu tak bisa dilepaskan dari kiprah album-albumnya. Memilih album mana yang paling bagus dan bernilai merupakan perkara sulit jika tak ingin dikata mustahil. Alasannya sederhana: Bowie tidak pernah membuat album jelek.
Tiap album Bowie menyimpan karakter tersendiri yang menggambarkan betapa atraktifnya ia sebagai seorang musisi. Bowie selalu menemukan jalan baru saat hendak membuat album. Kendati begitu, terdapat album yang menjadi momentum bagaimana perjalanan musik—dan hidup—Bowie berubah, yakni Berlin Trilogy.
Cerita bermula pada 1976 saat album Stasion to Stasion miliknya rilis ke pasaran. Album tersebut banyak dipuji sebab selain mampu meneruskan capaian The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972) dan Aladdin Sane (1973), juga berhasil meninggalkan konstruksi musikalitas bagi generasi Britpop beberapa dekade setelahnya yang digawangi Morrissey dan kroco-kroconya.
Kesuksesan memang diraih Bowie, tapi harus dicatat pula, ketika album Stasion to Stasion keluar, kehidupannya berantakan. Ketergantungannya terhadap kokain mencapai fase tertinggi, kondisi psikologisnya kacau dan berada di titik nadir, serta ia menjadi headline pemberitaan media-media lokal karena dianggap pro-fasis. Di balik segala hiruk pikuk popularitas dan jebret kamera juru warta, Bowie sebetulnya sedang mengalami kehancuran mental yang luar biasa.
Guna menyingkirkan segala prahara dalam dirinya, ia memutuskan pindah ke Berlin. Dibantu asisten pribadinya, Coco Schwab, Bowie menemukan apartemen di kawasan Berlin Schoneberg yang rindang. Suasana Berlin kala itu tidak sama seperti sekarang. Sisa-sisa kekalahan Jerman pada Perang Dunia II masih terasa; gedung-gedung rusak hingga kesepian menjalar di penjuru kawasan karena setengah populasi kota melarikan diri dari agresi lawan. Ditambah, Berlin terbagi jadi dua kekuasaan; Barat dan Timur.
The Guardian menyatakan, Bowie mendapati dirinya berada di sebuah kota yang mirip dengan keadaannya; panik, hancur, serta dihantui masa lalu dan masa kini. Di kota yang dulunya satu, bintang pop terbesar mencoba “memisahkan rintangan buatannya sendiri.”
Masa-masa awal ia tinggal di Berlin tidak berjalan mulus. Bowie masih suka berkeliling kota tak jelas, mabuk di klub setempat, dan terjaga semalam suntuk. Pernah suatu waktu, ia mengendari mobil bersama kawannya, Iggy Pop, di parkiran hotel. Mobil ia kendarai dengan kecepatan 70 mil per jam sembari berteriak ingin mengakhiri semuanya sampai bensin dalam mobil habis.
Untungnya Bowie memiliki Coco yang setia menemani dirinya berproses di Berlin. Coco, seperti diceritakan The Guardian, melakukan sejumlah cara untuk membantu Bowie ‘sembuh’ seperti dengan mengajak Bowie mengunjungi Museum Brucke guna melihat karya pelukis macam Ernst Ludwig Kirchner, Kathe Kollwitz, dan Erich Heckel sampai membacakan naskah-naskah filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche. Tujuannya Coco melakukan itu cuma satu: menangkap perasaan fana dalam imajinasi Bowie dan membuatnya lebih realistis.
Seiring waktu, pikiran dan hidup Bowie mulai tertata. Ia perlahan mampu menghilangkan ketergantungan kokain, menemukan jalan keluar atas kehidupannya yang berlebihan, dan menjadikan dirinya sebagai “orang biasa.” Bowie, di saat bersamaan, sadar bahwa tujuannya ke Berlin bukan hanya menenangkan pikiran atau memperoleh cara baru dalam membuat musik, melainkan juga kembali ke pribadinya sendiri.
Bowie lalu mengambil keputusan besar dalam karirnya: ia tak perlu lagi karakter alter-ego macam Ziggy Stardust untuk menyanyikan sebuah lagu. Ia lantas membuang semua alat peraga, kostum, dan pelbagai set panggung yang selama ini jadi ciri khas maupun daya tariknya. Sebagai gantinya, Bowie memilih mengenakan kemeja biasa dan celana longgar.
Di tengah fase hidupnya yang baru itu, Bowie mulai menikmati perjalanan di Berlin. Jauh dari perhatian dan keramaian, ia mengisi waktu dengan melukis, membaca, dan membuat beberapa fondasi musik baru. Untuk pertama kali dalam beberapa tahun, Bowie merasakan “kegembiraan hidup serta penyembuhan yang hebat.”
Baca juga:Bagaimana Rezim Konservatif di Inggris Melahirkan Musik Shoegaze?
Musim panas 1977 menjadi titik balik Bowie. Ia kembali berkarya dengan menggandeng kawan karibnya, Tony Viscoti dan Brian Eno. Album yang dibuat berjudul Low—bagian pertama dari Berlin Trilogy. Menurut Uncut, Low merupakan kepanjangan tangan dari Station to Station tapi lebih terdengar sembrono, yang berkisah tentang isolasinya di Berlin hingga bagaimana ia tampil perdana tanpa embel-embel karakter Ziggy Stardust.
Lewat Low, Bowie ingin menyampaikan emosi yang sudah dibangunnya melalui bahasa dan suara. Ada sedikit rapalan harap yang digaungkan Bowie kepada pendengar agar, setidaknya sekali lagi, memberikan kepercayaan kepadanya selepas serangkaian momentum buruk di masa-masa awal karir. Terpenting, album Low adalah cara Bowie menunjukkan pada dunia bahwa riwayatnya belum tamat.
Sembilan bulan usai Low rilis, Bowie kembali menelurkan album, Heroes. Keseluruhan materi album ini dibuat di studio yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari Tembok Berlin, dengan sekali proses perekaman. Walaupun begitu, Heroes memperlihatkan bakat dan sinar Bowie sebagai penulis lagu yang visioner.
Salah satu buktinya adalah balada “Heroes.” Lagu tersebut berangkat dari gambaran sederhana: Bowie melihat Viscoti memeluk seorang perempuan di luar studio. Dari situ, Bowie kemudian mengubahnya menjadi kisah yang lebih universal; tentang bagaimana Tembok Berlin memisahkan dua orang kekasih. Satu di Jerman Barat, satu di Jerman Timur.
Coba simak saja liriknya: “I, I will be king/And you, you will be queen/Though nothing will drive them away/ We can beat them, just for one day/We can be Heroes, just for one day.” Seketika, “Heroes” menjadi anthem untuk masyarakat Jerman baik yang berada di Barat maupun di Timur. Bowie dianggap pahlawan mereka sebab mampu menyalurkan emosi dalam kata-kata, lewat permadani nada yang syahdu dan menggugah perasaan, serta memberikan kekuatan cita tentang keinginan untuk meleburkan tembok pemisah.
Dua album sudah dibuat selama masa pengasingannya. Saat itu pula ia mulai mendapatkan kembali hidupnya dengan entitas yang baru. Tapi, Bowie tak ingin berhenti begitu saja. Usai melangsungkan tur dunia pada 1978, ia bersama Eno dan Viscoti kembali membuat album untuk melengkapi kepingan terakhir Berlin Trilogy. Maka jadilah, album bertajuk Lodger.Lodger direkam di Montreaux, Kanada dan diselesaikan di New York pada Maret 1979. Secara musikalitas, banyak yang berpendapat Lodger belum bisa menyamai Low atau Heroes. Apabila dua album sebelumnya sarat emosi, di Lodger, hal itu nyaris tidak nampak dan tergantikan oleh eksplorasi Bowie, Viscoty, maupun Eno terhadap eksperimen-eksperimen nada. MTV mencatat bahwa Lodger terdengar letih dan satu-satunya yang kemenangan dalam album ini ialah kembalinya ambisi seorang David Bowie.
Rilisnya Lodger turut menandai berakhirnya terapi Bowie di Berlin. Los Angeles Times dalam sebuah artikel pernah menuliskan, album Bowie dalam Berlin Trilogy berhasil membangkitkan semacam brutalisme kota yang diukur lewat irama dan ruang-ruang kosong. Bowie, seperti yang dikatakan Los Angeles Times, telah menyulut emosi menakutkan dengan eksperimen mesin synthesizer, melodi vokal melankolis, serta lirik-lirik sedih tentang hubungan yang dipisahkan beton tembok bangunan.
Dari Berlin, Ia melanjutkan perjalanan dan kali ini, New York menjadi tujuannya. Di sana, Bowie memulai lembaran baru dalam karir musiknya. Ia masuk ke ranah art-rock dengan merekam materi bersama John Cale (The Velvet Underground) dan Jimmy Destri (Blondie) serta menghadiri pementasan band-band banal semacam The Clash hingga Talking Heads. Tak sebatas itu saja, Bowie juga masuk ke lanskap post-punk yang dibuktikannya lewat kehadiran album Scary Monsters (and Super Creeps) (1980).
Bagaimanapun, kota Berlin tidak bisa dipungkiri menjadi momen penting dalam perjalanan hidup Bowie. Ia mengemukakan, kota tersebut dan triloginya merupakan nostalgia yang berhasil membentuk karakter Bowie seperti saat ini. Berlin Trilogy adalah obat kimia yang membantu Bowie bangkit dari keterpurukan.
“Saya tidak bermaksud meninggalkan Berlin, saya hanya hanyut pergi,” kata Bowie. “Mungkin saya membaik saat ini. Itu [Berlin] merupakan pengalaman yang tak tergantikan dan tidak dapat dilupakan. Dan mungkin saat paling membahagiakan dalam hidup saya. Saya punya banyak waktu hebat di sana dan saya tidak bisa mengungkapkan perasaan akan kebebasan yang saya rasakan di sana.”
Rasanya bosan jika harus mengatakan David Bowie merupakan salah satu musisi besar yang pernah dilahirkan dunia. Karisma, pesona, dan bagaimana ia melewati zaman dengan caranya sendiri adalah beberapa alasan mengapa ia pantas memperoleh predikat tersebut.
Baca juga:Gito Rollies, Rocker Eksentrik yang Ciamik
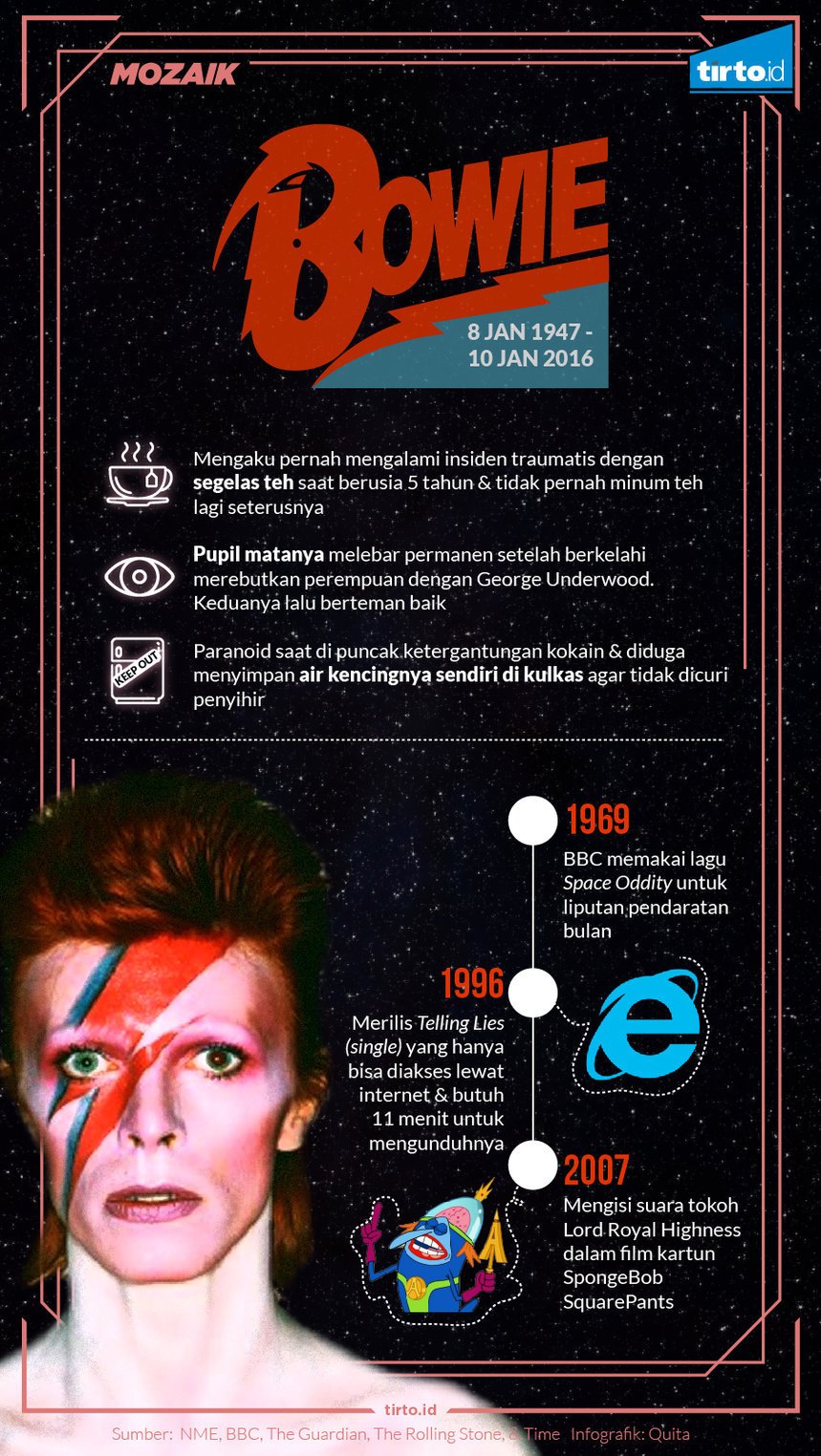
Bowie, seperti kita ketahui, memang tak punya karakter tetap. Ia tidak seperti Bob Dylan yang dikenal publik sebagai pahlawan folk Amerika dan senantiasa berpegang teguh pada jalur itu. Ia juga bukan Elvis Presley, yang konsisten bergoyang di lantai panggung dengan rambut jambul maupun pakaian necisnya. Bowie, seperti yang kita tahu, hampir tidak punya gaya baku sepanjang karir musiknya.
Secara musikalitas dan proses kreatif, ia terus berubah, bergulir, dan menggelinding mengikuti perkembangan zaman. Di awal karirnya, ia mungkin berdiri tegak pada mimbar pop dan mengubah keseluruhan lanskap musik pop ke titik yang belum pernah dicapai sebelumnya. Musik pop, tak lagi terdengar sama, semenjak Bowie menginjakkan kaki di studio dan membuat mahakarya The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
Tapi, pop bukan tujuan utama Bowie. Ia menolak tunduk pada garis musisi yang senantiasa dihormati. Ia secara sukarela, pindah dari satu layar ke layar lainnya. Ia secara sukacita, terjun dari satu samudera ke samudera lainnya untuk melihat seberapa jauh ia bakal bertahan. Bowie menolak batasan yang ada. Ia lebih suka mengubur satu warna musik dan membuat yang baru dibanding musti bertahan dengan warna sama sepanjang tahun hingga akhir hayatnya.
Alex Petridis dalam tulisan panjangnya tentang Bowie yang dipublikasikan The Guardian mengatakan, Bowie membuat sederet album yang diterima dengan begitu baik oleh dunia. Kekuatan album-album Bowie terletak pada musiknya yang tidak pernah berkubang dalam nostalgia, semacam ikonoklastik yang berlawanan dengan masa lalu. Album Bowie, tambah Petredis, mereferensi masa lalu untuk masa sekarang dan masa depan.
Sementara secara gaya dan penampilan, Bowie adalah rajanya. Setiap babak musik yang ia presentasikan lewat album-albumnya, selalu ditandai dengan perubahan karakter. Ia pernah melebur bersama alter-ego bernama Ziggy Stardust yang tersohor itu dan ia juga pernah menyatu dengan tokoh beridentitas Thin White Duke. Setiap karakter memiliki sisi emosional tersendiri yang, sayangnya, hanya dipahami Bowie seorang.
“Saya selalu memiliki kebutuhan yang menjijikan untuk menjadi sesuatu yang lebih dari manusia,” ungkapnya tentang karya-karyanya. “Saya pikir, ‘Fuck. Saya ingin jadi manusia super.’”
Kita semua tahu, tanpa adanya keinginan menjadi manusia super, Bowie sudah menjadi manusia super sejak pertama kali kemunculannya. Hari ini, tepat setahun kematiannya, kita diingatkan bahwa anggapan itu benar adanya.
Penulis: M Faisal
Editor: Ivan Aulia Ahsan











