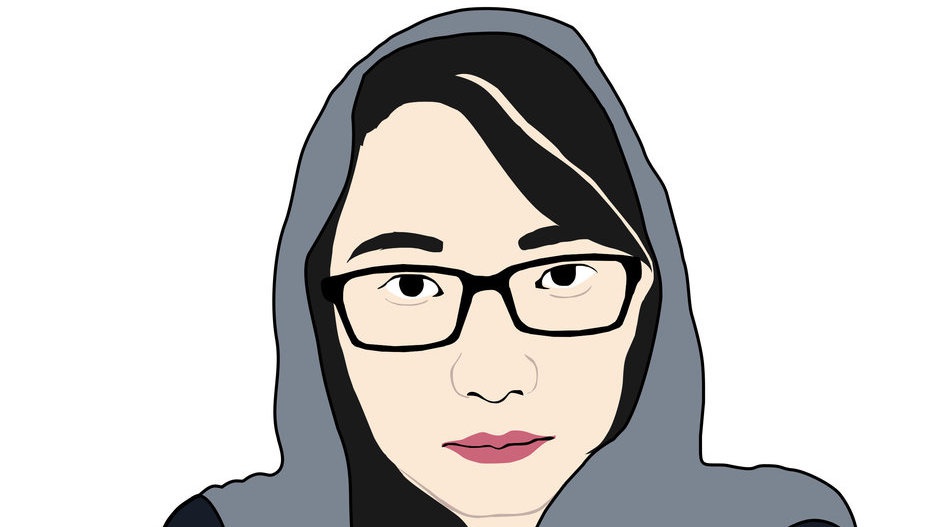tirto.id - Pekan lalu, tersebar sebuah video pawai 17 Agustusan yang menggambarkan anak-anak pra-sekolah bercadar dan menenteng alat peraga bedil. Karena kostum anak-anak itu dikaitkan dengan ISIS/Negara Islam dan kelompok-kelompok ekstremis lain, warganet sontak riuh berkomentar. Ada yang menyinggung peran orangtua, tak sedikit pula yang bertanya-tanya tentang TK yang mendidik anak-anak ini.
Baru diketahui kemudian bahwa anak-anak ini bersekolah di TK Kartika V-69 milik Kodim Probolinggo. Otoritas TK Kartika telah meminta maaf atas kostum pawai tersebut.
Saya pun teringat komentar para aktivis usai rentetan aksi teror yang menyasar Mako Brimob, Surabaya, dan Sidoarjo. Dikutip dari Tirto, Koordinator Komisi Orang Hilang dan korban Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mengatakan bahwa "melawan terorisme dengan gagasan" lebih mendesak daripada revisi UU Antiterorisme, sebab pelajar bisa dibentuk menjadi karakter inklusif, pluralis, dan toleran.
Tak hanya aktivis, sikap yang sama ditunjukkan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher. Ia mendesak pemerintah mempercepat deradikalisasi melalui kurikulum terpadu di institusi pendidikan.
Saya hanya tertawa membaca komentar-komentar itu.
Berbeda dari pendidikan dasar sejak SD, tidak ada kurikulum baku di tingkat PAUD. Jika anak-anak itu memakai kostum mirip ISIS, akar masalahnya memang bukan kurikulum, melainkan satu mata rantai vital dalam sistem pendidikan kita: kapasitas guru.
Reaksi Latah
Pada 2016, seorang kawan yang bekerja di sebuah lembaga penggiat HAM bertanya soal ujian yang saya buat. Sebelumnya, saya memang menyusun empat buah soal ujian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan-pertanyaan di dalamnya mewajibkan siswa menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM, kapitalisme, konsep Bela Negara, syariat Islam dan kerukunan umat beragama, serta apatisme politik publik.
Daftar pertanyaan itu sempat viral di media sosial, sampai-sampai Anies Baswedan—waktu itu masih menjabat Menteri Pendidikan—mengundang saya untuk bertemu saat beliau berkunjung ke Aceh.
Kawan saya pun bingung: bagaimana mungkin saya memberikan pertanyaan yang menghendaki siswa menganalisis persoalan HAM, sedangkan selama ini para aktivis HAM malah kesulitan untuk sekedar melakukan advokasi kurikulum di sekolah agar memuat konten seputar HAM?
Gantian kening saya yang berkerut. Pasalnya, kurikulum yang memuat pengajaran (dan analisis) HAM sudah ada sejak Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004. Saya membayangkan, jika waktu 14 tahun itu digunakan sebaik-baiknya oleh para aktivis HAM untuk membantu meningkatkan kapasitas guru sesuai tuntutan kurikulum dan membuat mereka lebih paham akan konsep dan praktik pelaksanaan HAM.
Lagi-lagi, reaksi latah ini bukan kali yang pertama. Tak sedikit teman-teman aktivis lain yang menyatakan kurikulum pendidikan dasar kita semestinya mengajarkan keragaman budaya dan kesetaraan.
Ketika saya sudah lelah mengajarkan itu semua, ironisnya, kawan-kawan saya ini baru berimajinasi. Yang lebih miris, bahkan orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan pun tak paham.
Sistem pendidikan kita kadang memang selucu ini.
Dan persis tahun 2018, saya harus mendengar kabar bahwa para aktivis penggiat HAM dan anggota DPR mendesak upaya percepatan deradikalisasi melalui kurikulum. Apa maksudnya?
Terlambat 14 Tahun
Kurikulum kita sebenarnya sudah maju pesat pasca-Reformasi, khususnya sejak Kurikulum Berbasis Kompetensi 2014 diterapkan di bidang kajian sosial dan pendidikan kewarganegaraan.
Pada era Orde Baru, pendidikan kewarganegaraan formal di taraf perguruan tinggi hanya mengajarkan hafalan P4 dan gotong royong. Sementara kini anak SMP dan SMA sudah belajar konsep, praktik, dan analisis menyangkut sistem politik dan pemerintahan, sistem hukum, sistem sosial, hingga hubungan internasional. Muatan HAM dan Kesetaraan dalam kurikulum KBK 2004 bahkan sudah menjadi perspektif dalam pembelajaran ilmu sosial dan kewarganegaraan.
Kurikulum 2013 (K13) bahkan lebih maju lagi. Jika KBK hanya menitikberatkan pada kapasitas Kognitif (pengetahuan), Kompetensi pada K13 memuat aspek Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap (Sosial dan Spiritual) di semua Mata Pelajaran. Pembelajaran dianggap berhasil jika peserta didik mampu memenuhi standar minimal dari Kompetensi yang ditetapkan dalam semua aspek.
Kompetensi Dasar tentang HAM bahkan sudah termuat di kurikulum SMP, dan khusus di SMA sejak jenjang kelas 1, 2 sampai kelas 3, dengan tingkat muatan dari konsep dasar hingga analisis Hubungan Internasional.
Kurikulum tentang Kesetaraan dalam Masyarakat Multikultur juga tercakup dalam kurikulum 2013 (dan ini sudah 2018!) pada pelajaran Sosiologi, bahkan dipelajari selama setengah semester.
Namun, yang lebih maju lagi, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang berisikan Sikap Spiritual dan Sikap Sosial yang salah satu penekanannya pada penghayatan dan penerapan Toleransi, terintegrasi di semua pelajaran bahkan di setiap bab materi ajar.
Sekali lagi: di semua bab di semua mata pelajaran.
Pada mata pelajaran Agama Islam, dicantumkan pada lembaran Kebijakan Kurikulum bahwa Kompetensi, materi, dan pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dikembangkan melalui pertimbangan kepentingan hidup bersama secara damai dan harmonis. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti secara umum dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam rahmatanlil’alamin, mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang humanis, toleran, demokratis, dan multikultural.
Konsep dan metode pembelajaran sendiri sudah dirancang sekontekstual mungkin. Terutama dalam Kurikulum 2013 (K13) yang mengharuskan para guru menggunakan pendekatan pembelajaran yang Saintifik dengan metode Penilaian Otentik, dengan tingkat kemampuan maksimal untuk analisis dan praktik.
Pada mata pelajaran PPKN dan Sosiologi, sudah bertahun-tahun saya mengajak siswa melakukan analisa media, studi kasus, observasi lapangan, diskusi dan debat tentang isu-isu krusial dalam masyarakat. Siswa-siswa saya bahkan sudah menulis artikel tentang keberagaman yang dimuat di media massa sebagai bagian dari penugasan sejak beberapa tahun lalu.
Tuntutan kurikulum memang tidak ringan. Kini guru memiliki otoritas (dan mestinya berani membuat terobosan) untuk mendesain aktivitas pembelajaran sesuai kapasitas peserta didik dan kebutuhan masyarakat.
Peran Aktivis
Jadi, pembicaraan tentang kurikulum toleransi di sekolah sekadar buang-buang waktu, karena pangkal permasalahannya ada di kapasitas guru.
Kurikulum adalah teks mati. Ia hanya berlaku di atas kertas, dan hanya jadi sampah jika tak dihidupkan dalam mental birokrat sekolah dan guru.
Tapi, apa sih yang diharapkan dari kecakapan guru yang hanya diajari tentang administrasi pendidikan selama pelatihan? Guru-guru Indonesia bahkan tak dibekali kapasitas untuk menguji pengetahuannya sendiri melalui basis ilmu logika dan epistemologi.
Kita dan para guru meyakini bahwa seluruh pengetahuan yang kita miliki adalah benar dan final. Masalahnya, jangan-jangan pengetahuan yang selama ini dimiliki para guru tak lebih dari sekadar doktrin, dogma, dan pengetahuan-pengetahuan yang tak bisa diuji dengan nalar. Sialnya, mereka menelan informasi bulat-bulat lalu mencekokinya ke peserta didik.
Jika memang serius, “kakak-kakak” aktivis mestinya bisa mendesain sebuah program yang mampu memengaruhi sistem pendidikan formal agar guru-guru memiliki pengetahuan yang benar tentang toleransi dan punya kapasitas intelektual untuk menganalisis permasalahan-permasalahan penting di dalam masyarakat.
Toh, kita semua tahu jika pendidikan sejak PAUD hingga universitas adalah basis produksi pengetahuan yang paling berpengaruh bagi masyarakat. Tak usahlah bicara perubahan sosial (apa lagi revolusi) kalau tidak punya niat serius memengaruhi kesadaran massa.
Tak usah puas diri dengan membangun sekolah-sekolah alternatif berkapasitas 30-100 orang—apalagi jika sekolah itu hanya diikuti (keluarga) lingkaran aktivis.
Saya jadi ingat omongan seorang teman: “Jangan seperti orang yang azan di tengah sawah: azan sendiri, dengar sendiri, salat sendiri, puas juga sendiri.”
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.