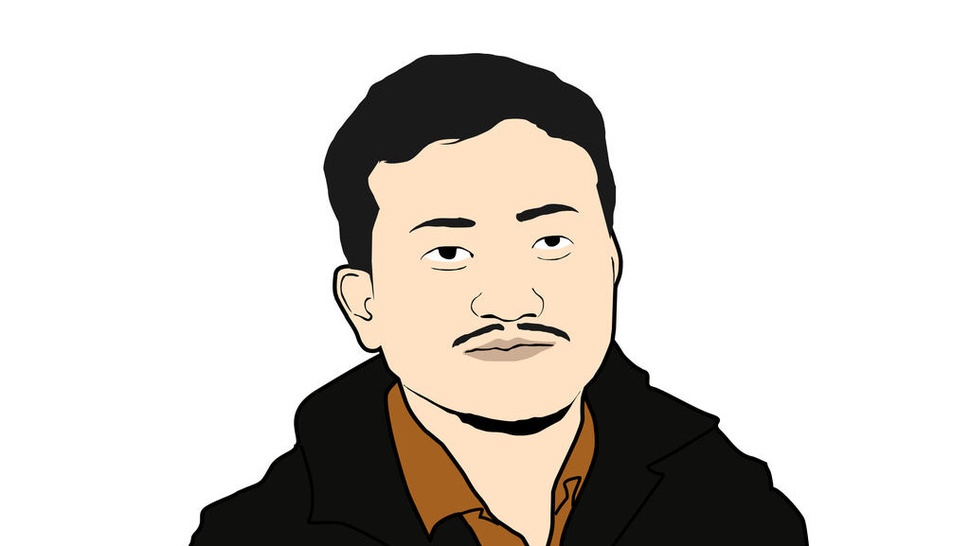tirto.id - Hampir tiap jelang tutup tahun, media sosial di Indonesia diramaikan oleh satu pertanyaan isu: bolehkan orang Islam mengucapkan “selamat Natal”?
Perselisihan di linimasa umumnya terbagi dalam dua kubu dengan posisi yang cukup gamblang. Orang-orang yang menentang pengucapan Selamat Natal akan menyebarkan fatwa-fatwa ulama yang melarang ucapan selamat Natal. Sebaliknya, kelompok yang berseberangan akan mengajukan fatwa tandingan dari ulama lain yang membolehkan praktik tersebut karena dianggap bagian dari toleransi beragama.
Polemik ini cukup sering berulang dalam beberapa tahun terakhir, sampai banyak orang lupa sejak kapan sebetulnya masalah ucapan Natal jadi sedemikian penting di ruang publik kita.
Keriuhan soal sikap muslim terhadap Natal bukanlah persoalan baru di negara ini. Isu ini pertama kali mencuat pada 1974. Ketika itu, yang menjadi persoalan bukan spesifik masalah pengucapan Selamat Natal, tapi partisipasi orang Islam dalam perayaan hari besar umat Kristen tersebut.
Dalam Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order (2006, PDF), Mujiburrahman menemukan perdebatan ini diawali dari pertanyaan pendengar radio pada Buya HAMKA di RRI. Pertanyaannya sederhana: “Apa yang harus dilakukan muslim ketika mendapatkan undangan perayaan Natal oleh tetangga Kristiani mereka?”
Jawaban HAMKA kemudian disampaikan dalam tulisan yang dimuat majalah Panji Masyarakat. HAMKA menyampaikan ucapan Selamat Natal oleh seorang muslim kepada tetangganya yang beragama Kristen dapat diterima sebagai ekspresi toleransi beragama. Namun, seorang muslim tidak boleh berpartisipasi dalam perayaan Natal karena dikhawatirkan dapat merusak akidahnya.
Ketika HAMKA mengeluarkan fatwa itu lewat Panji Masyarakat, tidak ada polemik. Mujiburrahman mencatat polemik baru terjadi ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didirikan dan dipimpin HAMKA mengeluarkan fatwa senada pada 1981. Dalam fatwa itu MUI menegaskan kembali fatwa haram soal partisipasi muslim dalam perayaan Natal karena sifatnya yang berbeda dari Maulid Nabi Muhammad.
Ketika fatwa itu beredar luas, pemerintah Orde Baru terutama Kementerian Agama yang dipimpin oleh Alamsyah Perwiranegara murka. Fatwa itu dianggap terlalu kaku dan berpotensi merusak hubungan antara kelompok Islam, Kristen, dan pemerintah.
Apalagi, dalam beberapa tahun sebelumnya, Kementerian Agama secara aktif mendorong umat beragama untuk saling berpartisipasi dalam perayaan keagamaan dari kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, kantor-kantor pemerintahan pada periode tersebut kerap mengadakan perayaan keagamaan bersama yang dihadiri beragam kelompok agama, termasuk Natal.
Fatwa MUI dalam hal ini dilihat sebagai bentuk tantangan langsung terhadap pemerintah. Polemik itu kemudian berbuntut panjang dengan pernyataan terbuka Alamsyah yang menyatakan rencana untuk mengundurkan diri.
HAMKA kemudian merespons pernyataan itu dengan pengunduran dirinya sebagai Ketua MUI. Belakangan, karena ditekan oleh Orde Baru, MUI menarik peredaran fatwa tersebut dari sirkulasi melalui surat keputusan. Pun demikian, HAMKA bersikukuh bahwa penarikan fatwa dari sirkulasi tidak menggugurkan validitas dari fatwa yang dikeluarkan sebelumnya.
Sampai beberapa dekade ke depan, MUI tidak pernah lagi mengeluarkan fatwa baru terkait Natal. Fatwa soal Natal baru muncul kembali pada 2016 ketika MUI mengeluarkan fatwa yang melarang muslim untuk menggunakan atribut Natal.
Fatwa lanjutan ini dikeluarkan MUI untuk menjawab keresahan soal kewajiban penggunaan atribut Natal bagi karyawan muslim di sejumlah pertokoan.
Meski demikian, fatwa lanjutan ini tidak mengubah atau menegaskan posisi fatwa HAMKA yang melihat ucapan Natal sebagai bentuk toleransi beragama. Pada perayaan Natal tahun lalu, misalnya, MUI membebaskan umat Islam untuk memilih sikap soal ucapan selamat Natal karena mereka tidak pernah mengeluarkan fatwa spesifik soal ini.
Absennya fatwa MUI soal ucapan Natal rupanya tidak menghilangkan perdebatan mengenai topik itu. Pendapat-pendapat ustaz yang populer belakangan, seperti yang bersumber dari Khalid Basalamah, Abdul Somad, sampai Felix Siauw yang melarang pengucapan tersebut, amat mudah ditemukan di internet.
Kenyataan bahwa pertanyaan itu kerap diajukan dan video jawabannya amat populer menunjukkan masalah pemberian ucapan Natal yang sebelumnya tidak terlalu dipermasalahkan hari ini jadi sedemikian penting. Pergeseran fokus isu ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan-perubahan sosial-politik di Indonesia.
Fatwa MUI yang disampaikan oleh HAMKA, misalnya, menyebar seiring anjuran dari pemerintahan Orde Baru terhadap antar-umat beragama untuk melakukan perayaan agama bersama. Dalam konteks lebih besar, Mujiburrahman menempatkan polemik Natal sebagai salah satu episode ketegangan antara kelompok Muslim dan Kristen yang terus menyeruak pada masa Orde Baru.
Serupa hari ini, banyak tokoh Islam ketika itu merasa umat Islam selalu dipinggirkan oleh pemerintah Indonesia. Pembatalan Piagam Jakarta dan pembubaran Masyumi adalah beberapa peristiwa yang kerap ditunjukkan oleh kelompok Islam politik sebagai bukti bahwa negara mengesampingkan kepentingan mereka.
Pada saat bersamaan, tekanan kelompok Islam politik untuk memasukkan kerangka hukum normatif dalam perangkat negara dipandang sebagai ancaman kebebasan beragama oleh kelompok Kristen.
Menurut Jeremy Menchik dalam Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism (2016), ketegangan semacam ini tidak dapat dilepaskan dari proses perumusan nasionalisme di Indonesia. Kerangka berbangsa di Indonesia tidak sama dengan kerangka sekuler negara-bangsa yang berupaya memisahkan negara dari kehidupan keagamaan.
Indonesia juga tidak tepat dilihat sebagai negara berdasarkan agama karena tidak secara lugas menggunakan kerangka agama tertentu sebagai rujukan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri pengaruh kerangka pikir agama banyak ditemukan dalam perangkat dasar negara Indonesia.
Karena itu Menchik melihat kerangka nasionalisme Indonesia sebagai bentuk kompromi yang ia sebut sebagai "nasionalisme berketuhanan" (godly nationalism).
Kerangka nasionalisme yang eklektik ini berimplikasi panjang dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia. Absennya batas yang jelas soal pengaruh agama di ruang publik membuat perdebatan soal praktik religius selalu muncul sewaktu-waktu. Oleh karena itu, fatwa HAMKA soal perayaan Natal bersama tidak pernah sekadar menjadi anjuran ulama, tapi bagian dari kontestasi panjang terkait bentuk ideal negara-bangsa bernama Indonesia.
Keriuhan soal ucapan Natal beberapa tahun terakhir juga tidak dapat dilepaskan dari konteks perkembangan Islam Indonesia yang disebut Martin Bruinessen (2013) sebagai conservative turn. Fenomena ini ditandai penguatan adopsi simbol-simbol keagamaan di ruang publik. Namun, yang lebih mendasar dari persoalan simbol adalah kecenderungan pemahaman keagamaan yang konservatif.
Di luar perkara Natal, misalnya, MUI telah mengeluarkan fatwa konservatif terkait kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah. Lembaga yang sama juga berperan mengeluarkan fatwa politis seperti dalam kasus penistaan agama terhadap Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama.
Kecenderungan ini tak hanya terjadi pada MUI. Sebaliknya, perkembangan ini mencerminkan perubahan pandangan tentang Islam di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
Riset LIPI (2018) menemukan lapis besar masyarakat di sejumlah provinsi yang mendukung penerapan Perda Syariah. Senada dengan itu, sebelumnya ISEAS (2017) menyatakan 67% responden survei meyakini penerapan syariah Islam mampu menjaga moral masyarakat. Dalam konteks semacam ini, tidak mengherankan jika persoalan ucapan Natal yang sekilas remeh menjadi isu yang amat mencemaskan bagi sebagian muslim.
Melihat perkembangan di atas, polemik soal Natal atau isu-isu serupa tampaknya belum akan hilang dalam tahun-tahun mendatang. Alih-alih memudar, kecemasan kolektif soal terpinggirkannya posisi umat Islam malah terlihat kuat bahkan jika dibandingkan masa ketika HAMKA masih hidup. Kecemasan ini terus tumbuh meski pengaruh kerangka normatif Islam semakin kuat dalam ruang sosial dan politik di Indonesia.
Persoalan ini tidak dapat dipecahkan sekadar menyebarkan anjuran normatif untuk menjadi warga negara yang toleran. Sebab, anjuran normatif soal toleransi tidak menjawab keresahan mengenai moralitas dan keimanan.
Dalam hal ini, fatwa keagamaan alternatif seperti yang dikemukakan oleh Gus Dur atau Quraish Shihab lebih punya peluang untuk menjawab kecemasan kolektif itu. Namun, sejauh mana suara mereka masih didengar di tengah kebisingan media sosial kita hari ini?
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.