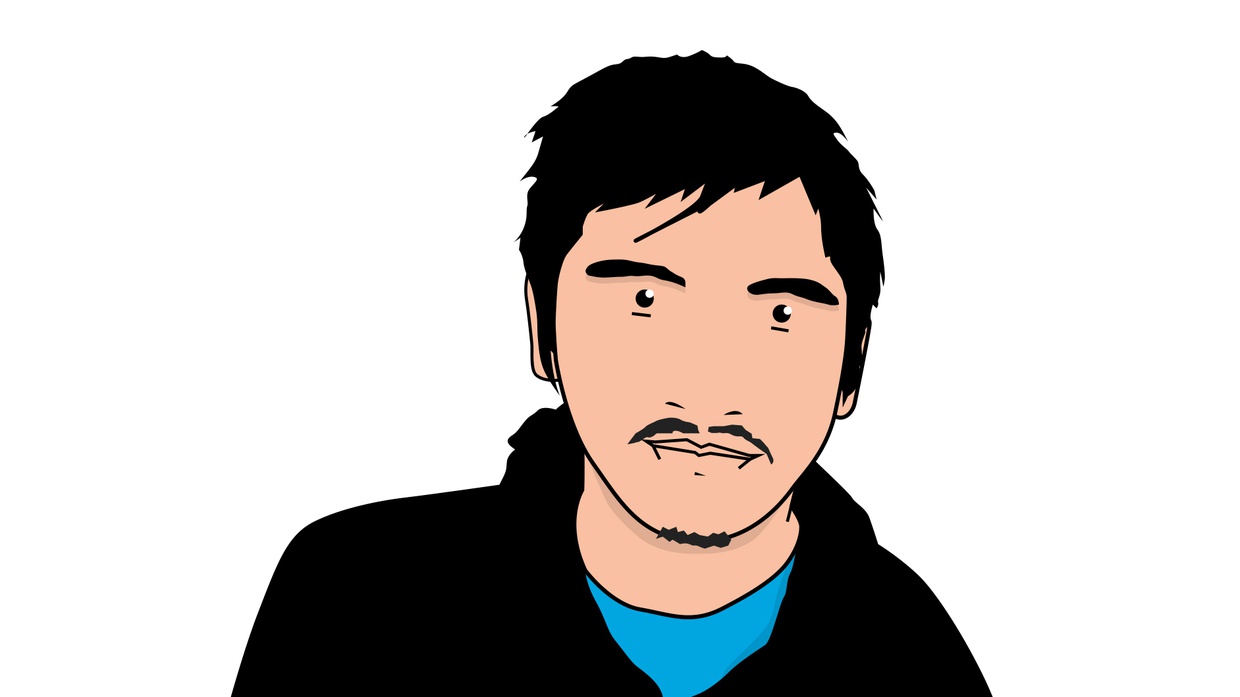tirto.id - Saat menginjakkan kaki di Istanbul, saya tak menemukan imaji Turki yang islami sebagaimana dibayangkan pengagum Recep Teyyip Erdogan dan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) di Indonesia. Saya juga tak banyak menemukan kemurungan (hüzün) yang berulang kali dibicarakan Orhan Pamuk sebagai jiwa Istanbul.
Mungkin saya salah memilih tempat, namun di seputar hotel tempat saya menginap di Jalan Istiqlal, hedonisme mudah terlihat. Di tepian jalan yang memanjang sejak Alun-alun Taqsim itu, berjejer toko-toko mewah, dipadati pengunjung berpakaian dandy, yang kecemerlangannya tak kalah dari orang-orang Eropa yang beberapa hari sebelumnya saya lihat di Frankfurt, Wina dan Praha.
Tentu gampang menemukan perempuan berhijab, namun jumlahnya tidak mencolok untuk ukuran negara dengan partai penguasa berbasiskan agama—yang di Indonesia banyak dianggap sebagai representasi pemerintahan Islam yang pantas diteladani. Beberapa orang terlihat mengenakan peci Turki, fez, namun rasa-rasanya kebanyakan orang-orang tua yang mengenakan. Jarang anak muda yang mengenakan fez di kepalanya.
Saat menelusuri beberapa tempat di Istanbul, bukan hal aneh melihat lagi apa yang terjadi di mobil berkap terbuka itu. Public display of affection, dari sekadar berangkulan sampai berciuman, beberapa kali saya lihat. Di sebuah jalan pintas berupa tangga yang menukik menuju Museum of Innocence, sebuah presentasi visual dari novel berjudul sama karya Orhan Pamuk, saya melihat anak-anak muda duduk melingkar dengan beberapa botol liquor (atau mungkin bir) yang sudah terbuka tutupnya.
Tiba di Jalan Istiqlal pada dini hari 29 Oktober, saya disambut konvoi mobil yang mengibarkan bendera Turki (hari itu peringatan Cumhuriyet Bayramı atau Republic Day, untuk mengenang peresmian Turki menjadi republik). Suara knalpot mobil, ditingkahi teriakan yang tak saya mengerti, memecah dentum suara musik dari klub-klub malam. Dari salah satu mobil dengan kap yang terbuka, sepasang anak muda mengibarkan bendera Turki sembari berciuman.
Di salah satu gang yang bertaut dengan Jalan Istiqlal, beberapa bar kecil masih buka, satu dua laki-laki muda melihat saya dengan tatapan tajam. Saat terjebak dalam konvoi, beberapa orang melongokkan kepala ke dalam taksi yang saya tumpangi. Bukan tatapan mengancam, melainkan tatapan yang—dalam cita rasa saya—mengingatkan pada apa yang disebut Orhan Pamuk sebagai "dunia laki-laki" saat membicarakan pretensi seksual sejumlah penulis Turki dalam bab “Kumpulan Fakta dan Keanehan Recet Ekrem Kocu” di memoar Istanbul: Memories of the City.
Tak sulit juga mencari “kehangatan”. Tak jauh dari kawasan turis Istana Topkapi, di belakang Blue Mosque yang indah itu, beberapa hotel memancarkan kemesuman yang tak ditutup-tutupi. Saya ingat cerita Gustave Flaubert, novelis besar Prancis yang berkunjung ke Istanbul pada 1850, kala Kekhalifahan Ottoman masih tegak berdiri, yang ditawari remaja perempuan oleh mucikari yang adalah ibunya sendiri. Hanya karena Flaubert sedang menderita sipilis, dan si remaja memaksa memeriksa penis Flaubert dulu, maka tak ada senggama.
Sebagai pembaca beberapa karya Pamuk, penulis yang memang berpandangan liberal dan sangat European-minded, tentu saya tak terkejut melihat scene-scene sekuler-hedonis tadi. Apalagi, Turki adalah negara yang resminya berstatus sekuler. Wajar jika imaji kehidupan sekuler mudah tercium.
Tapi tak berarti suasana religius absen. Di beberapa titik sangat dan mudah terasa. Saat waktu salat, persis seperti di Indonesia, suara azan segera menghampiri telinga di mana pun berada. Pada malam berikutnya, ketika kehidupan malam di Istiqlal mulai berdenyut, suara azan Isya terdengar di sela musik yang berdentam—sesuatu yang juga akan ditemukan jika nongkrong sampai subuh di berbagai tempat hiburan malam di Indonesia.
Namun, saya juga sulit menemukan kemurungan (hüzün) yang berulang disebutkan Pamuk sebagai jiwa Istanbul. Di gang-gang perkampungan tak jauh dari Istiqlal, di seputaran Museum of Innocence yang memang menjadi tempat Pamuk tumbuh, rasa-rasanya biasa saja. Kawasan Cihangir, tempat Pamuk dan beberapa pahlawan sastra yang dikaguminya sering hilir mudik, lebih tampak sibuk ketimbang kemuraman. Sesekali hawa malas menguar dari gang-gang di belakang Jalan Istiqlal, gang-gang berliku yang konturnya naik-turun, yang anehnya malah sepi di tengah terik hari dan mestinya sibuk. Di sebuah toko buku kecil tak jauh dari Nisantasi, yang memajang edisi Turki dari karya-karya Ilya Ehrenburg, Walter Benjamin, dan Vladimir Lenin, penjaga toko menyambut kedatangan saya dengan datar dan seperlunya, seperti menahan kantuk.
Pada salah satu senja, saya turun ke pantai yang letaknya tepat di bawah Istana Topkapi. Sembari menikmati Laut Marmara, saya menyesap segelas kopi instan yang dijual seorang bocah yang berjalan menenteng termos, hampir mirip dengan para penjual kopi di sekitar Monas. Di dermaga kapal feri, tak jauh dari Jembatan Galata, kapal-kapal bersandar dengan malas. Lagi-lagi saya tak mendapati kemurungan di sana. Sebagian besar kapal feri itu berusia muda dan klimis, dan ketika salah satunya melaju membelah Bosphorus saya tak menyaksikan, dalam kata-kata Orhan Pamuk, “[...] asap pekat yang membubung dengan kuat dari cerobong tak mau hilang-hilang juga dari langit, ada rekaman yang tak dapat disangkal tentang kemurungan yang ditinggalkan kapal feri itu.”
Di Istana Topkapi, tempat para penguasa Ottoman memimpin kekhalifahan, aura masa silam memang gampang terasa. Usaha menjaga dan merevitalisasi bangunan-bangunan bersejarah itu tampak sekali, namun kesilaman mustahil diabaikan di sebuah istana tua yang tak terpakai. Di puri para harem, saya mencium udara lembab dan asin yang tertiup dari Laut Marmara. Terdengar suara derit yang tajam saat saya mencoba mendorong pintu yang mengarah ke ruangan kecil yang tertutup.
Suara derit itu, ruangan harem itu, mengingatkan saya kepada Fatma, karakter perempuan sepuh dalam novel Silent House-nya Pamuk, yang membusuk di rumah tua yang bobrok ditemani budak yang merupakan anak haram suaminya. Menjelang klimaks cerita, dengan jerit memilukan, Fatma meradang dengan begitu pesimis: “Meski tak ada satu pun yang tersisa di dunia ini, tidak seekor burung, tak seekor anjing buluk, tidak juga seekor serangga yang dengan ngiung-nya mengingatkan kita tentang panasnya hari: waktu telah berhenti, [...] kursi kosong, meja-meja yang mengumpulkan debu, pintu yang tertutup, furnitur tak berpengharapan yang berderit dengan dirinya sendiri.”
Namun Istanbul hari itu, ketika saya ada di sana, bukanlah Istanbul tahun 1983 (ketika Silent House diterbitkan pertama kali). Saya mudah menemukan furnitur yang berpengharapan: jalan-jalan yang baru selesai diaspal, subway yang masih terus dibangun dan dipanjangkan, kereta-kereta yang masih kinclong, juga bandara Attaturk yang terus dipoles. Saya menangkap “kemalasan tertentu” di kapal-kapal feri yang bersandar di dermaga, tapi Istanbul yang saya lihat tidaklah semurung yang digambarkan orang Turki pertama yang dianugerahi Nobel Sastra itu.
Kegagalan saya menemukan imaji islami dan kemurungan boleh jadi dipicu pemahaman yang berbeda tentang apa itu islami dan kemurungan. Saya orang Indonesia, yang baru pertama kali berkunjung ke Turki, itu pun hanya kunjungan singkat beberapa hari, dan hanya di Istanbul saja. Bacaan tentang Turki pun jauh dari luas dan dalam. Beberapa buku tentang sejarah Turki pernah saya baca, juga beberapa karya Orhan Pamuk. Kombinasi dua hal itu pun, kalau dipikir-pikir, jauh dari cukup untuk memahami Istanbul, apalagi Turki, dengan memadai.
Pada 1940, dalam artikel berjudul "Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara" yang terbit di Panji Islam, Sukarno memulai argumentasinya dengan pernyataan hati-hati. "Orang yang tidak datang menyelidiki sendiri keadaan di Turki itu, atau tidak membuat studi sendiri yang luas dan dalam dari kitab-kitab mengenai Turki itu, [...] ia tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan vonis atas negeri Turki itu di muka umum," tulis Si Bung yang mengerjakan artikel panjang itu dari pembuangan di Bengkulu.
Si Bung menyebut sejumlah buku yang jadi rujukannya. Ia sempat menyebut "tidak lebih dari dua puluh kitab" tentang Turki yang ada di perpustakaan pribadinya. Toh itu tidak menghalanginya untuk bicara panjang lebar soal Turki Muda—istilah yang sempat populer di zaman itu untuk Turki versi Republik yang didirikan Mustafa Kemal Attaturk—sekaligus membela dan memuji langkah sekularisasi yang diambil Mustafa Kemal.
Kendati mencoba rendah hati, bahkan menyebut artikelnya semata hanya "sumbangan bahan untuk difikirkan sahaja", namun Muhammad Natsir menganggapnya sangat serius. Natsir tak memamah kalimat yang mengesankan kehati-hatian Sukarno, sebab baginya Si Bung sudah sangat serius berpihak kepada ide sekularisme dan artikel itu tak bisa dilihat sebagai "sumbangan bahan sahaja". Dengan menggunakan nama pena A. Muchlis, Natsir menulis serangkaian artikel untuk membantah argumentasi Sukarno.
Dari sanalah dimulai polemik legendaris soal relasi agama dan negara yang berlangsung di bawah bayang-bayang ancaman Perang Dunia II. Setelah berkorespondensi diselingi debat yang tajam mengenai berbagai topik tentang Islam, antara 1 Desember 1934 hingga 17 Oktober 1936, dengan A. Hassan selama diasingkan di Ende (korespondensi itu kelak diterbitkan menjadi buku Surat-Surat dari Ende), kali ini Sukarno menghadapi salah satu "murid" A. Hassan yang paling brilian. Jika Sukarno menakar langkah Kemal dari perspektif sejarah, Natsir memandangnya dari perspektif doktrin Islam.
Tentu sulit dicarikan titik temu dalam polemik yang masing-masing berangkat dari titik pijak yang berbeda, tapi polemik itu memperlihatkan dengan baik sekali bagaimana Turki memberikan sentuhan khas kepada kebangkitan nasionalisme Indonesia. Turki bahkan sudah lama menjadi bahan perbincangan para aktivis pergerakan jauh sebelum polemik pada 1940 itu.
Bersama kebangkitan di Mesir, kemenangan Jepang atas Rusia, juga kemajuan pergerakan di Filipina, keberhasilan Mustafa Kemal membebaskan Turki dari pendudukan Sekutu menjadi dian yang ikut menyalakan semangat para aktivis pergerakan Indonesia. Hampir semua diktat pelajaran sejarah di sekolah, dalam bagian tentang zaman pergerakan, selalu menyebut "Turki Muda" sebagai salah satu elemen yang ikut menyumbangkan peran dalam kebangkitan nasional.
Lebih dari yang lain, Turki dan Mustafa Kemal menghembuskan udara yang lebih segar karena menyodorkan dinamisme "kaum muda". Imaji "kemudaan" itu, tidak bisa tidak, dianggap sebagai injeksi moral bagi kaum pergerakan Hindia Belanda yang mayoritas juga berusia muda.
Pada 1932, kala pergerakan dibayangi kesuraman karena kekolotan Bonifacius Cornelis de Jonge, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang paling berangasan di abad terakhir kolonial, Mohammad Hatta merasa perlu membangkitkan semangat kaum pergerakan dengan mengisahkan usaha—negara mana lagi kalau bukan—Turki memerdekakan diri dari pendudukan Sekutu pasca-Perang Dunia I. Dalam artikel berjudul “Indonesia Dominion Apa Indonesia Merdeka”, Hatta menulis: "Riwayat Turki Muda membuktikan, bagaimana artinya kekerasan hati dan ketetapan haluan. Moga-moga hal ini menjadi ajaran pedoman bagi kita. [...] Pegang tetap haluan Indonesia Merdeka! Kalau tidak, kita durhaka kepada rakyat."
Saya akhirnya bisa memahami bagaimana Erdogan disukai banyak orang Indonesia. Suara Hatta di atas, sampai taraf tertentu, tergemakan dalam kesukaan banyak orang Indonesia terhadap Erdogan. Selain irisan persamaan politik dengan AKP, kesukaan pada islamisme ala Erdogan dan AKP agaknya dipicu oleh imaji tentang semangat menghidupkan lagi kejayaan Islam dengan cara-cara modern, yang mengesankan kesanggupan berhadapan dengan Barat secara berani. Ditatap dari jauh, sangat mungkin imaji tentang Erdogan dan AKP memang mewakili “semangat muda”—artinya kehendak untuk maju—Islam politik yang sedang berderap-berbaris, berbareng-bergerak.
Ia bukan hanya terjepit di antara Timur dan Barat, sebagaimana semua sultan Ottoman dulu. Berhadapan dengan Eropa yang menekankan standar tertentu jika Turki ingin diterima Uni Eropa, dikepung persoalan Timur Tengah yang pelik dan njlimet, Erdogan dan AKP mampu terus bertahan sejak berkuasa pada awal milenium ketiga. Saat wajah Islam di beberapa negara Timur Tengah diselimuti kemuraman, ketika intrik politik di negara-negara Arab mengemuka dan kabar hedonisme para pangeran Arab tak dapat dicegah peredarannya, Erdogan menjadi pilihan paling masuk akal bagi mereka yang rindu menyaksikan Islam (politik) berkibar dengan terhormat. Ingatlah kata-kata Napoleon itu: “A leader is a dealer in hope.”
Percakapan saya dengan seorang pemilik restoran niscaya disukai para penggemar Erdogan di Indonesia. Restoran yang terselip di antara toko-toko kecil yang menjual merchandise khas Turki dan lapak-lapak sayur serta ikan segar itu menjadi satu dari sedikit tempat makan yang sudah buka kala hari masih begitu pagi. Pemilik restoran berusia menjelang 60an tahun sangat antusias mengajak bicara begitu tahu saya berasal dari Indonesia. Sembari menyerahkan sebungkus kopi dalam kemasan berlogo AKP, ia menceritakan pencapaian-pencapaian Erdogan dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Dia membandingkan usaha Erdogan menegakkan kewibawaan Turki dan Islam di hadapan Barat dengan jerih payah Sultan Mehmet II kala menaklukkan Konstantinopel pada 1453.
Kendati masih mengakui sekularisme sebagai prinsip kenegaraan Turki, Erdogan terhitung bersemangat menghidupkan imaji kejayaan Ottoman. Saat merayakan penaklukan Konstantinopel yang ke-563 pada Mei lalu, misalnya, wajah Erdogan terpampang di baliho-baliho besar yang bertuliskan “Yeniden Diriliş, Yeniden Yükseliş” (Resurrection, Reascendance), lengkap dengan angka 563 yang dicetak besar. Saat Erdogan berpidato di puncak perayaan, barisan prajurit yang mengenakan seragam tentara zaman Ottoman berbaris rapi. Sudah terang pesan apa yang hendak disampaikan dari materi-materi visual seperti itu.
Dengan nada yang plastis dan retorika yang pas, Erdogan berkata: "Hidup yang dihabiskan tanpa melihat dan mencicipi dan melihat Istanbul adalah hidup yang tak lengkap. Aku merayakan ulang tahun penaklukan Istanbul ke-563, salah satu kemenangan paling megah dalam sejarah yang mengantarkan dunia kepada era baru setelah begitu lama menutup diri satu sama lain. "
Tak disangkal Erdogan dicintai banyak rakyat Turki. Saya bisa merasakan dukungan yang serius kepada Erdogan dari pemilik restoran yang menghadiahi saya kopi kemasan berlogo AKP itu. Lelaki tua itu dengan cuma-cuma bersedia menjadi juru kampanye yang gigih kepada orang asing seperti saya. Pada siang 29 Oktober, ketika melintasi Alun-alun Taqsim yang tengah ramai dengan perayaan Cumhuriyet Bayramı, semua orang nyaris tanpa kecuali berdiri dan dengan penuh takzim menyanyikan İstiklâl Marşı, lagu kebangsaan Turki. Saya melihat seorang anak muda, dengan pakaian yang “kebarat-baratan” (celana jeans, jaket kulit, sepatu Asics dan kacamata hitam), ikut bernyanyi dengan khidmat sembari menggenggam bendera AKP berukuran kecil. Imaji tentang—misalnya—simpatisan PKS di Indonesia tak tampak pada anak muda itu.
Scene itu memperingatkan saya akan satu hal: mungkin menjadi (simpatisan) islam politik di Turki bisa atau biasa diekspresikan tanpa harus “ber-arab-arab-ria”. Juga perihal kemungkinan nisbinya imaji politik identitas di antara dua negeri yang berjauhan—kendati tak kurang-kurangnya usaha mendekatkan maupun menjauh-jauhkan keduanya.
Percobaan kudeta yang terjadi akhir pekan lalu boleh jadi menjelaskan sejumlah hal, tidak terkecuali perlawanan terhadap Erdogan dan AKP. Orang seperti Orhan Pamuk, yang liberal dan sekuler, dan punya kecurigaan yang laten kepada islam politik sehingga tidak dapat sepenuhnya mewakili suara Turki, tidak kurang pula banyaknya.
Dua novel Pamuk, The Silent House dan Snow, berkisah tentang betapa berdarahnya peristiwa kudeta (Silent House berlatar Istanbul menjelang kudeta; Snow berlatar di Kars awal 1990an). Friksi dalam pergerakan islam politik, perseteruan antara kaum relijius dan sekuler, separatisme Kurdistan, dan represi aparat yang ngawur menjadikan Snow sebagai thriller politik yang mencekam. Kematian memburu, kebencian menahun, curiga mencurigai menyelubungi Kars, tak ubahnya salju yang dengan ganas mengisolasi kota.
Bahkan orang seperti Pamuk pun sadar berbahayanya permainan bersenjata untuk menuntaskan persoalan politik. Dalam sebuah wawancara Pamuk berkata: “Kaum sekuler tidaklah meremehkan kelompok religius, mereka hanya keliru terlalu percaya dapat mengendalikan kekuasaan hanya melalui tentara.”
Ia tidak percaya militer adalah solusi. Pamuk sudah menyaksikan kudeta militer 1980, yang menginspirasi novel The Silent House, juga mengalami kudeta yang disebut sebagai “sebuah kudeta lewat sepucuk surat” pada 1997. Militer Turki yang gerah dengan kepemimpinan Necmettin Erbakan yang dinilai menguatkan islam politik, mengirim memorandum yang menjadi awal—bukan hanya mundurnya Erbakan—represi militer terakhir sebelum pergantian milenium. Cevik Bir, salah seorang jenderal yang merancang kudeta itu, berkata: "Di Turki kami menyepakati pernikahan Islam dan demokrasi. [...] Anak dari pernikahan ini adalah sekularisme. Sekarang sang anak ini terserang sakit dari waktu ke waktu. Angkatan Bersenjata Turki adalah dokter yang akan menyelamatkan sang anak.”
Sebuah pernyataan alegoris yang, rasa-rasanya, mencoba menutupi watak khas militer. Sejarah junta militer di mana pun menjelaskan, hanya perlu pembangkangan dan perlawanan sedikit serius untuk mengubah pernyataan alegoris itu menjadi pernyataan terbuka, juga tindakan terang-terangan, yang tak malu-malu.
Saya teringat adegan ketika Kadife, karakter yang sangat religius dalam novel Snow, melepas jilbab dan lantas membakarnya di bawah tatapan ribuan orang di gedung Teater Nasional dan jutaan orang lain yang menyaksikannya di televisi. Kadife melakukan itu demi membebaskan Lazuardi, lelaki yang ia cintai, dari penculikan. Pertunjukan teater yang mementaskan lakon tragedi Spanyol itu berakhir menjadi pembantaian oleh tentara sekuler—sebuah amalgamasi puitik antara coup d’etat dan coup d’theatre.
Bagi kita yang jauh, percobaan kudeta pada akhir pekan lalu mungkin membuka banyak tabir politik, namun boleh jadi tidak. Sampai batas tertentu, rasa-rasanya negara itu terasa akrab dengan kita—kendati sebenarnya jauh secara geografis. Dari peci dan kebab hingga produk melodrama di televisi, juga “kecerewetan” para pemuja atau pembenci Erdogan di media sosial, Turki seakan tidak jauh-jauh amat. Betapapun sedikit atau dangkalnya pengetahuan kita tentang realitas yang pelik di Turki.
_________
Baca juga artikel tirto.id terkait Turki berikut:
Kelompok Kanan Kiri yang Meneror Turki
Tentang Fethullah Gulen, Tertuduh Kudeta Gagal Turki
Apa yang Terjadi di Turki Tinggallah di Turki
Kelompok Kanan Kiri yang Meneror Turki
Editor: Maulida Sri Handayani
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id