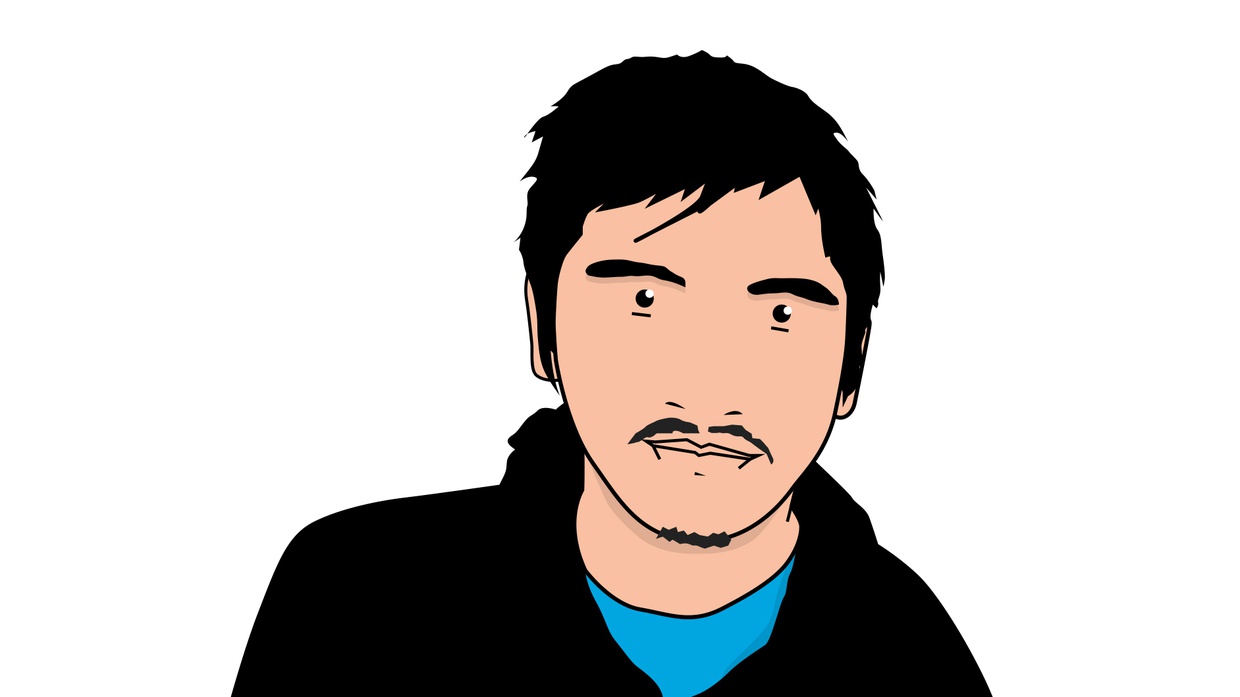tirto.id - Siapa bilang dwi fungsi TNI sudah dicabut? TNI sampai sekarang masih mempraktikkan dwi fungsi TNI: (1) sebagai tentara dan (2) sebagai oknum.
Nyaris tidak pernah TNI mengakui perilaku buruk anggotanya sebagai kesalahan institusional. Tiap ada anggota TNI melakukan kesalahan, bahkan kejahatan, selalu "oknum" yang dijadikan kambing hitam. Dari penculikan para aktivis di pengujung kekuasaan Orde Baru, kekerasan yang dilakukan tentara terhadap masyarakat sipil (dari para petani, aktivis, wartawan hingga suporter Gresik United), sampai pembantaian tahanan di Cebongan--semuanya dilokalisir tidak ada kaitannya dengan institusi – pendeknya: oknum.
Yang lebih memprihatinkan lagi, oknum yang sudah dinyatakan bersalah pun masih punya kemungkinan berkarir dan menjabat setinggi-tingginya. Ada sejumlah kejahatan yang dilakukan tentara, dan kemudian dihukum oleh pengadilan militer, artinya terbukti bersalah, bahkan dipecat, tapi itu semua tidak membuat karir terpidana menjadi berhenti.
Dari 11 anggota Tim Mawar Kopassus yang melakukan penculikan kepada para aktivis di pengujung Orde Baru, dan divonis bersalah dalam mahkamah militer 1999, empat di antaranya bahkan promosi sebagai jenderal. Dari empat orang itu, tiga di antaranya bahkan divonis dipecat. Bahkan Hartomo, seorang yang kini berpangkat mayor jenderal, yang dipecat dari militer oleh pengadilan militer Surabaya karena membunuh Theys Hiyo Eluay, aktivis Papua, diangkat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Salah satu yang membuat "keajaiban" itu bisa terjadi adalah tertutupnya proses pengadilan militer. Pengadilan militer menjadi sanctuary yang membuat banyak tindakan kriminal oleh tentara sulit diadili dengan standar-standar yang dialami rakyat sipil ketika diseret ke pengadilan.
Dalam kasus kejahatan HAM yang dilakukan Tim Mawar, mereka yang dipecat dari militer kemudian mengajukan banding sehingga pemecatan belum bisa dieksekusi. Koordinator Kontras Usman Hamid, pada Mei 2007, pernah menyesalkan ketertutupan proses pengadilan di tingkat banding. Hasil putusannya, berikut amar dan argumentasinya, sulit diakses publik. Sehingga tidak heran jika publik terkejut ketika seorang tentara yang sebelumnya terbukti melakukan kejahatan malah mendapatkan promosi sebagai jenderal beberapa tahun kemudian.
Situasi menjadi pelik karena masyarakat sipil (dari pemimpinnya sampai warganya) justru sering kali mendiamkan, mengafirmasi bahkan mengundang tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan militer. Dari Ridwan Kamil yang hanya menganggap pembubaran perpustakaan jalanan yang dilakukan Kodam Siliwangi dengan sewenang-wenang semata hanya "miskomunikasi", atau Ahok yang malah menggunakan tentara untuk melakukan penggusuran, hingga tidak sedikit warga Yogya yang berkampanye memberikan dukungan pada tentara yang dengan keji melakukan pembantaian terhadap tahanan di Cebongan.
Penetrasi militer ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa, yang bentuk paling intensnya terjadi pada masa Orde Baru, memang begitu mengakar dan menancap sangat dalam. Tentara diidealisasikan atau mengidealisasikan dirinya sebagai representasi paripurna dari nasionalisme. Bahwa tidak ada yang lebih setia kepada Indonesia selain tentara. Bahwa tidak ada yang lebih tanpa pamrih membela tanah air selain tentara. Bahwa pemimpin sipil (terbukti) sering tidak becus, kerap di/meragukan kesetiaannya, egois, lebih senang cekcok, dan lebih mengutamakan kepentingan politik sesaat.
Fragmen ketika pemimpin sipil republik (Sukarno-Hatta, dkk) menolak bergerilya saat Belanda melakukan Agresi Militer II, sedangkan Soedirman yang sakit-sakitan berani angkat senjata, sering dirujuk sebagai bukti kepengecutan pemimpin sipil. Sedangkan praktik demokrasi parlementer (1950-1959), yang ditandai jatuh bangunnya kabinet karena kontestasi partai-partai yang sengit, kerap dipropagandakan sebagai bukti sahih betapa sipil mabuk kekuasaan, senang berselisih, dan sibuk mementingkan kepentingan kelompok.
Pada masa kekuasaan Orde Baru, yang pada praktiknya adalah kekuasaan militer(istik), persisnya lagi Angkatan Darat, imaji tentang dahsyatnya pengorbanan dan kesetiaan tentara direproduksi secara masif melalui berbagai metode. Film-film perjuangan bersenjata diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, tidak sepadan (jika bisa dibilang tidak ada) dengan film-film perjuangan yang menggambarkan keterjepitan yang dialami pemimpin sipil saat menghadapi situasi politik yang centang-perenang, yang memaksa mereka untuk (tidak bisa tidak) membuat sejumlah kompromi dalam berbagai bentuk perundingan. Belum lagi jika bicara porsi tuturan tentang perjuangan bersenjata dalam narasi perjuangan bangsa di buku-buku pelajaran.
Bukan menihilkan pentingnya angkatan perang pada periode 1945-1949. Tanpa angkatan perang, hampir bisa dipastikan republik ini akan jauh lebih mudah dihancurleburkan kembali oleh Belanda. Akan tetapi penting sekali memandang sejarah secara proporsional.
Namun jangan sampai dilupakan bahwa tanpa pemimpin sipil maka tak akan ada angkatan perang. Bahkan bisa dikatakan tanpa pemimpin sipil boleh jadi republik ini tidak akan pernah ada. Indonesia adalah gagasan yang pada awalnya dilahirkan dan diperjuangkan oleh orang-orang sipil. Jika dilacak dari akhir abad-19 sampai dibacakannya proklamasi, semenjak Kartini sampai Sukarni, gagasan tentang Indonesia nyaris sepenuhnya dipikirkan, dirumuskan dan diperjuangkan oleh para pemimpin sipil.
Imaji tentang kepengecutan Sukarno-Hatta, dkk., karena menolak gerilya sangat tak adil karena mengabaikan satu hal yang amat penting: merekalah yang justru paling awal mempertaruhkan dan mengorbankan banyak hal untuk memperjuangkan Indonesia saat kolonialisme Belanda masih sangat gagahnya bertahta.
Saat Nasution muda atau TB Simatupang muda masih asyik-masyuk (belajar) menjadi serdadu Belanda (KNIL) yang tentu saja harus mengabdi kepada Ratu Wilhelmina, orang seperti Sukarno, Hatta, Mas Marco, dkk., sudah lebih dulu menghadapi berbagai risiko yang tak alang kepalang saat memperjuangkan Indonesia di hadapan kekuasaan Belanda. Mereka bukan hanya dipenjara, dibuang atau diasingkan, sangat banyak dari mereka yang tumpas-kelor oleh pelor Belanda atau tewas dalam pembuangan yang pahit di belantara Papua yang mematikan oleh penyakit dan kesunyian.
Ketika Soedirman muda atau Soeharto muda sedang khidmat berlatih di bawah bendera PETA bentukan Jepang, orang seperti Amir Sjarifuddin, Sjahrir atau Tan Malaka justru sibuk menggalang kekuatan massa-rakyat di bawah tanah dengan mempertaruhkan batang lehernya. Orang seperti Amir, Sjahrir dan Tan Malaka sibuk membangun simpul-simpul gerakan, menyelinap di sela-sela intaian kempetai dan endusan mata-mata, mengabaikan risiko yang tidak main-main. Saat aktivitas bawah tanah Amir terendus Jepang, ia langsung ditangkap, diadili, dan dihukum mati (yang eksekusinya berhasil ditunda berkat intervensi Sukarno-Hatta).
Kecuali Soepriyadi dan pasukannya di masa pendudukan Jepang, hampir tidak ada usaha dari orang-orang yang kelak menjadi petinggi-petinggi militer Indonesia itu untuk angkat senjata kepada Belanda. Nyaris semuanya "anteng", belajar dan berdinas sebagai serdadu KNIL yang baik.
Memerdekakan Indonesia adalah gagasan yang awalnya tumbuh dari kalangan sipil, dan sipil juga yang paling gigih bertungkus-lumus mengusahakannya, dan mereka juga yang mencicipi pahitnya pemenjaraan, pembuangan, pengasingan hingga kematian. Saya tidak menafikan bibit-bibit nasionalisme yang berkecambah di dada para serdadu KNIL bumiputera, tapi mesti jujur dikatakan bahwa inisiatif ke-Indonesia-an memang dilahirkan oleh orang-orang sipil yang kelak di kemudian hari diimajinasikan sebagai "pengecut" dan "hobi cekcok" itu.
Lagi pula, siapa bilang kontestasi yang berujung perselisihan dan cekcok itu hanya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sipil?
Dari usaha kudeta militer pada 17 Oktober 1952 (konflik Bambang Soepeno-Nasution), peristiwa Malari (Soemitro-Moertopo), hingga periode transisi 1998 (Wiranto-Prabowo), tentara Indonesia juga tidak kasip dari konflik internal. Coba simak juga peristiwa-peristiwa pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Dari DI/TII, PRRI/PERMESTA, bahkan hingga peristiwa 1965: semuanya melibatkan tokoh-tokoh militer. Dari Ibnu Hajar, Kahar Muzakkar, Ventje Sumual, Alex Kawilarang, hingga Kolonel Oentoeng.
Peristiwa 1965 juga tidak bisa dipisahkan dari konflik internal tentara. Salah satu versi penjelasan peristiwa 1965, yaitu naskah Cornel Paper, bahkan terang-terangan menyebutnya sebagai buah dari konflik internal Angkatan Darat – wabil khusus Divisi Diponegoro. Jangan lupa juga bagaimana peristiwa 1965 menjadi awal mula konflik tidak seimbang antara AD dengan AL dan (terutama AU): ketika AU dianaktirikan karena dianggap terlibat dalam peristiwa penculikan para jenderal. Tafsir atau bukan, perspektif atau bukan, sudah menjadi fakta sejarah yang tak bisa dibantah bahwa para pelaku penculikan sesungguhnya tentara juga, persisnya bahkan dari Angkatan Darat.
Pledoi bahwa tentara (AD) disusupi anasir-anasir yang tidak diinginkan, katakanlah komunis dalam peristiwa 1965, harus dimaknai sebagai bianglala penafsiran sejarah yang terus berkontestasi. Cukuplah dikatakan bahwa: tentara tidak benar-benar suci, bukannya tidak punya noda dalam perkara cinta tanah air dan kesetiaan pada tumpah darah.
Tinggal versi mana yang mau dipakai? Perspektif mana yang hendak digunakan? Jika menggunakan versi Pusat Sejarah TNI, ya tidak apa-apa juga. Asal tidak memaksakan versi lain sebagai khianat, subversif, atau (dikit-dikit dituduh) disusupi antek asing dan "aseng", "kuminis" atau "wahyudi". Apalagi kalau memaksakannya sambil membubarkan perpustakaan, menggebuki wartawan atau menghajar petani.
Dan konflik-konflik internal itu merembet ke mana-mana. Yang pada awalnya sebagai konflik internal kemudian merembet ke luar barak dan tangsi. Dampaknya menjangkau hingga ke masyarakat sipil. Tidak sedikit rakyat yang menjadi korban. Tidak sedikit yang mesti meregang nyawa. Mau bagaimana lagi? Kalau konflik terjadi di antara orang-orang yang memegang senjata, mana mungkin tidak ada muntahan peluru?
Kalau fakta-fakta itu dilokalisir sebagai oknum, maka proses otokritik tidak akan pernah terjadi. Kalau ujung-ujungnya hanya oknum yang dikambinghitamkan, maka percayalah: tidak ada institusi di negara ini yang bobrok, semuanya beres dan baik-baik saja, semuanya alim, macam nabi atau para wali. Mau institusi militer maupun sipil, kalau masih saja melulu melokalisir persoalan sebagai kelakuan oknum, ya akan sulit mengharapkan perkembangan.
Pokok soal satu ini, bahwa tentara adalah satu-satunya contoh ideal dalam urusan cinta tanah air, perlu terus menerus didiskusikan ulang. Terutama karena belakangan kian menguat penggunaan militer ke dalam persoalan-persoalan yang mestinya tidak lagi diselesaikan dengan cara-cara usang warisan Simbah dari Godean. Dari konflik di Papua, konflik agraria hingga penggusuran kaum miskin kota oleh gubernur yang paling punya niat baik sekaligus idaman mesin pencari.
Bahkan walikota yang dianggap paling gaul, paling kreatif, dan paling gemar bercanda pun merasa perlu mengirim tentara ke sekolah-sekolah sebagai pembina upacara untuk "mengajarkan karakter ksatria" dan "membentengi anak-anak kita dari nilai-nilai negatif yang menyerang nalar dan emosi". Padahal belum dua purnama militer di wilayah kekuasaannya mengacak kemerdekaan dan kebebasan sipil dalam mengakses pengetahuan dan bahan bacaan. Padahal belum sebulan tentara di wilayah kekuasaannya menghajar dan menggebuk para atlit kontingen provinsi lain di ajang PON 2016.
Setelah bertempur menghadapi pasukan Belanda dalam kampanye Trikora, tentara Indonesia sebenarnya tidak pernah lagi berperang dengan kekuatan asing. Setelah kejatuhan Sukarno, tentara Indonesia bahkan lebih sering memerangi anak bangsa sendiri. Dengan dalih memerangi separatisme, tentara Indonesia terlibat dalam pembunuhan para pembangkang di berbagai tempat. Ada yang memang menghadapi para pembangkang bersenjata, namun cukup banyak korban dari rakyat sipil non-kombatan.
Tidak cukupkah ribuan korban yang sudah jatuh selama beberapa dekade terakhir? Tidak cukupkah nyawa yang melayang di Aceh, Santa Cruz di Timor Leste, Talangsari, Tanjungpriok, Papua hingga sepanjang Mei 1998?
Pendekatan militeristik dalam menghadapi ketidakpuasan rakyat adalah cara-cara lama yang sudah tidak patut dipertahankan. Kekerasan di Papua, misalnya, tidak akan pernah berakhir selama negara masih menggunakan pendekatan-pendekatan keamanan yang militeristik. Demo sedikit ditangkapi, unjuk rasa sedikit digebuki.
Kita tidak bisa lagi menghadapi ketidakpuasan rakyat dengan cara-cara militeristik supaya tidak menjadi Belanda di zaman sekarang. Tuduhan bahwa pembangkangan rakyat itu disusupi kepentingan asing, misalnya, membuat Indonesia tidak awas terhadap malpraktik nasionalisme yang sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Jangan lupa, para aktivis pergerakan di zaman dulu pun dituduh disusupi kekuatan asing oleh Belanda: dari susupan pihak komunis Sovyet sampai susupan gerakan Pan-Islamisme.
Dan pendekatan militeristik mulai lagi dipakai untuk menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi.
Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2015 terdapat korban tewas lima orang, tertembak aparat 39, luka-luka 124 dan ditahan (kriminalisasi) 278 orang. Dua tahun sebelumnya, masih merujuk laporan KPA, korban tewas oleh aparat negara dalam konflik agraria bahkan mencapai 21 orang. Korban lain, 30 orang tertembak, 130 mengalami penganiayaan dan 239 warga ditahan. Pada 2013, di Jawa Timur saja, Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-Repdem) menyebutkan bahwa ada 25 konflik agraria yang melibatkan militer. Ini belum menyebut konflik di Urut Sewu dan tempat-tempat lain di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.
Biarlah TNI bekerja secara profesional mengurusi bidang pertahanan sebagaimana diamanatkan oleh reformasi. Mengutip Made Supriatma, tugas pemimpin sipil adalah menjamin tentara melakukan fungsi kemiliteran sebaik-baiknya, dan memberikan dana yang cukup untuk itu. Tugas sipil membangun sistem politik dan ekonomi yang membuat tentara tumbuh dan berkembang sebagai tentara. Pekerjaan rumah TNI untuk mereformasi dirinya dalam sistem demokrasi masih belum tuntas. Janganlah TNI digoda untuk kembali ke zaman pra-1998.
Jika kemarin (4/10/2016) Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, mengatakan bahwa TNI ingin kembali memiliki hak-hak politik (sebagaimana dwi-fungsi ABRI di zaman dulu?), itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kita harus meletakannya sebagai dampak dari tumbuh-kembangnya atmosfer pendekatan militeristik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sipil yang kembali menggejala belakangan ini.
Jika untuk menggusur kaum miskin kota, mengusir para petani, sampai menjadi pembina upacara pun sampai harus mengandalkan tentara, apa bedanya zaman sekarang ketika pemimpin (dari pusat dan daerah) dipilih langsung oleh rakyat dengan zaman ketika pemimpin dipilih oleh MPR dan DPRD yang masih diisi Fraksi ABRI?
Anda semua menjadi pemimpin, dari presiden hingga gubernur, bupati dan walikota, karena berkah reformasi yang (salah satunya) dilatari semangat memperkuat kehidupan dan kepemimpinan sipil serta mengembalikan tentara ke barak agar lebih profesional mengurusi bidang pertahanan. Bukan malah mengundang dan menggoda tentara untuk kembali mencampuri kehidupan sipil dengan beragam agenda, tajuk dan label. Ataukah tuan dan puan sekalian sudah lupa?
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id