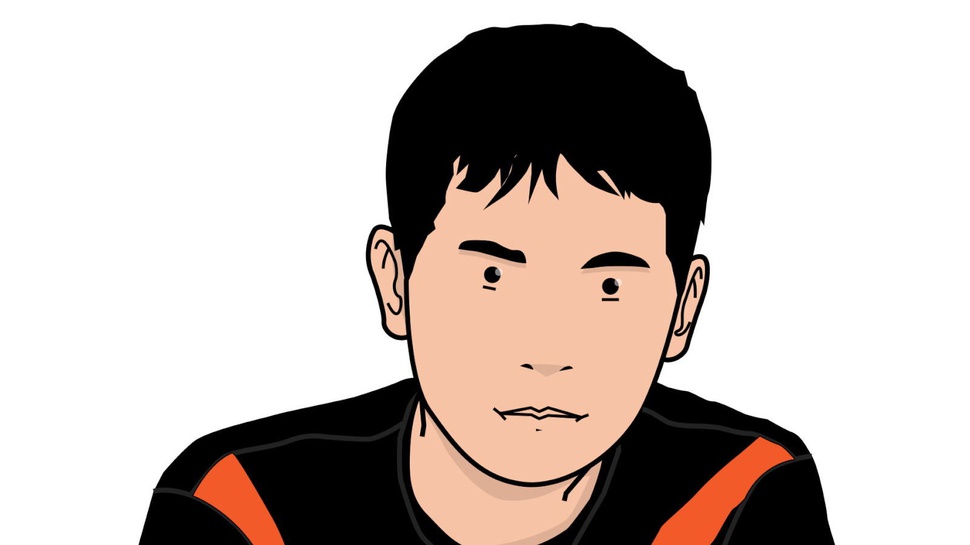tirto.id - Mengenai pernyataan Bapak Taufiq Ismail bahwa lirik lagu “bagimu negeri, jiwa raga kami” adalah sesat dan musyrik, dua penjelasan bisa dikemukakan. Penjelasan pertama berbasis buruk sangka; sedang yang kedua berlandaskan baik sangka.
Dengan buruk sangka berbalut argumentum ad hominem, dengan mempertimbangkan bahwa hampir tidak ada orang Indonesia sejak zaman kemerdaan hingga kini yang mempermasalahkan lirik itu, cukup terpahami bila ada kecurigaan: Di balik pernyataan itu, jangan-jangan ada suatu hal yang personal dengan pencipta lagu Bagimu Negeri, yakni Si Buaya Kroncong Kusbini, atau mungkin juga dengan Sukarno.
Sebagian besar isi lagu Bagimu Negeri digubah Kusbini pada 1942, dengan lirik terakhir berbunyi “bagimu negeri, Indonesia raya.” Sukarno lalu memintanya untuk mengganti frasa “Indonesia raya” dengan “jiwa raga kami” demi menghindari sensor penjajah Jepang. Demikian tutur Simbah Wikipedia yang meriwayatkan dari Hari Budiono dalam Sebuah Harapan Si Buaya Kroncong (1990).
Di situ tampak, dalam “jiwa raga kami”, frasa yang dipermasalahkan Pak Taufiq itu, ada jejak Sukarno. Lebih dari itu, Kusbini, yang namanya kini diabadikan untuk jalan di depan rumahnya dulu di Yogyakarta, juga menggubah lagu Nasakom Bersatu dan Hymne Nefo (The New Emerging Forces)—yang terakhir ini, yang digubah pada 1965 bersama Kamadjaja, adalah lagu ciptaan terakhirnya. Nasakom Bersatu bersama Bagimu Negeri pernah menjadi dua dari 16 lagu yang wajib diajarkan di sekolah, dan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44/1958 tentang Lagu Kebangsaan. Tak kalah penting, lagu Nasakom Bersatu juga masuk dalam buku lagu wajib “Api Kemerdekaan Indonesia” terbitan Lekra.
Kusbini, Sukarno, Nasakom—tiga kata ini sudah cukup sebagai bahan otak-atik-gatuk. Sebagaimana sudah jamak diketahui, Pak Taufiq sangat tidak menyukai kepanjangan suku kata “kom” dalam kata terakhir itu. Jadi, mungkin saja ada persoalan personal di sana.
Namun penjelasan ini, sebagaimana disebut di atas, berlandaskan buruk sangka, dan karena itu tidak baik—namanya juga “buruk” sangka. Karena itu, bagi yang hatinya tak ingin dinodai dosa, penjelasan di atas tidak dianjurkan untuk diadopsi, dan sebaiknya beralih pada penjelasan berbasis baik sangka: bahwa keberatan Pak Taufiq, yang menyatakan bahwa jiwa raga semestinya hanya untuk Allah semata, adalah benar-benar didasari ketulusan beragama dan, lebih khusus lagi, kemurnian bertauhid.
Pak Taufiq pernah menulis, di tahun ketika penulis artikel ini bahkan masih belajar baca-tulis, puisi berjudul “Padamu Negeri”: “Jadi setiap menyanyikan lagu ini/ Tiba pada baris terakhir sekali/ Jiwa raga cuma pada Tuhan kami beri.”
Bila memang demikian tulus adanya, dua jenis tanggapan bisa dikemukakan. Pertama secara teologis, dan kedua secara semantis.
Secara teologis, pernahkah ada perintah untuk memberikan jiwa raga demi negeri? Secara eksplisit tidak, tapi secara implisit ada.
Sebagaimana ditulis dalam buku-buku sirah Nabawiyyah, perintah perang dimulai setelah kaum Muslim diusir dari tanah airnya: Mekkah. Ayat pertama yang memerintahkan perang ialah surah al-Hajj ayat 39-40, yang menyatakan bahwa perang telah diizinkan bagi kaum Muslim karena mereka telah dizalimi. Bentuk kezaliman itu dinyatakan eksplisit, yakni karena mereka telah “dikeluarkan dari kampung mereka tanpa hak” (ukhriju min diyarihim bighairi haqq). Tentu saja perang juga berarti mempertaruhkan jiwa raga, dan alasannya adalah untuk keadilan: merebut kembali “diyar”, negeri mereka.
Dalam terang penafsiran seperti ini—dan ini tanggapan secara semantis—kalimat “bagimu negeri jiwa raga kami” dapat diberi penjelasan (syarah) menjadi “bagimu negeri, kami mempertaruhkan jiwa raga kami untuk kembali menegakkan keadilan, merebut kedaulatan atasmu, sebab demikianlah perintah-Nya”. Di sini sama sekali tidak ada pertentangan dengan loyalitas penghambaan pada-Nya.
Pak Taufiq barangkali terlalu harfiah memahami, sehingga beliau menutup adanya penafsiran lain yang masih dimungkinkan terhadap lirik itu, yakni bahwa memberikan jiwa raga bagi (keadilan dan kedamaian) negeri adalah juga bagian dari penghambaan pada-Nya.
Di samping itu, pernyataan Pak Taufiq yang mempersoalkan hal semacam itu boleh jadi adalah satu-satunya di dunia. Ada beberapa negara mayoritas Muslim lain yang mempunyai lagu kebangsaan dengan lirik seperti yang dipersoalkan Pak Taufiq, tapi tampaknya tak terdapati hal serupa yang diresahkan beliau.
Lagu kebangsaan Mesir sejak 1979 yang berujudul “Biladi”, misalnya, dimulai dengan lirik “biladi laki hubbi wa fuadi” (negeriku, bagimu cinta dan hatiku). Lagu kebangsaan Palestina, negeri yang pernah dibuatkan puisi oleh Pak Taufiq dengan judul Palestina, Bagaimana Bisa Aku Melupakanmu, memiliki lirik berbunyi “waasywaq dami liardhi wadari” (rindu-rindu darahku untuk tanah dan rumahku).
Bahkan lirik terakhir lagu kebangsaan Arab Saudi, “Sari’i”, memiliki lirik berbunyi “asya al-malik lil-‘alam wal-wathan” (hiduplah raja untuk bendera dan negara). Padahal lembaga fatwa Arab Saudi (al-Lajnah ad-Daimah lil-Buhuts al-‘Ilmiyyah wal-Ifta’) pernah berfatwa bahwa menghormati bendera adalah bidah dan haram. Beberapa ulama yang mendapat label “Wahabi” juga menyatakan bahwa berdiri saat menyanyikan lagu kebangsaan adalah tradisi orang kafir Eropa dan karena itu haram diikuti oleh orang Islam, karena ada hadis “Barang siapa mengikuti suatu kaum maka ia bagian dari mereka.”
Bila mengikuti cara berpikir Pak Taufiq, semestinya lagu kebangsaan Saudi itu wajib direvisi. Sebab hidup raja seharusnya hanya untuk Allah semata.
Hal yang dipersoalkan Pak Taufiq itu sebenarnya adalah hal yang bagi jutaan orang biasa saja. Di Indonesia, di kalangan “Ikhwani”, ada satu nasyid cukup populer dari grup Shoutul Harokah yang berjudul “Palestina Tercinta”. Dalam nasyid itu terkandung lirik “untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsha tercinta.”
Tapi ini semua tentu tidak berarti bahwa Pak Taufiq tidak punya kecintaan pada Indonesia. Dalam puisi Palestina-nya, Pak Taufiq menulis; saat mendengar berita-berita mengenaskan dari Palestina, jantungnya “berdegup dua kali lebih gencar lalu tersayat oleh sembilu bambu derita.” Kalau kepada Palestina saja sebegitu besar cintanya, apalagi pada Indonesia.
Persoalannya, ya, cuma itu tadi: terlalu letterlijk memahami lirik, padahal Pak Taufiq, sebagai seorang pujangga yang mengantongi banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri, sudah akrab dengan majas dan metafora.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.