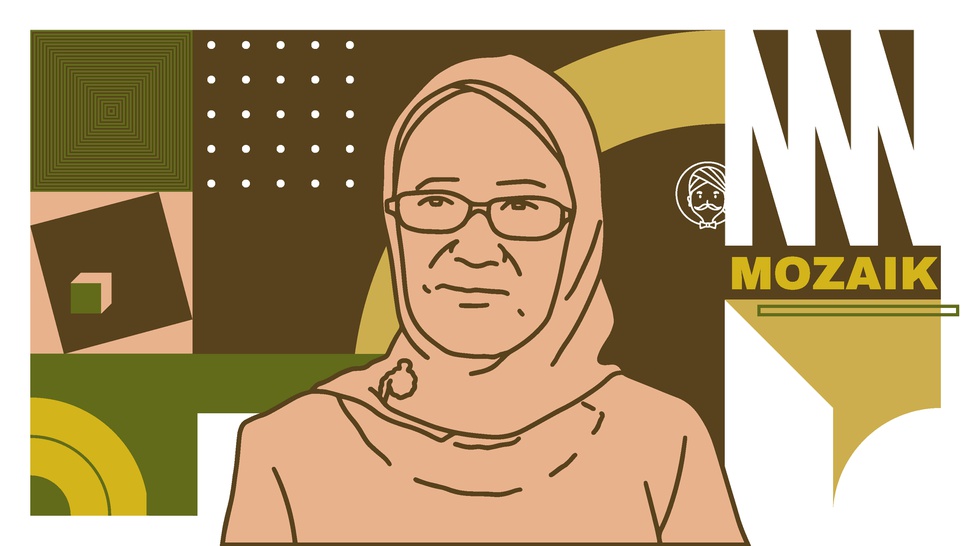tirto.id - Setelah Jepang kalah dan Perang Dunia II usai, masa perang di Indonesia berlanjut dengan revolusi kemerdekaan (1945-1949). Suasana perang juga mengancam Desa Gumukrejo, Kelurahan Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di situlah pasangan Wiroredjo dan Sani tinggal bersama anak-anaknya.
Sudjiatmi, anak perempuan satu-satunya dari pasangan tersebut, yang dilahirkan pada 15 Februari 1943, mengalami masa-masa penuh ketidakpastian itu. Semua kawula di bekas wilayah Hindia Belanda tentu harus hidup sulit pada 1940-an, termasuk keluarga pedagang kayu dan bambu ini.
Setelah Pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949, Boyolali bukanlah daerah yang sepenuhnya aman. Menurut catatan "Arsip Kabinet Perdana Menteri RIS Yogyakarta 1949-1950 nomor 142 tentang Keamanan di daerah sekitar Gunung Merapi Merbabu", di Boyolali terdapat pasukan Kumbojono yang di antaranya terdiri dari para penjahat. Pada 1950 pasukan ini kerap mengganggu keamanan.
Pasukan Kumbojono terkait dengan gerakan Merapi Merbabu Complex (MMC) yang sakit hati karena politik ketentaraan pada 1950-an. Tokoh terkenalnya adalah Suradi Bledeg yang, menurut Julianto Ibrahim dalam Dinamika Sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia (2018: 135), merupakan seorang benggol atau pemimpin para bandit di Boyolali dan sekitarnya. Keluarga Wiroredjo, baik secara langsung maupun tak langsung, kena imbas dari kacaunya keamanan. Sudjiatmi dan anak-anak Wiroredjo tumbuh besar di masa tak aman itu. Waktu baru bersekolah di Sekolah Rakjat (SR), Sudjiatmi merasakan zaman MMC di Boyolali.
Melewati Masa Sulit
Beruntunglah keluarga Wiroredjo. Meski kondisi ekonomi begitu sulit pada 1950-an, anak-anaknya bisa bersekolah. Tak semua anak di zaman Sudjiatmi bocah bisa bersekolah. Makan adalah hal sulit di zaman itu bagi kebanyakan orang Indonesia. Setelah MMC berlalu, pendidikan Sudjiatmi bisa berlanjut hingga SMP. Ketika SMP itulah Sudjiatmi mengenal Widjiatno Notomihardjo yang sudah duduk di bangku SMA. Keduanya pacaran waktu sekolah.
Sebagai anak kepala desa bernama Lamidi, Widjiatmo adalah pemuda beruntung. Seingat Sudjiatmi dalam Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi (2014: 21) yang ditulis Kristin Samah dan Fransisca Ria Susanti, Widjiatno saat itu sudah mengendarai sepeda motor pabrikan Birmingham Small Arms (BSA). Sudjiatmi pun merasakan dibonceng naik motor keren itu.
Widjiatno dan Sudjiatmi kemudian menikah di usia muda pada 23 Agustus 1959. Sudjiatmi masih 16 tahun dan Widjiatno masih 19 tahun. Setelah menikah, mereka hijrah ke kota Solo, pusat Karesidenan Surakarta.
Widjiatno menafkahi keluarganya dengan berbisnis kayu. Sudjiatmi, sebagai anak pedagang, terbiasa dengan dunia perniagaan. Seperti dicatat Domu D. Ambarita dan kawan-kawan dalam Jokowi - Spirit Bantaran Kali Anyar (2013: 65), Sudjiatmi terpengaruh keluarganya ketika melakoni bisnis penggergajian kayu bersama suaminya. Kakak Sudjiatmi, yang bernama Miyono, juga berbisnis. Dia pemilik PT Roda Jati, perusahaan ekspor mebel.
Sudjiatmi bisa saja menjadi ibu yang hanya mengurus rumah dan anak-anak, tapi dia memilih turut membantu suaminya. “Sesekali ia (Sudjiatmi) juga melakukan jual beli bambu di pasar dekat rumahya, saat usaha kayu milik suaminya lesu,” tulis Kristin Samah dan Fransisca Ria Susanti (hlm. 32). Tak hanya dagang, kursus merias pengantin pun dijalaninya.
Satu persatu anak Sudjiatmi dan Widjiatno lahir ketika mereka tinggal di Solo; mulai dari Joko Widodo, Iit Sriyantini, Ida Yati, hingga Titik Relawati. Pasangan ini sempat kehilangan—karena keguguran—bakal anak mereka yang diberi nama Joko Lukito. Keluarga Sudjiatmi dan Widjiatno pernah tinggal di Cinderejo Lor, sebuah kampung yang dicap "merah" di era Sukarno. Mereka juga pernah tinggal di sekitar Kali Pepe dan Kalianyar. Wawan Mas'udi dan Akhmad Ramdhoni (hlm. 51) menyebut keluarga Sudjiatmi dan Widjiatno pernah menjadi korban penggusuran. Mereka pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain.
Setelah melalui masa perang Indonesia-Belanda di zaman Revolusi dan masa penuh gangguan karena MMC, periode mencekam 1965 pun dilalui oleh Sudjiatmi dan Widjiatno. Solo, yang sejak 1948 dianggap kota "merah", pada 1960-an pun tidak berbeda. Tak heran bahwa Solo adalah kawasan banjir darah yang menandai lahirnya Orde Baru.
Banyak orang yang dicap sebagai bagian dari Partai Komunis Indoneisa (PKI) di Solo hilang kebebasan atau hilang nyawa. Ini berlaku bagi siapa saja, asal ada yang menuduh PKI atau terkait organisasi yang berhubungan dengan PKI. Kristin Samah dan Fransisca Ria Susanti (hlm. 29) menyebut beberapa tetangga Sudjiatmi dan Widjiatno kena ciduk aparat Orde Baru. Sementara itu, kepada pasangan ini, tak ada alasan bagi Orde Baru untuk menciduknya.

Menghadapi Isu Miring
Setelah masa 1965 berlalu, anak-anak Sudjiatmi-Widjiatno tumbuh besar. Joko Widodo alias Jokowi, si anak sulung, berhasil jadi sarjana di Jurusan Teknologi Kayu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah bekerja di pabrik kertas di Aceh, Jokowi berbisnis mebel di Solo, seperti pamannya. Lagi-lagi darah pengusaha menurun pada cucu Wiroredjo.
Setelah jadi pengusaha di Solo, Jokowi sukses terjun ke dunia politik dengan menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia. Jokowi adalah contoh bahwa "tampang Boyolali" bisa menjadi orang hebat di negeri ini. Sudjiatmi tentu boleh bangga dan bahagia dengan pencapaian anak sulungnya itu.
Menjadi Sudjiatmi di musim kampanye pilpres tidaklah menyenangkan. Selain berdoa untuk anaknya, Sudjiatmi harus menguatkan diri menghadapi isu bahwa Jokowi adalah keturunan PKI. Widjiatno, yang sudah tutup usia pada 23 Juli 2000, diisukan terkait gerakan terlarang G30S. Ada pula yang menyebut Widjiatno pernah menjadi komandan Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) Boyolali sekitar 1965—masa ketika Widjiatno berbisnis penggergajian kayu.
Menyanggah isu yang tidak jelas kebenarannya seperti sia-sia belaka sebab tidak akan membebaskan Jokowi dari tuduhan miring itu, terutama di kalangan yang anti terhadapnya. Isu PKI memang rentan bagi putra Sudjiatmi. Maklum, sebagian lawan politik anaknya masih gemar "menggoreng" isu soal PKI.
Sudjiatmi meninggal pada Rabu (25/3/2020) di Rumah Sakit TNI Tingkat III, Solo. Ia kini telah lepas dari masa-masa sulit dan tidak perlu lagi menghadapi “penjual isu PKI” yang mengganggu anaknya.
==========
Artikel ini terbit pertama kali pada 26 Maret 2020. Redaksi melakukan penyuntingan ulang dan menayangkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Ivan Aulia Ahsan & Irfan Teguh Pribadi