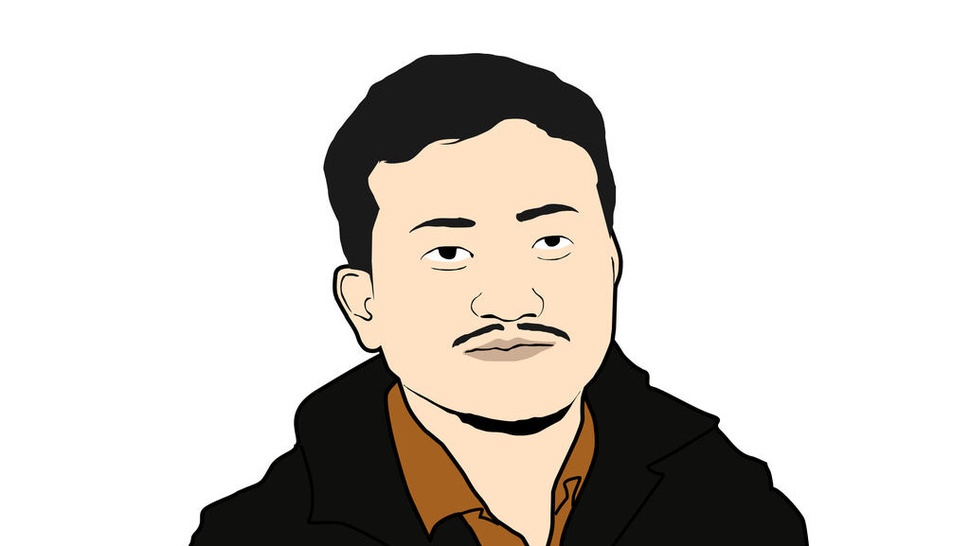tirto.id - “Selamat datang Rocky Gerung, presiden akal sehat,” tulis seorang kawan di laman Facebook pribadinya. Ucapan itu adalah bentuk antusiasme menyambut kedatangan Rocky di kota tempat kawan saya tinggal.
Dalam beberapa tahun terakhir, nama Rocky Gerung memang tidak dapat dipisahkan dari “akal sehat”, sebuah slogan yang konsisten ia angkat baik dalam acara televisi seperti ILC (Indonesian Lawyers Club), maupun ketika bersafari di berbagai kota.
Status kawan saya sendiri masih jadi pemandangan yang agak ganjil. Dalam kehidupan sehari-harinya, ia kerap menampilkan diri sebagai Muslim taat yang resah dengan beragam ancaman terhadap nasib Islam di Indonesia. Sedangkan Rocky, setidaknya sampai beberapa tahun lalu, sangat skeptis dengan mobilisasi identitas keagamaan di ruang politik. Jadi bagaimana pembicaraan soal “akal sehat” bisa mempertemukan mereka?
“Akal sehat” bukanlah sesuatu yang baru diusung Rocky menjelang pemilu presiden 2019. Pada penghujung 2010, ia telah menyampaikan orasi kebudayaan berjudul “Merawat Publik, Mengaktifkan Akal Sehat”. Dalam pidatonya tersebut, Rocky terlihat betul resah dengan berbagai persoalan republik di berbagai bidang. Salah satunya fenomena eksploitasi identitas keagamaan untuk memperoleh kekuasaan:
“Elit menunggangi kebodohan dan kepatuhan komunal, untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan. Sekarang ini, memimpin atau sekedar menjadi bagian dari suatu komunitas religius merupakan kebutuhan politis elit untuk mencapai status-status publik. Kesolehan menjadi simbol kewarganegaraan. Tatakrama menjadi pembatas kritisisme. Diskursus demokrasi menjadi tempat nyaman untuk mengorganisir kekuasaan dengan memanfaatkan peralatan agama. Simbol-simbol privat kini merajai kehidupan publik. Mayoritarianisme mendikte paham kedaulatan rakyat.”
Masih dalam orasi yang sama, Rocky juga mencurigai jargon “nasionalisme” yang dalam pandangannya kerap digunakan untuk mengaburkan persoalan kewarganegaraan yang lebih mendasar. Ia percaya bahwa republik yang baik seharusnya bersifat sekuler dan menjauhkan penerapan aspirasi agama di ruang publik sekaligus mampu menjamin hak-hak individu warga negara, termasuk perkara paling privat seperti orientasi seksual. Dalam konteks tersebut, Rocky mengadvokasi pentingnya menggunakan akal sehat sebagai kunci penting dalam menjaga nilai-nilai ideal republik.
Gagasan dalam pidato kebudayaan tersebut tidak terlalu banyak dibicarakan di luar lingkar cendekia, aktivis, dan pegiat sosial humaniora Indonesia. Namun, frasa “akal sehat” ini mendapatkan momentumnya pada tahun-tahun menjelang pemilu 2019. Rocky dalam periode ini hadir sebagai pengkritik konsisten pemerintah yang menurutnya sering bertindak dungu. “Akal sehat” dalam hal ini dihadirkan sebagai jawaban dari persoalan-persoalan di Indonesia.
Kritik yang dikemukakan Rocky pun bukannya tidak memiliki dasar. Pemerintahan Jokowi punya banyak persoalan hingga para pendukungnya sulit membangkitkan antusiasme yang sama seperti pada pilpres 2014. Pekerjaan rumah Jokowi terkait penyelesaian kasus HAM di masa lampau perlu diselesaikan. Ia juga masih harus membuktikan bahwa program infrastrukturnya betul-betul punya manfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat luas alih-alih sekadar memperkaya oligarki. Yang tidak kalah krusial, peristiwa seperti razia buku kiri, wacana soal dwifungsi TNI, hingga penangkapan Robertus Robet yang mengkritik tentara membuat orang juga mempertanyakan komitmen Jokowi pada penegakan demokrasi. Gugatan soal akal sehat dalam hal ini jadi terlihat amat wajar.
Frasa “akal sehat” dengan segera diangkat oleh tim pendukung Prabowo dalam kampanye mereka. Di ruang-ruang maya, “akal sehat” digunakan sebagai tagar yang melengkapi segala macam kritik terhadap pemerintah. “Akal sehat” juga tertera dalam spanduk-spanduk pendukung Prabowo yang tersebar di berbagai wilayah.
Akal Sehat tanpa Pijakan Jelas
Lalu, apa masalah penggunaan frasa “akal” sehat dalam kampanye politik?
Sedikitnya ada dua persoalan. Pertama, slogan “akal sehat” digunakan bertautan dengan upaya delegitimasi tidak hanya pada pemerintahan namun pilar-pilar demokrasi.
Beberapa waktu lalu misalnya, Rocky Gerung mencuit: “Hoax terbaik adalah versi penguasa. Sebab, mereka memiliki peralatan lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, ..lu tambah sendiri deh.” Dalam elaborasinya, Rocky membenarkan pernyataan itu dicuit bukan sebagai dukungan terhadap penyebaran berita bohong. Rocky menyatakan cuitan itu menunjukkan pandangan pribadinya bahwa persebaran hoaks adalah bukti bahwa pemerintah sudah kehilangan legitimasinya. Media arus utama dalam hal ini disebutnya telah bekerja sebagai corong pemerintah belaka. Perangkat kritik ini sejalan dengan strategi politik tim pendukung Prabowo yang juga kerap secara terbuka mempertanyakan media arus utama sekaligus institusi formal seperti KPU.
Kerja media arus utama di Indonesia, seperti juga kerja pemerintahan, tentu bukan tanpa permasalahan. Namun, bahkan dengan segala keterbatasannya, media arus utama masih menjadi sumber informasi yang bisa dimintai pertanggungjawaban ketimbang pesan berantai di Whatsapp maupun Facebook. Oleh karenanya, sumber informasi dari media arus utama masih penting jadi rujukan warga negara dalam membuat keputusan. Apalagi mengingat para pendukung Prabowo juga kerap secara aktif memproduksi hoaks, mulai dari soal penganiayaan Ratna Sarumpaet, kontainer surat suara yang dicoblos, hingga rumor “pemerintah pro-PKI” yang masih tersebar luas hingga kini.
Terkait upaya delegitimasi tersebut, masalah kampanye “akal sehat” yang kedua adalah bagaimana frasa ini digunakan untuk membuka jalan bahkan menjustifikasi eksploitasi identitas etnis dan agama dalam politik. Bicara soal Aksi Bela Islam 212, Rocky mengusulkan Monas sebagai akronim “Monumen Akal Sehat” alih-alih “Monumen Nasional”. Sebab, menurut Rocky, sebagai ekspresi kegelisahan rakyat pada pemerintah, 212 adalah gerakan yang menunjukkan akal sehat. Dukungan ini jelas mengabaikan implikasi nyata Aksi 212 pada peningkatan intoleransi seperti yang ditunjukkan Mietzner & Muhtadi (2018).
Selain itu, dengan menyatakan dukungan pada mobilisasi sentimen agama, Rocky justru mengabaikan keresahannya yang menjadi salah satu dasar tesis soal “akal sehat”. Sebaliknya, ketika belakangan dituntut menggunakan pasal serupa dengan Ahok, ia buru-buru mengeluarkan Maklumat Akal Sehat sebagai pembelaan. Dalam hal ini, frasa “akal sehat” dikeluarkan sesuai kebutuhan praktisnya.
Inkonsistensi penggunaan frasa “akal sehat” berakar pada minimnya elaborasi tesis itu sendiri. Baik dalam pidato kebudayaan sewindu silam hingga refleksi atas perkembangan reformasi tahun lalu, Rocky tidak secara khusus menjelaskan apa yang dimaksudnya dengan "akal sehat", apalagi menjabarkan langkah terperinci untuk merawatnya. Absennya elaborasi ini menjadikan frasa akal sehat amat mudah ditekuk dan dipelintir sedemikian rupa sebagai justifikasi untuk apapun.
Kelenturan inilah yang membuat kawan saya yang percaya pada penerapan hukum agama di ruang publik bisa dengan antusias menyambut Rocky yang meyakini pentingnya ruang publik sekuler. Mereka mungkin tidak pernah berbagi ide yang sama soal masa depan Indonesia, tapi sepertinya sama-sama percaya bahwa pemerintahan Jokowi harus diakhiri.
Slogan “akal sehat” dengan demikian direduksi sebagai “apapun asal bukan pemerintah Jokowi”. Pembicaraan soal akal sehat hari ini barangkali memang tidak pernah menyentuh visi tentang republik, melainkan cuma pragmatisme politik yang sudah lama kita kenal.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.