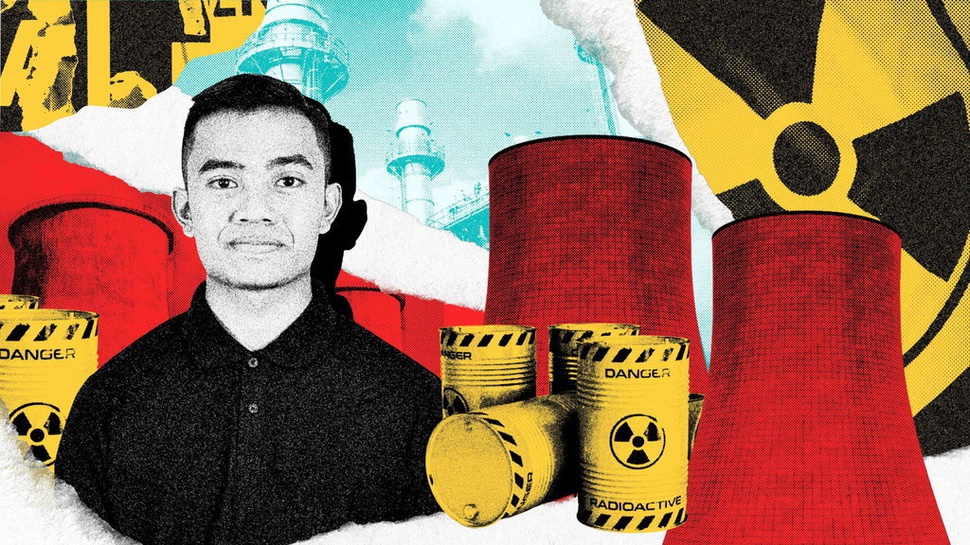tirto.id - Perjalanan nuklir Indonesia memasuki babak baru setelah penandatanganan kontrak kerja sama antara PT PLN Indonesia Power dan USTDA dalam “Indo-Pacific Chamber of Commerce and Industry Business Forum” pada 18 Maret 2023 lalu. Kerja sama itu merupakan tindak lanjut perencanaan awal dan penyusunan techno-economy assessment (TEA) antara PLN, BRIN, dan NuScale Power LLC mengenai agenda pembangunan small modular reactor di Kalimantan Barat.
Gagasan mendorong energi nuklir tanah air agar melesat tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Salah satu momentum pentingnya yakni terbentuknya IndonesiaCenter of Excellence on Nuclear Security and Emergency Preparedness (I-CoNSEP) pada 19 Agustus 2014. I-CoNSEP ini inisiatif bersama antara Bapetan, BIN, BRIN, serta lembaga dan kementerian dalam rangka merintis sistem keamanan dan kesiapsiagaan nuklir nasional. Langkah mengadopsi nuklir ini kian tegas setelah pembangunan PLTN Kalimantan Barat dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2020-2024.
Ibarat membentangkan layar, angin sedang kencang-kencangnya. Begitu juga narasi pengembangan PLTN ini. Narasi itu kian menguat seiring munculnya bayang-bayang ancaman gangguan energi nasional akibat krisis energi global, sehingga kebutuhan listrik berskala besar dan efisiensi energi menjadi krusial.
Akan tetapi, di balik narasi optimisme nuklir sebagai pilihan ideal tanpa celah, terselip pertanyaan sederhana mengenai seberapa banyak hal yang harus kita korbankan demi menggelar karpet merah bagi masa depan nuklir itu sendiri. Secara keseluruhan, nuklir akan membuat kita membayar mahal dalam berbagai hal meliputi penangguhan wacana demokratisasi energi, pengetatan regulasi, ketergantungan terhadap pendanaan asing, dan kompensasi dampak lingkungan.
Pertama, gagasan demokrasi energi yang fokus pada intensifikasi partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya strategis justru berisiko tergadaikan dengan pendekatan nuklir yang cenderung sentralistik. Pembatasan atau blokade informasi yang sering diterapkan pada kawasan nuklir seringkali mengesampingkan prinsip transparansi dengan dalih menjauhkan publik dari beragam kekhawatiran. Padahal, konsekuensi nuklir yang menentukan hidup banyak orang seharusnya menjadi pertimbangan untuk semakin menginklusikan perbincangan demokrasi energi sebagai lively public dialogue (dialog yang inklusif), sehingga warga negara dapat lebih akrab terlibat dalam proses energi bersih yang terjangkau.
Kedua, komitmen pemajuan nuklir juga menuntut kerangka regulasi ketat dalam runtutan tahapan mulai dari perencanaan hingga pemantauan. Pengetatan perlu mencakup keamanan siber, penetapan ambang batas konsekuensi radiologi, dan rencana kontijensi nasional. Hal tersebut menjadi tanggung jawab yang tak terpisahkan dalam menjamin keamanan masyarakat secara luas. Kedudukan regulasi sangat vital untuk menghadirkan stabilitas lingkungan, teknis, manusia, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, pola klasik tata kelola institusi yang tumpang tindih dan inkonsistensi kebijakanperlu segera diarahkan pada komitmen jangka panjang dalam memastikan terciptanya kepercayaan publik dan keteraturan ekosistem energi.
Ketiga, pendanaan juga menjadi komponen esensial sebagai penentu keberhasilan pembangunan berbiaya tinggi. Tidak dapat dipungkiri, industri nuklir merupakan investasi mahal karena aliran dana harus mampu mengakomodasi biaya pembangunan pembangkit, penelitian dan pengembangan intensif, penyimpanan dan pembuangan limbah selama ratusan tahun, pelatihan staf nuklir, penambangan dan pembelian bahan bakar uranium, serta asuransi kecelakaan.
Besarnya biaya infrastruktur nuklir di tengah kerentanan fiskal negara akan melanggengkan kebiasaan pemerintah Indonesia yang lebih mengandalkan investasi asing dan pembiayaan utang sebagai solusi instan. Sebagaimana bantuan pendanaan Amerika Serikat dalam pembangunan PLTN di Kalimantan Barat merupakan rangkaian proyek dalam Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII). Pendanaan asing pada satu sisi menghadirkan loncatan transformasi teknologi yang signifikan tetapi sebagai harganya kemandirian dan penguasaan penuh dalam tata kelola nuklir akan terdisrupsi.
Keempat, konsekuensi lingkungan juga menjadi pertimbangan utama untuk menilai optimalisasi nilai dari pemajuan energi nuklir. Sebagaimana nuklir pernah ditargetkan untuk menyuplai konsumsi energi nasional sebesar 5 persen pada 2025 tetapi proporsi tersebut sesungguhnya tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi karbon.
Maka dari itu, intensi dekarbonisasi perlu diarahkan pada progresivitas global daripada lokal. Penelitian terkini telah menghitung bahwa untuk menurunkan emisi secara optimal diperlukan reaktor sebanyak 2.000 unit. Harapan tersebut masih terlampau tinggi jika dibandingkan akumulasi reaktor global yang hanya berjumlah 411 reaktor hingga pertengahan 2022.
Selain itu, narasi nuklir sebagai energi bersih juga perlu ditinjau kembali. Memang dalam proses pengolahannya tidak dihasilkan CO² tetapi dalam penghitungan akumulatif siklus dari hulu ke hilir akan memperlihatkan penggunaan energi fosil yang masif. Di balik promosi energi bersih yang melekat pada nuklir terdapat proses destruktif dalam penambangan dan pengayaan uranium serta pembuatan batang bahan bakar pada persamaannya.
Selain itu, permasalahan limbah juga menjadi kesulitan utama karena belum ditemukan mekanisme pengelolaan yang dapat menyelesaikannya secara ideal. Tempat pembuangan permanen pun masih memiliki risiko laten jika bergeser ke kawasan hunian penduduk akibat peristiwa alam tertentu.
Limbah tersebut sangat rentan mengancam kesehatan lingkungan dan mengubah pemanfaatan ruang pada kondisi yang tidak bisa dikembalikan. Apalagi kekhawatiran atas risiko kecelakaan juga melekat dalam refleksi kita ketika melihat kondisi Fukushima terkini. Setidaknya pada maret 2022 lalu sekitar 32.400 penduduk masih hidup sebagai pengungsi hingga pencabutan perintah evakuasi baru terjadi di bulan juni 2022 tetapi angka pemulangannya hanya berkisar 3,6 persen.
Nuklir dinarasikan positif sebagai tawaran masa depan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pertimbangan untuk mengadopsi atau menentangnya perlu didasari pada kalkulasi utuh tentang seberapa besar pengorbanan yang harus dibayar, ketimbang semata-mata hanya mempertimbangkan manfaatnya. Terlebih kebiasaan akut homo sapiens yang eksploitatif dan gandrung mengubah konfigurasi lingkungan.
Oleh sebab itu pengembangan energi nuklir tidak hanya cukup menjawab kewajiban kompensasi atas risiko yang dibawa. Lebih dari itu, eksistensi nuklir harus memastikan kalau kedaulatan energi dapat benar dirasakan. Selama kedaulatan itu tak pernah nyata, segala pengorbanan bagi energi nuklir tidak akan terbayar dengan layak.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.