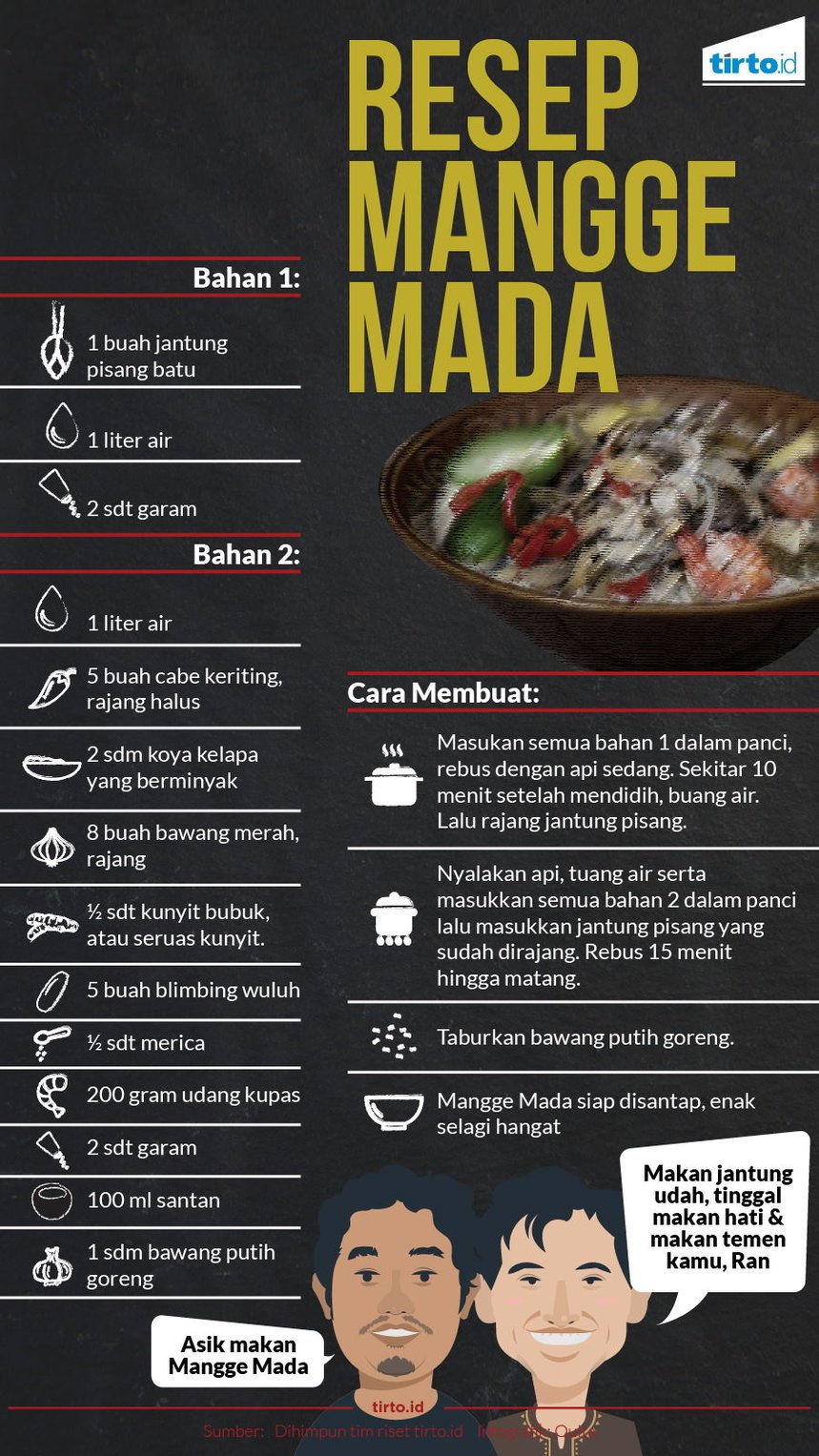tirto.id - Tentang pengingat melankolia terhadap kampung halaman, Orhan Pamuk punya petuah yang ia tulis dalam memoar hidupnya, Istanbul. "Untuk menikmati halaman belakang Istanbul, untuk menghargai juluran tanaman rambat dan pohon-pohonan yang memberkahi puing-puing dengan keagungan tanpa sengaja: pertama-tama dan paling penting, kamu harus menjadi orang asing terlebih dulu."
Didid Haryadi merasakan hal itu ketika ia berada di Istanbul, ribuan kilometer dari kampung halamannya di Bima, Nusa Tenggara Barat. Melankolia itu makin terasa ketika Ramadan tiba dan ia rindu makanan khas kota kelahirannya itu. Dalam momen seperti itu, Didid mungkin merasakan apa yang dirasakan oleh Pamuk.
Sebenarnya merantau bukanlah hal asing bagi Didid. Sejak lulus SMA pada 2005, ia pergi merantau ke Malang, Jawa Timur. Pria penyuka musik hip-hop ini diterima di jurusan Sosiologi, Universitas Brawijaya. Ia lulus pada 2009 dan sempat bekerja sebagai peneliti dan asisten dosen di almamaternya. Pada 2013, Didid kedatangan tamu; seorang kawan lama yang ingin berdiskusi soal beasiswa. Didid membantunya mengoreksi esai untuk keperluan beasiswa sang kawan.
Dari sana Didid penasaran ingin mencoba melamar beasiswa. Pada Ramadan 2014, Ia mendapat kabar baik, diterima di jurusan sosiologi di Istanbul University. Pada September 2014, akhirnya Didid tiba di kota yang dikenang Pamuk dengan sendu ini.
Sebagai mahasiswa, kegiatan Didid tak jauh dari kuliah dan mencari literatur untuk menggarap tugas. Akhir pekan, Didid kerap minum teh (çay) ataupun kopi Turki (Türk kahvesi) bersama teman-temannya. Kadang disela dengan pergi ke toko buku, toko musik, mengunjungi museum, atau menghadiri workshop dan seminar gratis yang diadakan oleh kampus.
Karena Didid dan kawan-kawannya sesama orang Indonesia di Turki menggemari literasi, mereka membuat kelompok diskusi bernama Indonesia Turkey Research Community. Sekarang Didid juga menjadi Pimpinan Redaksi portal Turkish Spirits. Situs ini yang belakangan menjadi rujukan terpercaya untuk berita dan cerita mengenai Turki.
Di Istanbul, Didid tinggal di yurt, alias asrama. Yurt punya mudur, semacam induk semang yang berkantor dalam asrama dan memantau para penghuninya. Salah satu peraturan di asrama adalah tidak boleh memasak. Peraturan ini dibuat untuk mencegah kebakaran. Apa daya, tak ada kekangan yang cukup kuat mengurung hasrat menyantap makanan kampung halaman.
Didid dan kawan-kawan beberapa kali mencoba memasak makanan Indonesia. Senjatanya adalah: rice cooker. "Kami pakai rice cooker buat masak nasi, opor ayam, goreng telur, atau memanaskan lagi ayam bakar," kata Didid tertawa. Ramadan tahun 2015, Didid dan kawan-kawannya menggoreng bakwan dengan rice cooker. Karena fungsi yang sudah melenceng jauh, tak heran kalau alat ajaib milik mereka ini cepat rusak. Selama 3 tahun Didid tinggal di Istanbul, sudah 3 rice cooker berganti.
Agar kegiatan memasak ini tak ketahuan, jendela dibuka supaya aroma masakan minggat. Tak lupa, detektor asap ditutup dengan plastik dan lakban. Kadang mereka juga pakai heater untuk memasak dengan metode rebus. Mereka pernah kepergok, dan heater disita. Peraturan memang ketat. Peralatan masak ini disimpan di bawah kasur. Sebab kalau ada sidak dan ditemukan alat masak semisal heater atau rice cooker, induk semang akan menyitanya.
"Tapi kami beli lagi, dan selalu masak tengah malam biar tak ketahuan," kata Didid tertawa geli.
Ramadan selalu mengingatkan Didit pada proses melamar beasiswa. Momen penting dalam hidupnya. Di Turki, Ramadan amat berbeda dengan di Indonesia. Secara suasana, Turki terasa lebih kalem dan kurang meriah. Tak ada bedug, nihil suara pengumuman jelang azan, apalagi ngabuburit. Secara durasi, berpuasa di Turki rata-rata berlangsung selama 17 jam.
Begitu pula soal makanan. Menurut Didid, menu sahur di Turki berpusat pada corba (sup), buah zaitun, keju, roti, juga telur rebus. Kalau berbuka, hidangan agak lebih variatif. Sesekali ada nasi atau makaroni sebagai sumber karbohidrat. Untuk protein, ayam panggang dan daging adalah pemasok utama. Yang juga sering hadir kala berbuka adalah manisan Turki atau kurma.
Namun ada pula banyak kesamaan antara suasana Ramadan di Indonesia dengan Turki. Misalkan tentang masjid besar yang selalu ramai oleh jamaah. Atau tadarus yang selalu dilantunkan selepas salat Tarawih. Selain itu, hampir semua masjid besar di Turki menyelenggarakan buka bersama atau membagikan takjil gratis.
"Suasananya bikin ingat Ramadan di Malang dan di banyak daerah Indonesia lain," ujarnya.
Tapi tentu saja, dari semua persamaan itu, ada hal-hal yang tak bisa tergantikan. Masakan hasil laut buatan ibu Didid, misalkan. Sejak kecil, Didid dan seluruh anggota keluarga memang biasa menyantap masakan laut. Tinggal di Bima itu artinya kamu bisa membeli bahan makanan laut dengan harga lebih murah. Di Turki, kantongmu harus cukup dalam untuk bisa makan hasil laut.
Masakan andalan ibu Didid adalah palumara, masakan yang selama ini identik dengan Makassar. Bima dan Makassar memang punya hubungan erat sejak dulu, sejak era Kesultanan Bima dan Kesultanan Gowa. Salah satu tanda keeratan ini adalah menikahnya Sultan Bima, Abdul Khair Sirajuddin dengan Karaeng Bonto Je'ne yang merupakan putri Kesultanan Gowa sekaligus adik kandung Sultan Hasanuddin, pada 1646.
Karena hubungan yang terjalin sejak ratusan tahun lalu, wajar kalau ada banyak bentuk kebudayaan yang nyaris sama antara Bima dan Makassar. Salah satunya adalah palumara ini. Selain nama, inti masakan ini juga sama: kuah kekuningan dari kunyit dan punya cita rasa asam segar dari asam Jawa (kadang diganti dengan belimbing wuluh). Ibu Didid biasa menggunakan ikan kerapu atau baronang sebagai bahan utama palumara.
Di keluarga Didid juga ada pembagian peran di dapur. Jika sang ibu memasak makanan utama, ayah Didid akan mengupas kelapa muda. Atau membuat do’co, kondimen yang terdiri dari mangga muda, tomat, bawang, cabe dan jeruk
Namun dari semua makanan Bima, yang membuat Didid begitu rindu rumah adalah takjil yang hanya bisa ditemui di kampung halamannya itu: karedo maci kandole dan ba'e neba (ada yang menulisnya sebagai bae neba). Nama pertama adalah bubur yang berisi bulatan dari beras ketan kukus. Dari bentuk dan rasa, nyaris serupa dengan bubur sumsum biji salak yang banyak ditemui di Jawa. Makanan ini juga berbahan santan dan gula aren.
"Bedanya, karedo maci kandole itu bola-bolanya sebesar kelereng," ujar Didid.
Sedangkan ba'e neba lebih istimewa lagi, ujar Didid. Jajanan ini hanya ada di Bima pada saat bulan Ramadan. Selain itu, karena proses pembuatannya yang rumit dan butuh waktu lama, hanya sedikit orang yang bisa membuatnya. Hasilnya memang bikin masygul: coba ketik ba'e naba di Google. Nyaris tak ada hasil memuaskan. Nihil resep dan proses pembuatannya. Begitu pula gambarnya. Jika tak segera dibuat dokumentasinya, bisa jadi jajanan tradisional ini akan dilupakan kemudian hilang sama sekali.
"Bentuknya sih seperti kue bolu atau sarang semut yang dipotong per bagian gitu. Hanya saja, ba'e neba ini punya kuah berupa air gula," ujar Didid.
Ramadan tahun ini Didid tak pulang ke Indonesia. Ia harus menahan diri. Tesisnya sedang digarap, tak lama lagi akan selesai. Targetnya: akhir tahun 2017 Ia sudah bisa kembali ke Indonesia. Pulang ke Bima, menyantap palumara kegemarannya. Sementara itu, Didid masih harus menahan diri dan bersabar.
Tapi bukankah memang itu memang hakikat puasa dan seorang perantau?
Penulis: Nuran Wibisono
Editor: Maulida Sri Handayani