tirto.id - Richard (Gading Marten) baru bangun pagi, cuma pakai singlet rombeng dan kolor yang tampak kedodoran.
Ia jalan dari kamar menuju balkon kecil rumahnya. Sambil mengusap-usap mata dan selangkangan, Richard menyapa Kelun—kura-kura 17 tahun yang didaku sebagai sahabat. Dari lantai dua ruko itu—yang juga dipakai jadi kantor percetakan warisan keluarga—Richard menyapa tetangganya sambil membelakangi kamera. Tangannya lalu merogoh ke dalam bagian belakang kolor kedodoran itu. Memamerkan bokongnya ke hadapan penonton.
Adegan itu adalah pembuka Love For Sale, sekaligus perkenalan pertama kita pada tokoh utama: Richard Ahmad Wijaya. Dari sana kita tahu, seberapa tak acuhnya sang karakter utama tentang penampilan diri.
Karakter ini memang antitesis dari tokoh-tokoh pemeran utama pria dalam banyak film Indonesia. Ia memang punya garis muka keturunan Roy Marten, tapi fitur lainnya medioker belaka: perut buncit dan fesyen yang jelek. Sungguh jauh dari karakter Ben atau Jodi yang diperankan Chico Jericho dan Rio Dewanto dalam Filosofi Kopi; atau tokoh-tokoh tampan, atletis, dan necis yang langganan diperankan Jefri Nichol, Adipati Dolken, dan Reza Rahadian.
Richard justru tampil apa adanya—persisnya culun. Ia lebih sering pakai kaos, singlet dan kemeja kedodoran, dengan jins atau celana bahan ukuran reguler, dan rambut klimis yang dibelah pinggir. Penampilan yang jarang dipotret film sebagai gaya atraktif.
Ia juga berperawakan ketus, judes, dan disiplin waktu. Karyawan di kantor percetakan Richard mesti datang, makan, dan istirahat di waktu yang sudah diaturnya. Kalau tidak, siap-siap saja dimarahi dengan kata-kata yang relatif kasar.
Namun yang bikin karakter ini menarik, ia cenderung terkesan santai dan nyaman-nyaman saja dengan hidupnya yang ironisnya berjalan lambat. Meski selalu merecoki karyawan-karyawannya soal disiplin waktu, di usia 41, Richard cuma peduli tentang bisnisnya dan Kelun.
Sampai suatu ketika, teman-teman nongkrong Richard bikin taruhan tentang nasib percintaannya. Mereka ingin lihat pacar kawan yang mereka panggil ‘om’ itu. Pasalnya, Richard memang selalu mengaku punya kekasih yang tak pernah tampak batang hidungnya.
Ia ditantang untuk membawa sang kekasih ke acara pernikahan salah satu kawannya, yang diadakan seminggu setelah taruhan itu dibuat. Kali ini Richard terpancing dan tak bisa santai lagi. Meskipun nantinya kelabakan mencari “pacar bohongan”, ia telanjur menjabani taruhan itu karena disinggung-singgung harga diri.
Plot ‘taruhan’ dan ‘pacar bohongan’ ini adalah lagu lama di dunia sinema Indonesia. Dua elemen itu biasanya akan dikawinkan dengan karakter jomblo yang sibuk mengejar karier hingga lupa urusan cinta. Tekanan sosial biasanya membawa mereka ke ide tersebut: mencari pacar sewaan. Salah satu plot serupa yang masih segar di ingatan adalah Kapan Kawin? (2015) yang diperankan Adinia Wirasti dan Reza Rahadian.
Richard bukan sekadar karakter bujang lapuk dalam film—ia adalah kita semua—orang Indonesia dengan segala tekanan sosialnya.
Namun, tak seperti karakter Adinia dalam Kapan Kawin?, Richard sama sekali tak mengejar karier apa pun, meski memang sibuk dengan usahanya. Hidupnya nyaris tanpa ambisi. Ruko di Jakarta Pusat itu saja jarang sekali ditinggalkannya. Kemang di Jakarta Selatan adalah jarak yang jauh bagi perspektif Richard. Ia bahkan bisa nyasar ketika harus pulang sendiri. Yang bikin ia kalem dalam urusan cinta: cuma trauma di masa lalu—sesuatu yang bikin ia enggan mencoba lagi.
Tema film ini memang bukan ide baru, tapi eksekusi dan solusi bagi nasib Richard adalah tawaran segar dari sutradara Andibachtiar Yusuf dan penulis naskah M Irfan Ramly.
Tak sengaja, Richard membaca selebaran aplikasi jodoh yang dicetak di kantornya. Dari sana, ia akhirnya menemukan Arini (Della Dartyan), yang kemudian dikontrak 45 hari sebagai pacar sewaan. Perempuan 24 tahun itu cantik, jangkung, atletis, dan punya senyum luar biasa manis. Ia juga luwes, cerdas, dan berpenampilan menarik—tipikal yang menonjol di kerumunan. Ini belum termasuk kemampuan memasak dan pengetahuannya tentang bola.
Meski didatangi sosok nyaris sempurna macam Arini, Richard tak sekonyong-konyong jatuh hati, lalu memuja-muja pacar sewaannya itu. Ia memang kagum, tapi lumayan selow di awal pertemuan. Richard bahkan sempat menyuruh Arini pulang lebih dulu dari masa kontrak yang mereka miliki—sebab ia ingin melanjutkan hidup ‘no life’-nya.
Ada waktu yang cukup sampai akhirnya Richard sadar kalau kharisma Arini mustahil ditolak. Jeda tersebut yang membuat film ini berisi. Tergila-gila dalam sekali pandang mata cuma bisa terjadi di film. Di kehidupan nyata—apalagi bagi karakter yang hidupnya macam Richard—jatuh cinta butuh waktu, dan malu-malu dulu. Kedalaman cerita ini yang membuat Love for Sale jadi istimewa.
Dunia Richard dibangun dengan sangat hati-hati dan teliti. Sepanjang film, kita akan terus menemukan hal baru tentang dirinya, yang masuk mulus lewat adegan-adegan sederhana dan dialog-dialog kecil. Misalnya tentang umur, jumlah saudara, dan latar belakang Cina.
Tak ada informasi yang buru-buru dijejalkan, atau terlambat datang. Rasanya seperti berkenalan dengan orang nyata di dunia sebenarnya.
Duet Manis Gading dan Della
Naskah yang dalam menggali karakternya ini tak akan bisa ditangkap baik, jika performa aktornya tak jitu. Karakter Richard yang getir-pahit-tapi-berhumor-gelap disajikan Gading Marten dengan sangat mantap. Richard memang punya aksen Betawi macam gaya bicara Gading Marten yang sering kita dengar, tapi selebihnya ia adalah bujang lapuk versi milenial yang benar-benar medioker. Susah untuk tak bersimpati pada karakter Richard.
Sementara Arini, sebagai debut Della juga karakter yang mustahil tak bikin jatuh hati (siapa pun, bukan cuma Richard). Semua dialog yang keluar dari mulutnya tak ada yang janggal atau berbau antinalar macam dialog-dialog yang sering muncul dalam sinetron atau FTV.
Meski karakternya dibangun dengan stereotipe asian-wife yang kental—misalnya tinggal di rumah saat pasangan kerja, bangun pagi buat sarapan, dan sangat-amat tipikal pelayan—Arini tetap punya pesan-pesan feminis yang kuat. Ia berani, pekerja keras, dan tak takut melakukan gerakan duluan saat melakukan seks. Khusus di poin terakhir, ia bahkan yang jadi pemandu Richard di atas ranjang. Memosisikan diri di atas lawan jenisnya—sebagai simbol bahwa Arini adalah perempuan yang kuat.
Adegan seks memang hadir bukan cuma sebagai pemanis belaka. Ia memperkuat jalan cerita, dan kedalaman sang tokoh. Keputusan Richard ingin melamar Arini jauh lebih masuk akal karena seks itu sudah lebih dulu dilakukan. Membuatnya jadi lebih sakral, karena tak memandang seks sebagai satu-satunya tujuan dari pernikahan. Mempertebal karakter Richard yang menghargai Arini.
Perintilan kecil ini jadi penting, karena di awal-awal film, Yusuf dan Ramly menitipkan adegan-adegan misoginis khas film Indonesia. Misalnya ketika teman-teman taruhan Richard bersiul pada perempuan di depan pub.
Karakter Arini, meski hadir untuk bikin Richard jatuh hati dengan kemampuannya ‘melayani’, setidaknya juga disisipi pilihan-pilihan berani. Lewat keberanian itu, kita bisa melihat bahwa Arini bisa tampil setara sebagai pasangan Richard.
Karakter Richard yang juga bias gender di awal—dibuktikan dengan memaki karyawan laki-laki yang telat, tapi tidak melakukan hal sama pada karyawan perempuannya—lambat laun juga berkembang jadi pasangan yang melihat Arini setara. Ia mulai peduli pada kebutuhan Arini, yang selama ini selalu memperhatikan kebutuhan Richard.
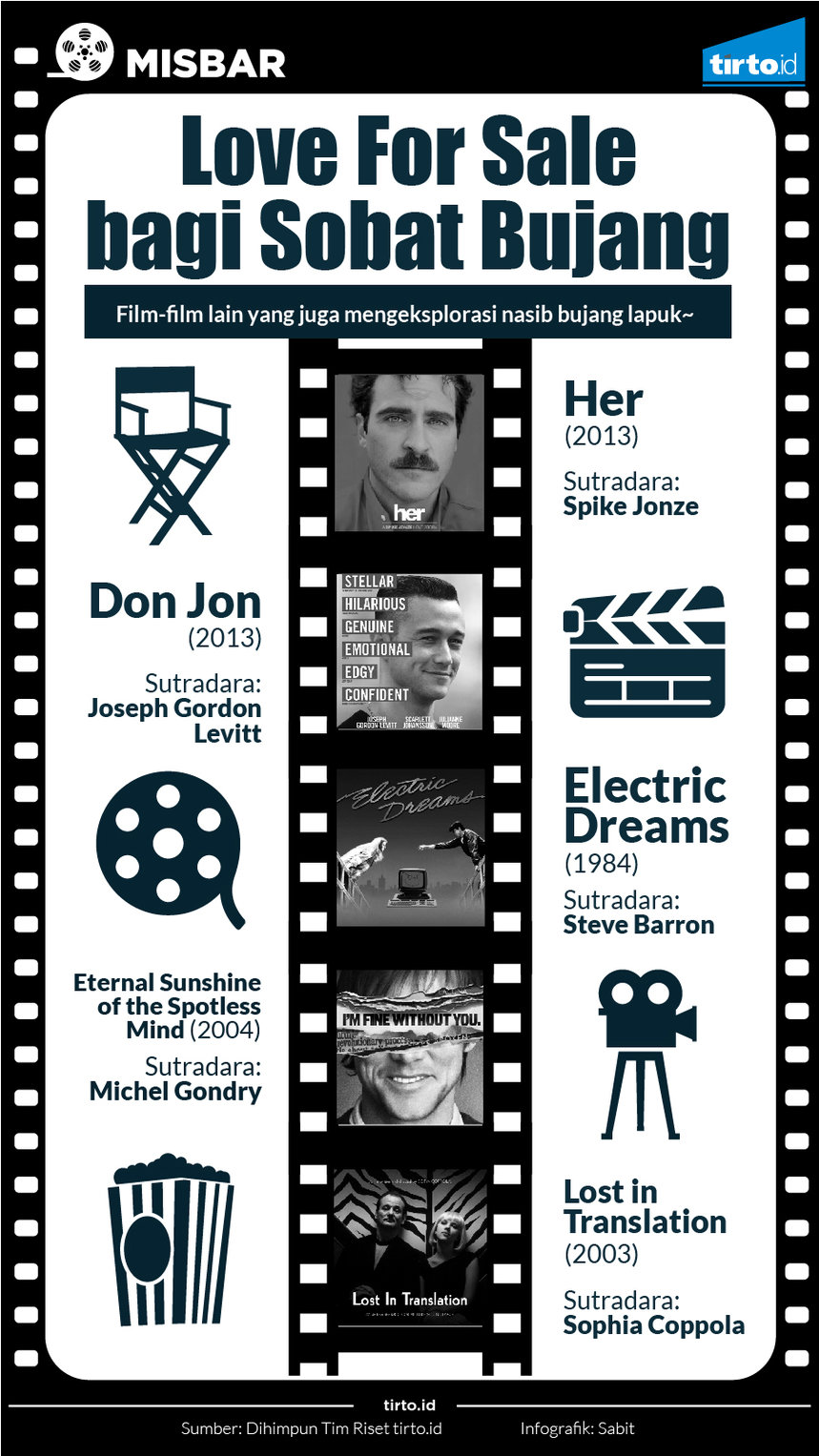
Duet lakon keduanya membuat hubungan itu terasa masuk akal dan nyata. Jadi, ketika Arini tiba-tiba hilang di hari terakhir kontraknya, bukan cuma Richard yang gerasak-gerusuk kehilangan. Penonton pun akan ikut merasakan.
Terutama karena Love for Sale memberi beberapa potong adegan dalam beberapa menit—semacam sebuah jeda—buat Richard dan penonton untuk benar-benar menghayati kehilangan si Arini yang nyaris sempurna.
Love for Sale ditutup dengan premis manis yang jarang ditawarkan roman-roman Indonesia serupa. Ia mengajarkan keikhlasan—yang mungkin saja susah bagi sebagian orang—tapi mau tak mau harus dipilih. Lewat simbol pemberian hadiah dari Richard ke karyawan-karyawannya, premis itu ditutup tegas oleh sutradara dan penulis naskah. Piring, jam, dan mobil antik miliknya adalah bentuk keikhlasan Richard menjemput pengalaman baru dalam hidupnya.
Meski manis di tengah, dan menggigit di ujung, Love for Sale tetap saja tak terlepas dari kekurangan ini-itu. Terutama urusan teknis yang terlalu kentara. Misalnya nama Richard Ahmad Widjaya yang jadi lebih panjang ketika ditelepon narahubung Love Inc., jadi Richard Ahmad Daniel Widjaya. Atau surat Arini yang tidak ikut terekam saat Richard bangun di pagi pertamanya tanpa Arini, lalu sekonyong-konyong hadir pada beberapa adegan berikutnya. Atau suara minta maaf Richard yang tertutupi desahan Arini, ketika dia orgasme duluan.
Film ini juga tak akan bisa dinikmati semua orang. Butuh jarak usia dan pengalaman agar paham alasan-alasan mereka para tokoh utama.
Namun, ihwal-ihwal kecil itu rasanya tak cukup untuk bikin kisah cinta Richard-Arini kita lupakan begitu saja. Lewat perspektif Richard—si Bujang Lapuk versi milenial ini—kita harusnya paham kalau masing-masing orang punya waktunya sendiri. Dan tak perlu jadi suara-suara bising yang heboh mencampuri urusan orang lain.
Penulis: Aulia Adam
Editor: Windu Jusuf











