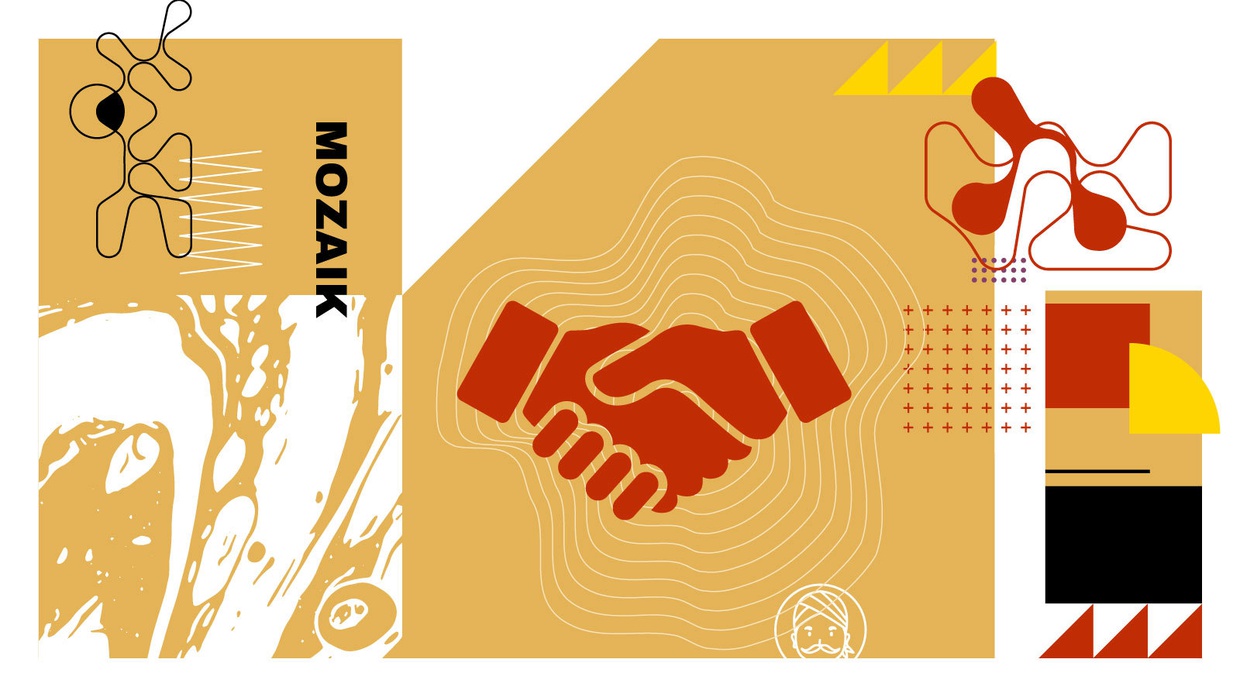tirto.id - Ketika ditunjuk menjadi pemimpin delegasi Belanda dalam perundingan formal pertama dengan Indonesia, mantan Perdana Menteri Belanda, Willem Schermerhorn (menjabat 1945–1946) sudah tahu ia akan dicemooh oleh publik negerinya sendiri. Dalam buku hariannya yang diterbitkan berjudul Het Dagboek van Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn (1970), ia telah menyatakan bersiap untuk menerima “gunjingan” dari seantero Kerajaan Belanda.
Kesiapan mental dan perkiraannya bukan tanpa alasan. “Gunjingan” yang perlu dinantikan olehnya itu telah menyasar salah satu pejabat terkemuka Hindia Belanda, Hubertus Johannes van Mook (Pelaksana Tugas Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1942–1948). Asal mula tanggapan buruk publik Belanda berasal dari tindakan awal yang dilakukan oleh rombongan pemerintah Hindia Belanda dalam pengasingan di Australia—Van Mook, Charles van der Plas, dan kawan-kawan—sesaat setelah Perang Dunia II usai sesudah pernyataan menyerah Jepang pada 15 Agustus 1945.
Setelah kembali ke Indonesia, Van Mook—atas usulan dari anggota Dewan Hindia yang nyentrik, Van der Plas—mengadakan perhubungan dengan Sukarno pada 5 Oktober 1945. Mendengar hal ini, Menteri Daerah Seberang Lautan (dahulu disebut Menteri Kolonial), Johann Logemann marah besar. Persoalannya, Sukarno dipandang sebagai kaki tangan Jepang dan bukan wakil yang sah dari orang-orang Indonesia, apalagi sebagai pihak yang setara dengan Van Mook.
Sesuai dengan yang pernah disepakati oleh Sekutu dalam konferensi di Yalta (4–11 Februari 1945), negeri koloni Belanda akan “dikembalikan” kepada negeri induknya seusai perang. Salah satu pertimbangan yang paling mendorong keputusan itu adalah dampak pendudukan Jerman di Belanda yang memorakporandakan keadaan ekonomi dan sosial negeri itu.
Setelah satu perang selesai, perang lain (Perang Dingin) mengikuti. Oleh sebab itu, untuk menghindari pengaruh komunisme yang menurut blok Amerika Serikat akan lebih subur di negeri yang ekonominya hancur, Belanda harus dikuatkan dengan diberi kembali koloni raksasanya di Asia, yakni Hindia Belanda. Para pembesar negeri koloni Hindia Belanda yang selama pendudukan Jepang mengasingkan diri ke Australia kemudian turut serta Sekutu untuk menginjak kembali tanah Hindia.
Namun, di luar perkiraan sebelumnya, tanah Hindia itu telah diproklamasikan sebagai negara merdeka pada 17 Agustus 1945 dengan nama Republik Indonesia. Kenyataan ini melenceng dari perkiraan Sekutu dan kemudian dikerdilkan sebagai siasat atau aksi Jepang yang mencoba mendirikan negara boneka.
Selain itu, Belanda memandang proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai tindakan yang tidak sah. Situasi peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang di Kalijati pada Maret 1942 menunjukkan adanya kesalahan diplomatik dari pihak Jepang.
Jenderal Imamura yang menjadi wakil tentara Jepang tidak melibatkan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh (menjabat 1936–1942) yang saat itu memegang kekuasaan sipil. Ia berpaling pada Jenderal Hein Ter Poorten yang beberapa hari sebelumnya diserahi kekuasaan seluruh angkatan perang koloni. Oleh sebab itu, dalam Kapitulasi Kalijati, tidak ada penyerahan sipil dan tidak ada tanda tangan dari sang wali negeri, Tjarda van Starkenborgh. Kekuasaan sipil kemudian dialihkan kepada Van Mook yang berada di pengasingan Australia pada tahun 1944. Dengan demikian, secara de jure, Belanda merasa punya kuasa atas Hindia Belanda.
Jepang di Kepulauan Indonesia hanya dipandang melakukan pendudukan militer, bukan mengadakan pemerintahan yang sah. Maka itu, Jepang dirasa tidak punya hak untuk memperbolehkan atau memberi janji kemerdekaan pada Indonesia. Dasar inilah yang dipegang teguh oleh Belanda selama periode yang dikenal luas sebagai masa revolusi Indonesia (1945–1949).
Pada 1 November 1945, Van Mook kembali menjadi sasaran tembak para politikus Belanda ketika mengadakan perundingan formal dengan Sukarno. Saat itu, Van Mook merasa perlu mengadakan perhubungan dengan pemerintah republik karena keadaan lapangan Indonesia memang menunjukkan adanya eksistensi republik, paling tidak di Jawa. Dengan demikian, eksistensi negara baru itu tidak dapat digaibkan menjadi nol—namun justru harus diajak duduk bersama.
Ketika berita sampai di Negeri Belanda, Twede Kamer—parlemen rendah Belanda—meradang dan mengutuk tindakan Van Mook. Suara di Belanda menyerukan Sukarno sebagai fasis kolaborator Jepang. Sutan Sjahrir yang lulusan pendidikan Eropa, pada saat itu, adalah figur yang lebih dapat diterima oleh publik dan politikus Belanda. Namun demikian, di dalam negeri, Sjahrir justru dituduh pengkhianat bahkan oleh kawan-kawannya di Kelompok Menteng Pemuda (Menteng 31)—Sukarni dan Chaerul Saleh—serta oleh kelompok pemuda revolusioner di bawah Tan Malaka. Bahkan, ia kelak sempat diculik oleh kelompok Tan Malaka pada 29 Juni 1946.
Perundingan Van Mook dan Sjahrir kemudian terlaksana secara informal pada 16 November 1945. Di balik wajah diplomasi, kekuatan militer Belanda terus bergerak memasuki Indonesia. Pada 30 Desember 1945, menjelang tahun baru, Angkatan Laut Kerajaan Belanda mendarat di Tanjung Priok. Pada titik itu, kedua pihak tetap teguh pada pendirian, Belanda menolak Republik Indonesia sebagai negara merdeka, dan Indonesia tetap mempertahankan argumen bahwa ia telah merdeka.
Saat delegasi Indonesia pergi ke Belanda pada April 1946 di bawah pimpinan Mr. Suwandhi, Perdana Menteri Schermerhorn—yang nantinya jadi delegasi Belanda di Linggarjati setelah selesai menjabat—tidak menerima delegasi di Den Haag (ibu kota pemerintahan) karena memandangnya sebagai utusan jajahan atau negara bagian, bukan negara merdeka. Mereka diterima di daerah kecil, Hoogeveluwe.
Perundingan ini tidak menemui titik temu sehingga pada 23 Juli 1946, Ratu Wilhelmina membentuk Komisi Jenderal yang diketuai oleh Schermerhorn untuk bertolak ke Indonesia dan memulai perundingan lain. Sang mantan perdana menteri, sekalipun sempat menolak delegasi Indonesia di Den Haag, dikenal sebagai orang yang pikirannya sejalan dengan Van Mook, lebih pro-Indonesia dibandingkan dengan rekan-rekan parlemennya yang lain.

Seperti dijelaskan K. M. L. Tobing dalam Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati (1986), sebelum perundingan antara Komisi Jenderal dan pihak Republik Indonesia diadakan, kerajaan mengutus satu komisi survei yang terdiri dari P. J. Koets, P. Honig, dan C. B. de Lange. Komisi ini—Komisi Koets—bertujuan meneliti keadaan Jawa pada umumnya. Komisi Koets menyampaikan bahwa daerah pedalaman Jawa lebih tidak menunjukkan konfrontasi terhadap kedatangan Belanda. Akhirnya, bertolak dari saran ini, daerah kecil Linggarjati dipilih.
Adrian B. Lapian dalam Menelusuri Jalur Linggarjati (1992) menggarisbawahi tentang perbedaan penyebutan tempat pelaksanaan perjanjian di naskah dan di publik. Publik setempat menyebut tempat itu sebagai “Linggarjati” sedangkan naskah perjanjian mencantumkan nama “Linggadjati”.
Perjanjian yang ditandatangani pada 15 November 1946 itu pada pokoknya berisi pengakuan Belanda terhadap wilayah de facto Republik Indonesia di Jawa, Sumatra, dan Madura. Pada sisi internasional, akan dibuat suatu persekutuan yang meletakkan Republik Indonesia dan Negeri Belanda pada posisi yang sama, namun di bawah mahkota Kerajaan Belanda.
Dari sisi Belanda, ini adalah perjanjian yang radikal, melangkahi apa yang semula diinginkan pihak Belanda. Sementara dari sisi Indonesia, pengakuan sekadar Jawa, Sumatra, dan Madura, juga menuai ketidakpuasan yang menyebabkan kekacauan sosial di mana-mana, termasuk bentrokan antara laskar dengan tentara resmi Indonesia, juga pembantaian orang Tionghoa di Tangerang, Nganjuk, dan wilayah lainnya.
Wakil kedua negeri yang sebenarnya duduk di Linggarjati—menurut catatan harian Schermerhorn—“dalam suasana yang hangat dan kekeluargaan”, langsung disambut hujatan dan cercaan oleh rakyat masing-masing. Anggota Komisi Jenderal, F. de Boer, sudah memperingatkan bahwa komisi dengan segera akan dipandang sebagai “orang gila” oleh rakyat Belanda.
Ketika menulis tentang Linggadjati dalam Het Akkoord van Linggadjati uit Het Daboek van Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn (Tanpa Tahun), Schermerhorn pulang dengan menyiapkan diri untuk menerima “disalahpahami [dalam taraf yang] paling hebat” oleh khalayak. Nasib sama juga dialami oleh Sutan Sjahrir.
Penulis: Christopher Reinhart
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id