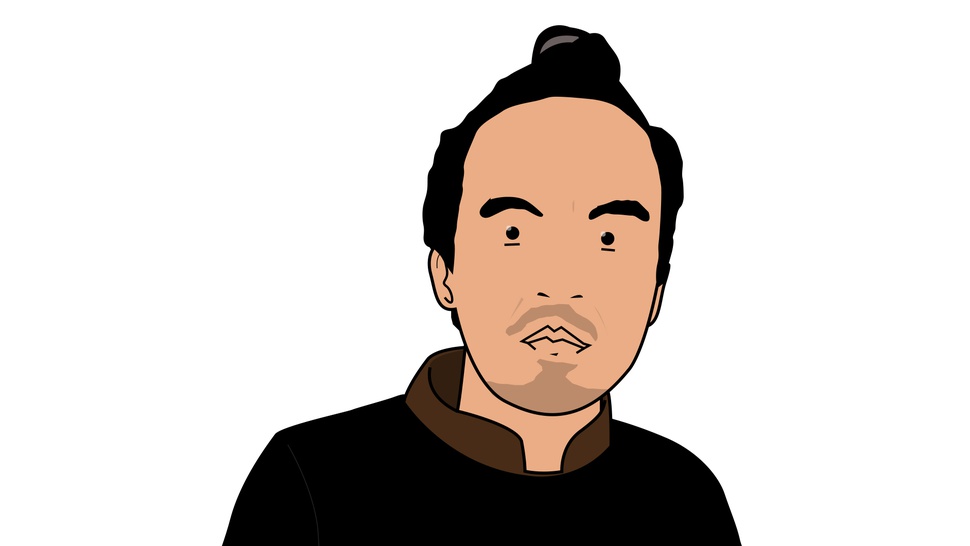tirto.id - -- Beware the crack! (anonim)
Dan, retakan (kecil) itu pada akhirnya keluar dari lidah api Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Ucapan Al-Maidah itu adalah retakan kecil yang melahirkan mobilisasi massa jutaan orang di Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Bahkan, aksi massa itu hadir secara serial.
Anda tahu, sejak penggulingan kekuasaan 1998 lewat aksi demonstrasi, tak ada mobilisasi massa sebesar ini. Sialnya, mobilisasi seakbar ini dilakukan umat Islam, dan bukan orang-orang “kiri” atau yang memiliki arsiran pandangan yang sama (baca: kelompok kidal).
Alih-alih mau menahan diri atau paling tidak melakukan refleksi ke dalam, kelompok yang kini bekerja paruh-waktu dalam simpul-simpul kecil kekuasaan ini terus-menerus melakukan ejekan dan insinuasi terhadap aksi massa ini di lini masa media sosial.
Macam-macam bentuk insinuasi itu yang pada pokoknya tak ada yang benar dengan aksi serial umat itu. Semua dicari kesalahannya. Bahkan, ada teriakan melarang agama dibawa-bawa ke politik. Bablas.
Islam itu sepanjang abad 20 adalah Islam Politik. Jika “organisasi Islam modern” di Indonesia dipatok bermula dari Sarekat Islam, maka maujudnya adalah Islam Politik, yakni Islam yang selalu melakukan negosiasi dengan kekuasaan kolonial. Dan, pada suatu kali bentrok dan saling memakan, tapi di lain kesempatan bisa saling memakai dan menunggangi.
Namun, sejarah mobilisasi Islam gigantis, ya, tak jauh-jauh dari isu “retakan kecil” sebagaimana yang terjadi tahun 2016 ini. Isunya berputar di sekitar ini saja: penistaan agama dengan beberapa turunannya: menggambar/menghina Kanjeng Nabi, masuk masjid tanpa sepatu, serta isu nabi palsu dan ajaran sesat.
Ayo, lihatlah 20 ribu massa Sarekat Islam dari Surabaya digiring meng-grudug Solo lantaran satu paragraf tulisan—SATU PARAGRAF—di halaman depan koran Djawi Hisworo tahun 1918. Dan subjek yang usil menulis itu ya wong-wong Sarekat Islam juga (SI Surakarta).
Ini juga barangkali sepele di mata Anda. Seorang tentara diisukan masuk ke masjid kecil dengan sepatu lars. Alhasil, “sepatu lars” itu memicu lahirnya kerusuhan berdarah Tanjung Priok 1984. Apa karena sepatu lars? Tentu bukan, ini akumulasi dari pemaksaan Asas Tunggal yang mendapatkan protes di mana-mana dan disertai beberapa penangkapan. Tapi, retakan kecil bernama “sepatu lars” itulah yang mengetuk keberanian umat untuk turun ke jalan berhadapan muka-muka dengan tentara.
Atau, demonstrasi di seantero dunia, bahkan menghebat di beberapa kota besar di Indonesia macam Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta saat Salman Rushdie merilis novel Ayat-Ayat Setan pada 1989.
Belum reda soal Ayat, si tangan Midas dalam tabloid hiburan Monitor, Arswendo Atmowiloto, meniup seruling perang besar dengan melakukan—yaolo, mungkin Anda sependapat dengan Mas Wendo—tindakan survei main-main saja. Hanya soal menempatkan Nabi Muhammad terlempar dari 10 besar di halaman Monitor—bahkan peringkatnya lebih buruk ketimbang peringkat Arswendo sendiri—melahirkan mobilisasi massa dan sekaligus mengantarkan Mas Wendo ke penjara.
Anggap saja domain “penistaan agama”—berapa pun gradasinya—jika dikelola secara baik oleh aktor dan agensinya, adalah isu yang menjanjikan mobilisasi massa luar biasa besarnya di kalangan umat Islam. Saya pastikan, tak ada isu lain selain isu satu ini yang bisa memantik “persatuan umat” untuk sama-sama memadatkan jalan raya di seantero kota.
Jadi, setiap kaum punya “isu khas” yang melahirkan mobilisasi massa. Tentu saja, bagi kalangan nasionalis, termasuk yang ultra sekali pun, isu yang menggerakkan mereka adalah kemerdekaan dan kedaulatan negara.
Sukarno adalah alamat paling mudah disigi sebagai agitator dengan anugerah mulut nomor satu tiada tanding menjadi pemompa semangat massa untuk berkumpul dan bergerak. Ketika dihadapkan pada pilihan saat berpolemik dengan Hatta, apakah massa atau kader, Sukarno jelas memilih di jalan massa dengan segala konsekuensinya.
Dengan hanya mengikuti lini masa sejarah hidup Sukarno kita bisa dengan presisi mengenali gelombang mobilisasi massa sebulan setelah kemerdekaan di Lapangan Ikada hingga aksi Trikora dan Dwikora di tahun awal 60-an.
Ini tak terhitung setiap tanggal 17 Agustus atau perayaan-perayaan khusus—bahkan upacara keagamaan dan olahraga—Sukarno tampil berpidato dalam samudera massa. Termasuk kaum yang sami'na wa atho'na dengan Sukarno dan menjadikan aksi massa sebagai ritus sehari-harinya adalah PKI bersama organisasi satu keluarga ideologis dengannya.
Orde Baru Harto bahkan dilahirkan oleh massa gabungan seluruh kekuatan anti Sukarno dan PKI dengan mempertontonkan mobilisasi massa sebagai sebuah teater berdarah di seluruh negeri. Dan, itulah mobilisasi massa tiada tanding dengan tingkat kejatuhan korban yang paling mengerikan—atau dalam bahasa para hakim Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag tahun 2015: genosida!
Ketika di Ciamis ada kabar muncul aksi long march ke Jakarta untuk aksi umat Islam Seri III pada 2 Desember, mestinya tak perlu kaget. Long march adalah metode perjuangan memenangkan opini. Itu pertunjukan sosial yang jika bukan karena isu yang kuat sulit sekali terlaksana; bahkan dibayar berlipat-lipat sekali pun.
Di Madiun 1948 ketika kekalahan sudah di depan mata, PKI/Pesindo mengambil langkah long march untuk memenangkan opini massa di perdesaan di sepanjang perjalanan. Sebagai aksi protes atas Perjanjian Renville, tentara Siliwangi melakukan long march dari Jawa Tengah dan Yogya ke Jawa Barat pada 1949.
Demikian itu juga yang dilakukan petani-pejuang Jambi saat mengadukan nasib ke para priyayi agung di Jakarta (Maret 2016); atau petani pejuang Kendeng yang berjalan kaki dari Pati ke Semarang untuk aksi keadilan agraria di kamar pengadilan (November 2015).
Aksi tetap sama dengan tujuan yang sama: protes. Namun, isu yang menggerakkannya yang berbeda.
Baik kiri, tengah, dan kanan—sipil (dari buruh hingga perawat) atau militer—dalam praktiknya semua percaya: mobilisasi massa adalah metode perjuangan yang efektif untuk protes sekaligus unjuk kekuatan. Dan dalam beberapa momen politik, aksi massa ini bisa merampas kekuasaan dan mengubah haluan sebuah negara.
Anda kira setiap tanggal 1 Juni atau 5 Oktober kepolisian RI dan TNI melakukan parade bersenjata dengan segala keahlian dan ketangkasannya itu untuk apa kalau bukan unjuk kekuatan paling mutakhirnya dan menebarkan “ancaman”: jangan coba-coba bermain api dengan kami.
Bukankah Presiden Joko Widido juga sudah menikmati gulali manfaat aksi-aksi mobilisasi massal saat terjadi mobilisasi (politik) massa 5 Juli 2014 yang dibungkus dengan nama Konser Salam 2 Jari.
Ini negara teater, Saudara. Mobilisasi massa itu (konser) pertunjukan sosial.
Dan ingat, setiap mobilisasi massa membutuhkan kelihaian menangkap momentum isu. Yang lebih organik lagi adalah kemampuan tanpa batas untuk mengelola komunikasi dalam persekutuan dengan para massa di arus bawah.
Aksi serial umat Islam di paruh akhir tahun 2016 ini adalah buah dari perkawinan isu dan pengelolaan organik dengan arus bawah massa pengajian dan majelis talim yang kebanyakan orang-orang melarat di kampung-kampung.
Mari menonton pertunjukan sosial ini dengan antusias karena potensi memobilisasi massa dalam jumlah sangat besar masih sangat terbuka dan sembari belajar kepada mereka tentang aksi sosial!
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.